Oleh : Drs. Muhapril Musri, M.Ag
 Zainuddin Labay el-Yunusi, lahir di sebuah “rumah gadang” (rumah adat lima ruang) yang terletak di jalan menuju Lubuk Mata Kucing Kenagarian Bukit Surungan, Padang Panjang tahun 1890 M atau bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1308 H. Ia lahir dari pasangan Syeikh Muhammad Yunus al-Khalidiyah dan Rafi’ah. Ayahnya Syekh Muhammad Yunus al-Khalidiyah adalah seorang ulama terkenal dan memegang jabatan sebagai qadhi di daerah Pandai Sikek.
Zainuddin Labay el-Yunusi, lahir di sebuah “rumah gadang” (rumah adat lima ruang) yang terletak di jalan menuju Lubuk Mata Kucing Kenagarian Bukit Surungan, Padang Panjang tahun 1890 M atau bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1308 H. Ia lahir dari pasangan Syeikh Muhammad Yunus al-Khalidiyah dan Rafi’ah. Ayahnya Syekh Muhammad Yunus al-Khalidiyah adalah seorang ulama terkenal dan memegang jabatan sebagai qadhi di daerah Pandai Sikek.Kakeknya bernama Imaduddin, juga seorang ulama terkenal, pemimpin aliran tarikat Naqsyabandiyah dan ahli ilmu falak (hisab) di daerahnya. Bila ditelusuri lebih jauh silsilah keturunannya dari pihak ayah, maka akan diperoleh suatu gambaran bahwa ia mempunyai hubungan pertalian darah dengan Haji Miskin salah seorang tokoh “harimau nan salapan” dalam gerakan Paderi. Ibunya bernama Rafi’ah, juga seorang wanita yang taat beragama. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal pada sekolah tertentu, karena waktu itu jenjang pendidikan formal masih tertutup bagi anak perempuan, khusunya di Minangkabau. Akan tetapi ia bisa membaca al-Quran, membaca dan menulis huruf Arab. Ada kemungkinan ini berkat bimbingan kakaknya Kudi Urai, yang sangat menyangi dan memanjakannya. Silsilah keturunan Zainuddin Labay dari pihak ibu berasal dari nagari IV Angkat Candung Agam.
Tidak diketahui secara pasti siapa kakek dan buyutnya di pihak ibu. Namun dari data yang diperoleh ternyata bahwa ibunya berasal dari keluarga yang taat beragama juga. Sebab, daerah IV Angkat Candung merupakan daerah tempat lahirnya ulama-ulama besar Minangkabau seperti, Ahmad Khatib, Syeik Sulaiman Arrasuli, dan lain-lain. Perjalanan hidup Ibu Zainuddin Labay, Rafi’ah, selanjutnya diurusi oleh saudara kandungnya, Kudi Urai. Kudi Urai inilah yang mengasuhnya hingga dewasa dan mencarikan pasangan hidup, menginginkan agar adiknya Rafi’ah tersebut kawin dengan ulama, atau setidak-tidaknya dengan orang yang taat menjalankan agamanya.
Keinginan Kudi Urai (setelah menunaikan ibadah haji namanya diganti dengan Hajjah Khadijah), akhirnya terpenuhi ketika pilihannya jatuh kepada seorang ulama dari Pandai Sikat yakni Muhammad Yunus al-Khalidi, sekalipun hati kecil Rafi’ah enggan menerimanya disebabkan Muhammad Yunus telah mempunyai isteri enam orang. Perkawinan Rafi’ah dengan Syeikh Muhammad Yunus adalah perkawinan yang agak unik.
Dikatakan demikian karena ada beberapa alasan. Pertama, jarak umur antara Rafi’ah dengan Muhammad Yunus sangat jauh berbeda. Rafi’ah baru berumur 16 tahun, sedangkan Muhammad Yunus berusia 42 tahun. Kedua, salah satu fenomena yang berkembang pada awal abad kedua puluh adalah adanya tradisi ulama atau tokoh agama beristeri lebih dari satu orang. Seorang ulama yang beristeri lebih dari satu orang mampunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Ketokohan dan keahlian seseorang dalam ilmu agama menjadi salah satu faktor bagi masyarakat lain untuk mengawinkan anaknya dengan seorang ulama, sekalipun ulama itu telah mempunyai isteri sebelumnya. Ada semacam berkah yang akan diperoleh bila seseorang kawin dengan tokoh agama.
Syeikh Muhammad Yunus sebagai seorang ulama juga mengalami hal serupa. Sebelum kawin dengan Rafi’ah, Syeikh Muhammad Yunus telah enam kali kawin dan mempunyai beberapa orang anak, Rafi’ah akan dijadikan sebagai isteri ketujuh. Sebagai seorang perempuan, ia tidak mau hidup di madu. Dalam konteks yang lebih jauh, ia takut nanti dianggap mengambil isteri orang.
Berdasarkan kepada hal-hal tersebut sebetulnya Rafi’ah, merasa enggan dikawinkan dengan orang yang sudah kawin berkali-kali, namun berkat bimbingan kakaknya, Hajjah Khadijah, yang telah berjasa memelihara dan membesarkannya, Rafi’ah tidak berani menolak keinginan kakanya tersebut agar ia kawin dengan Muhammad Yunus. Ada setitik harapan keluarga yang tertumpang dari perkawinan Rafi’ah dengan Muhammad Yunus ini, yaitu agar nanti dapat melahirkan keturunan yang baik-baik, alim, cerdas dan taqwa kepada Allah SWT.
Buah perkawinan Rafi’ah dengan Syeikh Muhammad Yunus, lahir lima orang putera dan puteri. Dua di antaranya muncul sebagai tokoh paling berpengaruh dalam gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau, masing-masing Zainuddin Labay el-Yunusi dan rahmah el-Yunusiyah.
Zainuddin Labay adalah anak tertua, sedangkan Rahmah adalah anak paling bungsu dari lima bersaudara tersebut. Keduanya telah mengukir riwayat hidupnya sendiri-sendiri dalam lembaran sejarah tanah air tercinta ini dengan perjuangan dalam bidang pendidikan Islam. Lima orang putra dan putri yang lahir dari hasil perkawinan antara Syeikh Muhammad Yunus dan Rafi’ah adalah:
1. Zainuddin Labay (1890-10 Juli 1924 M/1308-1342 H)
2. Mariah (1893-7 Januari 1972 M/1311-1391 H)
3. Muhammad Rasyad (1895-Februari 1956 M/1313-1375 H)
4. Riahanah (1898-8 Desember 1968 M/1316-1388 H)
5. Rahmah (1900-26 Februari 1969 M/1318-1388 H)
Hanya ibu tercinta inilah (kemudian lebih akrab dipanggil Ummi Rafi’ah) yang mendidik putera dan puterinya hingga dewasa dan dapat menyaksikan perjuangan anak-anaknya, sebab pada tahun 1906, suaminya Syeikh Muhammad Yunus (Tuangku Pandai Sikek), berpulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun, di saat anak-anaknya masih kecil. Ummi Rafi’ah sendiri wafat pada tanggal 1 Juli 1948 bertepatan dengan 23 Sya’ban 1369 H (seminggu menjelang bulan Ramadhan) dalam usia 76 tahun.
Dilihat dari garis keturunannya sebagaimana diterangkan di atas, maka nampaklah bahwa Zainuddin Labay, berasal dari keturunan ulama, cendekiawan muslim, taat beragama serta pelopor gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Ayahnya, Syeikh Muhammad Yunus, di samping sebagai seorang qadhi di Pandai Sikat, juga tercatat sebagai penganut dan tokoh aliran tarikat Naqsyabandiyah di Minangkabau, mengikuti jejak kakeknya Syeikh Imaduddin yang juga penganut aliran tarikat Naqsyabandiyah.
Ketokohan ayahnya dalam tarikat ini, dapat dilihat dari gelar “khalidiyah” yang dipanggilkan di belakang nama Muhammad Yunus, menunjukkan bahwa dia adalah penganut tarikat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah. Martin van Bruinssen, mencatat bahwa Syeikh Muhammad Yunus, merupakan salah seorang khalifah tarikat Naqsyabandiyah yang terpenting dan paling berpengaruh di daerah Koto Lawas kenagarian Batipuh. Bila dikaitkan ketokohannya dalam bidang tarikat Naqsyabandiyah dengan pendapat Bruinessen di atas, menurut analisa penulis, hal tersebut ada benarnya, karena isteri keempat Syeikh Muhammad Yunus, berasal dari Koto Lawas kenagarian Batipuh. Ia tinggal bersama isterinya di daerah tersebut, sekaligus berfungsi sebagai tokoh tarikat Naqsyabandi di sana. Sedangkan dari pihak ibu, walaupun tidak diperoleh data rinci tentang latar belakang dan silsilah keturunannya, namun dapat diduga bahwa ibu Zainuddin Labay, berasal dari keluarga yang taat beragama juga. Ini terbukti dari cara dia mendidik anak-anaknya hingga menjadi dewasa, dua di antaranya menjadi orang besar dalam sejarah Islam di Minangkabau khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
Di antara pendidikan rumah tangga, sebagai pembinaan pribadi yang diterima Zainuddin Labay bersaudara dari orang tuanya adalah berkaitan dengan penanaman sistem nilai, yakni mendidik dengan memberikan contoh pengalaman hidup. Sistem nilai itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pula serta jangan suka pendendam. Jangan suka menyampaikan omongan orang lain kepada seteru (musuh)-nya. Anak gadis tidak baik berdiri di depan pintu/jendela seraya melihat orang lalu lintas di jalan raya. Bila saudara laki-laki atau paman datang ke rumah segeralah letakan air minum (kopi atau teh). Anak perempuan tidak sopan berbicara keras dan tertawa terbahak-bahak. Jangan sombong dan membanggakan diri karena itu bukan sifat manusia, apalagi sifat seorang muslim.
Zainuddin Labay el-Yunusi pertama kali menikah pada tahun 1912 dengan Sawiyah, seorang gadis berasal dari Bukit Surungan Padang Panjang. Dari perkawinan ini, ia dikarunia dua orang anak, seorang perempuan bernama Zuraida Zainuddin (lahir 1914) dan seorang laki-laki bernama Tanius Mathran Hibatullah Zainuddin (lahir 1917). Zuraida, anak perempuan Zainuddin satu-satunya yang sempat menjadi staf pengajar pada Diniyah Putri yang didirikan adiknya Rahmah el-Yunusiyah, setelah menyelesaikan pendidikan di sana selama tujuh tahun. Bahkan sempat pula memimpin Kulliyatul Mu’allimat el-Islamiyah (KMI) cabang Riau di Pekanbaru. Adiknya Tanius Mathran Hibatullah, tidak begitu terlihat kiprahnya, karena ia telah wafat lebih dahulu dari Zuraidah.
Perkawinan Zainuddin dengan Sawiyah, ternyata tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Di satu sisi, sebagai seorang yang masih berusia muda, Zainuddin Labay tidak ingin kehidupan rumah tangganya berakhir hanya karena perceraian dengan isteri pertamanya. Untuk dapat meringankan beban pikiran dan memotivasi dirinya dalam mewujudkan cita-citanya yang luhur, ia tetap memerlukan seorang pendamping hidup yang setia. Di sisi lain terlihat kesan bahwa tradisi ulama dan tokoh agama beristeri lebih dari satu orang masih tetap berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu Zainuddin menikah lagi dengan seorang gadis dari desa Jambu, Gunung - Padang Panjang, bernama Djaliah. Namun sampai akhir hayatnya, Zainuddin tidak memperoleh anak dengan isterinya yang kedua ini. Cita-cita Zainuddin dilanjutkan oleh adiknya Rahmah el-Yunusiyah.
Latar belakang keluarga, dalam perjalanan karir seorang Zainuddin Labay, sebagaimana di atas, menurut hemat penulis, sangat mempengaruhi keberhasilannya menggapai cita-cita pembaharuan. Suatu fakta yang sulit dibantah adalah pada umumnya mereka yang tampil sebagai ulama dan tokoh agama adalah mereka berasal dari keturunan ulama dan keluarga taat beragama. Beberapa orang di antaranya dapat disebut seperti Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syeikh Abdul Karim Amrullah, Syeikh Abdullah Ahmad, Zainuddin Labay, Rahmah el-Yunusi, dan lain-lain. Mereka berasal dari keturunan ulama dan keluarga yang taat menjalankan ajaran agama.
Berangkat dari kenyataan ini dapat dikatakan, mereka yang berasal dari keturunan ulama lebih sering mendapat pengajaran berupa penanaman nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup baik ketika ia belajar agama di surau ayahnya maupun ketika mereka berada di lingkungan keluarga, ketimbang mereka yang berasal dari keluarga biasa. Oleh karenanya tradisi ulama beristeri lebih dari satu berkembang pesat. Kharisma ulama semakin tinggi. Setiap orang tua selalu berkeinginan mengawinkan anak gadis mereka dengan seorang ulama, walaupun ulama itu telah beristeri sebelumnya. Karena diharapkan dari perkawinan itu akan lahir generasi-generasi alim, cerdas dan bertaqwa kepada Allah SWT.
B. Latar Belakang Pendidikan
Pada masa Zainudin Labay el-Yunusi, ada dua bentuk sistem pendidikan bagi penduduk pribumi di Minangkabau khususnya dan di Indonesia umumnya. Pertama, adalah sistem pendidikan surau bagi para penduduk muslim (di Jawa sistem pendidikan Pesantren), yang mengajarkan ilmu-ilmu agama semata. Kedua, adalah sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan mempersiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi pemerintahan, baik pada tingkat rendah maupun menengah. Dalam perkembangan selanjutnya, sekolah Belanda untuk penduduk pribumi (Holland Inlandsche Scholen atau HIS) yang mulai didirikan awal tahun 1914, sangat terbatas. Selain sekolah pemerintah, juga ada sekolah swasta pribumi yang berorientasi pendidikan Barat Keterbatasan ini dapat dilihat dari prosentase murid yang masuk kesekolah tersebut dari kalangan penduduk pribumi. Hanya anak-anak keluarga tertentu yang dapat mendaftarkan diri. Masa belajarnya hanya tujuh tahun dan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus ke negeri Belanda. Karenanya tidak semua orang mendapat kesempatan belajar pada sekolah Belanda ini. Apalagi bila dikaitkan dengan suatu “image” yang berkembang waktu itu bahwa mengikuti pendidikan Barat (Belanda) hukumnya adalah haram karena karakter dari sekolah tersebut sekuler dan tidak sesuai dengan tradisi Islam.
Jadi, karena adanya kebijaksanaan pemerintah yang membatasi kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi dan keyakinan sebagian besar kaum Muslim akan status kaum kolonial yang kafir, maka institusi pendidikan yang tersedia bagi mayoritas penduduk pribumi adalah surau dan pesantren. Belajar di surau atau di pesantren tidak hanya terjangkau dari segi ekonomis, bahkan juga bernilai ibadah. Dalam konteks yang lebih jauh, produk pendidikan surau atau pesantren dapat melanjutkan pendidikan ke Makkah dan Kairo. Suatu keinginan yang selalu dicita-citakan oleh setiap masyarakat muslim pada waktu itu.
Pendidikan Zainuddin Labay el-Yunusi, sama dengan yang dialami oleh kebanyakan orang Islam seusianya. Pendidikan awal yang dilaluinya tentu saja pendidikan infomal (di dalam keluarga) dan pendidikan agama yang diberikan ayahnya. Pada usia 8 (delapan) tahun, Zainuddin Labay, dimasukkan ayahnya ke sekolah pemerintah (HIS), namun ia hanya belajar sampai kelas IV. Kemudian ia keluar dari sekolah tersebut karena dalam banyak hal ia tidak setuju dengan pola pendidikan kolonial yang tidak akomodatif terhadap pendidikan agama Islam.
Setidak-tidaknya, ada dua hal yang menyebabkan Zainuddin Labay keluar dari sekolah pemerintah (HIS). Pertama, di sekolah pemerintah tidak dimasukan mata pelajaran agama karena pihak pemerintah (Belanda), sehingga sekolah terkesan sekuler dan hanya untuk kepentingan duniawi semata. Kedua, bahwa tujuan dari pemerintah Belanda mendirikan sekolah bukan untuk kepentingan rakyat, akan tetapi hanya untuk kepentingan kolonial Belanda itu sendiri, yakni untuk mempersiapkan calon-calon tenaga pegawai terdidik yang akan ditempatkan dalam birokrasi lokal termasuk penyediaan personil dalam urusan tanam paksa kopi. Pengetahuan yang diberikan di sekolah-sekolah pemerintah itu nantinya juga merupakan bagian dari upaya membentuk warga negara yang “baik” dan secar berangsur-angsur mereka juga akan diperbelandakan, dalam arti mencontoh gaya hidup Eropa. Sehingga hasilnya terkesan lebih menguntungkan pihak penjajah. Untuk itu, Zainuddin Labay, memutuskan untuk tidak lagi belajar di sekolah pemerintah tersebut. Setelah keluar dari sekolah pemerintah,
Zainuddin kembali belajar dengan ayahnya memperdalam ilmu-ilmu agama. Waktu-waktu senggang dipergunakan untuk belajar mandiri dan membaca. Masa 2 (dua) tahun belajar dengan ayah tercinta dirasakannya tidak begitu lama, sebab ayahnya dipanggil Yang Mahakuasa. Akibatnya pendidikan Zainuddin terbengkalai di saat ia sedang sangat memerlukan pendidikan untuk masa depannya.
Keterangan lain mengatakan bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, Zainuddin Labay sempat menjadi “preman” (istilah yang diberikan kepada anak-anak yang tidak menentu pekerjaannya). Kerjanya sehari-hari adalah bermain layang-layang, meniup serunai yang terbuat dari batang padi, bersalung, bermain rabab, dan lain-lain sebagainya. Suatu pekerjaan yang sering dilakukan anak-anak yang tidak sekolah. Bila perut terasa lapar, segera pulang untuk makan dan kemudian pergi lagi. Kondisi seperti ini berlangsung selama dua tahun. Berkaitan dengan aktivitas Zainuddin Labay belajar silat sejauh ini penulis belum mendapatkan data lengkap. Namun jika dilihat dari tradisi yang berkembang di masyarakat pada masa awal abad ke XX, dapat dikatakan bahwa Zainuddin Labay pernah belajar silat selama hidup preman.
Aktivitas keseharian yang dilakukan Zainuddin sebagaimana diterangkan di atas dapat dimaklumi, karena ia telah kehilangan seseorang yang selama ini sangat dicintainya dan sangat berperan membina kepribadian dan memasukkan nilai-nilai pendidikan agama kepadanya. Dalam tataran yang lebih ekstrim, sebagai anak tertua dari lima bersaudara, ia mengalami trauma dengan perginya orang yang sangat dicintainya itu. Keinginannya untuk belajar agama muncul kembali setelah ia mendengar ada seorang ulama yang sangat dalam ilmunya di Sungai Batang, suatu daerah yang terletak di pinggiran Danau Maninjau. Ulama itu adalah H. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul), yang baru saja kembali dari Makkah. Tetapi karena daerah “danau” (istilah yang masyhur waktu itu) terlalu jauh dan alat transportasi ke sana sangat sulit, ibu Zainuddin Labay, Ummi Rafi’ah, keberatan melepas anaknya “merantau” (belajar) ke daerah danau tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa alat transportasi yang digunakan pada masa itu hanya bendi. Untuk sampai ke Sungai Batang itu, orang harus ke Bukittinggi terlebih dahulu. Dari sana barulah orang naik bendi ke Sungai Batang setelah melewati “kelok 44” Maninjau. Umumnya orang berangkat ke sana pagi dan sore harinya baru sampai di Sungai Batang. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hubungan transportasi ke daerah tersebut ditambah lagi dengan kondisi jalan yang sangat rawan dan terjal, pada hal jarak antara Bukittinggi dan Maninjau tidak begitu jauh. Setelah gagal meneruskan pelajaran agama ke “danau”, tahun 1910, Zainuddin Labay, menyampaikan keinginannya untuk pergi belajar kepada salah seorang ulama moderen di Padang, yang bernama Dr. H. Abdullah Ahmad (1878-1933). Keinginan Zainuddin ini diperkenankan oleh ibunya dan ia diberi biaya sebanyak 20 gulden serta bekal hidup lainnya untuk belajar ke Padang. Tapi hanya delapan hari ia belajar dengan Abdullah Ahmad di Padang, kemudian Zainuddin kembali ke Padang Panjang. Biaya 20 gulden yang diberi oleh ibunya untuk biaya dan bekal hidupnya selama menuntut ilmu dibelikannya kepada buku-buku, majalah dan koran-koran berbahasa asing. Dari prilakunya yang seperti ini, jelas menunjukkan bahwa Zainuddin adalah seorang yang anak yang memiliki kepribadian fenomenal yang sangat jarang dilakukan oleh anak-anak segenerasi dengannya. unik dan sulit ditebak kemauannya. Agar pendidikan Zainuddin tidak terbengkalai, ibunya menyarankan agar ia pergi belajar kepada Syeikh Abbas Abdullah (1883-1957, di Padang Japang Payakumbuh, seorang ulama yang sealiran dengan Syeikh Abdul Karim Amrullah dan Dr. H. Abdullah Ahmad. Anjuran ibunya diterima dan kemudian, ia pergi ke Padang Japang Payakumbuh dan belajar di surau Syeikh Abbas Abdullah, dari tahun 1911-1913.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua Zainuddin Labay lebih cenderung menyuruh anaknya belajar ke Padang Japang, Payakumbuh. Pertama, Syeikh Abbas Abdullah adalah seorang ulama moderen yang sealiran dengan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Abdullah Ahmad. Kedua, transportasi ke sana lebih lancar ketimbang ke Sungai Batang, Maninjau. Transportasi yang digunakan orang ke Payakumbuh masa itu adalah kereta api, sama dengan alat transportasi yang digunakan ke Padang. Sedangkan ke Sungai batang hanya kendaraan bendi semata.
Selama dua tahun belajar dengan Syeikh Abbas Abdullah, Zainuddin Labay termasuk murid yang “nakal” dan “keras hati”. Suatu ketika di mana semua murid harus mengaji, Zainuddin dengan beberapa orang temannya yang lain pergi bermain sepak bola. Sang guru bertanya mengapa Zainuddin tidak hadir ? salah seorang temannya mengatakan bahwa ia pergi bermain bola. Sang guru sangat marah, sehingga perlengkapan Zainuddin, seperti kasur, pakaian dan barang-barang lainnya dilempar ke dalam kolam. Mendapat kabar bahwa gurunya marah, ia segera kembali ke surau dan mengumpulkan barang-barangnya tersebut untuk kemudian terus pulang ke Padang Panjang. Seminggu setelah itu, Zainuddin kembali lagi ke Padang Japang dan sang guru pun telah memaafkan kesalahannya.
Selama dua tahun Zainuddin belajar di Padang Japang, Syeikh Abbas Abdullah melihat bakat dan kecerdasan yang dimiliki Zainuddin melebihi kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawanya yang lain. Untuk itu ia diangkat menjadi guru bantu.
Bahkan tidak jarang terjadi perdebatan sengit antara ia dengan gurunya tersebut dalam hal keilmuan. Karena hal-hal yang belum ia pelajari telah diajarkannya kepada murid-murid yang lain. Sekalipun demikian, Zainuddin tidak lama melanjutkan pelajarannya, karena tahun 1914, ia harus pulang ke Padang Panjang dan tidak kembali lagi ke Padang Japang.
Di Padang Panjang, Zainuddin belajar dengan guru yang sudah lama ditunggu-tunggunya, yakni Syeikh Abdulkarim Amrullah, yang pada saat itu telah menetap di Padang Panjang dan mengajar di Surau Jembatan Besi. Di surau Jembatan Besi, menurut Hamka, Zainuddin Labay tidak selalu duduk berhalaqah menghadap mengaji dengan gurunya “Inyiak Rasul”, karena otaknya cerdas dan mampu belajar sendiri. Jika terdapat kesulitan dalam memahami pelajaran, barulah ia bertanya kepada gurunya. Kemampuan intelektual yang dimiliki Zainuddin Labay, menyebabkan “Inyiak Rasul” berani memberikan kepercayaan kepadanya menjadi guru bantu di Surau Jembatan Besi.
Latar belakang pendidikan yang dilalui Zainuddin Labay sebagaimana dipaparkan di atas, memang relatif pendek dan tidak sistematis. Pola pendidikannya yang tidak sistematis dan tidak teratur tersebut menurut hemat penulis, setidak-tidaknya dipengaruhi oleh sikap dan kepribadiannya yang unik namun berpotensi untuk maju.
Dikatakan unik, karena dalam proses pendidikan yang dilaluinya, tidak dijalaninya menurut semestinya. Itu terlihat ketika ia belajar di sekolah gubernemen (pemerintah Belanda) hanya sampai kelas IV. Bahkan ketika ia belajar dengan Syeikh Abbas Abdullah (Padang Japang), sempat terjadi kericuhan kecil antara ia dengan gurunya karena tidak mengindahkan peraturan dan disiplin belajar. Belajar dengan Syeikh Abdullah Ahmad di Padang, hanya menghabiskan waktu seminggu kemudian kembali lagi ke Padang Panjang.
Dilihat dari faktor umur, pola pendidikan seperti itu memang tidak wajar dilakukan oleh seseorang yang masih membutuhkan pendidikan formal yang teratur dan sistematis. Apalagi pada usia muda di mana seseorang harus menimba ilmu dari bangku sekolah secara teratur.
Ia juga memiliki potensi untuk maju, sebab lompatan-lompatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Zainuddin terkesan agak aneh dan tidak biasa dilakukan orang pada waktu itu. Ketika tidak lagi belajar di sekolah gubernemen, ia lebih memilih belajar sendiri, di samping belajar agama dengan ayahnya. Ketika belajar di Padang Japang, walaupun terjadi kericuhan kecil dengan gurunya, namun karena kecerdasan intelektual yang dimilikinya, Zainuddin diberi kepercayaan sebagai guru bantu. Biaya sekolah yang diberikan ibunya ketika belajar dengan Abdullah Ahmad, akhirnya dibelikannya kepada buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar berbahasa asing. Dengan modal itu ia bisa belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Melihat kemampuan intelektualnya yang tinggi, akhirnya Syeikh Abdulkarim Amrullah, yang saat itu mengajar di surau Jembatan Besi mengangkat Zainuddin sebagai guru bantu.
Dengan latar belakang pendidikan seperti itu, didukung oleh ketajaman intelektual, keuletan serta wawasanya yang jauh ke depan, Zainuddin dapat merombak kekolotan sistem pendidikan yang sedang berkembang. Di atas reruntuhan dan puing-puing kekolotan itu dibangunnya gagasan-gagasan pembaharuan yang kelak membawa perubahan besar khususnya di bidang pendidikan Islam. Eksistensi tiga orang guru yang berhaluan moderen, yakni Haji Rasul, Abbas Abdullah dan Abdullah Ahmad, serta peranan mereka dalam riwayat pendidikan Zainuddin Labay, tampaknya, sangat berpengaruh besar. Sebab merekalah yang paling bertanggung jawab mengajarkan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran moderen di lembaga pendidikan di mana mereka mengajar. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang pernah mereka timba di Timur Tengah, disebarluaskan kembali di tanah air
Zainuddin Labay, termasuk orang yang menerima pemikiran-pemikiran moderen dari ketiga tokoh ulama pembaharu tersebut. Karena Zainuddin pernah belajar di surau mereka bahkan sempat menjadi guru bantu. Zainuddin Labay tidak pernah belajar kepada ulama-ulama tradisional kecuali kepada ayahnya. Itupun hanya sebatas pengetahuan tentang dasar-dasar agama dan waktunya pun tidak terlalu lama. Dengan demikian pengaruh pemikiran moderen lebih banyak ia terima ketimbang pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercorak tradisional.
C. Kondisi Sosial Masyarakat Padang Panjang Awal Abad XX
Padang Panjang adalah kota tempat lahirnya tokoh-tokoh pembaharuan Islam khususnya di Minangkabau. Kota ini bukan saja berfungsi sebagai pelopor pembaharuan, akan tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam. Berkat kepeloporannya dalam bidang pendidikan Islam ini, Padang Panjang disebut sebagai kota serambi Mekkah. Munculnya daerah ini sebagai pelopor pembaharuan dan pusat pendidikan Islam di Minangkabau bukanlah secara kebetulan. Akan tetapi dilatarbelakangi oleh “seting” sosial kemasyarakatan yang berkembang waktu itu.
Kondisi sosial masyarakat yang berkembang di Padang Panjang khususnya tidak jauh berbeda dengan “setting sosial” masyarakat Minangkabau secara umum. Lahirnya gerakan Paderi pada awal abad XIX M, merupakan jawaban dari setting sosial masyarakat Minangkabau yang telah berkembang secara turun temurun semenjak masuk dan berkembangnya Islam di daerah ini. Apalagi dalam perkembangannya, ajaran Islam telah dicampur baurkan dengan tradisi-tradisi adat yang sudah berkembang semenjak lama.
Untuk melihat secara jelas “setting sosial” dan kehidupan masyarakat Minangkabau pada kurun waktu abad XIX dan awal abad XX, perlu diperhatikan suasana sosial religius kota itu di samping kondisi masyarakat dibawah tekanan penjajah Belanda.
1. Tatanan Sosial Keagamaan
Sebelum Islam datang, masyarakat Minangkabau secara umum merupakan komunitas masyarakat yang sangat teguh memelihara nilai-nilai adat. Nilai-nilai tersebut sangat mewarnai berbagai bentuk interaksi sosial dan pandangan hidup mereka. Masuknya pengaruh Hindu dan Buddha telah memberikan warna tersendiri terhadap prilaku hidup keseharian masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan berdirinya kerajaan Pagaruyung di bawah pemerintahan Aditiawarman, secara nyata mengembangkan corak kebudayaan Hindu. Adat-istiadat dan kehidupan sosial budaya masyarakat Minangkabau berakulturasi secara evolusi dengan kebudayaan Hindu dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sebelumnya (animisme dan dinamisme).
Ketika Islam masuk dan berkembang di Minangkabau, masyarakat dapat menerima dengan sangat terbuka. Namun demikian beberapa praktek adat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam masih tetap dilaksanakan dalam berbagai dimensi kehidupan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, menurut Azyumardi Azra, banyak ajaran agama yang dicampuradukkan dengan praktek-praktek adat dan kepercayaan tradisional yang masih langgeng tersebut.
Di antara praktek-praktek adat yang masih berkembang adalah kebiasaan ngobrol-ngobrol di kedai kopi (Minang: lapau). Anak-anak muda masih suka menyabung ayam, minum arak, menghisap candu dan tembakau, berjudi, dan lain-lain. Sedangkan kepercayaan tradisional yang masih eksis di antaranya kepercayaan terhadap hantu dan arwah nenek moyang, melakukan kenduri arwah pada bilangan malam tertentu, mandi safar (diyakini bisa membuang sial). Praktek-prektek kepercayaan seperti itu, menurut Hamka, hakikatnya merupakan warisan dari faham animisme dan dinamisme. Kepercayaan seperti itu sangat erat hubungannya dengan ajaran agama Hindu dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Praktek adat istiadat masyarakat seperti itu, ternyata membawa pengaruh besar terhadap aqidah umat Islam. Apalagi bila dikaitkan dengan tradisi yang berkembang di kalangan sebagian umat Islam, yakni praktek-praktek tasawuf (tarekat) yang sudah menyimpang dari ajaran Islam yang murni seperti kepercayaan yang terlalu berlebihan kepada guru; mencium kaki guru, memakan makanan sisa guru, memijat guru, dan lain-lain semakin menambah suramnya dinamika berfikir umat.
Dalam konteks ini, agaknya benar apa yang dituturkan Hamka, bahwa di seluruh Minangkabau sebelum terjadinya gerakan pembaharuan, umat Islam mengalami kemunduran. Tidak dapat dibedakan lagi antara ajaran agama, perbuatan bid’ah, syirik dan agama bercampur aduk saja dengan tradisi-tradisi yang berkembang sebelum Islam datang. Ilmu sihir berkembang pesat, suka membuat azimat serta adanya kepercayaan terhadap kekeramatan kuburan. Yang lebih menarik lagi, menurut Edwar (ed.), paham sufi dan tarikat serta suluk dianggap suatu keharusan. Ajaran wahdat al-wujud berkembang dan suasana keagamaan hanya tampak pada upacara-upacara kematian, kenduri peringatan maulid, isra’ mi’raj, dan lain-lain.
Pengamalan ajaran agama melalui berbagai macam ibadah ritual masih dipengaruhi oleh paham animisme dan dinamisme yang bercampur dengan ajaran agama Hindu dan Buddha yang telah berakar dalam masyarakat Minangkabau. Identitas keagamaan umat seperti itu, menurut Hamka, barulah sebatas keislaman saja tapi belum mengamalkan Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Etika kehidupan sosial kemasyarakatan cenderung diabaikan oleh masyarakat.
Usaha gerakan Paderi dalam membina kehidupan masyarakat yang Islami ternyata sia-sia belaka. Apalagi setelah kaum Paderi menderita kalah dalam perang melawan kolonial Belanda, dinamika kehidupan masyarakat semakin suram dan ruwet. Perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama seperti judi, minum tuak, aksi ilmu sihir, pelecehan seksual, persengketaan mengenai harta pusaka hingga terjadi pembunuhan semakin merajalela.
Tidak ada ulama yang berani turun tangan memberantas dan memperbaiki semua itu, karena mereka tidak berwibawa lagi dan bahkan mungkin mereka sebahagian terlibat dalam kasus-kasus serupa.
2. Intervensi Kolonial Belanda
Campur tangan kolonial Belanda dalam berbagai segi kehidupan masyarakat terutama segi ekonomi, telah menambah suram dan ruwetnya dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau. Belanda berusaha sekuat tenaga mencari berbagai peluang melalui “politik etis”-nya.
Di saat terjadi konflik antara ulama dengan kaum adat, kolonial Belanda berusaha mendekati kaum adat. Dengan cara demikian mereka bisa lebih leluasa mematikan gerak langkah kaum agama dalam dinamika kehidupan masyarakat. Siasat seperti itu ternyata menjadikan kaum agama (ulama) lebih terpojok, karena harus berhadapan dengan pemerintah kolonial dan kaum adat.
Secara historis, pemerintah kolonial Belanda, memang sangat menghargai adat Minangkabau dan pemuka-pemukanya, karena golongan ini banyak membantu kelancaran program-program pemerintah kolonial di daerah ini. Mereka bisa jadi “patner” yang baik dan kawan nomor satu dalam menghadapi kaum oposisi dari pihak Islam. Kedekatan kaum adat dengan Belanda dapat dilihat ketika gubernur Jenderal Limburg Stirum, berkunjung ke Bukittinggi, tokoh-tokh adat menyambut kedatangannya dengan segala kebesaran adat.
Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa adanya sikap Belanda memihak kaum adat dan menentang kaum ulama, terutama yang mengadakan pembaharuan, merupakan suatu realita bahwa mereka di samping menjajah, juga melakukan penyebaran (missionaris) agama Kristen. Untuk memantapkan gerakan missionaris ini, mereka mendirikan sekolah-sekolah “zending” yang mengajarkan injil dan sedikit berhitung tingkat dasar.
Untuk umat Islam dibuat suatu peraturan yang sangat membatasi kebebasan berpendidikan. Peraturan itu adalah “ordonantie goeroe”, yakni suatu peratuaran yang menyatakan bahwa setiap guru yang akan mengajarkan mata pelajaran agama Islam harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda karena dikhawatirkan mereka bisa menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan kolonial Belanda. Akibatnya pendidikan Islam terkebelakang dan merosot, yang menonjol hanyalah lembaga pendidikan kolonial. Aktivitas pendidikan Islam hanya berlangsung di surau-surau tradisional. Umat Islam belum mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pendidikan Islam karena takut dicurigai sebagai penyaing pendidikan Belanda.
Keadaan umat Islam sebagaimana yang digambarkan di atas, menurut hemat penulis, sebetulnya bukan saja terjadi di Minangkabau. Secara historis, berbagai wilayah di nusantara, hingga akhir abad XIX dan awal abad XX M, umumnya diliputi oleh suasana pengamalan ajaran agama yang bercorak tarikat (tasawuf). Tradisi-tradisi lama ternyata memang tidak mudah untuk melenyapkannya, sebab harus berhadapan dengan institusi-institusi yang sangat kuat mempertahankannya. Diperlukan waktu bahkan pergantian generasi untuk dapat merubah paham-paham lama dan menyesuaikannya dengan ajaran agama Islam sebagaimana yang dikehendaki al-Qur’an dan Sunnah.
Perubahan-perubahan besar dalam bidang pendidikan belum dilakukan orang. Aktivitas pendidikan Islam baru di lembaga pendidikan surau di mana pendidikannya lebih banyak bersifat individual. Orang yang ingin belajar agama atau mengaji al-Qur’an harus mendatangi guru dan belajar di surau. Fokus pendidikan menurut Steenbrink, adalah mengaji al-Qur’an, sedangkan pelajaran tafsir diberikan bila seseorang telah menamatkan al-Qur’an lebih dari satu kali.
Campur tangan pihak kolonial Belanda dalam berbagai latar belakang kehidupan masyarakat di Minangkabau ternyata sangat menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Kolonial Belanda tidak hanya menguasai sumber-sumber perekonomian rakyat akan tetapi juga membatasi kesempatan belajar bagi warga pribumi.
Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sekolah pemerintah Belanda dan itupun untuk kepentingan pihak kolonial. Pendidikan agama dianaktirikan bahkan ditiadakan dan diganti dengan pendidikan zending Kristen. Kondisi seperti ini menambah parahnya kehidupan rakyat dan dikalangan ulama tradisonal timbul semacam “image”, bahwa meniru segala sesuatu yang berkaitan dengan kolonial adalah haram hukumnya, karena mereka adalah orang yang anti terhadap Islam.
Padang Panjang sebagai salah satu bagian yang integral dari wilayah kebudayaan Minangkabau, mengalami hal yang sama sebagaimana daerah-daerah lainnya. Kondisi sosial masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kodisi yang terjadi di daerah lain. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya praktek-praktek keagamaan yang diwarnai oleh paham tarikat yang dianggap sudah terlalu jauh menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya.
Silsilah keturunan Zainuddin Labay sendiri merupakan realita yang tidak dapat dibantah. Ayah dan kakeknya adalah tokoh tarikat terkemuka di Minangkabau. Bahkan ketika ayahnya meninggal dunia, umat Islam ingin menjadikan kuburan ayahnya sebagai tempat keramat, namun tidak diperkenankan oleh Zainuddin Labay.
“Image” masyarakat yang juga berkembang waktu itu di Padang Panjang adalah menganggap meniru pola dan cara hidup kaum kolonial Belanda adalah haram, sebab kolonial Belanda adalah kafir dan mereka sangat anti terhadap agama Islam. Zainuddin Labay sebagai orang yang berfikiran maju, tidak mau terjebak dengan pemahaman masyarakat seperti itu. Secara radikal, ia mencoba mendobrak pola pikir masyarakat yang sangat tradisional itu.
Dalam berbagai kesempatan dan cara berpenampilan (berpakaian), Zainuddin Labay selalu berpenampilan lain dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat waktu itu. Bila hendak ke surau, baik guru maupun murid pada umumnya memakai sarung dan peci. Begitulah gambaran umum pola berpakaian kaum agamawan (para ulama dan santri) masa itu.
Suatu keanehan, bila seseorang pergi mengaji atau belajar di surau tidak memakai sarung dan peci. Bahkan dalam pengertian sempit mereka yang berpakaian tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu, dapat dicap sebagai kaki tangan kolonial.
Zainuddin Labay, dengan jiwa dan semangat pembaharuannya yang berkobar-kobar berusaha sedemikian rupa menampilkan pola baru dari segi berpakaian. Bila hendak mengajar di surau atau di sekolahnya (Diniyah School atau Thawalib), ia hanya menggunakan kemeja dan pakai celana panjang tidak pakai peci namun rambut disisir rapi. Tingkah lakunya yang lain dari kebiasaan masa itu ternyata mengundang sikap anti pati masyarakat. Ejekan dan cemoohan dilemparkan orang kepadanya. Dalam tataran yang lebih ekstrim ia dianggap sebagai ulama perusak agama, dan telah keluar dari Islam karena suka meniru pola hidup orang Belanda yang kafir. Namun semua itu diterimanya dengan hati yang tulus dan lapang dada.
Dalam pikirannya tertanam suatu cita-cita yang mulia dan agung, yakni berusaha semaksimal mungkin mengangkat citra golongan agama dan para ulama di mata masyarakat yang telah terlanjur berkembang sebagai kaum kolot dan anti terhadap kemajuan. Melalui usaha itu, Zainuddin Labay ingin memperlihatkan dan membuktikan kepada khalayak umum, bahwa golongan agama dan para ulama adalah juga manusia yang menginginkan kemajuan. Hanya kolonial Belanda-lah yang membuat kondisi sosial mereka seperti itu.
Belanda tidak hanya memporakporandakan sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dijajahnya, akan tetapi juga membatasi wawasan dan cara berfikir mereka terhadap kemajuan. Akibatnya masyarakat, terutama golongan agama dan para ulama terkebelakang dalam bidang pendidikan serta kolot cara berfikir. Wawasan berfikir mereka menjadi picik, hanya sebatas urusan-urusan agama dan keakhiratan tanpa mau peduli terhadap perkembangan dan kemajuan zaman. Pada hal kalau ditinjau lebih jauh lagi, Islam mengajarkan agar umatnya juga memperhatikan dimensi kehidupan duniawi di samping urusan-keakhiratan. Terabaikan salah satu aspek itu dinilai sebagai orang yang tidak adil dalam menjalankan kehidupannya dan terhadap dirinya sendiri. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama. Inilah yang ditekankan Zainuddin Labay dalam membina dirinya sendiri dan tentu juga agar menjadi pola hidup Islami yang menekankan keseimbangan.

























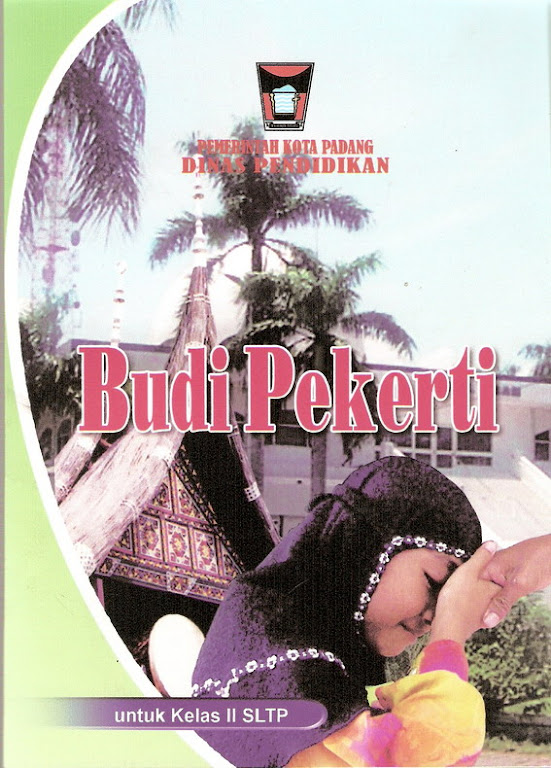





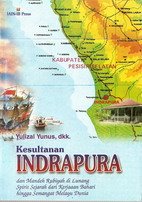




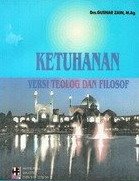
















Assalamualaikum...Bisa sya mendapatkan keterangan sebuah pandangan islam menurut zainuddin labay
BalasHapusBisa ngak
BalasHapusterima kasih atas blognya,sangat berguna sekali bagi saya
BalasHapus