oleh : Drs. Maksum, M.Ag I’rab sebagai bentuk fenomena akhir kata dalam struktur kalimat arab mulai dibicarakan setelah dirasakan berbagai kelemahan dalam praktek berbahasa serta kesulitan menangkap makna kata, kemudian term tersebut terus berkembang. Di tengah pergumulan menuju kematangan keilmuan i’rab (nahwu), muncul kontrovesri pemikiran mengenai urgensinya dalam menetukan makna kata, yang terpolarisasi ke dalam dua kelompok, kelompok yang tidak mengakui dan kelompok yang mengakuinya. Masing-masing mengemukakan alasan logika, dan fakta kebahasaan. Dari penulusuran dan analsis yang dilakukan, pendapat yang mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna kata kelihatannya dipandang lebih kuat.
I’rab sebagai bentuk fenomena akhir kata dalam struktur kalimat arab mulai dibicarakan setelah dirasakan berbagai kelemahan dalam praktek berbahasa serta kesulitan menangkap makna kata, kemudian term tersebut terus berkembang. Di tengah pergumulan menuju kematangan keilmuan i’rab (nahwu), muncul kontrovesri pemikiran mengenai urgensinya dalam menetukan makna kata, yang terpolarisasi ke dalam dua kelompok, kelompok yang tidak mengakui dan kelompok yang mengakuinya. Masing-masing mengemukakan alasan logika, dan fakta kebahasaan. Dari penulusuran dan analsis yang dilakukan, pendapat yang mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna kata kelihatannya dipandang lebih kuat.
Pembicaraan i’rab sebagai bentuk fenomena akhir kata di dalam struktur kalimat arab baru muncul di kalangan bangsa arab belakangan sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua hijrah, yaitu, setelah mereka merasakan adanya berbagai kelemahan dalam praktek berbahasa serta sulitnya menangkap makna kata dalam struktur kalimat. Sedangkan sebelum itu bahasa arab yang memiliki berbagai ragam dialek ini tidak membicarakan soal itu. Mereka tidak memperhatikan i’rab, malainkan, cenderong mengabaikannya, kecuali pada karya-karya sastra seperti karya syi’ir (puisi).
Pembicaraan mengenai i’rab muncul pertama kali dengan di latar-belakangi oleh peristiwa, dimana seorang anak berkata kepada ayah, yang kemudian oleh ayah disalah-pahami. Diceritakan, bahwa suatu kali anak perempuan Abu Aswad al-Dualiy (605 – 688 M) berkata kepadanya dengan mengungkapkan kata-kata: " ما أجملُ السماء ", atau di dalam riwayat yang lain ditemukan: " ما أشدُّ الحر ". Kedua ungkapan ini menggunakan kata tanya. Ketika Abu Aswad menjawabnya sesuai dengan konteks pertanyaan, lantas, si anak mengatakan: Saya bukan bermaksud untuk bertanya, melainkan untuk menyatakan kekaguman (ta’ajjub). Semenjak itu, Abu Aswad menulis sebuah kitab yang membahas tentang persoalan ta’ajjub (Raidh, 1988:94) . Penulisan kitab ini kemudian diapandang sebagai awal dari penyusunan ilmu nahwu (i’rab).
Setelah itu, berkembanglah pembahasan i’rab dengan berbagai aspek-aspek kajiannya di kalangan linguis arab, yang pada akhirnya membentuk sebuah keilmuan yang disebut sekarang dengan ilmu i’rab atau ilmu nahwu (sintaksis).
Sejalan dengan perkembangan pembahasan i’rab dengan berbagai aspek kajianya menuju terbentuknya kematangan keilmuan nahwu ini muncul pula pertentangan pemikiran di kalangan linguis arab mengenai kedudukan i’rab dalam menentukan makna. Kontroversi pemikiran di sekitar persoalan, apakah i’rab berperan dalam menentukan makna atau tidak ini terus berlanjut dan berkembang sehingga melahirkan polarisasi pemikiran di dalam sejarah linguistik arab.
Bertolak dari permasalahan diatas, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana kotroversi pemikiran di kalangan linguis arab mengenai urgensi i’rab dalam menentukan makna, apa pendapat mereka dan apa pula yang melandasi pemikiran tersebut. Inilah yang akan dikemukakan oleh tulisan ini dalam bentuk kajian analitis.
PENGERTIAN I’RAB.
Kata i’rab adalah bentuk mashdar dari أعرب – يعرب – إعرابا, yang secara etimologis berarti: أوضح – أبان – حسّن و أفصح (memperindah /membaguskan dan jelas, menyatakan /menerangkan, menjelaskan). Misalnya, ungkapan: أعرب كلامَه berarti حسّنه وأفصح ولم يلحن (Ia memperindah bahasanya sehingga menjadi jelas tidak ada kelemahan), dan ungkapan: أعرب الشيئَ, berarti أبانه (ia menyatakan /menjelaskan sesuatu). Demikian juga ungkapan: أعرب الكلمةَ berarti بيّن وجهها من الإعراب وأوضحها, yakni, menyatakan segi i’rab kata serta menjelaskannya (Lowes Ma’luf, 1986:496). Pengertian etimologis ini berkaitan erat dengan pengertian terminologinya.
Secara terminologi, i’rab didefenisikan oleh para linguis arab dengan beberapa definisi. Antara lain seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Jinni, i’rab yaitu: الإبانة عن المعاني بالألفاظ, yakni, menjelaskan makna melalui kata (Ya’qub, 1982:127). Selain itu terdapat defenisi yang menyatakan bahwa i’rab adalah: “أثر يجلبه العامل”, yakni, pengaruh /efek yang ditimbulkan oleh amil (Ya’qub, 1982:128)
Kedua defenisi ini sebetulnya belum menggambar pengertian i’rab secara utuh. Keduanya kelihatan saling melengkapi. Bila defenisi pertama, lebih menekankan pengertian kepada proses atau fungsi i’rab itu dalam menjelaskan makna melalui pemahaman perubahan akhir kata, sedangkan yang kedua cenderong menekankan pengertiannya kepada bentuk perubahan di akhir kata yang disebabkan oleh amil yang memsukinya.
Defenisi lain, dikemukakan oleh Magalisah. Menurutnya i’rab: تغيير حركة آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر، وفق تغيير موقعها من الإعراب, yakni, perubahan harkat akhir kata dari rafa’ menjadi nashab atau jar sesuai dengan kedudukan i’rab kata tersebut (Maghalisah, 1991:27). Definisi ini kurang lebih sama dengan yang dikemukakan oleh Abbas Hassan. Kecuali itu, Abbas menyebutkan di dalam defenisinya bentuk perubahan itu secara umum, tidak fokus pada bentuk harkat. Hal ini berarti bahwa perubahan itu juga mencakup bentuk huruf. Selain itu, Abbas menyatakan pula bahwa perubahan dimaksud disebabkan oleh amil, bukan kedudukan kata sebagaimana Husaini (Hassan, 1979:) . Meskipun secara redaksional berbeda dalam menyebutkan factor penyebab perubahan akhir kata, namun, substansi keduanya adalah sama. Kedudukan kata sangat terkait erat denga amil. Kedudukan kata sesungguhnya ditentukan oleh amil, dan kedudukannya sekaligus menggambarkan amil yang ada sebelumnya.
Dari beberapa defenisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa i’rab merupakan perubahan di akhir kata yang disebabkan oleh amil yang mendahuluinya, atau disebabkan oleh fungsi kata tersebut di dalam struktur kalimat arab. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam bentuk harkat (baris), maupun, dalam bentuk huruf akhir kata sebagai pengganti harkat (tanda asli). Kemudian melalui perubahan tanda ini dapat pula dipahami makna kata dalam struktur kalimat.
Sebagai contoh, dapat dilihat kata القرآن yang terdapat pada ungkapan: قرأ الطالب القرآنَ dan القرآنُ كتاب مجيد . Pada ungkapan pertama, kata القرآن dibaca dengan harkat fathah, menunjukan kedudukannya di dalam struktur kalimat sebagai objek (maf’ul bih). Sedangkan kata القرآن pada ungkapan yang kedua dibaca dengan dhommah, sebagai mubtada’, yang dalam hal ini merupakan subjek.
Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan unsur-unsur i’rab sebagai berikut:
a. Amil, yang menyebabkan perubahan tanda di akhir kata
b. Ma’mul, kata yang dipengaruhi oleh amil atau mendapatkan efek dari amil.
c. Mauqi’u al-i’rab, kedudukan kata yang dipengaruhi oleh amil (sebagai fa’il, naib fa’il, mafulbih dan sebagainya)
d. Alamat al-i’rab, tanda yang merupakan bekas dari pengaruh amil.
PANDANGAN LINGUIS TENTANG URGENSI I’RAB
DALAM MENENTUKAN MAKNA KATA
Para linguis arab berbeda pendapat mengenai urgensi i’rab dalam menentukan makna kata. Perbedaan tersebut pada dasarnya terpolarisasi kedalam kedua kelompok. Kelompok pertama, adalah mereka yang tidak mengakui urgensi i’rab, sedangkan kelompok kedua, yang mengakuinya.
Kelompok pertama, yang tidak mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna mengatakan, i’rab sama sekali tidak memberikan implikasi terhadap makna, malainkan, hanya sekedar penghias (asesoris) bahasa untuk melahirkan irama atau musik di dalam berbahasa (Ya’qub, 1982:132). Pendapat ini di dukung antara lain oleh al-Khalil bin Ahmad al-Farahidiy dan Muhammad bin al-Mustanir yang lebih dikenal dengan nama Quthrub serta sejumlah pengikutnya pada abad modern ini.
Sedangkan kelompok kedua, yang mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna mengatakan bahwa baris (harkat) akhir kata memberikan implikasi terhadap makna. Menurut mereka, orang arab tidak mungkin memberikan perhatian khusus terhadap i’rab kalau ia hanya sekedar asesoris bahasa, tidak memberikan implikasi terhadap makna (Ya’qub, 1982:132). Pendapat ini didukung oleh sejumlah linguis arab, diantaranya adalah al-Zajjajiy yang pernah membantah pemikiran Quthrub, Ibnu Faris, Ibrahim al-Faiy dan sejumlah linguis lainnya.
Selanjutnya kelompok pertama, yang tidak mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna mengajukan sejumlah alasan dan fakta kebahasaan untuk memperkuat pendapat mereka, antara lain (Ya’qub, 1982:133-135):
1. Di dalam bahasa terdapat kata-kata yang fungsinya sama, yaitu, sebagai subjek (musnad ilaihi), akan tetapi, baris (harkat)-nya berbeda. Seperti kata الرجل pada ungkapan di bawah ini:
(Laki-laki itu berada di rumah) الرجلُ في البيت
(Laki-laki itu benar-benar berada di rumah) إنّ الرجلَ في البيت
(Laki-laki itu memiliki seorang saudara di rumah) للرجلِ أخ في البيت
Kata الرجل di dalam ungkapan di atas dibaca dengan harkat yang berbeda, namun, kesemuanya memiliki fungsi yang sama sebagai musnad ilaihi.
2. Terdapat kata-kata yang harkatnya sama, akan tetapi, fungsi gramatikanya berbeda, seperti hal, tamyiz, dan al-maf’ulat al-khamsah. Meskipun berbeda fungsi gramatikalnya, namun, kesemuanya dibaca dengan cara manshub.
3. Di dalam bahasa arab terdapat sejumlah kata yang berbeda maknanya, namun, i’rab-nya sama. Seperti ungkapan:
(Sesungguhnya Zaid adalah saudara-Mu) إنّ زيدًا أخوك
(Moga-moga Zaid adalah saudara-Mu) لعلّ زيدًا أخوك
(Seolah-olah Zaid adalah saudara-Mu) كأنّ زيدًا أخوك
Kata زيدًا di dalam ungkapan di atas dibaca dengan harkat yang sama. Padahal ungkapan itu mengandung makna yang berbeda. Ungkapan yang pertama mengandung makna penegasan (ta’kid), kedua, mengandung harapan (tarajjiy) dan yang ketiga, mengandung perumpamaan (tasybih).
4. Sebaliknya, terdapat pula sejumlah kata yang berbeda i’rab-nya, namun, maknanya sama. Seperti ungkapan:
(Zaid tidak pengecut dan tidak pula kikir) ليس زيد بجبان ولا بخيلٍ أو ولا بخيلاً
(Zaid tidak berdiri) ما زيدٌ قائمًا أو قائمٌ
(Saya memiliki satu liter madu) عندي رطل عسلٍ أو عسلٌ أو عسلاً
Kata بخيل , قائم dan عسل meskipun dibaca dengan harkat yang berbeda, namun, memiliki makna yang sama. Hal yang sama dapat pula dilihat pada: “لا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله”, “لا حولٌ ولا قوةٌ إلاّ بالله”, “لا حولَ ولا قوةٌ إلاّ بالله”, “لا حولٌ ولا قوةَ إلاّ بالله”, “لا حولَ ولا قوةً إلاّ بالله”. Meskipun kata حول dan قوة dibaca dengan harkat berbeda, namun, semuanya memiliki makna yang sama.
5. Seandainya harkat akhir kata berimplikasi terhadap makna, megapa boleh berbeda qira’at al-Qur’an dan mengapa pula boleh di-sukun-kan bacaan ketika waqaf (berhenti). Hal itu tentu dapat mengubah makna.
6. Orang yang tidak paham sedikitpun dengan ilmu nahu (i’rab), bila dibacakan kepadanya suatu berita koran, ia dapat memahaminya tanpa tergantung dengan ilmu nahu.
7. Bukti bahwa harkat akhir kata hanya sekedar untuk kemudahan dan keindahan berbahasa adalah apa yang dilakukan oleh Zujjal, seorang yang berkebangsaan Libanon. Ia merubah harkat akhir kata demi untuk kemudahan serta keindahan berbahasa.
8. Seandainya i’rab itu penting untuk mendapatkan pemahaman (makna) dalam berbahasa tentu orang arab akan melestarikannya dalam kehidupan mereka.
Semua alasan yang dikemukakan di atas dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi kelompok yang tidak mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna kata.
Jika i’rab tidak berperan dalam menentukan makna sebagaimana dikemukakan diatas, lalu, apa akan yang menjadi pembeda makna kata dalam struktur kalimat arab. Menurut kelompok ini, makna suatu kata dalam struktur kalimat ditentukan oleh dua hal; pertama, oleh situasi dan kondisi yang mengitari pembicaraan, yang dipahami melalui hubungan antara penutur dengan pendengar, serta konteks dan situasi yang menyebabkan terjadinya pembicaraan. Kedua, ditentukan oleh system kalimat arab serta tempat (kedudukan kata) yang tersistimatis yang memiliki makna-makna kebahasaan (Ya’qub, 1982:135). Sebagai contoh adalah ungkapan: “ظننت زيدا أخاك” (Aku kira Zaid adalah saudaramu) dan “ظننت أخاك زيدا” (Aku kira saudaramu adalah Zaid). Pada ungkapan pertama, yang menjadi sumber keraguan adalah tentang saudara, yaitu, apakah Zaid itu saudaramu atau tidak. Sedangkan pada ungkapan kedua, yang menjadi sumber keraguan adalah tentang nama, yaitu, apakah saudaramu bernama Zaid atau tidak. Dalam hal ini yang dilihat adalah system kalimat (susunan kata), seperti fa’il terletak sesudah fi’il dan sebelum maf’ulbih. Begitu seterusnya.
Sebaliknya, kelompok yang mengakui urgensi i’rab memiliki implikasi makna, bukan sekedar asesoris sebagaimana dikemukakan oleh kelompok pertama mengajukan pula sejumlah alasan yang menjadi dasar pemikiran mereka, antara lain adalah (Ya’qub, 1982:137-138):
1. Kalau sekiranya harkat akhir kata itu sekedar untuk takhfif, yang bertujuan untuk kemudahan menyambung kata bila diiringi oleh tanda sukun, lalu, kenapa orang arab tidak memiliki satu harkat saja. Jika mereka beralasan hal itu dapat menyulitkan, lantas, kemudian mereka menetapkan beberapa alternative harkat untuk kemudahan/keindahan, di samping tidak melarang dengan satu harkat seperti yang dikemukakan oleh Quthrub, maka, tentu fa’il terkadang dapat dibaca dengan harkat jar, atau dengan harkat rafa’ atau harkat nashab. Demikian juga mudhaf ilaih, terkadang bisa dibaca dengan harkat nashab, tidak seperti biasanya, dengan jar. Jika demikian halnya, tentu bahasa arab akan menjadi kacau serta tidak sesuai lagi dengan kenvensi bahasa.
2. Mendasarkan pemahaman makna kata pada situasi dan kondisi yang mengitari pembicaraan melalui pehaman hubungan antara penutur dan pendengar merupakan cara pecarian makna yang amat sulit. Hal itu merupakan pekerjaan yang dipaksakan, karena untuk memahami satu bait syi’ir saja, misalnya, kita harus membuka sejumlah buku untuk mengetahui situasi dan kondisi dimana bait-bait itu diucapkan oleh penyair. Sedangkan penentuan makna dengan melihat i’rab kata, tentu tidak harus demikian.
3. Sebetulnya, pendapat yang mengatakan bahwa makna kata hanya ditentukan oleh system kalimat dan kedudukan (kata) yang tersistimatis yang memiliki makna kebahasaan, maka pendapat tersebut terlalu berlebihan. Hal itu disebabkan, dalam struktur bahasa arab tidak dikenal adanya ruang-ruang, dimana masing-masingnya hanya ditempati oleh satu fungsi nahwu, seperti fa’il memiliki satu tempat, fi’il tempat yang lain dan maf’ulbih tempat selanjutnya, demikian seterusnya. Di dalam struktur kalimat arab, satu tempat kadangkala diduduki oleh fa’il, kadangkala fi’il dan kadangkala maf’ulbih. Sebagai contoh dapat dilihat pada ungkapan:
“أكلَ الولدُ التّفاحةَ”, “أكلَ التّفاحةَ الولدُ”, “التّفاحةَ أكلَ الولدُ”, “التفاحةَ الولدُ أكلَ”, “الولدُ أكلَ التّفاحةَ” dan “الولدُ التّفاحةَ أكلَ”. Meskipun susunan kata dalam ungkapan ini tidak sama, namun semuanya memiliki makna yang sama. Makna itu dapat diperoleh melalui pemahaman i’rab kata.
4. Banyak ditemui di dalam bahasa arab kata-kata yang memiliki makna beda disebabkan berbedanya harkat akhir kata. Antara lain, terlihat pada ayat al-Qur’an berikut ini:
إن الله بريء من المشركين ورسولُه
Kata رسول dalam ayat di atas dapat dibaca dengan harkat dhommah sebagai mubtada’ atau fathah dengan meng-’athaf-kannya kepada kata الله. Jika dibaca dengan kasrah, dengan cara menga-‘athaf-kan kepada kata المشركين, maka akan menimbulkan pemahaman yang dapat membawa kepada kekafiran (pengengkaran terhadap ayat Allah). Contoh ini banyak ditemui di dalam al-Qur’an.
Bentuk yang sama juga ditemui pada bahasa percakapan, misalnya, ungkapan: “اشتريت ثلاثة صناديق كتبا” tidak sama maknanya dengan “اشتريت ثلاثة صناديق كتب”. Jika yang pertama bermakna “saya membeli tiga kotak buku” maksudnya adalah tiga kotak yang penuh buku, sedangkan ungkapan yang kedua “saya membeli tiga kotak buku”, maksudnya adalah tiga buah kotak untuk tempat buku.
ANALISIS KONTROVERSI PEMIKIRAN
TENTANG URGENSI I’RAB
Seperti yang telah dijelaskan bahwa para linguis arab berbeda pandangan mengenai urgensi i’rab dalam menentukan makna kata dalam struktur kalimat. Mereka pada dasarnya terpola ke dalam dua kelompok, yaitu, kelompok yang tidak mengakui dan kelompok yang mengakui. Meskipun pada kesimpulan mereka kelihatan bertolak belakang, namun bila ditelusuri alasan-alasan yang dikemukakan, perbedaan tersebut tidaklah sekontras kesimpulan yang diambil. Sebab, sebagian alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang tidak mengakui justru tidak sepenuhnya membatalkan pemikiran kelompok yang mengakui.
Bila ditelusuri lebih jauh delapan alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang tidak mengakui, maka alasan-alasan tersebut dapat dipilah ke dalam dua bentuk. Pertama, alasan yang berbentuk fakta-fakta kebahasaan, dan kedua, alasan yang bercorak logika. Alasan yang berbentuk fakta kebahasaan, antara lain –seperti yang terlihat pada poin pertama-- adalah karena terdapatnya di dalam bahasa arab kata-kata yang fungsinya sama, sedangkan harkat akhirnya berbeda. Kata-kata tersebut, antara lain seperti kata”الرجل” pada ungkapan berikut:
(Laki-laki itu berada di rumah), الرجلُ في البيت
(Laki-laki itu benar-benar berada di rumah) إن الرجلَ في البيت
(Laki-laki itu memiliki seorang saudara di rumah) للرجلِ أخ في البيت
Fakta lain yang dikemukakan adalah kata-kata yang i’rab-nya sama, sedangkan maknanya berbeda (alasan ke-3). Diantara contoh yang dikemukakan adalah kata ” زيدًا” pada ungkapan: إنّ زيدًا أخوك , لعل زيدًا أخوك dan كأنّ زيدًا أخوك.
Sebaliknya, terdapat pula kata-kata yang i’rab-nya berbeda, sedangkan maknanya sama (alasan ke-4). Contoh yang dikemukakan untuk ini, diantaranya kata ”بخيل”, “قائم”, “عسل” pada ungkapan berikut: ليس زيد بجبان ولابخيل أو بخيلا , ما زيد قائما أو قائم. Termasuk juga ke dalam contoh ini kata “حول” dan “قوة” pada ungkapan: لاحول ولا قوة إلا بالله dengan lima cara membacanya.
Bila dicermati fakta-fakta kebahasaan yang dikemukakan diatas agaknya tidak sepenuhnya menggambarkan penolakan terhadap urgensi i’rab dalam menentukan makna. Sebagian fakta tersebut menurut hemat penulis kurang relevan dan sebagian lagi perlu dilakukan reinterpretasi. Fakta yang mengatakan bahwa di dalam bahasa arab terdapat kata-kata yang fungsinya sama, tapi harkat-nya berbeda, seperti kata ”الرجل” pada: الرجلُ في البيت (Laki-laki itu berada di rumah), إن الرجلَ في لبيت (Laki-laki itu benar-benar berada di rumah) dan للرجلِ أخ في البيت (Laki-laki itu memiliki seorang saudara di rumah), fakta ini hanya dikaitakan dengan menyebutkan fungsi gramatikal kata ”الرجل” sebagai musnad ilaih dan sama sekali tidak dikaitkan secara langsung dengan persoalan makna. Oleh karena itu, fakta ini menurut hemat penulis kurang relevan dijadikan sebagai dasar penolakan urgensi i’rab dalam menentukan makna kata. Kecuali itu, kata ”الرجل” pada ungkapan ketiga menurut struktur bahasa arab bukan sebagai musnad ilaih, melainkan, musnad.
Persoalan yang sama juga terlihat pada alasan kedua yang menyebutkan bahwa di dalam bahasa arab terdapat kata-kata yang harkat-nya sama, akan tetapi, fungsi grmatikanya berbeda, seperti hal, tamyiz dan al-maf’ulat al-khamsah. Kesemua fungsi ini dibaca dengan manshub. Disini dengan jelas dibedakan antara fungsi kata dengan fenomena akhir kata (harkat). Padahal kedua aspek ini merupakan satu kesatuan di dalam kajian i’rab. Fenomena akhir kata terjadi disebabkan oleh amil atau oleh kedudukan /fungsi kata di dalam struktur kalimat. Sebaliknya, amil atau kedudukan /fungsi kata akan menyebabkan perubahan akhir kata. Akan tetapi, persolannya disini tidak dikaitkan sama sekali dengan makna kata. Oleh karena itu, hal ini kurang relevan dijadikan dasar dasar penolakan.
Sedangkan fakta berikutnya yang terkait langsung dengan makna adalah kata-kata yang i’rab-nya sama, tapi maknanya berbeda, atau sebaliknya, i’rab-nya berbeda, maknanya sama. Untuk yang pertama, contoh yang dikemukakan adalah kata ”زيدًا” pada ungkapan: إنّ زيدًا أخوك , لعل زيدًا أخوك dan كأنّ زيدًا أخوك. Sebetulnya, kata ”زيدًا” dalam ungkapan ini meskipun dipandang sebagai musnad ilaih dan dibaca manshub, namun, fungsi i’rab masing-masingnya sesungguhnya berbeda. Kata ”زيدًا” pada ungkapan yang pertama adalah sebagai isim إنّ , pada ungkapan yang kedua sebagai isim لعلّ sedangkan yang ketiga sebagai isim كأنّ. Masing-masing dari kata “إن” , “لعلّ” dan “كأنّ” ini memiliki makna yang berbeda. Kata yang pertama, memiliki makna penegasan (ta’kid), yang kedua, harapan (tarajjiy) dan yang ketiga, perumpamaan (tasybih). Dengan demikian, dapat dihamai bahwa i’rab kata ”زيدًا” di dalam masing-masing ungkapan tersebut sesungguhnya tidaklah sama. Oleh karena itu, perbedaan makna ungkapan tersebut adalah sesuatu yang sangat logis.
Adanya pendapat yang mengatakan bahwa kata ”زيدًا” dalam ungkapan diatas mempunyai i’rab sama, pemikiran tersebut barangkali didasarkan kepada pandangan yang mendefinisikan i’rab itu hanya sebatas fenomena harkat akhir kata (bentuk luar i’rab). Padahal i’rab itu juga terkait dengan fungsi i’rab seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Pandangan ini pulalah agaknya yang menyebabkan kelompok yang tidak mengakui urgensi i’rab mengatakan, hal, tamyiz dan al-maf’ulat al-khamsah mempnyai i’rab yang sama, karena sama-sama dibaca secara manshub. Padahal hal, tamyiz dan al-maf’ulat al-khamsah, masing-masingnya memiliki i’rab yang berbeda yang memberikan implikasi yang berbeda pula pada makna. Adanya pandangan demikian menurut hemat penulis adalah sesuatu yang logis karena ia muncul di tengah pergumulan kajian nahwu (i’rab) dan perumusannya menuju kematangan keilmuannya.
Sedangkan untuk yang kedua, yakni, i’rab-nya berbeda dan maknanya sama, contoh yang diangkat adalah kata قوة ، حول، عسل، قائم، بخيل pada ungkapan-ungkapan:
ليس زيد بجبان ولا بخيلٍ أو ولا بخيلاً
ما زيدٌ قائمًا أو قائمٌ
عندي رطل عسلٍ أو عسلٌ أو عسلاً
"لا حولَ ولا قوةَ إلاّ بالله"، "لا حولٌ ولا قوةٌ إلاّ بالله"، "لا حولَ ولا قوةٌ إلاّ بالله"
"لا حولٌ ولا قوةَ إلاّ بالله"، "لا حولَ ولا قوةً إلاّ بالله"
Kata بخيل pada ungkapan pertama dapat dibaca dengan majrur (kasrah) dengan cara meng-‘athaf-kan kepada kata جبان (harkat mengikut) yang ada sebelumnya, dan dapat pula dengan manshub (fathah) dengan cara meng-’athaf-kan kepada kedudukan i’rab kata-kata بجبان (terdiri dari jar dan majrur) yang berada pada tempat manshub sebagai khabar ليس. Baik meng-‘athaf-kan kepada kata جبان , maupun kepada kedudukan i’rab kata-kata بجبان , pada hakikatnya kedua bentuk ini adalah khabar dari ليس. Apabila disederhakan, ungkapan tersebut bisa menjadi:
ليس زيد بخيلاً , ليس زيد ببخيلٍ , ليس زيد بجبانٍ
Oleh karena itu, wajar kalau kedua kata tersebut di dalam ungkapan di atas memiliki makna yang sama, meskipun, fenomena akhir katanya berbeda.
Sama dengan kata بخيل , kata قائم pada ungkapan kedua juga membuktikan, i’rab tidak memberikan implikasi sedikitpun terhadap makna kata. Namun, bila ditelusuri lebih jauh permasalahannya berawal dari perbedaan pandangan mengenai kedudukan ما (nafi) yang ada sebelumnya, apakah ia ber-amal atau tidak. Kalangan penduduk Hijaz, Tihamah dan Nejed memberlakukan ما (nafi) tersebut seperti ليس, dengan pengertian bahwa ia me-nashab-kan isim (mubtada’) dan me-rafa’-kan khabar (Al-Galayayni, 1987:293). Dengan demikian, mereka lalu membaca kata قائم dalam ungkapan tersebut dengan nashab (قائمًا). Sedangkan penduduk Tamim tidak demikian. Mereka menganggap bahwa jumlah sesudah ما (nafi) adalah terdiri dari mubtada’ dan khabar yang harus di-rafa’-kan (Al-Galayayni, 1987:294). Oleh karena itu, mereka membaca kata قائم di ungkapan tersebut dengan rafa’ ( قائمٌ). Meskipun berbeda fenomema i’rab akhir kata, namun, kedua kata ini sama-sama berfungsi sebagai musnad (predikat) yang harus menjelaskan keadaan musnad ilaih (subjek) yang di dalam hal ini adalah si Zaid. Oleh karena itu, meskipun berbeda, namun tidak memberikan implikasi terhadap makna.
Berbeda dengan kedua kata sebelumnya, kata حول، عسل dan قوة di dalam ungkapan di atas memberikan implikasi yang kuat terhadap makna. Kata عسل di dalam ungkapan ketiga di atas bila dibaca dengan kasrah, memberikan pengertian bahwa yang dimiliki itu belum tentu satu liter madu. Akan tetapi, boleh jadi yang dimiliki itu sebuah liter yang digunakan untuk menakar madu. Sebaliknya, bila dibaca dengan fathah, maka yang dimaksudkan adalah satu liter yang berisi madu. Persoalan ini sama dengan ungkapan: “اشتريت ثلاثة صناديق كتبا” atau “اشتريت ثلاثة صناديق كتب” yang dikemukakan oleh kelompok kedua, sebagai bantahan mereka terhadap kelompok yang tidak mengakui.
Demikian juga kata حول, قوة pada ungkapan:“لاحولَ ولاقوةَ إلاّ بالله”, “ لا حولٌ ولا قوةٌ إلاّ بالله”, “ لا حولَ ولا قوةٌ إلاّ بالله”, “لا حولٌ ولا قوةَ إلاّ بالله”, “لا حولَ ولا قوةً إلاّ بالله”. Kata حول dan قوة bila dibaca dengan harkat fathah tanpa ber-tanwin berarti berkedudukan sebagai isim لا النافية للجنس, dan sebaliknya, bila di baca dengan dhommah berarti berkedudukan sebagai isim لا yang ber-amal seperti ليس .
Syauqi Dheif di dalam bukunya tajdid al-nahwi menjelaskan, لا النافية للجنس me-nafi-kan jenis. Misalnya ungkapan: لاطالبَ في الفصل (mahasiswa tidak ada di kelas), berarti, di dalam kelas tidak ada mahasiswa, baik satu orang, dua orang, maupun tiga orang dan seterusnya (Dheif, 1985:150). Sedangkan لا yang beramal seperti ليس, yang oleh Syauqi Dheif disebut dengan istilah لا النافية للوحدة hanya me-nafi-kan dalam bentuk tunggal. Misalnya, لاكتابٌ عندي (saya tidak memiliki kitab), berarti, saya tidak memiliki satu buah kitab. Ungkapan ini tidak me-nafi-kan bahwa saya memiliki dua buah kitab atau tiga buah kitab dan seterusnya (Dheif, 1985:152) .
Dengan demikian, pemahaman kata حول dan قوة bila dibaca dengan harkat fathah tanpa ber-tanwin yang berkedudukan sebagai isim لا النافية للجنس, berarti, me-nafi-kan segala bentuk حول (daya) dan قوة (upaya/kekuatan), baik dalam bentuk tunggal, dual maupun jamak. Sebaliknya, bila dibaca dengan harkat dhommah yang berkedudukan sebagai isim لا yang beramal seperti ليس, berarti, me-nafi-kan bentuk tunggal. Dengan kata lain, yang di-nafi-kan dalam konteks ini hanya satu bentuk daya dan upaya/kekuatan. Sedangkan bentuk-bentuk daya dan upaya/kekuatan yang lain tidak di-nafi-kan oleh ungkapan ini.
Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang tidak mengakui, baik dalam bentuk logika, maupun, fakta kebahasaan, agaknya alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat untuk menolak urgensi i’rab dalam menentukan makna. Meskipun sebagian fakta kebahasaan yang dikemukakan tersebut sekilas memperlihatkan tidak adanya pengaruh i’rab terhadap makna kata dalam struktur kalimat arab, namun, bila ditelusuri lebih jauh tidaklah demikian halnya. Kata-kata yang diduga i’rab-nya berbeda, akan tetapi, maknanya sama, setelah dianalisis, ternyata maknanya juga berbeda. Begitu juga sebaliknya.
Sebaliknya, kelompok kedua, yang mengakui urgensi i’rab dalam menetukan makna kata membantah argument kelompok pertama yang menganggap harkat akhir kata hanya sekedar asesoris bahasa. Mereka juga membantah cara penetuan makna yang hanya di dasarkan kepada konteks (situasi dan kondisi) yang melatar belakangi pembicaraan yang dipahami melalui hubungan pnutur dengan pendengar, karena itu sangat sulit untuk dilakukan. Atau didasarkan pada sytem bahasa dan tempat /kedudukan kata yang tersistim yang kadangkala tidak bersifat konstan (stabil) di dalam struktur kalimat arab. Kadangkala maf’ulbih mendahului fa’il dan khabar mendahuli mubtada’ , tidak seperti biasanya.
Berdasarkan analisis di atas serta memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang kedua, kelihatannya pendapat kedua, yakni, yang mengakui urgensi i’rab dalam menentuka makna kata dalam struktur kalimat arab agaknya dipandang kuat. Bukti-bukti bahwa i’rab ini memberikan implikasi kuat terhadap makna kata sesungguhnya banyak ditemui di dalam bahasa arab, termasuk al-Qur’an.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Term i’rab sebagai bentuk fenomena perubahan akhir kata yang disebabkan oleh kedudukan kata atau amil di dalam struktur kalimat arab muncul pertama kali sekitar akhir abad pertama hijrah, yaitu, ketika telah dirasakan berbagai kelemahan dalam praktek berbahasa dan kesulitan menangkap makna kata dalam strukutur kalimat. Dan setelah itu, pembahasan mengenai i’rab terus berkembang. Di tengah-tengah perkembangan dan pergumulan kajiannya menuju kematangan keilmuan nahwu (i’rab), muncul pula kontroversi pemikiran di kalangan para linguis mengenai urgensi i’rab dalam menentukan makna kata dalam struktur kalimat. Mereka terpolarisasi ke dalam dua kelompok, yaitu, kelompok yang tidak mengakui urgensi i’rab dalam menentukan makna, dan kelompok yang mengakuinya.
2. Untuk memperkuat pendapat tersebut, masing-masing kelompok mengemukakan berbagai alasan, baik dalam bentuk logika, maupun berupa fakta kebahasaan. Setelah dilakukan penulusuran dan analisis terhadap berbagai alasan dan fakta kebahasaan tersebut ternyata alasan kelompok yang tidak menerima tidak cukup kuat untuk menolak urgensi i’rab dalam menentukan makna. Sebagian fakta kebahasaan yang sekilas diduga tidak memperlihatkan adanya pengaruh i’rab terhadap makna kata, ternyata memberikan impilkasi makna.
3. Munculnya perbedaan pandangan di kalangan linguis arab mengenai urgensi i’rab dalam menentukan makna kata selain disebabkan oleh adanya berbagai fakta kebahasaan tersebut, kelihatannya juga disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka yang mendefinisikan i’rab itu hanya sebatas fenomena harkat akhir kata, tidak menyintuh fungsi i’rab. Padahal, pengertian i’rab mencakup kedua aspek tersebut.
Selasa, 24 Maret 2009
Kontroversi Pemikiran dalam Kajian Linguistik Arab
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























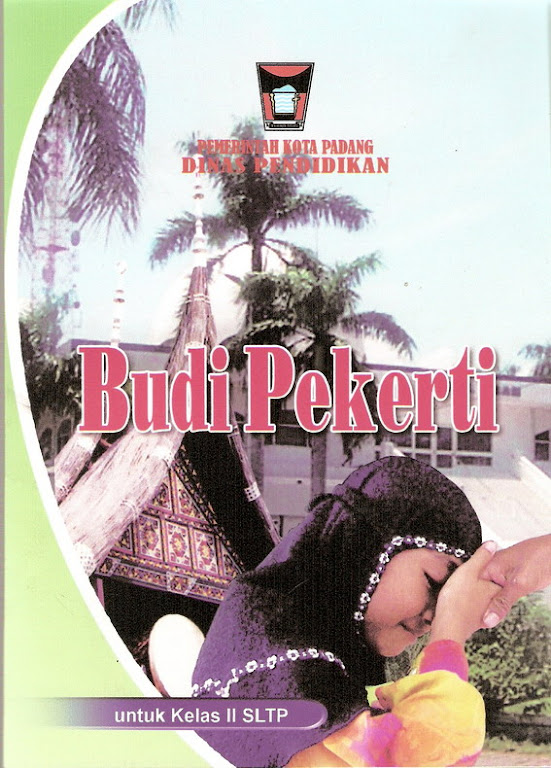





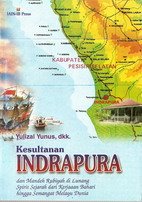




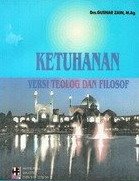
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar