Oleh : Muhammad Natsir, SS
 Kekerasan demi kekerasan mengalir begitu saja di negeri ini. Datang dan pergi silih berganti, seolah-olah menjadi tradisi baru dalam masyarakat Indonesia yang sedang sakit. Fenomena terakhir, Tragedi Monas 1 Juni 2008. Massa Komando Lasykar Islam Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
Kekerasan demi kekerasan mengalir begitu saja di negeri ini. Datang dan pergi silih berganti, seolah-olah menjadi tradisi baru dalam masyarakat Indonesia yang sedang sakit. Fenomena terakhir, Tragedi Monas 1 Juni 2008. Massa Komando Lasykar Islam Front Pembela Islam (FPI) bentrok dengan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).Selain itu, ingatan bangsa dijejali berbagai aksi kekerasan di institusi rumah tangga (KDRT) di institusi pendidikan (IPDN Jatinangor dan STIP Jakarta), Kampus Unas Jakarta, adu fisik anggota parlemen, perusakan properti Ahmadiyah dan sebagainya. Semuanya belum terselesaikan dan menjadi misteri yang nyaris tak akan terungkapkan, mengingat derasnya arus sirkulasi kekerasan demi kekerasan.
Pesan di balik kekerasan itu jelas, bahwa kekerasan telah menjadi cara baru untuk mengekspresikan keinginan. Lebih dari itu, kekerasan ternyata hampir dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Lihatlah negara, polisi, rumah tangga, mahasiswa, pelajar, anak-anak dan entah siapa lagi. Kekerasan tidak hanya dominasi agama, tetapi oleh siapa saja yang hidup di negeri ini.
Sungguh gambaran yang memilukan. Anak-anak bangsa yang beranjak dewasa dipaksa menerima kenyataan, betapa kerasnya hidup dan apakah dengan cara seperti itu kehidupan harus dijalankan? Lalu wilayah mana yang sunyi dari kekerasan di republik ini?
Referensi Teatrikal Kekerasan
Kekerasan tidak selamanya berusan dengan bentrok pisik, saling pukul atau saling serang dengan berbagai senjata. Lebih dari itu, ucapan dan aksi teatrikal juga menjadi varian kekerasan yang kadang tidak disadari. Ada banyak manusia yang terhinakan, budaya yang terhinakan serta agama yang terlecehkan dalam aksi-aksi tersebut.
Misalnya, bagaimana patung seseorang diperlakukan dalam aksi demonstrasi adalah kekerasan. Diarak, ditendang, dipukuli kemudian (meskipun patung) adalah kekerasan. Betapa tidak, pesan yang di bawa oleh aksi teatrikal itu adalah tawaran cara untuk memperlakukan seseorang.
Ayam betina, pakaian dalam wanita, serta perlengkapan asesories yang berhubungan dengan wanita adalah bentuk penistaan terhadap wanita yang menjadi ibu, saudara perempuan atau kerabat pelaku.
Bahkan, properti yang erat dengan ritual atau tradisi peribadatan tidak luput dari penghinaan. Misalnya, bagaimana keranda mayat (meski tidak sakral) sebagai salahsatu alat penghormatan kepada manusia yang mati disalahgunakan dalam aksi.
Dalam tradisi umat Islam keranda mayat digunakan sebagai usungan. Mayat diletakkan dalam posisi yang baik, diselimuti dengan kain yang bagus bahkan tidak jarang dihiasi dengan kalimat “Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji’un.” Kita Milik Allah dan Akan kembali kepada Allah.
Dalam aksi demonstrasi replika keranda mayat diusung sebagai simbol kematian. Setelah puas diusung, replika itu dihempaskan, diinjak-injak lalu dibakar. Begitu sadiskah perilaku umat Islam terhadap kematian?
Antagonisme Semangat Zaman
Reformasi dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih baik, bebas dari kekerasan dan militerisme Orde Baru. Tetapi kebebasan di era reformasi diartikulasi secara salah. Milisterisme yang menjadi prilaku buruk Orde Baru menular kepada rakyat. Berbagai organisasi kelasykaran dan berbagai metode kekerasan diterapkan secara massif. Rakyat tiba-tiba berubah menjadi preman.
Begitu kuatkah citra kekerasan Orde Baru sehingga terhunjam kuat di ingatan rakyat? Apakah ingatan itu yang mendorong masyarakat untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan supremasinya?
Orde Baru tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Orde Baru hanyalah waktu referensial di mana kekerasan menjadi dominasi negara. Sungguh suatu yang paradoks jika kekerasan sebagai yang ditolak menjadi prilaku masyarakat.
Sesungguhnya, bangsa Indonesia telah melupakan semangat zamannya; semangat anti kekerasan. Kelompok- kelompok yang mempunyai track record kekerasan adalah tokoh antagonisme sesungguhnya. Selamanya, ibarat pementasan teater, tokoh antagonisme tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat.
Akhirnya, kekerasan demi kekerasan menjadi pertunjukan teater. Emha Ainun Nadjib (1998) mengatakan, layaknya sebuah pertunjukkan respon penonton akan sangat beragam. Ada yang melihat kostum dan tata riasnya, ada yang melihat ceritanya, ada yang melihat kemegahan panggung, ada yang melihat aksi para aktor dan begitulah seterusnya kekerasan direspon oleh masyarakat.
Tidak heran, merespon Tragedi Monas 1 Juni 2008 yang lalu tidak muncul satu tanggapan. Ada yang melihat FPI dan AKKBB. Ada yang melihat negara atau polisi, ada yang melihat panggung, ada yang melihat cerita kronologis. Nyaris tidak ada kesepakatan semisal “Peristiwa Monas tidak layak ditonton dan dipertontonkan!”

























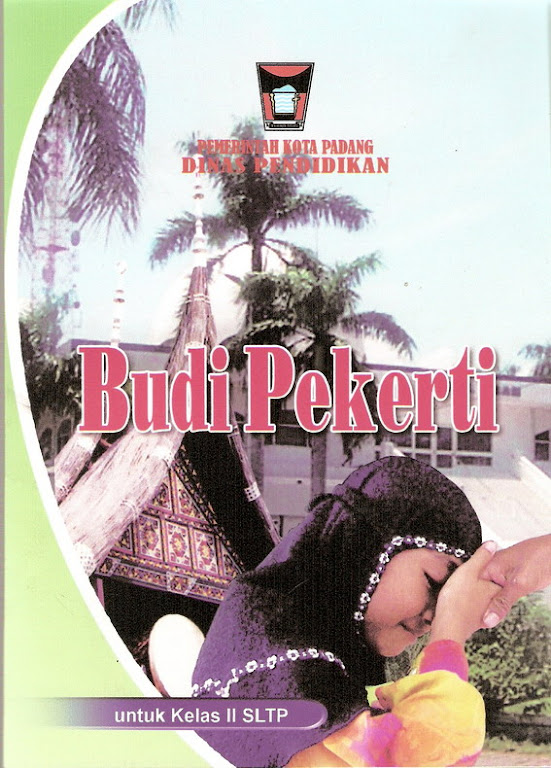





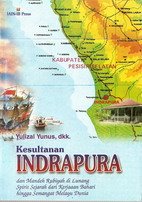




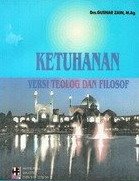
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar