Oleh : DR. Firdaus, M.Ag.  Existence of sentence of qathi'i and zanni in al-Qur'an represent the characteristic and demeanour al-Qur'an in explaining law. Certainty mean the qath'i dalalah of a sentence come from a group of theorem zanni (ahad) contain the same meaning possibility so that one another is supporting each other and having the power of separate....
Existence of sentence of qathi'i and zanni in al-Qur'an represent the characteristic and demeanour al-Qur'an in explaining law. Certainty mean the qath'i dalalah of a sentence come from a group of theorem zanni (ahad) contain the same meaning possibility so that one another is supporting each other and having the power of separate....
Adanya ayat-ayat qathi’i dan zanni dalam al-Qur’an merupakan ciri dan tabiat al-Qur’an dalam menjelaskan hukum. Kepastian makna qath’i dalalah suatu ayat berasal dari sekumpulan dalil zanni (ahad) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. Umumnya, ayat qath’i mengatur tentang pokok-pokok ajaran Islam yang bersifat tetap (al-tsawabit) sehingga tidak berpeluang dilakukan takwil dan dirubah. Ayat zanni merupakan ayat dengan lafal mengandung kebolehjadian beberapa makna sehingga menjadi ruang lingkup ijtihad menentukan makna mana yang dimaksudkan ayat. Ayat-ayat zanni banyak berkaitan dengan bidang muamalat.
PENDAHULUAN
Dalam kajian terhadap al-Qur’an, ada dua hal penting yang mutlak diperhatikan, yaitu al-tsubut (kebenaran sumber) dan al-dalalah (kandungan makna). Dari sisi al-subut al-Qur’an, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (qath’i tsubut) berasal dari Allah karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga memfaedahkan yakin (Zaidan, 187: 160).
Semua ayat al-Qur’an yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad saw. yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim di seluruh penjuru dunia, disepakati umat Islam, tidak berbeda dan berubah semenjak awal turun sampai sekarang dan masa yang akan datang.
Sementara dari sisi dalalah atau kandungan redaksi ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang qath’i dan zanni. Kajian mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’an menunjukan bahwa adanya ayat-ayat yang qathi’i dan zanni merupakan ciri al-Qur’an tersendiri dalam menjelaskan hukum (ahkam). Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi’at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qathi’i dan yang lain zanni dengan maksud dan makna tertentu.
Pembahasan tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hakekat qath’i dan zanni, kriteria dan hubungannya dengan ijtihad serta hubungan keduanya dengan hakikat, majaz dan takwil.
KRITERIA AYAT-AYAT QATH’I DAN HUBUNGANNYA DENGAN IJTIHAD
Dalam pandangan Syatibi, jarang sekali dalil-dalil syara’ bila dilihat secara berdiri sendiri (ahad) yang qath’i. Pandangan ini didasarkan kepada prinsip bahwa bila dalil-dalil syara’ itu ahad tentu ia tidak qath’i, melainkan bersifat zanni. Penentuannya sangat bergantung kepada naql al-luqhah dan pendapat-pendapat ahli nahwu (Syatibi, 1997: 35).
Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat qath’i dalam al-Qur’an, tetapi ia sesungguhnya ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian qath’i dalalah sebagai istilah yang populer dipakai mengalami suatu proses sehingga suatu hukum yang diangkat dari ayat-ayat itu pada akhirnya disebut qath’i dalalah. Menurutnya, kepastian makna (qath’i dalalah) suatu nash berasal dari sekumpulan dalil zanni (ahad) yang semuanya mengandung kemungkinan makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri. Kekuatan dari himpunan dalil ini membuatnya tidak bersifat zanni lagi. Ia menjadi semacam mutawatir maknawi. Inilah yang kemudian dinamakan qath’i dalalah (Syatibi, 1997:36).
Sehubungan dengan itu, Syatibi mengemukakan contoh mengenai perintah sholat. Apabila perintah sholat dipahami hanya dari firman Allah yang potongan nya berbunyi: aqimu al-sholah, maka ia akan bersifat zanni (Syatibi, 1997: 36). Namun, karena didukung oleh sejumlah dalil lain yang menjelaskan adanya pujian dari Allah bagi orang yang melakukan sholat, celaan dan ancaman bagi yang meninggalkannya dan perintah kepada mukallaf melakukannya dalam keadaan bagaimanapun, baik ketika sehat atau sakit, damai atau perang serta dalil-dalil lain tentang sholat. Kumpulan nash yang semakna dengan ini secara keseluruhan kemudian disepakati ulama melahirkan ketentuan secara pasti (qath’i) tentang wajib sholat.
Dari penjelasan qath’i dalalah di atas, dapat diamati dari dua sisi, yaitu: pertama, suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. Qath’i dalalah dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain secara pasti”.
Al-Ghazali mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam rumusan yang berbeda. Menurut ulama ini, qath’i dalalah adalah suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat semenjak asalnya (Ghazali, t.t: 265).
Tampaknya yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat qath’i dalam Qur’an adalah qath’i yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung oleh dalil lain.
Kedua, qath’i dalalah dari sisi bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian makna lain yang didukung oleh dalil.
Dalam ide yang sama al-Ghazali pun menyatakan bahwa suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalil (Ghazali, t.t: 265).
Dengan berpegang kepada pengertian qathi’i bentuk kedua ini, cukup banyak ayat-ayat qathi’i terdapat dalam al-Qur’an. Pengertian qathi’i ini pula yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Misalnya, Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa qath’i dalalah ialah nash qath’i dalalah ialah lafal yang terdapat di dalam al-Qur’an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal (Wahbah, 1986: 442).
Dengan maksud yang sama Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan qath’i dalalah adalah suatu lafal yang dipahami darinya satu makna tertentu dan tidak mengandung kebolehjadian takwil serta tidak mengandung kemungkinan untuk dipahami makna lain selain ditunjukkan lafal itu (Khallaf, 1978: 35).
Beberapa definisi qath’i dalalah di atas, menggambarkan bahwa suatu ayat disebut qath’i manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini takwil tidak berlaku.
Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang termasuk dalam kategori qath’i dalalah ialah ayat-ayat yang menyangkut ushul al-syariah yang merupakan ajaran-ajaran pokok agama Islam, yaitu ibadah seperti sholat, zakat dan haji, perintah menegakkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan keadilan dan kewajiban mensucikan diri dari hadas (Syatibi, 1997: 16). Di samping itu termasuk dalam kelompok ayat qath’i adalah ayat yang berbicara tentang akidah, akhlak dan sebagian masalah muamalat (Thowilah, t.t: 42).
Penempatan ayat-ayat itu dalam kategori qath’i dalalah dilatar belakangi pertimbangan bahwa ajaran-ajaran yang dikandung ayat tersebut termasuk pokok-pokok agama (essensial) yang bersifat tsawabith (tetap) dan tidak bersifat mutaghaiyyirat (berubah), karena perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Andai kata ayat-ayat itu termasuk dalam kategori zanni yang menjadi objek ijtihad tentu akan muncul ketidakstabilan dalam agama dan sangat mungkin mengalami perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, tidak pernah dalam sejarah muncul mazhab fiqh dalam ayat-ayat qathi’i, tetapi yang ada dalam ayat-ayat zanni.
Lebih jauh Syatibi menyatakan bahwa maqasid syari’ah dalam menetapkan syari’ah yang meliputi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat didasarkan kepada dalil-dalil qath’i karena ketiganya merupakan ushul al-syari’ah, bahkan ia adalah ushul ushul al-syari’ah. Logikanya, bila ushul al-syariah ditetapkan dengan dalil qath’i, maka ushul ushul al-syari’ah lebih utama ditetapkan dengan dalil qath’i. Dengan kata lain, ushul ushul al-syari’ah ditetapkan pula dengan ayat-ayat qath’i.
Meskipun Syatibi tidak mengemukakan ayat qath’i mana yang berhubungan langsung dengan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, namun diasumsikan bahwa ayat-ayat yang mendukung terwujudnya ketiganya yang tersimpul dalam pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama, diri, akal, keturunan dan harta merupakan ayat-ayat qath’i. Misalnya, ushu al-ibadat yang meliputi iman, mengucapkan sahadatain, sholat, puasa, zakat dan haji yang ditujukan untuk pemeliharaan agama ditetapkan dengan ayat-ayat qath’i.
Beberapa contoh ayat-ayat qath’i dalam Qur’an diantaranya mengenai sholat, zakat, puasa, haji, waris, hudud dan kaffarat. Mengenai sholat Allah berfirman: “Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat” (QS. 2:43). Dalam memerintahkan haji kepada muslim Allah berfirman: “Merupakan kewajiban manusia kepada Allah untuk melakukan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan”“ (QS.4:96). Mengenai perintah puasa Allah berfirman: “Diwajibkan atasmu berpuasa” (QS.2:183).
Ketiga contoh ayat qath’i di atas, tidak dapat sekaligus dipahami dari redaksi ayatnya, melainkan didukung oleh penjelasan ayat lain dan penjelasan dari Nabi sendiri baik melalui perkataan, perbuatan maupun sekaligus gabungan antara perkataan dan perbuatan Nabi sehingga tidak mungkin terdapat kebolehjadian makna lain (Thowilah, t.t: 289).
Contoh lain tentang ayat qath’i dapat diamati dalam firman Allah tentang warisan berikut: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak” (QS.. 4:12). Begitu pula ayat qath’i ditemukan pula dalam kasus hukuman zina dalam firman Allah berikut: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (QS.24:2).
Ayat qath’i lain yang dapat diangkat sebagai contoh adalah kaffarat sumpah seperti dalam firman Allah berikut: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari (QS.5:89).
Bilangan-bilangan dalam ketiga ayat di atas, bagian waris “setengah” bagi suami yang meninggal istrinya dan tidak punya anak, “seratus kali” dera bagi orang yang melakukan zina, dan puasa “tiga hari” untuk kaffarat sumpah mengandung hukum yang qath’i dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain dari apa yang tertulis dalam ayat tersebut.
Dilatar belakangi ayat-ayat qath’i dalalah dari sisi lafaznya sehingga tidak mengandung kebolehjadian makna lain dari apa yang dikandung oleh lafal ayat itu, maka jelas peluang ijtihad tidak dimungkinkan pada setiap ayat yang qath’i dalalah. Mempertegas ketentuan ini para ulama merumuskan suatu kaedah fikih yang berbunyi: “Tidak diperkenankan melakukan ijtihad ketika sudah ada ketetapan nash (Zarqa’, 1968: 1008).
Nash yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah nash yang qath’i dalalah. Dengan kata lain, ayat-ayat yang qath’i dalalah tidak menjadi majal (ruang lingkup) ijtihad bagi para mujtahid. Mujtahid dan umat Islam menerima apa adanya seperti yang terdapat dalam ayat. Umat Islam dalam hal ini tinggal melaksanakan isi kandungan ayat yang qath’i tersebut.
Al-Ghazali berpendapat bahwa ayat-ayat qath’i bila berupa lafal umum tidak boleh ditakhsis dengan khabar ahad karena hadis ahad zanni wurud. Demikian pula ayat-ayat qath’i tidak bisa ditakhsis dengan qiyas karena qiyas adalah zanni dalalah. Al-Ghazali mengemukakan contoh firman Allah yang bersifat umum seperti terdapat dalam surat al-An’am ayat 121 berikut: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik (QS.6:121). Ayat ini tidak boleh ditakhsis dengan hadis ahad yang berbunyi: “seseorang mukmin dinilai selalu menyembelih hewan dengan nama Allah, baik disebutkan atau tidak disebutkannya nama Allah tersebut” (al-Hadis).
Dengan demikian, dalam pandangan al-Ghazali berdasarkan ayat di atas, tetap saja mukmin tidak boleh makan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah karena hadis ahad dalam contoh itu tidak dapat mentakhsis keumuman ayat 121 surat al-An’am.
Meskipun dari sisi lafalnya suatu ayat qathi’i, tetapi dari sisi makna mungkin saja zanni sehingga bisa dikembangkan maknanya, tetapi bukan dimaksudkan menggeser pengertian ayat tersebut. Adapun metode untuk mengembangkannya adalah melalui qiyas, seperti halnya mengqiyaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman, seperti wiski, brandy, tuak dan narkoba yang sengaja dibuat untuk memabukan. Pengharaman khamar dalam Qur’an dan Hadis karena illat memabukkan. Sementara wiski, brandy, tuak dan narkoba dapat memabukkan, bahkan lebih parah dari hal itu.
Pengembangan makna yang terdapat pada ayat qathi’i dapat dilakukan pada larangan mengucapkan kata kasar kepada orang tua karena dapat menyakiti hati dan perasaan mereka. Dalam kaitan ini, Allah berfirman: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. 17:23).
Secara mantûq, ayat ini menegaskan bahwa haram hukumnya mengucapkan kata “ah” dan menghardik orang tua. Larangan ini dijelaskan oleh ayat qath’î. Meskipun qath’î, pengertian yang dikandung ayat ini dapat dikembangkan maknanya kepada larangan memukul orang tua dan meliputi semua bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya. Pengembangan dengan cara ini dalam kajian usul fikih disebut mafhûm.
Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa ayat qathi’ dikembalikan kepada zat al-lafaz ayat al-Qur’an itu, bukan karena ketidakmampuan manusia dalam memahaminya. Bila qathi’i didasarkan atas pertimbangan ketidakmampuan manusia, menempatkan al-Qur’an sebagai kitab petunjuk yang tidak relevan dengan kemampuan manusia. Ini merupakan suatu kemustahilan karena al-Qur’an diturunkan Allah untuk dipahami dan dilaksanakan isi petunjuknya.
KRITERIA ZANNI DALALAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN IJTIHAD
Dari uraian tentang qath’i dalalah sebelumnya, secara implisit dapat dipahami pengertian zanni dalalah. Namun, agar lebih jelas dikemukakan beberapa definisi zanni dalalah dalam pandangan ahli ushul. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi zanni dalalah: “suatu lafal yang terdapat dalam al-Qur’an, mengandung kebolehjadian makna lebih dari satu sehingga dapat ditakwilkan” (Wahbah, 2001:442).
Abd Wahbah Abd al-Salam menyetujui pendapat di atas dan mendefinisikan zanni dalalah sebagai: “Apabila dilalah suatu lafal tidak menunjukkan untuk makna tertentu, tetapi mengandung kebolehjadian makna lain, di mana lafal itu sendiri mengandung dua makna atau lebih”.
Dari definisi di atas, jelas bahwa nash atau ayat-ayat zanni dalalah mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan ijtihad bagi para ulama untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya (Hasballah, 1971:80). Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat-ayat zanni dalalah.
Ayat-ayat zanni banyak berkaitan dengan bidang muamalat dan pada umumnya ditetapkan Syari’ dalam bentuk global sehingga dapat ditarik illatnya untuk dikembangkan seiring dengan perubahan masa dan tempat. Dalam hal ini, para ulama menyusun suatu kaidah: “Hukum asal dalam masalah muamalah dapat dipahami maknanya”.
Biasanya yang menjadi pertimbangan ulama dalam menafsirkan ayat-ayat zanni adalah kaidah-kaidah bahasa, maqasid al-syari’ah dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Namun, karena perbedaan metode dan kaidah yang digunakan dalam memahami ayat-ayat zanni sehingga melahirkan perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (QS. 2:228).
Kata quru’ dalam ayat di atas merupakan lafal musytarak yang mengandung dua makna, dapat berarti suci dapat pula berarti haid sehingga wanita yang ditalak suaminya, iddahnya tiga kali suci sebagaimana yang diperpegangi imam Syafi’i atau tiga kali haid sebagaimana yang dipahami imam Abu Hanifah. Contoh ayat zanni yang lain: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan (QS.5:38).
Kata “tangan” dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau tangan kiri, di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “tangan” ini ditentukan dalam hadis Nabi SAW.
Ayat-ayat zanni bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan metode istinbath hukum yang meliputi qiyas, istihsan, istislah dan urf.
HUBUNGAN QATH’I DAN ZANNI DENGAN HAKIKAT, MAJAZ DAN TAKWIL
Dapat dimaklumi bahwa setiap lafal mempunyai arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami orang ketika lafal itu diucapkan atau ketika ia membaca lafal itu dalam tulisan. Lafal dari segi penggunaannya dapat digolongkan kepada hakikat dan majaz. Sementara itu, dari segi untuk kejelasan arti suatu lafal yang dipakai kadangkala digunakan takwil.
Hakikat secara bahasa sewazan dengan fa’îlah yang bisa berarti fa’il atau maf’ul, terambil dari kata al-haq yang berarti tsubut (tetap). Secara istilah hakikat adalah: suatu lafal yang digunakan sebagaimana makna aslinya dalam istilah percakapan (Usman, 1986:182). Definisi hakikat ini sejalan pula dengan yang dikemukakan al-Syarkhisi. Menurut ulama ini, hakikat adalah setiap lafal yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu (Syarkhisi, 1973:170).
Kedua definisi hakikat ini menegaskan bawa hakikat adalah suatu lafal yang dipakai menurut asalnya untuk maksud tertentu. Tegasnya lafal itu dipakai oleh perumus bahasa memang untuk itu. Misalnya, kata “kursi” yang secara asalnya dipakai untuk menunjukkan tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun demikian, kata kursi sering pula dipakai untuk pengertian “kekuasaan”. Namun, tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu, tetapi sebagai “tempat duduk”.
Dilihat dari penggunaannya hakikat dapat berupa hakikat lughowiyat, hakikat syar’iyyah, hakikat ‘urfiyah khassah dan ‘urfiyah ammah. Misalnya lafal “sholat” yang terdapat dalam berbagai ayat al-Qur’an sebagaimana dimaksud syari’ dan kemudian dipopulerkan ahli fiqh berarti ibadah khusus yang meliputi perkataan dan perbuatan. Penggunaan lafal sholat dengan makna ini disebut hakikat syar’iyyah (Amir, 1997: 27).
Sementara itu, majaz secara bahasa sewazan dengan maf’al, terambil dari kata al-jawaj berarti menyeberang. Secara istilah majaz adalah suatu lafal yang digunakan bukan berdasarkan makna asalnya disebabkan ada hubungan antara makna asal dengan makna diinginkan. (Hasyimi, 1988:291). Dengan makna yang hampir sama al-Syarkhisi mendefinisikan majaz adalah nama untuk setiap lafal yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan (Syarkhisi, 1973:170).
Dari definisi majaz di atas tampak, apabila suatu lafal tidak dipakai menurut makna asalnya karena ada qarinah yang mendukung peralihannya kepada makna lain, maka lafal yang demikian disebut majaz. Misalnya, kata “kursi” dalam contoh di atas dipinjam untuk arti “kekuasaan”, padahal semula kata kursi dipakai untuk “tempat duduk”. Antara “kekuasaan” dan “tempat duduk” memang mempunyai kaitan erat. Biasanya kekuasaan dijalankan dari “kursi” (tempat duduk) dan selalu disimbolkan dengan kursi singasana.
Dalam pandangan sejumlah ulama, majaz terbagi kepada majaz lughawi, majaz mursal dan majaz aqli. Misalnya, penggunaan majaz mursal dapat diamati dalam firman Allah berikut: sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS.4:10).
Kata al-nâr yang terdapat dalam ayat itu tidak mungkin diartikan secara hakiki, tetapi harus diartikan dengan makna majazi karena tidak mungkin manusia makan api. Sesungguhnya manusia hanya makan makanan. Oleh sebab itu, kata al-nâr dalam ayat itu dialihkan artinya kepada makanan yang haram. Dengan demikian, ayat ini menegaskan larangan memakan makanan yang haram yang diantaranya melalui mengambil harta anak yatim.
Sedangkan takwil secara bahasa mengandung pengertian “rujuk” yang berarti kembali. Kata takwil dengan pengertian ini dapat ditemukan dalam Qur’an. Disamping itu, dalam Qur’an kata takwil dapat pula berarti tafsir atau penjelasan (bayan).
Dalam mendefinikan takwil secara istilah ada sejumlah pendapat ulama, tetapi maksudnya saling berdekatan dan saling mendukung. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan takwil adalah mengeluarkan lafal dari lahir maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu (Zahrah, 1953:135).
Dari definisi takwil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takwil ialah: memalingkan lafal dari arti lahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil.
Pada prinsipnya setiap lafal mesti dipahami menurut lahirnya. Namun, dalam keadaan tertentu, tidak mungkin memahami suatu lafal berdasarkan lahirnya. Dalam keadaan seperti inilah ada peluang menggunakan takwil bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kajian ushul fiqh..
Apabila ketiga istilah ini dihubungkan kepada penjelasan tentang ayat-ayat qath’i dan zanni yang telah diuraikan sebelumnya, agaknya ayat-ayat qath’i selalu menggunakan makna hakikat, tidak menggunakan makna majazi sehingga tidak perlu ditakwilkan. Dalam contoh sebelumnya, bagian waris suami yang istrinya meninggal dan tidak mempunyai anak mendapat setengah, bagi pelaku zina didera seratus kali dera dan puasa tiga hari untuk membayar kaffarat pelanggaran sumpah merupakan bilangan yang dipahami dengan makna hakikat bukan majaz dan tidak perlu dilakukan takwil terhadapnya.
Berbeda halnya dengan ayat-ayat zanni yang mengandung kebolehjadian berupa makna majazi sehingga untuk memahami maknanya perlu ditakwilkan, seperti pengertian kata al-nâr (api), bagi orang yang memakan harta anak yatim disamakan dengan orang yang memakan api kedalam perutnya, padahal manusia tidak ada yang memakan api. Oleh sebab itu, ditakwilkan pengertian api yang terdapat dalam surat al-Nisa’ ayat 10 sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya untuk larangan memakan makanan yang haram.
KESIMPULAN
Adanya ayat-ayat qathi’i dan zanni dalam al-Qur’an merupakan ciri al-Qur’an dalam menjelaskan ahkam. Atas dasar ini, yang menjadi pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi’at ayat itu sendiri. Dalam hal ini, Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qathi’i dan yang lain zanni.
Dengan menggunakan paradigma “suatu lafal yang tidak mengandung kebolehjadian makna lain dengan dukungan sejumlah dalil”, maka banyak ayat-ayat qath’i dalam al-Qur’an, meskipun tidak sebanyak ayat zanni. Ayat-ayat qath’i ini hanya mengandung makna tunggal dan dari sisi ajaran yang dikandungnya merupakan pokok-pokok ajaran agama yang bersifat tetap (al-tsawabith) sehingga tidak berpeluang ditakwil dan dirubah.
Meskipun lafal suatu ayat qathi’i, tetapi maknanya mungkin saja zanni sehingga maknanya bisa dikembangkan, bukan dimaksudkan untuk menggeser pengertiannya. Metode mengembangkannya melalui qiyas, seperti mengqiyaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman dan makanan lain yang memiliki illat sama..
Ayat-ayat zanni adalah ayat-ayat yang lafalnya mengandung kebolehjadian beberapa makna sehingga menjadi ruang lingkup ijtihad menentukan makna mana yang dimaksudkan ayat itu. Ayat-ayat zanni banyak berkaitan dengan bidang muamalat. Melalui ijtihad menggunakan metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, istislah memungkinkan ayat-ayat zanni dikembangkan substansinya.
Kamis, 22 Januari 2009
Qathi dan Zanni dalam al-Qur'an
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























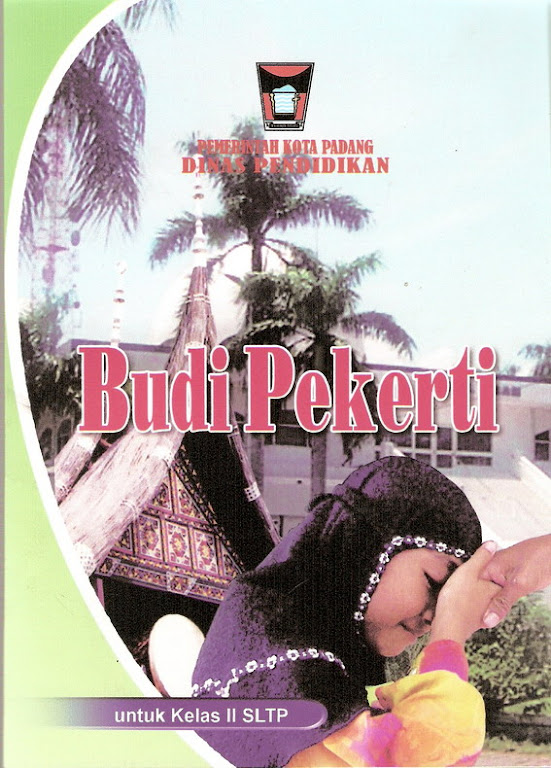





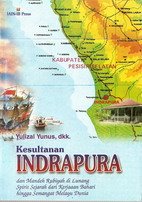




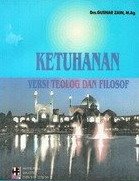
















Hatur Terima Kasih Ustadz, saya lagi mencari Definisi Qath'i dan Zanni...Barli, SE, M.Ag.
BalasHapus