Oleh : Muhammad Ilham Padang Ekspress, 21 Januari 2008. Euforia kemenangan Obama telah sampai pada klimaksnya. Tanggal 20 Januari 2008, pria yang ber-ayahkan Kenya ini dilantik. George W. Bush mengakhiri kekuasaannya dengan peristiwa tragis : “Cara baik melemparkan sepatu”. Jelang tanggal 20 Januari, PM Israel Ehud Olmert dan Presiden Shimon Peres menarik pasukan dari Jalur Gaza. Bentuk penghormatan buat saudara tuanya Amerika Serikat, apresiasi jelang pelantikan Obama.
Padang Ekspress, 21 Januari 2008. Euforia kemenangan Obama telah sampai pada klimaksnya. Tanggal 20 Januari 2008, pria yang ber-ayahkan Kenya ini dilantik. George W. Bush mengakhiri kekuasaannya dengan peristiwa tragis : “Cara baik melemparkan sepatu”. Jelang tanggal 20 Januari, PM Israel Ehud Olmert dan Presiden Shimon Peres menarik pasukan dari Jalur Gaza. Bentuk penghormatan buat saudara tuanya Amerika Serikat, apresiasi jelang pelantikan Obama.
Ban-Ki Moon, diplomat Korea yang Sekjen PBB, rasanya mungkin “tertampar”. Setengah frustrasi, sejak Israel membombardir Jalur Gaza, Ban-Ki Moon setengah menghamba-berharap agar tentara Israel mundur. Lebih 1000 orang Palestina tewas, Ban-Ki Moon tak mampu menghentikan tragedi ini. Pelantikan Obama-lah yang justru mengakhiri “sementara” penderitaan rakyat Palestina. Dalam logika sederhana, Amerika Serikat-lah yang merestui secara total penyerbuan Israel ke Jalur Gaza.
Dunia berharap banyak pada Obama. Barangkali memang yang bisa “menghentikan” Israel adalah saudara tuanya Amerika Serikat, dan power itu hanya terdapat pada Obama. Bisakah kita berharap pada Presiden Amerika Serikat yang pernah “singgah sementara” di Indonesia ini? Bagaimakah track record pro-Israel pria kulit hitam yang telah meruntuhkan mitos W-A-S-P, bahwa Presiden Amerika Serikat haruslah White-Anglo Saxon and Protestant ini? Pada Obama yang bernama tengah Hussein ini, hanya terdapat satu, Protestant. Ia bukan putih tapi hitam, walaupun unsur white ada padanya karena kontribusi sang ibu, tapi tetap “darah” Kenya ayahnya lebih dominan. Obama juga bukan “trah” Anglo-Saxon – keturunan British yang dalam sejarah dimaknai sebagai komunitas “pencari dunia baru”.
Saya ingat, pada waktu inaugurasi kemenangannya, Obama berpidato secara elegan dengan bahasa tertata rapi, sebuah kelebihan yang pantas untuk ditiru. Pidato yang disiarkan secara lengkap oleh salah satu TV swasta Indonesia ini, Obama berdiri dengan gagah di atas podium. Di depan podium itu, tertera 4 (empat) huruf kapital besar – AIPAC. Seketika, saya ingat buku karangan Paul Findley yang telah diterjemahkan oleh Penerbit Mizan “Mereka Berani Bicara”. Dalam buku ini, Findley mengupas-tuntas pertanyaan : “Mengapa lobi Yahudi-Israel begitu kuat dalam ranah politik Amerika Serikat pasca Perang Dunia ke-2?”.
Findley mengatakan bahwa politik negeri Paman Sam ini tidak bisa berkata “tidak” pada Yahudi-Israel karena sebuah organisasi-publik kemitraan bernama AIPAC (American Israel Public Agency Council). Dalam AIPAC ini berkumpul para ekonom-pialang, politisi dan intelektual Amerika Serikat keturunan Yahudi. Mereka inilah yang dominan mempengaruhi politik Amerika Serikat, mulai dari “pengkondisian calon-calon Presiden hingga kebijakan politik luar negeri. AIPAC kata Findley, adalah bentuk lain dari “Gedung Putih”. Pada tahun 2007, menurut Congressional Research Service, Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer pada Israel USD 30 milyar. Konon, AIPAC berperan besar atas bantuan yang spektakuler ini mensikapi pengaruh Iran yang semakin besar di Timur Tengah.
Pidato Obama di forum AIPAC menunjukkan kepada kita, Obama tak bisa melepaskan diri dari Yahudi-Israel. Penggalan pidatonya yang mengatakan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris dan kebijakan negara Israel harus didukung, memperjelas posisi politik Obama. “When I am the President, the United States will stand shoulder to shoulder with Israel …..”. Ketika masih menjadi senator, Obama memiliki voting record pro-Israel. Tahun 2006, beliau menjadi salah seorang sponsor the Palestian Anti Terorism Act yang dalam salah satu item-nya menempatkan Hezbollah sama dengan Al-Qaeda. True Friends of Israel pantas disandang Obama.
Lalu, pantaskah kita mempersalahkan Obama? Pantaskah kita berharap banyak pada Obama ke depan? Findley sebenarnya telah menjawab, bahwa siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat, pengaruh AIPAC sulit untuk dihindari. Penunjukkan Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri kabinet Obama memperjelas pengaruh lobi Yahudi yang luar biasa. Konon, Obama tidak sreg dengan Bill Clinton, suami Hillary. Clinton dan Hillary merupakan sahabat “politik” terdekat dari Benjamin Netanyahu – ultranasionalis Israel. Namun, hampir 1/3 anggota kabinet Obama adalah “kerabat politik” Bill Clinton.
Kecil kemungkinan persoalan Palestina bisa terselesaikan dengan baik pada era Obama ke depan. Sangat tidak mungkin Obama melawan arus “pakem” kebijakan politik standar Amerika Serikat, apalagi Obama nyata-nyata telah mendukung Israel sebelum ia jadi Presiden. Persoalan Palestina-Israel, lebih memungkinkan hanya bisa diselesaikan oleh komunitas Timur Tengah, khususnya negara-negara Islam Teluk. Kita tak bisa berharap banyak pada PBB, demikian juga dengan Amerika Serikat, siapapun presidennya. Dalam ilmu politik, antara Israel dan Palestina telah terjadi cyrcle bargaining, siklus tawar-menawar. Siapa yang menunggangi dan ditunggangi, tidak jelas secara konkrit. Apakah Israel yang menunggangi Amerika Serikat atau sebaliknya. Namun yang jelas, hubungan Amerika Serikat dan Israel adalah hubungan simbiosis mutualis, saling menguntungkan. Oleh karena itu, kemauan politik negara-negara teluk-lah yang lebih rasional dan memungkinkan.
Apakah bisa hal ini terjadi? Ingat, negara teluk pernah memiliki seorang Raja zuhud-bertalenta pemimpin. Raja Faisal namanya, kakak dari Raja Abdullah – penguasa kerajaan Saudi Arabia sekarang. Pada masa beliau menjadi raja Saudi Arabia, karengkang-nya Israel dan hipokritnya Amerika Serikat bisa ditaklukannya. Sejarah mencatat, raja Faisal menjadi “pilar terdepan “Politik Minyak”. Dengan kekuatan cadangan 2/3 minyak dunia berada di Saudi Arabia, raja Faisal menghentikan ekspor minyak ke negara-negara sekutu Israel, khususnya Amerika Serikat.
Sebagai negara yang berbasiskan industri, tentu AS menjadi kalimpasingan. Politik minyak ini akhirnya membuat Israel melunak, dengan tentunya akibat tekanan AS. Perjanjian Camp David antara Anwar Sadat (Presiden Mesir) dan Menachen Begin (PM Israel) kala itu, ditandatangani yang difasilitasi oleh Jimmy Carter. Timur Tengah sedikit melunak. Tapi sayang, Politik Minyak ini akhirnya tidak berkelanjutan sampai sekarang seiring dengan tewasnya raja Faisal. Sejarah kemudian mencatat, para penguasa negara-negara teluk, terus berada dibawah “ketiak” Paman Sam (terkecuali Iran, Suriah dan sedikit Yordania).
Sejarah telah memberikan kepada kita pelajaran berarti. Negara-negara Islam di Timur Tengah pada prinsipnya memiliki “daya tawar” politik potensial dalam menyelamatkan masa depan Palestina. Tapi apa yang terjadi ? Raja Abdullah dari Saudi Arabia membisu, Klan Al-Nahayan dari UEA diam, Klan Al-Sabah tak ambil pusing, Qabus dari Oman tak bersuara. Rakyat Irak sibuk dengan “penyakit mereka”, bahkan Husni Mubarrak dari Mesir justru menutup perbatasan Mesir-Jalur Gaza. Mungkin hanya Ahmadinedjad dan rakyat Iran yang lantang. Seandainya, raja Faisal dan Gamal Abdeel Nasser masih hidup, mungkin Palestina tidak seperti ini. Know your enemy, kata Sun Tzu dalam Kitab Perangnya The Art of War.
Dan yang bisa menyembuhkan Palestina hanyalah kemauan politik negara-negara Islam Timur Tengah. Obama akan terus berjalan dengan garis politik yang tidak bisa dihindarinya, walaupun ada kata-kata Hussein dalam penggalan namanya. Dan Syeikh Mansor Zayed al-Nahayan (adik dari Sultan Uni Emirat Arab) akan terus “mengejar” Kaka dari AC. Milan untuk bermain di klub yang baru dibelinya, Manchester City. Harganya, hampir 2 trilyun, di tengah-tengah kondisi pengungsi Palestina butuh bantuan. Padahal, jarak negara Syekh yang kaya-flamboyan ini hanya sejauh mata memandang dengan Palestina.
Rabu, 21 Januari 2009
Euforia Obama
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























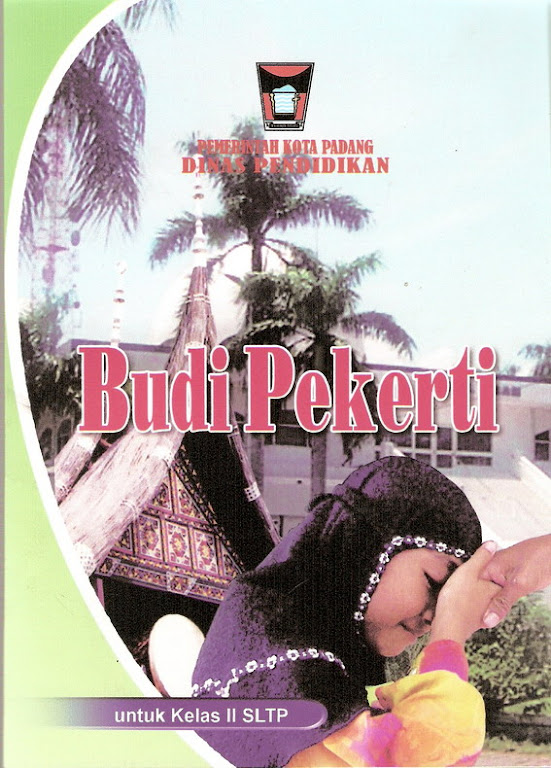





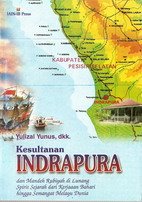




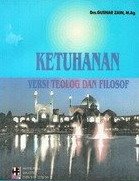
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar