Oleh : Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd
 Self esteem is a realization about how big a value given to oneself. As the value which is clued to one’s personality, it is common if Minangkabau community known as very respectful to cultural values always refers to the values of Minangkabau cultural philosophy in giving opinions, showing attitudes and doing actions. On the other hand, a wrong interpretation about the meaning of self esteem often occurs. This is because self esteem is often similarized as prestige which is manifestated in Minangkabau social reality nowadays.
Self esteem is a realization about how big a value given to oneself. As the value which is clued to one’s personality, it is common if Minangkabau community known as very respectful to cultural values always refers to the values of Minangkabau cultural philosophy in giving opinions, showing attitudes and doing actions. On the other hand, a wrong interpretation about the meaning of self esteem often occurs. This is because self esteem is often similarized as prestige which is manifestated in Minangkabau social reality nowadays.A. PENDAHULUAN
"Demi harga diri, apapun akan kulakukan". Statemen seperti itu sering didengar, sering diungkapkan, sering dipajang, bahkan sering dijadikan slogan oleh hampir setiap insan, baik dari kalangan intelektual maupun nonintelektual. Seolah-olah, harga diri memang segalanya bagi manusia dan tiada yang lebih berharga dari apa yang disebut dengan harga diri.
Diskursus dewasa ini sering menampilkan persoalan harga diri. Akan tetapi, pengemasannya sangat bervariasi, seperti: sastrawan menuangkan masalah harga diri melalui dialognya; seniman mengukir harga diri melalui karyanya; dan budayawan mengemas persoalan harga diri dalam tulisannya. Media komunikasi juga ambil bahagian dalam ajang itu, seperti layar kaca RCTI yang menampilkan sinema yang bertajuk “Harga Diri”.
Harga diri hadir bersama individunya atau hadir bersama komunitasnya. Maksudnya, di satu sisi harga diri merupakan perwujudan dari sosok pribadi, namun di sisi lain, harga diri tampil sebagai sosok dari kelompok sosialnya (keluarga atau masyarakatnya). Hal ini mengindikasikan bahwa harga diri merupakan cerminan dari ciri individual dan sekaligus ciri sosial.
Jika ditelusuri masa lalu, ternyata sejarah mencatat bahwa pada umumnya komunitas Minangkabau merupakan komunitas yang paling mengutamakan harga diri. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai falsafah Minangkabau yang banyak terkait dengan persoalan harga diri. Maksudnya, ketika berbicara tentang manusia dan individu, maka dalam ajaran falsafahnya, selalu dikaitkan dengan harga diri: malu, raso jo pareso, dll. Kesemuanya itu tetap me-referent kepada harga diri.
Sehubungan dengan itu, adalah suatu hal yang lumrah jika fenomena yang terjadi di lingkungan kita, terutama masyarakat Minangkabau, melulu mengapungkan persoalan harga diri. Sekolah merupakan harga diri; sarjana harga diri; bekerja adalah harga diri; berprestasi juga harga diri; pakaian dan penampilan juga harga diri; begitu juga jabatan dan kekayaan; ya, semua harga diri. Hampir setiap aspek kehidupan adalah harga diri. Dapat dikatakan, bahwa tak ada satupun celah kehidupan yang menanggalkan harga diri.
Akan tetapi, banyak di antara kita yang salah menempatkan dan memaknai konsep "harga diri". Dalam komunitas sosial, sering ditemukan pemakaian istilah harga diri yang salah kaprah. Dalam realitas hidup bermasyarakat, sering ditemukan penggunaan harga diri untuk makna yang lain. Pemakaian yang seperti itu dapat dilihat dari contoh berikut.
1. Slogan "Demi harga diri" dalam konteks-konteks tertentu bermakna demi kepentingan diri.
2. Pernyataan " Sepertinya aku tak punya harga diri" dalam konteks yang berbeda dapat dimaknai sebagai Sepertinya aku tidak dihormati lagi.
3. Perkataan "Kemana kamu tarok harga dirimu?" dapat diinterpretasikan dengan Kemana kamu hadapkan mukamu?
Contoh di atas memberikan gambaran bahwa jika dicermati kehidupan berbahasa masyarakat kita, ungkapan harga diri sering digunakan untuk makna yang lain, meskipun sebenarnya kata, istilah, atau ungkapan tersebut bukanlah bersinonim. Untuk itu, sebelum berbicara tentang realitas yang terkait dengan harga diri dalam konteks sosiokultural Minangkabau, perlu dikemukakan konsep yang jelas dan tegas tentang harga diri.
Berbicara tentang makna, pemahaman, atau interpretasi terhadap harga diri, berarti berbicara tentang konsep harga diri. Pembicaraan itu tidak akan terlepas dari kajian linguistis dan paradigma pemakai konsep tersebut. Dalam tulisan ini, konsep harga diri lebih diwarnai oleh nilai-nilai filosofis budaya Minangkabau.
B. HARGA DIRI DALAM FILOSOFIS BUDAYA MINANGKABAU
Harga diri merupakan sesuatu yang dibentuk dan dilahirkan oleh setiap individu terhadap dirinya sendiri. Kata sesuatu mengacu kepada nilai-nilai yang dilengketkan oleh setiap individu terhadap dirinya yang terwujud melalui sikap dan tingkah lakunya, baik tingkah laku verbal maupun tingkah laku nonverbal. Pengertian seperti itu juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:340), bahwa "harga diri ialah kesadaran akan betapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri."
Navis (1986: 65-66) memaparkan bagaimana nilai penting harga diri dalam tataran masyarakat Minangkabau sebagai berikut:
Merasa diri kurang berharga merupakan kesia-siaan. Merasa diri lebih berharga merupakan kegilaan. Akan tetapi, harga diri yang jatuh merupakan hal yang memalukan. Tingkah laku yang merupakan aib bukan hanya menurut ukuran moral dan etik yang umum, juga meletakkan harga diri lebih rendah dari orang lain yang berada di luar lingkungan dan kerabat sendiri merupakan keaiban yang tidak dapat dimaafkan. Keaiban yang demikian akan menampar semua kaum kerabat secara etnis atau lingkungan.
Mencermati apa yang diutarakan Navis di atas, secara ekstrim dapat diperikan bahwa setiap individu yang merasa dirinya orang Minangkabau sudah selayaknya menjaga, mempertahankan, dan menjunjung tinggi harga dirinya. Sebaliknya, bagi individu yang tidak mampu untuk menjaga harga diri sesuai dengan posisinya, apalagi menjatuhkan harga diri tidak layak untuk diklasifikasikan kepada komunitas masyarakat Minangkabau.
Pemahaman di atas senada dengan pengertian yang didasarkan atas tinjauan linguistis terhadap istilah harga diri. Sebagai istilah, harga diri dapat mengacu kepada kata martabat yang berarti tingkat harkat kemanusiaan seseorang, bahkan dalam konteks yang lebih global, kata martabat sinonim dengan kata harga diri. Kedua istilah tersebut (harga diri dan martabat) secara implisit mengisyaratkan bahwa tingkat kemanusiaan dari setiap manusia atau undividu ditentukan oleh harga diri manusia itu sendiri. Dengan formulasi lain, manusia tidak dapat dikatakan manusia jika manusia itu sendiri tidak memiliki dan menjaga harga dirinya.
Konsep harga diri yang demikian pada prinsipnya dapat dipahami secara sempit maupun secara luas berdasarkan ruang lingkup pemaknaannya. Pemahaman secara sempit dimaksudkan sebagai pemaknaan yang bersifat individual, sedangkan pemahaman secara luas diartikan sebagai pemaknaan yang bersifat sosial. Hal ini sejalan dengan hakekat manusia, yakni manusia merupakan makhluk sosial, di samping sebagai makhluk zoonpolitikon. Manusia tidak akan dapat hidup sendiri, melainkan manusia hidup secara berkelompok atau bermasyarakat.
Secara sempit, harga diri dipahami sebagai nilai yang ikut mengembel-embeli sikap dan perilaku seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa setiap individu memiliki harga diri. Yang membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya adalah taraf atau derajat harga dirinya. Taraf dan derajat harga diri itu sangat tergantung dengan paradigma individu itu sendiri. Barangkali, individu yang satu merasa memiliki harga diri kalau memiliki jabatan, harta, dan dapat menaklukkan orang lain dalam konteks yang beraneka ragam. Individu yang lain mungkin merasa memiliki harga diri kalau dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya meskipun tidak memiliki jabatan dan harta. Dalam konteks ini, harga diri identik dengan sosok individu tersebut.
Secara implisit, konsep seperti di atas memperlihatkan bahwa harga diri didukung oleh ego yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Oleh sebab itu, harga diri yang merupakan profil pribadi bersifat relatif. Konsep seperti ini banyak dianut oleh kaum oportunis. Orang-orang dalam kelompok inilah yang sering mengkambinghitamkan harga diri sebagai alasan untuk bertindak atau bersikap.
Secara luas, harga diri dapat dipahami sebagai nilai yang melengket kepada kemanusiaan diri seseorang dan terealisasikan melalui sikap dan perilakunya, baik secara eksplisit maupun implisit, dengan menggunakan moral, etika, dan agama sebagai standar penilaian. Pemaknaan seperti ini berlaku secara universal, di mana manusia hidup dalam sebuah komunitas yang terikat pada sistem-sistem tertentu, apakah sistem sosial, sistem budaya, atau sistem agama. Konsep ini mengindikasikasikan bahwa taraf atau derajat harga diri seseorang tidak tergantung kepada paradigma individu yang bersangkutan, melainkan tergantung kepada penilaian komunitasnya berdasarkan standar atau tolok ukur yang berlaku secara positif bagi komunitas secara komprehensif.
Hal itu disebabkan oleh setiap komunitas menganut sistem yang berbeda. Sistem yang berbeda akan menghasilkan kriteria-kriteria yang berbeda. Masyarakat Minangkabau, misalnya, menganut sistem yang berbeda dengan masyarakat Batak, berbeda pula dengan sistem masyarakat Betawi, dsb. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki culture yang berbeda akan menganut nilai-nilai yang berbeda.. Perbedaan itu juga memberikan corak yang berbeda terhadap standar penilaian harga diri.
Harga diri sebagai nilai yang melekat pada kemanusian diri seseorang tidak terlepas dari kepribadian yang dimiliki dan ditampilkannya. Bagi masyarakat Minangkabau, standar penilaian harga diri kaumnya itu didasarkan kepada nilai-nilai luhur yang tercantum dalam pedoman falsafah Minangkabau.
Terkait dengan konsep penilaian kemanusiaan itu, pedoman falsafah Minangkabau memberikan tiga timbangan pokok bagi penilaian manusia, yaitu samo, raso, dan malu. Setiap manusia memiliki tanggapan dan penghayatan yang berbeda karena pada hakikatnya manusia tidaklah sama. Ada manusia yang yang mampu menghayati ketiganya; ada yang hanya mampu menghayati dua atau satu diantara ketiganya. Dari sisi inilah, ajaran falsafah Minangkabau seperti yang dituangkan (Navis, 1986: 95), manusia dapat dikategorikan kepada empat ragam seperti berikut.
1. Orang, yaitu orang normal yang merasakan baik dan buruk, yang tinggi dan yang rendah, dan merasa malu kalau tidak dapat sama dengan orang lain.
2. Takah orang, yaitu orang yang tampaknya seperti orang yang normal, tetapi tidak memiliki sikap.
3. Angkuh orang, yaitu orang yang berlagak tahu seperti orang, tetapi sebenarnya ia tidak memahami apa yang dipahami orang, dan orang yang seperti ini tidak memiliki malu.
4. Orang-orang, yaitu orang yang tidak dapat bergerak sendiri yang senantiasa memerlukan orang lain.
Apabila konsep harga diri dikaitkan dengan empat ragam manusia yang dikategorikan berdasarkan falsafah Minangkabau di atas, maka secara tegas dapat dikemukakan bahwa hanya ragam manusia pertamalah yang layak untuk disebut sebagai manusia yang memiliki harga diri. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hanya oranglah --manusia yang bisa merasakan baik dan buruk, bisa merasakan yang tinggi dan yang rendah, dan merasa malu apabila tidak bisa sama dengan orang lain-- yang memiliki harga diri, sedangkan ragam manusia takah orang dan angkuh orang tidak memiliki harga diri, apalagi ragam manusia orang-orang.
Sebelum mencermati fenomena yang ada di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, atau lingkungan masyarakat (Minangkabau), alangkah lebih baiknya dipertanyakan pada level ragam manusia manakah saya berada ? Pantaskah saya selalu mengemukakan harga diri sebagai alasan, menggunakan harga diri sebagai slogan, atau merasa memiliki harga diri ? Yang tahu dengan pasti jawabannya hanya diri kita sendiri; bukan orang lain. Akan tetapi, gunakanlah norma-norma sosial, norma-norma budaya, dan norma-norma agama sebagai standar pengklsifikasian itu. Tidak ada cara yang lebih bijak dalam hal ini, kecuali intropeksi diri.
C. FENOMENA HARGA DIRI DALAM KOMUNITAS MINANGKABAU
Merujuk kepada uraian di atas, pada umumnya, komunitas Minangkabau merupakan komunitas yang paling mengutamakan harga diri. Pernyataan ini dapat dipahami melalui nilai-nilai falsafah budaya masyarakat Minangkabau yang banyak mengemukakan persoalan yang terkait dengan harga diri. Realitas pun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau men-canel-kan persoalan harga diri dengan aktivitas yang dilakukannya. Mulai dari persoalan makanan, pakaian, penampilan, pendidikan, sampai pekerjaan dan jabatan, selalu dikaitkan dengan harga diri. Hampir dapat dipastikan bahwa masyarakat Minangkabau mengaku selalu mengutamakan dan menjaga harga diri pada setiap lini kehidupan.
Semua itu merupakan suatu kebenaran yang memang perlu dibiasakan, apalagi oleh komunitas Minangkabau yang notabene diposisikan sebagai masyarakat yang mengagung-agungkan nilai moral, baik yang bersumber dari ajaran adat-istiadat maupun yang bersumber dari ajaran agama. Hal ini sejalan dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah; syarak mangato adat mamakai. Konsep inilah yang menjadi landasan berakhlak bagi masyarakat Minangkabau.
Ungkapan "Jaga harga dirimu" sering diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya, mamak kepada keponakannya, kakak kepada adiknya, dan suami kepada istrinya. Ungkapan itu seringkali digunakan untuk menegur seseorang yang berperilaku menyimpang, di samping digunakan sebagai upaya yang bersifat preventif dalam rangka menasehati seseorang agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama dalam berperilaku, sehingga seseorang (anak, ponakan, adik, dan istri) tersebut memiliki akhlak yang mulia.
Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak di antara kita yang salah menempatkan dan memaknai konsep "harga diri". Akibatnya, sering kali "harga diri" terkontaminasi oleh kepentingan diri, bahkan, seolah-olah harga diri identik dengan gengsi yang harus ditempatkan pada posisi tertinggi. Kerancuan cara pandang yang demikian dapat diidentifikasi melalui perilaku dan sikap masyarakat kita, baik dalam konteks individual maupun dalam konteks kelompok yang pada hakekatnya merupakan wujud dari kesalahan interpretasi terhadap konsep harga diri. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka kesalahan interpretasi itu pada hakekatnya terjadi akibat landasan aqidah tauhid yang seharusnya ditanamkan sejak usia dini.
Kesalahan interpretasi akan “harga diri” bukan merupakan sesuatu yang asing lagi, melainkan sudah merupakan bagian yang dianggap lumrah. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi yang salah terhadap "harga diri" tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat metropolis, melainkan juga terjadi di lingkungan masayarakat yang kaya dengan ajaran moral --seperti masyarakat Minangkabau.
Fenomena seperti itu dapat ditemukan di mana -mana, tanpa mengenal batas budaya, sosial, dan agama. Persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi sarapan bagi yang bertendensi sebagai pengamat sosial budaya . Bahkan , hal itu dijadikan sumber inspirasi bagi penuangan ide, sikap, dan ekspresi budayawan, sastrawan, seniman, ilmuwan, dan sejumlah wan-wan lainnya.
Penuangan ide yang dikemas dari realitas itu pun amat bervariasi, seperti sosok Gondo yang ditampilkan Emha (1992:86) dalam "Satu Truk Pasir" pada kumpulan cerpennya Yang Terhormat Nama Saya.
Hidup ini, haruslah penuh, gengsi. Sebab pada gengsilah terletak harga diri Dan tanpa harga diri, apa gerangan yang bisa dihadirkan oleh seseorang di tengah teman-teman, para tetangga, dan relasi-relasi?…
Gondo, dengan istri dan empat putra-putrinya, memang hanya seorang supir truk. Tapi gengsi sama sekali tak ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat profesi seseorang. Melainkan tergantung kepada kemampuannya menghadirkan harga diri, memberi kesan, dan mengolah arti profesinya itu bagi penampilan harga dirinya…Yang penting seseorang itu jangan sampai bodoh dalam meletakkan harga diri.
Pada fragmen cerpen di atas, Cak Nun melukiskan Gondo yang gila hormat. Kegilaan Gondo dibangun Cak nun melalui kontradiksi perwatakan dari tokoh pratagonis yang di satu sisi tahu akan ketidakberdayaan dan di sisi lain memiliki ambisi yang besar untuk bisa hidup bergengsi meskipun pada hakekatnya si tokoh tidak memiliki modal yang mapan. Di akhir cerita, si Gondo harus membayar mahal harga dirinya karena ternyata gengsi tidak membawa harga dirinya ke level yang lebih tinggi, melainkan menghadirkan malapetapaka dalam kehidupan keluarganya. Penokohan yang seperti itu dapat dipahami sebagai centilan Cak Nun terhadap model kehidupan yang memposisikan harga diri setaraf dengan gengsi. Artinya, harga diri dibangun dengan nilai-nilai emosional-individual, yaitu dibangun dengan menghadirkan kesan atau dengan memoles penampilan di antara teman-teman, keluarga atau relasi.
Apakah fenomena seperti yang dimunculkan Cak Nun di atas dapat ditemukan di lingkungan masyarakat Minangkabau? Kalau pun tidak persis sama dengan realitas yang diangkat Cak Nun, setidaknya realitas yang cenderung mengarah ke sana bisa ditemukan , untuk tidak menyebutnya banyak.
Barangkali realitas di atas belum bisa dijadikan contoh konkret dari kesalahan cara pandang seseorang terhadap harga diri karena Cak Nun mengemas realitas dengan dibumbui kemampuan imajinasinya. Untuk itu, pada kesempatan ini akan ditampilkan sebuah fakta sebagai sebuah model kesalahan interpretasi terhadap konsep harga diri.
Sebutlah namanya Hz (bukan inisial sebenarnya); seorang sarjana ; putra asli Minangkabau; tokoh adat di daerahnya sehingga dia memperoleh gelar datuk; taat beragama; punya jabatan yang lumayan. Ia memiliki persoalan harga diri yang menurut perspektifnya lumayan pelik. Dalam keluarga, ia merasa kurang berperan karena tidak memiliki kelebihan yang dapat dihandalkan. Hz tak pernah dimintai pendapat dalam mengambil keputusan dan tidak pernah dilayani hanya karena penghasilannya yang lebih kecil dibanding anggota keluarganya. Perilaku anggota keluarganya yang seperti itu menyebabkan ia merasa tidak dihargai dan lari dari keluarganya. Di sisi lain, Hz malu jika ia tak bisa selevel dengan anggota keluarga yang lain. Jika yang lain memiliki mobil starlet dan HP, minimal ia harus punya volvo dan HP meskipun yang second dan sering rusak. Menurutnya yang penting penampilan karena semua terkait dengan harga diri.
Fakta di atas memperlihatkan bahwa kesalahan interpretasi dalam memaknai “harga diri” tidak hanya terjadi di kalangan awam, melainkan juga terjadi di kalangan intelektual, tokoh adat, dan kalangan lainnya. Realitas ini mengindikasikan bahwa penerjemahan konsep harga diri sangatlah beragam. Keberagaman itu terjadi akibat perbedaan background di berbagai bidang, baik lingkungan, pendidikan, pekerjaan, maupun pengalaman.
Jika dicermati kasus si Hz di atas, sebenarnya Hz amat memahami makna harga diri; hanya saja Hz mengungkung diri dalam konstelasi cara pandangnya sendiri. Pada suatu ketika, Hz mengungkapkan bahwa pengetahuannya amat terbatas karena ia tidak suka membaca walau ia menyadari buku adalah jendela dunia. “Akan tetapi, membuka konstelasi pengetahuan bukan hanya lewat membaca apa yang tertulis, hal-hal yang tidak tertulis pun bisa dibaca,” sela temannya. Hz menuturkan bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk itu karena alasan kesibukan di kantor. Hz memang memiliki beribu alasan untuk mempertahankan pandangannya. Akibatnya, ia merasa tidak dihargai dan mencoba menghadirkan kesan sebagai sosok yang mampu menyaingi, bahkan berusaha untuk bisa berpenampilan lebih. Pada hal, segala sesuatunya akan harmonis jika yang satu belajar memahami yang lainnya sehinga yang satu menghargai yang lainnya.
Secara teoretis, Hz mengetahui bahwa untuk dihargai oleh orang lain, perlu menghargai orang lain. Akan tetapi, pada tataran praktis Hz mengungkung diri di bawah tempurung keegoannya sehingga tidak pernah menyempatkan diri untuk mengetahui bias dari perilakunya terhadap orang lain. Ia tidak pernah berfikir bahwa apa yang diterimanya merupakan bias dari perilakunya. Sebaliknya, ia malah berfikir bahwa semua terjadi karena kelemahan dalam menghadirkan “siapa dia’.Di dalam dirinya, telah tertanam konsep “harga diri” yang salah, yakni harga diri identik dengan gengsi dan taraf ekonomi.
Di satu sisi, ada benarnya ide Hz. Memang segala persoalan selalu bermuara kepada harga diri. Pada dasarnya setiap orang memiliki konsep harga diri. Beragamnya realitas yang dilalui setiap individu tidak lebih dari sekedar gambaran yang nyata dari konsep harga diri yang dianutnya. Hal ini boleh-boleh saja.
Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melepaskan diri dari komunitasnya, dan untuk bisa hidup dalam komunitasnya manusia perlu berinteraksi dan berintegrasi. Interaksi dan integrasi sosial itu hanya dapat dilakukan dengan cara memposisikan diri sebagai bagian yang integral dari habitat setempat . Artinya, ketika manusia menjadi bahagian dari masyarakat, manusia mau-tidak mau atau suka-tidaksuka, harus membuka konstelasi keindividuannya.
Sehubungan dengan itu, setiap individu perlu menata dirinya dengan mengeksiskan harga dirinya. Untuk bisa kembali kepada fitrah kemanusiaannya, tidak ada upaya lain selain dari mengontrol diri dengan nilai-nilai moral. “Segalanya punya moral”, seperti yang dikatakan Elice dalam petualangannya di negeri ajaib, “Asalkan kau mampu menemukannya”, ( Suria Sumantri, 1996:236). Artinya, setiap orang harus membangun harga dirinya dengan bersandarkan kepada ajaran moral (budaya) dan agama. Akan tetapi, ketika seseorang terlalu berambisi untuk membebaskan diri dari nilai-nilai tersebut, ketika itu juga orang yang bersangkutan harus siap memiliki harga diri semu, yang notabene ke-universalitas-annya sangat rendah dan bahkan, sampai ke titik nol.
Nilai estetika ada dimana-mana yang dapat berfungsi sebagai media penghalus budi pekerti di samping berperan sebagai ekspresi yang memperkaya batin. ‘Selalu terdapat ladang moral yang subur’, kata Gilbert Chesterton. Semua tergantung manusianya.
Jika dikaitkan dengan ajaran moral, maka dapat diketahui bahwa ada suatu mustika hidup yang berharga terkandung dalam ajaran adat Minangkabau. Mustika hidup itulah yang memberikan arah yang baik dalam kehidupan manusia untuk mencapai segala tujuan yang baik, dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat, demi tercapainya kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan bathin yang diridhoi oleh Allah. Mustika berharga yang terkandung dalam adat Minangkabau itu ialah ajaran budi pekerti yang luhur.
Budi pekerti yang baik itu dimanifestasikan melalui raso, pariso, malu, dan sopan. Raso ialah setiap yang dirasakan oleh indera yang lima. Pariso merupakan yang dirasakan oleh hati manusia. Malu adalah suatu sifat yang menjadi tanggungan bagi hati setiap manusia, sedangkan sopan yaitu tingkah laku, gerak-gerik dalam pergaulan sebagai cerminan kepbribadian, seperti makna yang terkandung dalam pepatah adat berikut.
Nan kuriak iyolah kundi,
nan merah iyolah sago,
nan baiak iyolah budi,
nan indah iyolah baso
Memakai raso jo pareso,
manaruah malu jo sopan
Pepatah adat di atas mengajarkan bahwa setiap gerak dan perilaku manusia, terutama masyarakat Minangkabau, harus dijiwai oleh budi pekerti yang baik. Seseorang dikatakan memiliki budi pekerti yang baik jika ia memiliki sifat raso, pareso, malu, dan sopan. Kalau keempat sifat tersebut telah hilang dari diri seseorang, maka jatuhlah martabatnya kepada martabat hewani (Hakimy, 1997: 37).
Martabat pada pengertian di atas mengacu kepada pengertian “harga diri” seperti pengertian yang dikemukakan pada bagian awal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga diri tidak terlepas dari nilai-nilai. Dalam formulasi lain, harga diri adalah bagian diri yang sarat dengan nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai keimanan, dan hanya orang-orang yang menghayati dan mengamalkan keempat sifat itulah yang memiliki harga diri; bukan orang yang mampu menghadirkan kesan dan membangun gengsi, seperti si Gondo dan Hz.
Justru itu, pendidikan merupakan key word yang dapat meluruskan persoalan tersebut mengingat kepribadian merupakan maifestasi dari nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan. Pendidikan yang paling dominan mempengaruhi kepribadian individu itu ialah pendidikan informal, terutama pendidikan yang berasal dari keluarga. Hal ini disebabkan oleh keluarga merupakan wadah yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai sehingga pendidikan keluarga dijadikan acuan, contoh, dan model, di samping keluarga merupakan unit pendidikan yang memungkinkan anggotanya untuk berinteraksi secara optimal. Meskipun demikian, lingkungan sebagai komunitas yang sarat dengan nilai-nilai, seperti: nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral, tidak kalah berperan. Peran lingkungan terimplemantasi melalui corak kepribadian dari kelompok sosialnya.
Dinamika yang terjadi dalam suatu kelompok sosial memang berbeda-beda sesuai dengan background terbentuknya kelompok tersebut. Akan tetapi, keseluruhannya merupakan tempat proses internalisasi moralitas atau tingkah laku sehingga ia senantiasa meninggalkan pengaruh bagi anggotanya masing-masing.
Tentunya, implikasi tersebut meliputi implikasi positif dan implikasi negatif. Terlepas dari implikasi-implikasi yang ditimbulkannya, kelompok bagi manusia sangat urgen, karena dengan kelompok itu manusia dapat memperkecil keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan yang melekat pada masing-masing individu tidak sama, sehingga kebersamaan dapat saling melengkapi.
Dari diskursus ilmu-ilmu sosial yang berkembang dewasa ini, terlihat dengan jelas betapa pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan atau agent of change. Sebagai alat perubahan, pendidikan tidak semata-mata mengandalkan akses dan penggalian ilmu pengetahuan serta teknologi, melainkan juga menambah dan mengakumulasikan nilai-nilai yang mempengaruhi suatu masyarakat terhadap kemungkinan dan keinginan perubahan tersebut.
Sejalan dengan pernyataan di atas, sebagai makhluk sosial, seyogianya setiap individu membuka konstelasi pengetahuannya. Sinyalemen ini sesuai dengan kisah orang awam dengan filosof yang dikemukan Suriasumantri (1996:19) berikut.
Seorang awam bertanya kepada filosof yang arif bijaksana, “Coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya!”
Filosof itu menarik nafas panjang dan berpantun:
“Ada orang yang tahu di tahunya
Ada orang yang tahu di tidaktahunya
Ada orang yang tidaktahu di tahunya
Ada orang yang tidaktahu di tidaktahunya”
“Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar?” sambung orang awam itu.
Mudah saja, jawab filosof itu. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu!
Dialog filosof dan orang awam itu relevan dengan perkataan orang bijak Arab yang menyebutkan:
كن عالما أو متعلما أو سامعا ولا تكن رابعا
(Jadilah engkau sebagai orang yang berilmu, atau sebagai penuntut ilmu, atau sebagai pendengar dan janganlah engkau menjadi golongan yang keempat)
Kisah di atas mengisyaratkan bahwa keluar dari tempurung pengetahuan itu sangat penting untuk dilakukan, sedangkan untuk keluar dari tempurung pengetahuan itu seseorang perlu mengetahui apa yang diketahuinya dan apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, introspeksi dan kontrol adalah satu-satunya upaya yang terbaik dalam rangka merumuskan kerangka berfikir atau paradigma kita dalam memandang, menilai, dan memutuskan sesuatu, termasuk dalam memahami, memaknai, dan menghayati konsep harga diri.
D. PENUTUP
Harga diri merupakan bagian diri yang paling sensitif karena pembicaraan tentang harga diri tidak bisa dilepaskan dari persoalan moralitas yang merupakan manifestasi dari kepribadian seseorang. Pembentukan kepribadian itu banyak dipengaruhi oleh pendidikan, baik pendidikan informal maupun pendidikan formal. Pendidikan informal diperoleh melalui keluarga dan masyarakat, sedangkan pendidikan formal diperoleh melalui jenjang pendidikan.
Relevan dengan statemen tersebut, maka intropeksi dan kontrol merupakan manifestasi dari dua di antara empat sifat yang harus dimiliki masyarakat Minangkabau, yaitu raso jo pareso. Dengan Dua sifat itu akan menuntun seseorang memiliki dua sifat lainnya, yaitu: malu dan sopan. Keempat sifat itulah yang harus dijadikan acuan atau standar oleh masyarakat Minangkabau dalam berperilaku, menentukan sikap dan keputusan.
Mengingat moralitas amat terkait dengan proses pendidikan, maka seyogianya keempat sifat itu diperkenalkan, diajarkan, disosialisasikan, dibudidayakan, dan dilestarikan dalam setiap wadah yang berperan sebagai pendidik, terutama di lingkungan keluarga. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Minangkabau, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, memiliki perspektif yang tepat tentang harga diri.
Sosok pribadi adalah harga diri.
Oleh karena itu, harga diri
tidak dapat direnggut dan diinjak.
E. DAFTAR RUJUKAN
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Hakimy, Idrus,.Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Rosdakarya, 1997 a.
______, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau. Bandung: Rosdakarya, 1997 b.
Najib, Emha Ainun, Yang Terhormat Nama Saya,Yogyakarta: SIPRESS, 1992.
Navis, A.A., Alam Takambang Jadi Guru, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1986.
Piliang, Yasraf Amir, Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Era Millenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme, Bandung Mizan,1998.
_______, Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, Yogyakarta: Jala Sutra, 2004.
Suriasumantri, Yuyun S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

























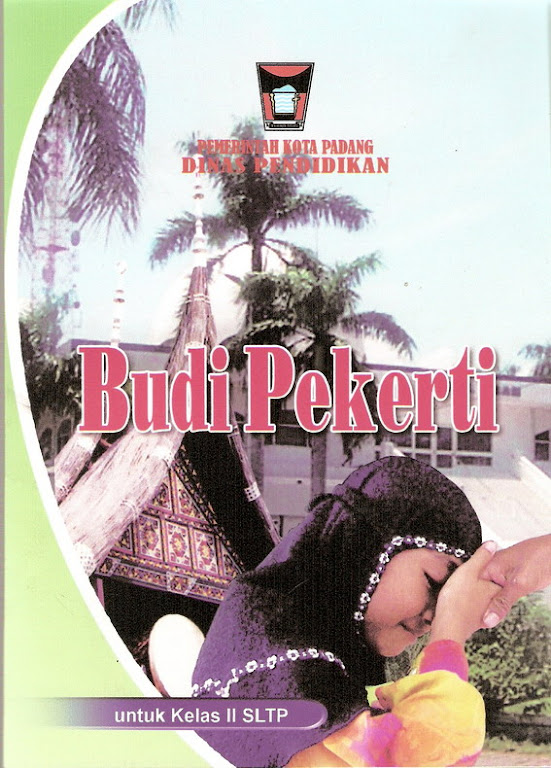





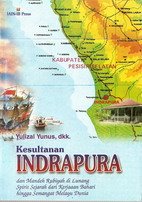




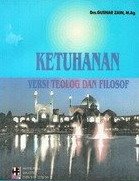
















Tulisan yang sangat membantu saya untuk menemukan konsep harga diri yang dibangun oleh masyarakat Minang. Mury-LABEL
BalasHapus