Oleh : DR. Firdaus, M.Ag Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur’an dan Sunnah (nash) dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.
Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur’an dan Sunnah (nash) dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.
Pendahuluan
Sejak dahulu sampai saat ini tidak ada ulama yang mengingkari akan penting peranan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam kajian ilmu syariah. Para ulama menghimpun sejumlah persoalan fiqh yang ditempatkan pada suatu al-qawaid al-fiqhiyyah. Apabila ada masalah fiqh yang dapat dijangkau oleh suatu kaidah fiqh, masalah fiqh itu ditempatkan di bawah kaidah fiqh tersebut.
Melalui al-qawaid al-fiqhiyyah atau kaidah fiqh yang bersifat umum memberikan peluang bagi orang yang melakukan studi terhadap fiqh untuk dapat menguasai fiqh dengan lebih mudah dan tidak memakan waktu relatif lama. Dengan menguasai al-qawaid al-fiqhiyyah secara baik tidak perlu dalam setiap persoalan merujuk kepada uraian yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh. Upaya merujuk terhadap kitab-kitab fiqh menjadi penting untuk menguasai seluk beluk suatu persoalan ketika memang dibutuhkan untuk mengetahui landasan filosofis dan rincian masalah agar pemahaman tentangnya menjadi komprehensif.
Meskipun demikian, yang menjadi persoalan apakah al-qawaid al-fiqhiyyah dapat dipakai sebagai dalil dalam mengistinbath hukum. Tulisan ini mencoba menjelaskan persoalan tersebut dengan berupaya mencari terobosan baru terhadap pendapat ulama yang pernah ada dalam memfungsikan al-qawaid fiqhiyyah dalam penetapan hukum.
Pengertian al-qawaid al-fiqhiyyah
Kata qawaid merupakan bentuk jama’ dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi. Kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qowa’id al-din yang berarti dasar atau asas agama. Qaidah dengan makna ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdo`a): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. 2: 127).
Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Ibrahim dan Ismail diberi amanah oleh Allah untuk meninggikan dan membina dasar-dasar (al-qawaid) atau pondasi baitullah.
Musthafâ Ahmad Zarqa’, dengan mengutip pendapat para ahli nahwu menegaskan bahwa qawaid secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya.
Sementara kata fiqh secara etimologi berasal dari kata fiqhan (فقها) yang merupakan masdar dari fi’il madhi faqiha (فقه) dan fi’il mudhori’nya yafqahu (يفقه), berarti paham. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata fiqh berarti paham mendalam untuk sampai kepadanya perlu mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh. Kedua arti fiqh ini dipakai para ulama dan masing-masingnya mempunyai alasan yang kuat. Kata fiqh dengan arti paham atau memahami didukung firman Allah surat Hud, 11:91.
Kata fiqh juga digunakan untuk menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu dengan baik secara lahir maupun batin. Makna ini sejalan dengan firman Allah berikut: “Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya.” (QS.6:65)
Kata fiqh yang berkembang di kalangan ulama secara khusus berarti paham secara mendalam. Orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh disebut faqîh. Kata faqaha atau yang seakar dengannya muncul dalam Qur’an sebanyak 20 kali yang sebagian besarnya mengacu kepada makna pemahaman mendalam.
Pada periode awal Islam, para ulama (kalangan sahabat dan tabi’in) memahami fiqh dengan pengetahuan atau pemahaman tentang agama Islam yang terdapat dalam Qur’an dan Hadis. Pada masa selanjutnya, para ulama memahami fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah. Dalam pengertian terakhir ini, Abd al-Wahhab al-Khallaf mendefinisikan fiqh, yaitu mengetahui tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui pengkajian terhadap dalil-dalil tentang suatu persoalan hukum yang terdapat dalam Qur’an dan Sunnah. Ini mengisyaratkan fiqh bukan dihasilkan para ulama melalui taqlîd.
Dari pendekatan bahasa terhadap kata qaidah dan fiqh, dapat mempermudah dalam memahami definisi al-qawaid fiqhiyyah secara terminologi. Dalam kaitan ini, ada beberapa definisi kaidah fiqh secara terminologi yang dikemukakan para ulama. Ibn Subki mengemukakan definisi kaidah fiqh seperti dikutip al-Nadawi yaitu:
الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها
Suatu kaidah kulli (bersifat umum) yang sesuai dengan juz’iyyah (bagian-bagian) yang banyak, yang melaluinya diketahui hukum-hukum juz’iyyah.
Definisi ini menggambarkan ada beberapa unsur penting dalam definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidahnya bersifat umum, kaidah umum itu dapat diterapkan pada bagian-bagiannya, dan melalui kaidah umum itu dapat diketahui hukum-hukum juz’iyyah.
Setelah mempelajari definisi al-qawaid fiqhiyyah yang dikemukakan para ahli fiqh, Zarqa’ merumuskan definisi al-qawaid fiqhiyyah, yaitu kaidah fiqh yang bersifat umum, tersusun dalam teks-teks (nash) yang singkat lagi mendasar mengandung hukum-hukum syara’ yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya.
Melalui definisi itu Zarqa’ mengemukakan sejumlah unsur yang terdapat pada al-qawaid fiqhiyyah yaitu, kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat dan meliputi sejumlah masalah fiqh yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya.
Dengan demikian, al-qawaid fiqhiyyah adalah suatu kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum sejumlah masalah yang berada dalam lingkupnya.
Perbedaan al-qawâid al-fiqhiyyah dengan al-qawâid al-ushuliyyah
Dalam kajian keislaman, fiqh merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana ushul fiqh yang merupakan disiplin ilmu tersendiri. Kedua displin ilmu ini mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang satu sama lain berbeda.
Menurut Ali al-Nadawi, imam Syihab al-Din al-Qarafi merupakan ulama yang pertama kali membedakan antara kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah. Al-Qarafi menegaskan bahwa syariah yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui ushul dan furu’. Adapun ushul dari syariah tersebut ada dua macam. Pertama, ushul fiqh. Ushul fiqh memuat kaidah-kaidah istinbath hukum yang diambil dari lafal-lafal berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari lafal bahasa Arab itu kaidah tentang nasakh, tarjih, kehendak lafal amar untuk wajib dan kehendak lafal nahi untuk menunjukkan haram, dan sighat khusus untuk maksud umum. Kedua, al-qawaid fiqhiyyah yang bersifat kulli (umum). Jumlah kaidah tersebut cukup banyak dan lapangannya luas yang mengandung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Setiap kaidah diambil dari furu’ yang terdapat dalam syariah yang tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian ushul fiqh, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perinciannya.
Dalam penilaian Ibn Taimiyyah, ada perbedaan mendasar antara qawaid ushuliyyah dengan qawaid fiqhiyyah. Qawaid ushuliyyah membahas tentang dalil-dalil umum. Sementara qawaid fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah yang membahas tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, qawaid ushuliyyah membicarakan tentang dalil-dalil yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyyah membicarakan tentang hukum-hukum yang bersifat umum.
Perbedaan al-qawaid fiqhiyyah dan kaidah ushul fiqh secara lebih rinci dan jelas dapat diamati dalam uraian di bawah ini.
1. Al-qawaid al-ushuliyyah adalah kaidah-kaidah bersifat kulli (umum) yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian dan objeknya. Sementara al-qawaid fiqhiyyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, kadangkala ada pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut.
2. Al-qawaid al-ushuliyyah atau ushul fiqh merupakan metode untuk mengistinbathkan hukum secara benar dan terhindar dari kesalahan. Kedudukannya persis sama dengan ilmu nahwu yang berfungsi melahirkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Al-qawaid al-ushuliyyah sebagai metode melahirkan hukum dari dalil-dalil terperinci sehingga objek kajiannya selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap amar atau perintah menunjukkan wajib dan setiap larangan menunjukkan untuk hukum haram. Sementara al-qawaid al-fiqhiyyah adalah ketentuan (hukum) yang bersifat kulli (umum) atau kebanyakan yang bagian-bagiannya meliputi sebagian masalah fiqh. Objek kajian al-qawaid al-fiqhiyyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf.
3. Al-qawaid al-ushuliyyah sebagai pintu untuk mengistinbathkan hukum syara’ yang bersifat amaliyyah. Sementara ¬al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan himpunan sejumlah hukum-hukum fiqh yang serupa dengan ada satu illat (sifat) untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya qawaid fiqhiyyah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fiqh.
4. Al-qawaid al-ushuliyyah ada sebelum ada furu’ (fiqh). Sebab, al-qawaid al-ushuliyyah digunakan ahli fiqh untuk melahirkan hukum (furu’). Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyyah muncul dan ada setelah ada furu’ (fiqh). Sebab, al-qawaid al-fiqhiyyah berasal dari kumpulan sejumlah masalah fiqh yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya.
5. Dari satu sisi al-qawaid al-fiqhiyyah memiliki persamaan dengan al-qawaid al-ushuliyyah. Namun, dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Adapun segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawahnya. Sementara perbedaannya, al-qawaid al-ushuliyyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fiqh yang berada di bawah cakupannya semata.
Signifikansi al-Qawaid al-Fiqhiyyah
Sebagai suatu kajian tersendiri bagi mereka yang menekuni dan melakukan studi terhadap ilmu syariah, hukum Islam dan fiqh, keberadaan al-qawaid al-fiqhiyyah mempunyai arti penting. Betapa pentingnya ilmu ini sehingga al-Qarâfî menggambarkan bahwa al-qawaid fiqhiyyah memberikan manfaat besar terhadap fiqh. Dengan menguasai kaidah fiqh dapat menambah pengetahuan ahli fiqh sehingga ia dapat memahami fiqh dengan baik dan melalui al-qawaid fiqhiyyah akan tersingkap metode fatwa.
Abdul Mudjib dengan mengutip pendapat Izzuddin bin Abd al-Salam menyatakan bahwa al-qawaid fiqhiyyah sebagai jalan untuk mendapatkan maslahah dan menolak mafsadah. Isyarat ini ditegaskan Izzuddin Abd al-Salam dalam tujuan penulisan kitabnya Qawâid al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anam. Ulama ini menjelaskan tujuan penyusunan kitab tersebut untuk menerangkan maslahat-maslahat ketaatan, muamalat dan seluruh tasyaruf untuk pedoman usaha daya-upaya hamba dalam rangka menghasilkan maslahat-maslahat tersebut, menerangkan maksud-maksud kemudharatan agar hamba berusaha untuk menolaknya, dan menerangkan maslahat-maslahat ibadah agar para hamba berada dalam kebaikan karenanya, dan menerangkan maslahat mana yang harus didahulukan dan mafsadat mana yang harus dikemudiankan, serta menerangkan apa yang termasuk dalam kemampuan usaha hamba, bukan hal-hal yang di luar kemampuannya yang tidak ada jalan untuk menuju kepadanya.
Pernyataan hampir senada ditegaskan pula oleh imam Suyuthi dalam bukunya al-Asbâh wa al-Nazhâir. Ia menegaskan bahwa ilmu al-Asbâh wa al-Nazhâir atau kaidah fiqh merupakan ilmu yang agung. Melaluinya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat diperolehnya, tempat pengambilan dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu itu pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fiqh dan mampu untuk menghubungkan dan mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum masalah-masalah yang tidak tertulis, hukum peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang tidak habis-habisnya sepanjang masa. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa fiqh ialah mengetahui persamaan-persamaan atau bandingan-bandingan.
Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan dalam bukunya “Pengantar Hukum Islam” bahwa tidak diragukan lagi seeorang yang hendak melakukan ijtihad membutuhkan kaidah-kaidah kulli (bersifat umum) atau al-qawaid fiqhiyyah yang menjadi pedomannya dalam menetapkan hukum Islam.
Selain itu, arti penting al-qawaid al-fiqhiyyah secara lebih rinci dapat diamati dalam uraian berikut:
1. Al-qawaid al-fiqhiyyah mempunyai kedudukan penting untuk mempermudah dalam mempelajari fiqh. Melaluinya furû’(cabang) fiqh yang demikian banyak dapat dipisahkan dalam kaidah fiqh tertentu. Apabila tidak ada al-qawaid al-fiqhiyyah, tentu persoalan hukum yang demikian banyak tetap berserakan di berbagai kitab fiqh sehingga sulit untuk dipelajari ahli fiqh dengan mudah dan baik.
2. Mempelajari al-qawaid al-fiqhiyyah dapat membantu untuk menguasai fiqh dengan masalah-masalahnya yang demikian banyak. Sebab, al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai jembatan dan sarana melahirkan hukum-hukum.
3. Membantu kalangan yang melakukan studi fiqh untuk membahas bagian hukum dan mengeluarkan hukum dari topik-topik yang berbeda dan meletakkannya pada satu topik dengan tetap memelihara pengecualian (istisna’i) dari setiap kaidah. Hal ini akan menghindarkan terjadi pertentangan hukum yang kelihatan sama.
4. Dengan mengikatkan hukum-hukum yang berserakan pada satu ikatan menunjukkan bahwa hukum-hukum fiqh membawa misi untuk mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengannya atau mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.
5. Mengetahui al-qawaid al-fiqhiyyah penting untuk memperkuat jalan mengetahui furû’ fiqh yang demikian banyak. Hal ini tergambar dalam al-qawaid fiqhiyyah yang menegaskan bawa: “sesungguhnya ungkapan dalam suatu akad mengandung sejumlah makna”. Penerapan kaidah ini dapat diamati dalam sejumlah kasus muamalah yang berada dalam lingkupnya. Misalnya, akad al-bay’u atau jual beli adalah transaksi pemindahan milik suatu benda dengan membayar nilai ganti benda itu. Sementara ijarah adalah transaksi untuk mengambil manfaat suatu benda dengan disertai bayaran terhadap pengambilan manfaat tersebut. Sedangkan hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa membayar gantinya.
Sejalan dengan itu, Zarqa’ mengakui arti penting dan manfaat al-qawaid fiqhiyyah terhadap fiqh. Dengan mengetahui dan menguasai al-qawaid al-fiqhiyyah dapat menambah kemampuan ahli fiqh dan memperjelas bagi mereka metode-metode melahirkan fatwa. Orang yang berpegang kepada furu’ fiqh tanpa memperhatikan al-qawaid al-fiqhiyyah akan menemukan pertentangan yang banyak dalam masalah furu’ fiqh. Hal ini menuntutnya untuk menguasai rincian persoalan fiqh yang banyak tersebut. Ini tentu sulit dan menghabiskan waktu yang lama bagi orang tersebut.
Dari uraian di atas tampak bahwa al-qawaid fiqhiyyah mempunyai arti penting bagi fiqh dan mempunyai peranan signifikan dalam bidang tasyri’. Dengan alasan ini pula para ulama sejak dahulu dari semua mazhab fiqh memberikan perhatian besar dalam rangka merumuskan dan menyusun kaidah-kaidah fiqh sehingga tersusun kitab-kitab khusus yang membahas tentang kaidah-kaidah tersebut.
Bagi mereka yang mempelajari dan mengunakan al-qawaid fiqhiyyah dalam kajian mereka perlu memperhatikan secara seksama, terutama terutama terhadap pengecualian-pengecualian dari kaidah itu. Dalam konteks ini, diperlukan sikap teliti dan hati-hati dalam penerapan kaidah fiqh tersebut. Hal ini penting agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan kaidah-kaidah fiqh.
Peran al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Istinbath Hukum
Dalam memposisikan al-qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil istinbath hukum dapat diamati dari berbagai pendapat ulama tentang masalah tersebut. Dalam kaitan ini, Alî al-Nadawî memaparkan sejumlah pendapat ulama tentang masalah ini. Imam Haramain al-Juwaini dalam kitabnya al-Ghayâtsî ketika menjelaskan tentang kaidah ibahah dan bara’ah zimmah menegaskan bahwa ia tidak bermaksud menggunakan kedua kaidah tersebut sebagai dalil. Ini isyarat dari imam Haramain untuk tidak menggunakan kaidah fiqh sebagai dalil istinbath hukum. Al-Hamawî dengan ungkapan lebih tegas menyatakan penetapan fatwa tidak boleh didasarkan kepada kaidah fiqh karena ia tidak bersifat kulli, tetapi bersifat aqlabiyyah (kebanyakan). Isyarat serupa dikemukakan pula oleh Alî Khaidar dalam syarah al-Majallah al-Adliyyah bahwa mereka yang berwenang menetapkan hukum tidak boleh menetapkan hukum dengan semata-mata berpijak pada al-qawaid al-fiqhiyyah.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak ulama yang tidak membolehkan pemakaian al-qawaid fiqhiyyah sebagai dalil-dalil dalam menetapkan hukum. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan furû’ (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara’. Namun, kesimpulan ini tidak dapat diberlakukan secara umum, mengingat sebagian al-qawaid fiqhiyyah ada yang langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur’an dan Sunnah (nash).
Ada beberapa al-qawaid fiqhiyyah yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Pertama, kaidah yang menegaskan bahwa sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihapus oleh keraguan. Kaidah fiqh itu berbunyi:
اليقين لا يزول بالشك
Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan
Kaidah ini menegaskan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan, kecuali yang meragukan meningkat menjadi meyakinkan. Ini menunjukkan semua tindakan mesti berdasarkan pada yang diyakini. Yakin adalah puncak pemahaman yang disertai dengan tetapnya hukum. Dalam penilaian Alî al-Nadawî, yakin adalah ketetapan dan ketenangan tentang hakikat sesuatu sehingga tiada lagi keragu-raguan. Menurut ibn Manzûr, yakin adalah mengetahui dengan pasti tentang suatu persoalan sehingga menghilangkan adanya keraguan. Sedangkan syak secara bahasa berarti sikap ragu antara ada atau tidak ada sesuatu dan ia merupakan lawan dari yakin. Menurut ahli fiqh, syak adalah sikap ragu antara ada atau tidak adanya sesuatu, baik sikap ragu itu sama atau ada salah satu dari keduanya yang lebih kuat. Sementara ahli ushul fiqh mendefinisikan syak adalah adanya dua kemungkinan yang sama, apabila ada salah satu yang lebih kuat disebut zhan (praduga) dan yang lain disebut wahm (dugaan yang kurang kuat).
Kaidah fiqh di atas menghimpun sejumlah masalah fiqh. Melalui kaidah ini juga tergambar kemudahan dan kelapangan dalam hukum Islam. Kaidah ini mendorong untuk menghilangkan kesulitan selama didasarkan atas keyakinan. Ini penting karena keraguan banyak muncul akibat penyakit was-was (bisikan setan), yang biasa terjadi dalam masalah bersuci dan sholat. Kaidah fiqh tersebut didasarkan pada dalil yang kuat, diantaranya hadis berikut:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: apabila seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perutnya ataukah belum, maka janganlah ia keluar masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau (memperoleh bukti telah batal wudhunya) (H.R. Muslim).
Hadis ini menginformasikan kepada muslim, apabila merasakan sesuatu dalam perutnya sehingga ia ragu apakah telah keluar sesuatu dari perut yang menyebabkan batal wudhu atau tidak ada yang keluar, ia tidak perlu keluar masjid untuk berwudhu sampai mendengar secara pasti suara (kentut) atau merasakan bau.
Kaidah fiqh di atas juga didasarkan pada hadis Nabi berikut:
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda: apabila ragu salah seorang kamu dalam sholat, apakah telah satu rakaat atau dua rakaat sholatnya, maka hendaklah ia menetapkan satu rakaat sholat yang telah dilakukan. Dan apabila ia ragu antara dua atau tiga rakaat sholat yang telah dilakukan, maka hendaklah ia menetapkan dua rakaat yang telah dilakukan. Hendaklah ia melakukan dua kali sujud sebelum salam (H.R. Tirmidzi).
Hadis ini mengisyaratkan orang yang ragu tentang bilangan rakaat sholat, antara dua dan tiga, maka hendaklah yang bersangkutan memilih bilangan rakat sholat yang paling sedikit karena itulah yang yakin atau pasti, sementara bilangan yang tertinggi dari rakaat sholat itu yang dikeragui. Dalam kasus, ini orang yang ragu tentang bilangan rakaat sholat diperintahkan (sunat) untuk melakukan sujud sahwi sebelum ia salam sebagai penutup sholatnya.
Mengingat kaidah fiqh tentang “sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan” langsung didasarkan pada nash, ia dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.
Kedua, kaidah fiqh yang menegaskan kemudharatan harus dihilangkan dari kehidupan manusia. Kaidah fiqh itu berbunyi: :
الضرر يزال
Kemudharatan itu harus dihilangkan
Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudharatan selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun akan datang. Islam menginginkan agar kemudharatan itu dihilangkan dari kehidupan manusia.
Kaidah ini dibangun atas dasar dan dalil yang cukup kuat, diantaranya firman Allah berikut:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS.7:85)
Ayat ini melarang muslim berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemampuan mentaati ketentuan ini sebagai bukti kebenaran iman seorang mukmin. Disamping itu, Allah menegaskan bahwa Ia tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, seperti pada firman-Nya berikut:
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS.28:77).
Kaidah fiqh di atas juga didasarkan pada hadis Nabi berikut:
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW. menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain (H.R. Ibn Majah)
Kaidah fiqh ini mencakup banyak masalah fiqh dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik bidang muamalat, munakahat, maupun jinayat. Dalam bidang muamalat, kaidah fiqh ini dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena ada cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis (orang yang jatuh pailit), safih (orang dungu) untuk melakukan transaksi dan hak syuf’ah. Pertimbangan utama diberlakukan ketentuan-ketentuan ini untuk menghindarkan semaksimal mungkin kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.
Selain itu, kaidah fiqh ini menjadi dalil pula dalam menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum qishash, hudud, kaffarat, mengganti rugi kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontak dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal. Disamping itu, kaidah fiqh tersebut meliputi persoalan munakahah. Diantaranya, Islam membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi, agar suami-istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan dan tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga bahagia.
Ketiga, kaidah fiqh yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah itu berbunyi:
العادة محكمة
Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum
Dalam penilaian al-Râghib kata ‘urf yang seakar dengan kata ma’rûf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Q.S. 3: 104. Kata ‘urf dan ma’rûf dalam Qur’an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Q.S. 7:199. Menurut Ibn al-Najar kata al-‘urf yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia dan sejalan dengan nilai-nilai syarî’ah.
Secara istilah, menurut Al-Jurjânî ‘urf adalah semua yang telah tetap dalam jiwa, didukung akal, dan dapat diterima tabiat. Sementara adat merupakan segala yang dipraktekkan manusia secara terus menerus yang sejalan dengan akal sehat dan telah menjadi kebiasaan mereka. Al-Jurjânî membedakan antara ‘urf dan adat. Sesuatu yang disebut ‘urf bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka.
Abû Zahrah membatasi ‘urf menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah. Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalan bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Qur’an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur ‘urf di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur ‘urf setelah sumber hukum Islam, Qur’an dan Hadis lengkap diturunkan.
Mushthafâ Ahmad Zarqâ’ menyimpulkan bahwa ‘urf bersumber dari adat kebanyakan kaum dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Ia tampaknya tidak mensyaratkan sesuatu yang disebut ‘urf dilakukan oleh semua orang, tetapi cukup dilakukan oleh mayoritas kaum atau masyarakat. Dalam hal ini, ‘urf tidak hanya cukup dalam bentuk perbuatan, dapat pula berupa perkataan.
Makna adat dalam kaidah fiqh di atas meliputi ‘urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nash tidak ada. Adat atau ‘urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara ‘urf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan ‘urf itu.
Menurut al-Suyûthî, banyak sekali masalah hukum Islam yang didasarkan pada kaidah ini, diantaranya penentuan usia haid, lama masa suci dan haid, usia baligh, lama masa nifas, batasan sedikit najis yang dapat dimaafkan, batasan berturut-turut (muwalat) dalam wudhu, jarak waktu ijâb dan qabûl, jual beli salam, jual beli mu’âthah, merawat bumi yang tidak bertuan (ihyâ’ al-mawât), masalah titipan, memanfaatkan harta sewaan, masalah hidangan yang boleh dimakan ketika bertamu, keterpeliharaan harta di tempat penyimpanan dalam masalah pencurian, dan menerima hadiah bagi hakim.
Kaidah fiqh tentang urf’ atau adat di atas dapat dijadikan sebagai dalil yang mengkhususkan keumuman nash. Dalam nash dijelaskan tentang larangan melakukan jual beli yang diiringi dengan syarat seperti yang ditegaskan Hadis berikut:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه احمد)
Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: tidak halal jual beli salam, dua syarat dalam satu akad jual beli, mengambil keuntungan yang tidak disertai jaminan, dan jual beli sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R. Ahmad)
Larangan melakukan jual beli yang diiringi dengan syarat dalam Hadis ini bersifat umum yang kemudian ditakhsis oleh ‘urf. Atas dasar ini, bay’ al-wafâ’, dimana merupakan jual beli yang diiringi dengan syarat dibolehkan hukum Islam. Bagi mayoritas ulama mazhab Hanafi pembolehan bay’ al-wafâ’ karena membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat dalam kegiatan muamalah mereka. Jual beli ini sebagai jalan keluar menghindarkan diri dari riba.
Praktek bay’ al-wafâ’ berasal dari tradisi masyarakat Bukhâra dan Balkh pada pertengahan abad ke 5 H. Hal ini muncul karena para pemilik modal tidak mau memberi hutang kepada mereka yang membutuhkan dana, apabila mereka tidak mendapat imbalan. Situasi ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan dana. Untuk itu, mereka menciptakan transaksi sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun tercapai. Ini alasan mereka membolehkan bay’ al-wafâ’.
Sejalan dengan penjelasan terdahulu, hakim dan mufti tidak boleh menetapkan putusan dan fatwanya dengan semata-mata berpegang pada al-qawaid al-fiqhiyyah. Hakim dan mufti tersebut boleh menggunakan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam menjalankan tugasnya apabila menemukan dalil (nash) fiqh yang dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya.
Apabila suatu kasus tidak ditemukan nash fiqh sebagai dasarnya karena tidak diketahui bahasan fuqaha tentang hal itu, tetapi ada kaidah fiqh yang dapat mencakup peristiwa atau kasus itu, dalam situasi demikian dibenarkan melandaskan fatwa dan putusan hakim di pengadilan menggunakan kaidah fiqh. Penerapan hal ini dapat diamati secara seksama dari contoh kasus yang dikemukakan di bawah ini.
Dalam sebuah kaidah fiqh yang cukup populer ditegaskan bahwa situasi yang sulit memberikan peluang bagi muslim memperoleh kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan urusannya. Hal itu diungkapkan kaidah fiqh berikut:
اذا ضاق الأمر اتسع
Suatu urusan apabila telah sempit ia akan lapang.
Dengan berpegang pada kaidah fiqh ini, imam Syafi’i memberikan solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi seorang wanita, dimana ketika tidak ada wali wanita yang sedang melakukan perjalanan bersamanya, ia boleh mewakilkan walinya kepada laki-laki yang dipercayai dan dipandangnya memiliki sifat amanah. Ketika imam Syafi’i ditanya orang kenapa ia memberikan solusi yang demikian. Ulama ini menegaskan bahwa apabila suatu urusan sempit, maka ia akan lapang.
Imam Abd al-Aziz bin Ahmad al-Kalawani, membolehkan praktek jual beli buah-buahan yang sebagiannya telah tampak, sementara yang lain belum tampak. Dengan telah tampak sebagian buah-buahan itu semakin mendekatkan kepada hasil buah-buahan itu apabila telah matang nanti. Disamping itu, didasarkan pula pada pertimbangan berupa aturan main seperti itu telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.
Secara faktual terbukti sebagian kaidah fiqh yang terdapat dalam al-qawaid al-fiqhiyyah dipakai para ulama dalam menetapkan hukum dan melahirkan berbagai fatwa untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Misalnya, para ulama tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) dalam menetapkan hukum terhadap sejumlah kasus yang diajukan masyarakat seringkali merujuk pada kaidah fiqh sebagai penguat pendapat mereka setelah mengemukakan sejumlah ayat Qur’an dan hadis.
Kesimpulan
Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang dirumuskan para ulama yang tidak langsung terambil dan berdasarkan nash tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan furû’ (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara’. Namun, apabila kaidah fiqh itu langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur’an dan Sunnah (nash), ia dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.
Senin, 02 Februari 2009
Kedudukan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah dalam Penetapan Hukum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























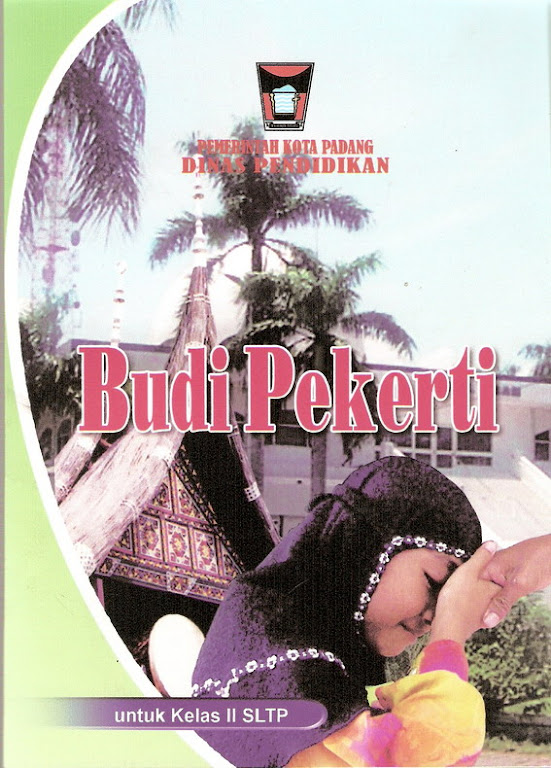





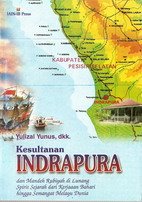




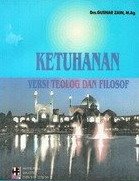
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar