Oleh : Lisna Sandora, M.Pd (Dosen Jur. SKI)
 Dunia, menurut Marx, adalah muara akhir dari hidup manusia. Soal akhirat, surga, neraka, Tuhan, baginya hanya merupakan proyeksi manusia. Tuhan-menurut Marx-sebenarnya tidak ada. Tuhan ada karena diciptakan oleh pikiran manusia. (God is created by man). Karena manusia takut menhadapi masa depan yang tak jelas, maka ia menciptakan dan mengakui Tuhan untuk menentramkan hatinya. annya dikesampingkan begitu saja.
Dunia, menurut Marx, adalah muara akhir dari hidup manusia. Soal akhirat, surga, neraka, Tuhan, baginya hanya merupakan proyeksi manusia. Tuhan-menurut Marx-sebenarnya tidak ada. Tuhan ada karena diciptakan oleh pikiran manusia. (God is created by man). Karena manusia takut menhadapi masa depan yang tak jelas, maka ia menciptakan dan mengakui Tuhan untuk menentramkan hatinya. annya dikesampingkan begitu saja.Moralitas dan Marxisme, dipakai sekedar untuk legalisasi tujuan-tujuan material. Mialnya pemihakan terhadap kelas proletar. Sampai di sini memang masih terasa nuansa moralnya. Namum follow up dari pemihakan itu justru mengidap suatu metodologi yang sangat tidak bermoral: mengahncurkan kelas borjuis. Diakhir riwayat, kelas proletar itu mesti menjadi borjuis-borjuis baru yang tak kalah kejam dalam menghisap darah kelas lawannya.
Islam selalu melangkah dengan standar moral illahiyah yang berintikan tauhidillah, pengesaan dan penomorsatuan Allah di atas segalanya. Seluruh bangunan konsepsi Islam dinafasi oleh struktur nilai ini. Dalam urusan penjelasan masyarakat, perubahan sosial, dan pemerataan rizki ekonomi tidak ada sandaran lain kecuali paradigma Rabbaniyah, tata nilai sempurna yang datang dari Rabbul ‘Alamin.
Di dalam Islam, teori klassentrijd (perlawanan kelas) seperti ajaran Marx, adalah penalaran yang syadz (asing, tak dikenal). Ada baiknya dinukil pendapat Dr. Kuntowijoyo di sini, “Di dalam Islam, pemihakan kelas diakui sah adanya. Tapi elan vital yang mendasari pemihakan tersebut lebih didasarkan pada semangat untuk menegakkan keadilan, bukan perjuangan kelas untuk melenyapkan kelas yang lain. Islam mengakui diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Banyak ayat al Qur’an yang memaklumkan dilebihkannya derajat sosial, ekonomi atau kapasitas-kapasitas lainnya dari sebagian orang atas sebagian yang lainnya. Kendatipun demikian, ini tidak dapat diartikan bahwa al Qur’an mentoleransi sosio-inequality”. Lebih tegas lagi, perbedaan status sosial dalam masyarakat merupakan ujian keimanan agar jelas siapa yang mengikuti syari’at Allah dan siapa yang kufur. Firman Allah: “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Amin: 165).
Adanya struktur masyarakat yang bertingkat lebih dimaknai sebagai perangkat normatif; Bukan pada obyektivitas sikon tinggi rendahnya jenjang derajat ekonomi, sosial, politik dan seterusnya. Oleh karena itulah, ukuran manusia dihadapan Allah Adalah Taqwa (QS. 49:13), bukannya berhenti pada nilai-nilai bendawi yang telah diraih. Pada dasarnya, menjadi orang miskin ataupun aghniya’ (kaya), masing-masing dari keduanya memiliki mas’uliyah (tanggung jawab) yang sama dihadapan mahkamah Allah. Dalam Islam, kaum aghniya’ tidak dengan sendirinya berderajat lebih tinggi dari kaum masakin. Dan kaum masakin tidak digitimasikan untuk iri hati atas previlis-previlis kaum aghniya’! Tidak. Malah sebaliknya, orang-orang kaya dibebani amanah untuk mendistribusikan kekayaannya secara adil. Sebab pada hakikatnya, konsep pemilikan mutlak tidak diakui dalam Islam. Nabi Muhammad Saw. bersabda ketika beliau hendak menegaskan amanah da’wah kepada Mu’adz bin Jabbal ke negeri Yaman. Setelah menda’wahkan syahadatain dan perintah menegakkan shalat, Muadz diperintah untuk memungut zakat atas harta mereka. “Tu’khadzu min ghaniiyihim, fa ruddu’ala raqiirihim”. (Diambil zakat itu dari orang-orang kaya mereka, lantas dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka). (HR Bukhari).
Kata fa ruddu (maka dikembalikan) dalam hadits di atas mengandung konotasi bahwa harta kekayaan di tangan aghniya’ pada hakikatnya ada hak orang miskin di dalamnya. Sehingga lafadz yang dipakai Rasulullah Saw. Adalah fa ruddu (dikembalikan) seakan-akan beliau ingin menyatakan bahwa harta itu juga milik fakir miskin. Kata ini sekaligus menunjukkan bahwa zakat buka merupakan kebaikan hati si kaya kepada si miskin-seperti infaq, shadaqah-melainkan lebih merupakan kewajiban sistem yang digariskan Allah bagi kelas kaya yang dikaruniai kelebihan harta benda untuk menegakkan keadilan sosial. Pemihakan yang dilakukan Islam terhadap mustadh’afin dalam konteks zakat ini, bukanlah bertujuan untuk menghancurkan kelas kaya. Namun lebih menitikberatkan pada penciptaan struktur sosial yang adil, merata dan distribusi ekonomi yang sehat.
Khalifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah upaya kekuasaan Islam untuk memberlakukan hukm Allah semata dan bukan untuk menghancurkan orang-orang kaya seperti dalam Marxisme. Juga terhadap gerakan yang dilancarkan Abu Dzar al-Ghifari di zaman Mu’awwiyah. Bukanlah disemangati oleh kebencian terhadap para aghniya’. Melainkan lebih diilhami oleh panggilan suci menegakkan hukum Rabbani dalam kehidupan nyata. Kritik Abu Dzar terhadap penguasa waktu itu semata-mata disebabkan oleh keinginnannya yang tulus agar konsentrasi modal dan kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang diakhiri. Dalam memetakan perbedaan struktur sosial, Islam tidak menghadapkannya sebagai kemestian dikotomis, tapi fungsional. Masyarakat tidak diajari untuk mengilahkan harta. Sebaliknya, mereka tidak didik untuk mencintai kemiskinan yang fatalis. Namun, Islam meletakkan potensi ekonomi secara proporsional.
(Lebih lengkap : hubungi fiba.pdg@gmail.com / abahiffa@yahoo.com

























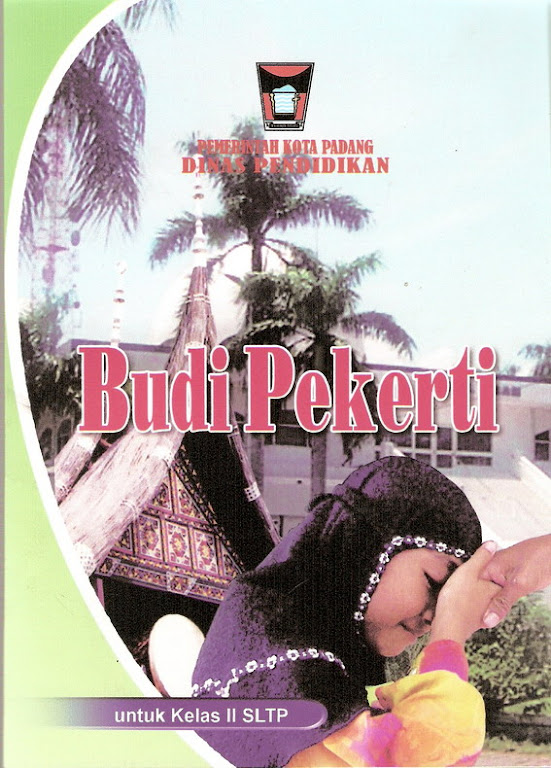





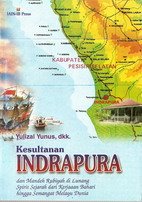




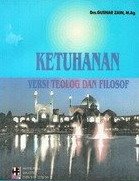
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar