Oleh : Dr. Ahmad Taufik Hidayat, M.Ag (Dosen Studi Naskah FIB-Adab)
 Perang Paderi berakhir dengan kekalahan di pihak kaum Paderi. Walaupun demikian, setidaknya ada dua dampak dari peperangan ini, pertama, supremasi syariat atas adat dalam konsepsi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kedua, tercapainya Plakat Panjang (1833) yang menjamin dan melindungi aset perekonomian rakyat dari Belanda. Dalam perkembangannya, dampak pertama menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks seiring terpecahnya elit agama ke dalam dua kekuatan: ulama tradisional dan modern. Pola hubungan antara dua elit agama ini ditandai dengan perubahan pada aspek-aspek tertentu. Hal itu setidaknya tergambar dalam dinamika perkembangan surau. Sebagian ulama tradisi mengubah surau mereka menjadi madrasah, meninggalkan system belajar halaqah, namun tetap berorientasi pada pemikiran tradisional. Sebagian lain mendirikan sistem pendidikan modern secara berdampingan dengan surau.
Perang Paderi berakhir dengan kekalahan di pihak kaum Paderi. Walaupun demikian, setidaknya ada dua dampak dari peperangan ini, pertama, supremasi syariat atas adat dalam konsepsi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Kedua, tercapainya Plakat Panjang (1833) yang menjamin dan melindungi aset perekonomian rakyat dari Belanda. Dalam perkembangannya, dampak pertama menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks seiring terpecahnya elit agama ke dalam dua kekuatan: ulama tradisional dan modern. Pola hubungan antara dua elit agama ini ditandai dengan perubahan pada aspek-aspek tertentu. Hal itu setidaknya tergambar dalam dinamika perkembangan surau. Sebagian ulama tradisi mengubah surau mereka menjadi madrasah, meninggalkan system belajar halaqah, namun tetap berorientasi pada pemikiran tradisional. Sebagian lain mendirikan sistem pendidikan modern secara berdampingan dengan surau.A. Bermula dari Perang Paderi
Perang Paderi berakhir dengan kekalahan berada di pihak kaum Paderi. Tetapi gerakan ini cukup berhasil dalam dua hal: pertama meletakkan supremasi syari’at di atas adat dalam konsepsi (ABS-SBK). Sebelumnya, kesepakatan terjauh yang mungkin tercapai adalah perimbangan antara adat dan syari’at sebagai pedoman kehidupan masyarakat Minang yang dirangkum dalam konsepsi adat basandi syarak, syarak basandi adat. Konsensus ini berimplikasi pada aspek normatif adat yang formulasinya dapat dilihat dalam pepatah-petitih Minangkabau lainnya. Sanusi Latif mencatat sekurangnya tiga ungkapan yang mencerminkan hal itu, seperti, syarak mangato, adat mamakai, syarak batilanjang adat basisampiang. Supremasi ini diterima dalam tradisi adat masyarakat Minang yang mereka sebut adat nan saban adat. Pada gilirannya, demikian Azra, adat dianggap sebagai manifestasi yang benar dari hukum-hukum agama.
Persoalan yang berhubungan dengan perselisihan antara kaum adat dengan kaum agama juga relatif telah dapat diatasi. Beberapa gejolak yang muncul belakangan mengarah pada wacana intelektual saja dan agaknya kurang mendapat respon dari masyarakat luas. Kedua, melindungi aset perekonomian rakyat karena telah berhasil mencapai kesepakatan dengan pihak Belanda yang ditulis dalam Plakat Panjang (1833). Kesepakatan ini berisi bahwa Belanda tidak akan membebankan pajak langsung kepada rakyat serta tidak akan mencampuri masalah adat dan agama dalam nagari-nagari di Minangkabau.
Tetapi isu-isu pemurnian yang sebelumnya diemban kaum Paderi tetap disuarakan dengan kental, namun diletakkan dalam jubah “ke-modern-an”. Sifat modernitas dalam keyakinan beragama yang mereka perkenalkan adalah memberi porsi lebih pada potensi akal untuk menggali dan memahami norma-norma agama. Bermazhab bukannya tidak boleh, namun harus diterima dengan sikap kritis, karena sesungguhnya Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia agar tidak taklid dalam beragama. Pada sisi berseberangan, ulama tradisional senantiasa menganjurkan kepada pengikutnya untuk selalu berpegang teguh kepada mazhab-mazhab yang ada sebagai bentuk ketaatan dalam menerima ajaran dari guru-guru mereka.
Namun di sini persoalannya bukan sekedar teguh menjalankan prinsip keagamaan. Mengenai ketokohan Syekh Ahmad Khatib, tekanan kolonial serta gaung pembaharuan terutama dalam bidang pendidikan yang begitu mendunia mengharuskan ulama tradisi merevisi kembali batas-batas prinsip tersebut. Meskipun pada beberapa fase terjadi polemik antara Syekh Ahmad Khatib vs Syekh Saad Mungka (1227-1339 H) seputar amalan-amalan kaum tarekat dan persoalan ibadah pada umumnya, tetap tidak dapat membendung pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh murid-murid Ahmad Khatib. Berdasarkan beberapa catatan, selain ulama dari kalangan modernis, sejumlah ulama tradisional juga pernah belajar kepadanya. Sebut saja misalnya Syekh Muhammad Chatib al-Fadaniy dan Syekh Bayang. Hal itu setidaknya menunjukkan bahwa ketokohan Syekh Ahmad Khatib di Mekah pada masa peralihan abad 19 ke abad 20 sangat signifikan dalam membentuk karakter Islam di Minangkabau.
Tetapi fakta di atas sedikit membuka diskusi ke arah lain. Spektrum pertikaian faham sesungguhnya lumayan longgar. Kelompok ulama tradisi (terutama Syattariyah dan Naqsha-bandiyah) dapat bersatu ketika isu-isu faham keagamaan—meskipun keduanya berseberangan arah dalam praktek dan amalan tarekat—tradisional diserang oleh ulama dari kelompok modernis. Sekedar tambahan, Tuanku Nan Tuo, seorang ulama yang garang dalam perang Paderi berlatar tarekat Syattariyah.
Ada banyak kasus inkonsistensi dalam pola-pola hubungan sosial semacam itu yang mungkin tidak akan habis untuk didiskusikan. Tetapi yang ingin dikejar di sini adalah spektrum pertikaian antara ulama modernis dan ulama tradisional cenderung mengarah pada sikap moderasi manakala kebutuhan untuk memajukan pendidikan sama-sama dirasa penting, dan oleh karena itu ulama tradisional dapat kembali bersatu dalam payung tradisional, mungkin ditingkahi dengan semangat kompetisi internal, untuk membendung faham-faham pembaruan.
Kiprah murid-murid Ahmad Khatib di Minangkabau telah mencitrakan diri mereka sebagai kelompok yang membawa perubahan, terutama dalam bidang pendidikan. Kenyataan yang sama dapat dijumpai diberbagai wilayah dunia Islam, seperti di Turki, Mesir, India dan tempat-tempat lain. Oleh karenanya, tidak heran bila tokoh-tokoh yang melanjutkan perjuangan Paderi dalam bentuk baru ini dikenal dengan kaum Muda. Sebuah gelar yang mengingatkan orang dengan gerakan Turki Muda pimpinan Anwar Pasya dan Kemal Attaturk di Turki pada awal abad ke-20.
Ciri kemodernan yang diperlihatkan Turki Muda yang terpenting adalah mengangkat harkat bangsa Turki setara dengan bangsa Eropa. Dalam kerangka itu, selain dimotivasi oleh semangat pembaharuan di belahan dunia Islam lainnya, seperti di Mesir, kaum Muda Minang menyuarakan pesan serupa. Namun persoalan yang bersifat politis agaknya tidak terlalu kelihatan dalam pergerakan mereka. Gerakan modern yang mereka usung lebih terfokus pada isu-isu pendidikan dan pencerahan dalam hal keagamaan. Hal itu boleh jadi dikarenakan kuatnya pengaruh Ahmad Khatib daripada tokoh-tokoh lain semisal Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Jamal al-Din al-Afghani dan tokoh-tokoh di Turki. Sebagian besar murid Ahmad Khatib terhubung dengan gerakan Paderi jilid 2.
Kecenderungan perubahan yang mereka lakukan terlihat jelas pada model pendidikan yang mereka bina. Adabiah School, Sumatera Thawalib dan Diniyah Padang Panjang, merupakan bentuk gerakan modernisme Islam yang berorientasi kepada pendidikan, yang untuk masa selanjutnya dijadikan basis pemahaman kelompok modernis. Sekolah-sekolah ini menerapkan sistem modern, dengan pengertian menggunakan sistem kelas, tidak seperti sebelumnya dengan sistem halaqah yang dipraktekkan di Surau-Surau, kurikulum yang dipaketkan dengan memadukan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, serta diselenggarakan dalam jangka waktu 7 tahun. Pada masa itu, sekolah-sekolah yang didirikan kelompok modernis di Minangkabau banyak diminati oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal, namun juga dari luar wilayah Minangkabau. Bahkan Aceh, sebagai daerah yang dahulu pernah dijadikan tempat menimba ilmu bagi orang Minang malah mengirimkan putera-putera terbaik mereka ke daerah ini.
Karena itu, tidak pula mengherankan bila gema perubahan dunia Islam juga menyentuh kelompok tradisi. Secara kelembagaan, respon kalangan tradisi terhadap kedatangan arus modernisasi ini sebagaimana terlihat dalam institusi Surau yang mereka bina tergambar dalam tiga kecendrungan umum. Pertama, Sebagian ulama-ulama tradisi yang telah tercerahkan ikut ambil bagian dengan memekarkan fungsi Surau menjadi madrasah, namun dengan orientasi berbasis pemikiran tradisional. Mereka mengartikulasikannya dalam model pendidikan yang juga berbau modern dan meninggalkan sistem halaqah. Kedua, sebagian lagi tetap dalam bentuk tradisionalnya. Diantara Surau-Surau yang dahulunya menjadi basis pergerakan kalangan tradisi, terutama Surau-Surau yang mengembangkan praktek-praktek tarekat termasuk dalam barisan ini, walaupun pada saat yang sama, penganut tarekat sendiri sering mengalami konflik pemikiran, terutama antara penganut tarekat Syattariyah dengan tarekat Naqsyabandiyah, dan ketiga, menciptakan model pendidikan modern, tetapi juga mempertahankan institusi Surau.
Untuk mencapai hal itu, mereka membangun madrasah berdam-pingan dengan Surau yang menjadi basis awal mereka. Pada tahap ini, agaknya dinamika perubahan dalam dunia pendidikan Islam telah memisahkan kecenderungan kalangan tradisional, terutama dari aspek fisik. Tetapi secara umum, dalam prakteknya arah perubahan kalangan tradisional terlihat pada sikap menerima perubahan yang digagas oleh kalangan pembaharu dan perkembangan yang terjadi di dunia Islam.
Namun demikian—jika boleh hal itu dianggap sebagai keberhasilan kalangan modernis mengkomunikasikan ide-ide pembaharuan lewat berbagai cara kepada kelompok tradisional—maka pencapaian tersebut jelas tidak mudah. Baru pada tahun 1928 ulama tradisi melihat aspek positif dari keberadaan sekolah-sekolah modern, tentunya didahului oleh semakin berkurangnya minat masyarakat terhadap Surau, dan adanya semacam himbauan dari kelompok pembaharu agar ulama tradisi mengikuti apa yang telah mereka lakukan.
Dari pemaparan di atas terlihat bahwa kecenderungan perubahan semangat beragama masyarakat Islam Minangkabau, baik kelompok modernis maupun kelompok tradisional mengarah pada pengembangan aspek intelektual yang tercipta melalui pergesekan dinamika pemikiran antar dua kelompok, yang melahirkan sekolah-sekolah unggul pada masanya. Fokus mereka pada aspek pendidikan merupakan sebuah indikasi kuat bahwa, masyarakat Minang yang dianggap taat beragama, adalah juga masyarakat yang mengerti skala prioritas dalam membangun manusia. Karena, sebagaimana yang diinginkan oleh kalangan pembaru, jika ingin membangun masyarakat, maka bangunlah generasi mudanya. Kesadaran itu diperkuat dengan adanya tekanan pihak kolonial dan perkembangan sekolah-sekolah yang mereka dirikan.
Oleh karenanya penting dicatat, bahwa suburnya sekolah-sekolah Islam modern yang diprakarsai tokoh-tokoh muda juga dapat dilihat sebagai respon terhadap sistem pendidikan yang dibentuk Belanda. Sebagaimana dimaklumi, dengan politik etis-nya, Belanda juga mendirikan beberapa sekolah bagi masyarakat pribumi yang mencetak tenaga-tenaga administrasi siap pakai dengan kurikulum pendidikan umum. Surau Jembatan Besi dan Adabiah School merupakan bentuk konkret kaum muda untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Belanda. Perubahan yang mereka lakukan dalam hal ini, meminjam pemetaan Steenbrink, setidaknya dapat dilihat dari 3 motif dasar :
• Usaha menyempurnakan sistem pendidikan Surau
• Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat
• Upaya untuk menjembatani ketertinggalan model pendidikan lama dengan kemunculan sistem pendidikan baru yang diprakarsai Belanda dan negara-negara Barat lainnya.
Untuk mewadahi motif-motif ini, kalangan Islam modernis menerima Muhammadiyah sebagai organisasi mereka, sedangkan kelompok Islam tradisional menerima Perti menjadi basis pergerakan. Pada gilirannya, kedua wadah organisasi ini menyatu dalam kultur keagamaan umat Islam di Minangkabau yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana menyatunya adat dan syari’at, meski masih memelihara konflik. Setiap saat selalu dihadapi oleh upaya untuk menemukan jalan moderasi yang berdampak pada corak beragama masyarakat Minang yang disebut oleh Azra sebagai Islam Garis Tengah.
Dengan demikian, semangat beragama yang difokuskan kepada upaya pembaharuan pendidikan meningkatkan sikap terbuka dalam beragama dalam masyarakat Minang dan membuka cakrawala keagamaan yang dikembangkan pada lembaga-lembaga pendidikan mereka, baik kelompok modernis maupun kelompok tradisionalis. Pada periode ini, sikap fanatik yang dipelihara sebelumnya di kalangan ulama tradisional sebagian besar tersalurkan melalui wadah organisasi yang ada, termasuk dalam hal ini sebagian Surau-Surau yang dengan konsisten memelihara fanatisme terhadap keyakinan dan fanatisme serta mempertahankan struktur Surau, dalam pengertian tidak merubah diri menjadi madrasah, juga mengidentifikasi diri ke dalam kelompok tradisionalis (Perti).
Wacana perbedaan yang diperselisihkan kedua belah pihak lebih diarahkan ke dalam tulisan-tulisan yang dipublikasikan melalui media cetak masing-masing. Walaupun ada juga polemik yang dilempar dalam ceramah-ceramah ataupun debat-debat terbuka, namun perselisihan tersebut berjalan tanpa konflik serius.
B. Peran Surau Bagi Pembentukan Karakter Islam Tradisional
Secara tradisional, ada dua arena pembentukkan karakter masya-rakat Minangkabau, Surau dan lapau. Keduanya sangat berpengaruh besar dalam perkembangan mental masyarakat ini. Surau adalah lambang kesakralan mencerminkan sikap relijius, sopan santun serta kepatuhan kepada Allah, sedangkan lapau mencerminkan aspek keduniawiyan (profan) yang mengandung kekerasan, keberanian. Kecendrungan perkembangan anak-anak suku Minangkabau ditentukan dari banyaknya porsi waktu yang mereka habiskan sebagai bagian hidupnya sehari-hari dari tempat ini. Jika seorang anak lebih banyak berada di lapau tanpa pernah mengaji di Surau, maka orang menyebut mereka parewa. Sebaliknya, jika waktu yang dihabiskan oleh seseorang lebih banyak di Surau, maka orang itu disebut urang siak atau pakiah.
Karena itu, dari aspek mental keagamaan, bagi masyarakat tradisional Minang, terutama kaum pria-nya, fungsi Surau jauh lebih penting dalam membentuk karakter mereka di kemudian hari. Selain untuk memperoleh informasi keagamaan, juga dijadikan ajang bersosialisasi. Semenjak berumur 6 tahun, kaum pria telah akrab dengan lingkungan Surau. Struktur bangunan rumah tradisional orang Minang yang dikenal dengan rumah gadang memang tidak menyediakan kamar bagi anak laki-laki. Karena itu, setelah berumur 6 tahun, anak laki-laki di Minang-kabau seperti terusir dari rumah induk. Hanya pada maktu siang hari mereka boleh bertempat di rumah guna membantu keperluan sehari-hari. Sedangkan pada waktu malam, mereka harus menginap di Surau. Selain karena tidak disediakan tempat, mereka juga merasa risih untuk berkumpul dengan urang sumando (suami dari kakak/adik perempuan) dan mendapat ejekan dari orang-orang karena masih tidur dengan ibu. Dalam ucapan yang khas, lalok di bawah katiak mande. Tetapi, di Surau mereka bukan sekedar menginap.
Banyak aktifitas penting yang mereka lakukan di sana. Belajar silat, adat istiadat, randai, indang menyalin tambo dilaksanakan berbarengan dengan aktifitas keagamaan seperti belajar tarekat, mengaji, shalat, salawat, barzanji dan seterusnya. Karakter pembentukan Islam tradisional sesungguhnya berangkat dari aktifitas seperti ini. Demikian besar fungsi Surau bagi perkemba-ngan generasi muda Minang pada masa lalu. Karena itu sungguh sebuah ironi, bila lembaga yang demikian strategis akhirnya mengalah pada perubahan.
Surau mewadahi proses lengkap dari sebuah regenerasi masyarakat Minang, sesuatu yang sulit dicari tandingannya dalam kultur manapun di dunia ini. Segala kebutuhan yang bersifat praktis, skill, kebijaksanaan, tutur kata dan tata krama yang diperlukan orang Minang pada masa dewasanya sebagian besar diperoleh di Surau. Adat budaya yang mengacu pada konsepsi alam takambang jadi guru yang melahirkan kebijkasanaan sehingga orang Minang harus tahu di nan-ampek (kato mandaki, kato manurun, kato mandata dan kato malereang), adalah bentuk kearifan yang diperoleh melalui pelatihan terpadu yang mengintegrasikan antara konsepsi ideologis dengan norma-norma budaya dan praktis lewat lembaga semacam Surau. Masyarakat tardisional yang di-back up oleh adat sangat kaya dengan prinsip-prinsip hidup semacam ini, sekedar menyebut contoh, misalnya untuk memberi i’tibar terhadap sikap tawadhu’ ada ungkapan ilmu padi, makin barisi makin marunduak.
Seiring dengan berkembangnya Islam, Surau menjadi aset yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan dan mengenalkan konsep-konsep dasar Islam. Kedatangan Syekh Burhanuddin di penghujung abad ke-17 dengan mendirikan Surau di daerah Ulakan Pariaman menjadi titik awal dari terbentuknya karakter tradisional Islam hampir di seluruh wilayah penyebaran maupun pengaruhnya. Hal itu disebabkan karena kemampuan Tarekat Syattariyah yang dibawa oleh Burhanuddin sangat meng-akomodasi tradisi lokal. Aspek-aspek tasauf yang dikandung dalam ajaran ini—sebagaimana halnya dengan pengalama-pengalaman awal islamisasi di wilayah nusantara—memudahkan diterimanya Islam, karena memiliki kesamaan-kesamaan dengan ajaran Hindu/Budha yang telah terlebih dahulu dipraktekkan.
Kedekatan emosional masyarakat Minang dengan Surau menjadi faktor kunci lestarinya pemahaman tradisional di ranah Minang dan buah dari sebuah interaksi antara dua kultur yang saling berdialog. Sudut pandang kelompok modernis terhadap Surau tradisional sesungguhnya melepaskan ikatan-ikatan kul-tural ini yang telah terjalin demikian lama sehingga memuncul-kan bentuk-bentuk Islam tradisi yang mapan di wilayah Minang-kabau. Ada narasi sejarah yang terpenggal dari sudut pandang seperti ini, meskipun pada tataran kebutuhan praktis yang bersifat temporal, pembaharuan yang digaungkan Islam modernis patut diapresiasi juga. Pemaksaan atas narasi besar Islam Arabia (ideologisasi Islam seolah-olah hanya tipikal Arab-lah yang benar) di gelanggang persemaian Islam kultural tentu sulit diterima, apapun alasannya.
Ada sekian proses-proses penyesuaian dalam narasi kecil Islam nusantara yang tidak harus dinilai sebagai bid’ah, kafir, jumud dan seterusnya. Dengan demikian, Surau dalam kerangka demikian—meminjam sebutan yang digunakan Nurcholish Madjid untuk Pesantren di Jawa—tidak hanya identik dengan makna keislaman, namun juga mengandung keaslian (indigenous) yang berangkat dari kearifan lokal. Dengan kata lain, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan tersendiri ketika Islam hadir dan mengidentifikasi diri terhadap unsur lokal. Kemampuan Tarekat Syattariyah melakukan pendekatan dengan cara sufistik terhadap membuat islamisasi yang terjadi di wilayah Minang-kabau tidak mengancam fondasi dasar masyarakat Minang, bahkan memperkaya elemen-elemen kultural yang ada.
Dari perspektif ini, Taufik Abdullah melihat bahwa pembentukan tradisi—sebagai sesuatu yang dilestarikan dari masa lampau—lebih dari sekedar persoalan legitimasi, namun juga menyangkut persoalan otoritas dan kewenangan. Sesuatu yang disebutnya sebagai paradigma kultural untuk melihat dan memberi makna terhadap kenyataan, yang tumbuh dari proses seleksi, dimana harapan berbenturan dengan kenyataan, dan kebebasan ekspresi harus mencari bentuk terbaik dengan keharusan-keharusan sturktural. Pada saaat itu, tradisi dapat dianggap sebagai seperangkat nilai dan sistem pengetahuan yang mengarahkan sifat dan corak komunitas. Dengan kata lain, menurut Abdullah, tradisi telah memberi kesadaran identitas serta rasa keterkaitan dengan sesuatu yang dianggap lebih awal.
Mengikatkan diri kepada sumber atau person-person masa lalu adalah sebuah keharusan bagi tarekat Syattariyah bila ingin memperkenalkan Islam dalam struktur adat yang sudah terbentuk. Bukankah terbentang jarak yang sangat jauh antara wilayah Minangkabau dengan pusat Islam di Timur Tengah? Dan disepakati oleh para ahli sejarah bahwa pengenalan Islam ke wilayah ini bukan dengan wajah kekerasan. Lalu bagaimana Islam mengidentifikasi diri jika tidak dengan melakukan penyesuaian pada taraf tertentu terhadap tradisi yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat lokal, sebagaimana ia harus mengidentifikasi diri sebagai bagian otentik dari dunia Islam meskipun terpencil ?
Sebagai kelanjutan dari menguatnya posisi agama dalam struktur adat Minangkabau, maka berakibat pula pada menguat nya kedudukan ulama dan guru-guru agama. Di bawah pengelolaan ulama-ulama tradisional, surau-surau melanjutkan peran-peran lamanya sebagai pusat pencerdasan masyarakat dengan warna tradisional yang kental.
Tulisan Lengkap : diterbitkan dalam Jurnal KHAZANAH Vol. II/No. 1

























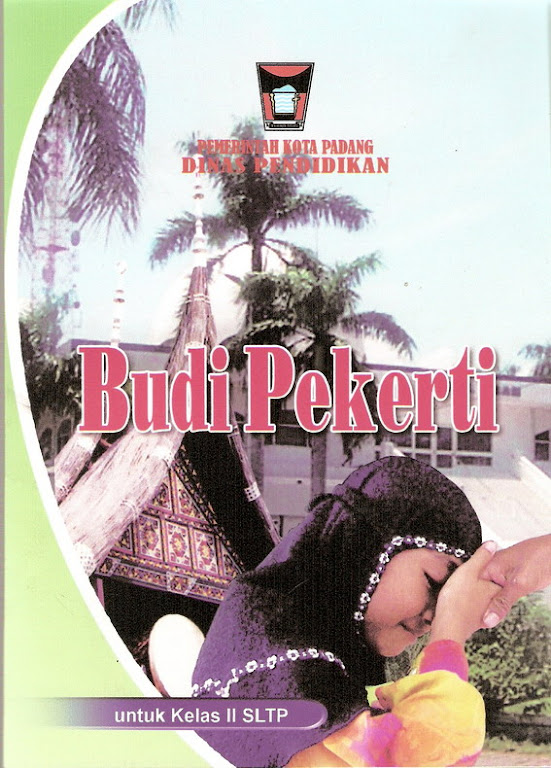





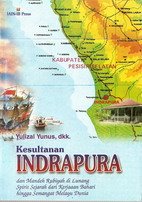




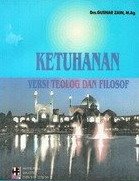
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar