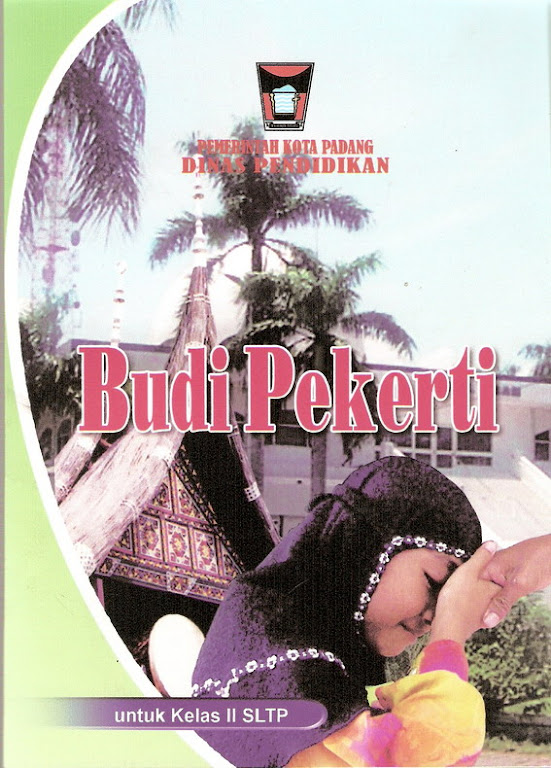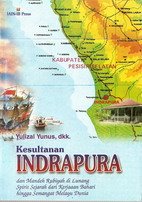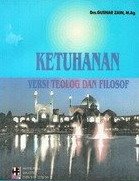Oleh : Andri Rosadi, M.Hum (Dosen Antropologi FIBA)

Dari permukaan, kita bisa melihat bahwa globalisasi dan fundamentalisme Islam merupakan dua fenomena yang kontras. Globalisasi menggiring seluruh dunia menuju universalitas budaya yang direpresentasikan oleh kultur Barat, dan lebih khusus lagi, Amerika Serikat. Sementara fundamentalisme Islam menolak segala sesuatu yang berbau barat, kecuali beberapa produk teknologi yang berkaitan dengan militer dan informasi. Namun, dalam tataran yang lebih dalam, sebenarnya fundamentalisme Islam memiliki semangat yang sama dengan globalisasi: universalisasi budaya. Gerakan-gerakan Islam trans-nasional, seperti Hizbu Tahrir dan Gerakan Salafi secara jelas menunjukkan kecenderungan tersebut.
Pengantar
Hizbut Tahrir memiliki cabang di puluhan negara, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat; sementara Gerakan Salafi lebih banyak berkembang di negara-negara yang memiliki konflik langsung dengan kekuatan Barat. Dalam konteks ini, maka pertentangan antara hegemoni Barat dan fundamentalisme Islam sebenarnya terjadi karena adanya kontestasi pengaruh untuk merebut dominasi, dan oleh sebab itu, gerakan-gerakan tersebut lebih bercorak politik daripada agama. Secara sederhana, ada dua sasaran perlawanan para fundamentalis Muslim: far enemy yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan close enemy yaitu rezim di negara Muslim (Gerges 2005: 1). Dalam konteks ini, saya akan meletakkan kontestasi pengaruh tersebut dalam kerangka challenge and response, dalam pengertian bahwa respons kelompok-kelompok fundamentalis Islam lebih merupakan jawaban terhadap tantangan yang mereka hadapi akibat penetrasi langsung ataupun tidak langsung dari kekuatan Barat. Universalitas budaya Barat, di mata kelompok fundamentalis, telah mengancam universalitas Islam, dan oleh sebab itu muncul reaksi perlawanan. Maka hal yang sangat wajar bila kita melihat bahwa kebangkitan fundamentalisme Islam selalu berjalan seiring dengan menguatnya dominasi Barat di dunia Muslim, terutama yang ditandai dengan kehadiran militer. Sebagai representasi gerakan fundamentalis, saya akan lebih terfokus pada Gerakan Salafi Indonesia yang bersifat trans-nasional.
Perspektif Memahami Gerakan Salafi
Fundamentalisme merupakan konsep yang pemaknaannya merujuk pada seluruh kelompok-kelompok keagamaan--apapun agamanya--yang ingin dan berusaha untuk hidup sesuai dengan pemahaman mereka terhadap wahyu (Mousally 1999: 66-67), yang biasanya dipahami sangat literal. Pemaknaannya merujuk baik pada tataran diskursus ataupun aktivisme (ibid: 120). Selain istilah fundamentalisme yang digunakan oleh Tibi (1998), Azra (1996), Watt (1997), Choueri (1997), Burrel (1995) dan Karyono (2003), para sarjana juga menggunakan beberapa istilah lain dengan makna yang relatif sama, seperti radikal (lihat Sivan (1985); Anderson (1997); Zada (2002); dan Turmudi, et. al. (2005)), Islamist (lihat Ismail: 1993) dan neofundamentalisme (Roy: 2005). Dalam makalah ini, saya menyebut Gerakan Salafi sebagai kelompok fundamentalis berdasarkan luas cakupan perubahan yang mereka inginkan dan strategi perjuangan yang mereka pilih untuk mencapai perubahan tersebut. Secara sederhana, cakupan perubahan yang mereka inginkan meliputi seluruh dunia, dengan strategi yang mentoleransi penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam gerakan radikal fundamentalis, perubahan ditandai dengan penolakan secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku, karena adanya kejengkelan moral yang kuat terhadap kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa (Kartodirjo 1984: 38). Berdasarkan uraian tersebut, gerakan Salafi saya letakkan dalam konteks respons terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia dengan tujuan untuk memperbaiki, mengurangi ataupun menolak berbagai pelanggaran agama yang terjadi, baik karena pengaruh internal maupun eksternal. Ada anggapan yang kuat di kalangan para Salafi bahwa Indonesia sudah jauh dari cita-cita negara Islam yang ideal. Absennya penerapan syariah Islam, kuatnya pengaruh Barat, terutama Amerika Serikat, dan seringnya orang Islam menjadi korban kekerasan seperti yang terjadi di Poso, Ambon dan Aceh adalah bukti dari anggapan tersebut.
Kata Salafi berasal dari bahasa Arab salaf, secara etimologis berarti masa lalu atau telah terjadi di masa lalu (Ma’luf 1986: 346). Dari kata salaf ini, kemudian berkembang istilah Salafiah, Salafiyun dan Salafi. Salafiah adalah khazanah ilmu atau ajaran salafusshaleh (pious ancestors); Salafiyun (bentuk tunggalnya: Salafi) adalah orang-orang yang mengikuti ajaran salafusshaleh (al-Thalibi 2006: 8-9). Seiring perkembangan, Salafiah kemudian menjadi mazhab Islam yang menyandarkan pendapat dan perilakunya berdasarkan apa yang telah dilakukan para sahabat Nabi Muhammad di masa lalu (Ma’luf 1986: 346; al-Thalibi 2006: 8; Buthi 1998: 9; Adonis 1998). Proses penyebaran mazhab Salaf ini disebut Gerakan Salafi yang berintikan seruan agar umat Islam kembali pada aqidah yang murni, sebagaimana yang dipraktikkan para sahabat Nabi. Menurut Lembaga Riset WAMY (2006) yang berpusat di Mekkah, Gerakan Salafi sebenarnya nama lain gerakan Wahhabi yang berkembang di Saudi Arabia. Secara genealogis, pemikiran Salafi bisa dirunut sebagai berikut: Salafusshaleh—Ibnu Taymiyah—Muhammad bin Abdul Wahhab—Ulama Saudi dan Yaman (lihat Samudera: 2004; Baabduh: 2005; Abdul Haq al Makky: 1998; Buthi: 1998; al Thalibi: 2006).
Salafisme merupakan gerakan keagamaan yang muncul sebagai respons terhadap penyimpangan internal dalam tubuh umat Islam sendiri dan ancaman eksternal yang dihadapi. Berkaitan dengan pengertian gerakan keagamaan, saya merujuk pada definisi Nottingham (1985: 155) yaitu: setiap usaha yang terorganisasi untuk menyebarkan agama baru, atau interpretasi baru mengenai agama yang sudah ada. Untuk kepentingan operasional, definisi ini kemudian saya perluas mencakup juga revitalisasi dan kontekstualisasi tafsir yang pernah ada. Gerakan Salafi berusaha untuk merevitalisasi ajaran-ajaran yang mereka anggap berasal dari Nabi dan para salafusshaleh, dan pada saat yang sama menolak bahkan mengkafirkan semua praktik-praktik yang mereka anggap tidak berasal dari Nabi. Sebagai organisasi keagamaan, Salafi juga memiliki acuan duniawi dan ukhrawi yang terrefleksi dari target-target kekuasaan dan ekonomi yang mereka perjuangkan. Dalam tataran ini, operasinya tidak berbeda dengan pemegang kekuasaan politik. Sementara acuan ukhrawi merujuk pada digunakannya teks suci sebagai basis legitimasi gerakan. Penggunaan doktrin agama sebagai basis legitimasi gerakan inilah yang membedakan Geraka Salafi dengan komunitas ekslusif lainnya.
Para aktifis Salafi saya posisikan sebagai komunitas eksklusif, bercirikan pola pikir dikotomis dan menolak yang tidak sesuai dengan prinsip dan keyakinan mereka. Dalam komunitas ekslusif, ada batas-batas, hierarki, kohesi sosial dan loyalitas kelompok yang jika diterapkan terlalu rigid, akan menghasilkan kekerasan terhadap kelompok lain (Ahmed 2003: 43). Pola-pola inklusi dan ekslusi yang dipraktikkan dalam komunitas Salafi bisa disebut sebagai identitas sosial yang mempengaruhi proses pemaknaan dalam hidup mereka sehari-hari. Proses konstruksi identitas sosial tersebut bersifat dialektis, yang mengandung klaim dan anti klaim, yang berujung pada terbentuknya suatu identitas tersendiri (Lukens-Bull 2004: 26). Dalam proses konstruksi tersebut, negara dan rezim keagamaan memainkan peranan penting (Doja 2004: 75) yang akan menentukan karakter politik suatu gerakan keagamaan.
Setiap komunitas eksklusif biasanya berusaha melakukan perubahan mendasar dengan kekuatan yang bertumpu pada kekuatan sosial dalam hubungan komunal mereka (Calhoun 2000: 894-895). Berdasarkan cakupan perubahan, Giddens, sebagaiman dikutip Azhar (1999: 26) membatasi perubahan yang diinginkan oleh kelompok ekslusif tersebut sebatas pada tatanan yang menyimpang dan merugikan, bukan keseluruhan. Azhar (1996: 26) menambahkan ciri lain dalam proses perubahan tersebut: kekerasan. Sebagai kelompok yang saya posisikan sebagai komunitas ekslusif, kekerasan yang dilakukan oleh para Salafi ada yang bersifat simbolik dengan menyalahkan, bahkan mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham, dan ada juga kekerasan fisik seperti yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudera.
Sebagai suatu komunitas, para Salafi yang bersifat trans nasional tidak merasa terikat pada wilayah tertentu. Basis loyalitas mereka adalah agama, bukan negara. Dalam kerangka ini, komunitas Salafi bersifat non teritorial, dan para anggotanya memiliki ciri-ciri serupa, biasanya dihimpun oleh suatu rasa memiliki, ikatan dan interaksi sosial tertentu sehingga menjadi entitas sosial tersendiri (Azarya 2000: 145). Ikatan kebersamaan yang dibangun dalam komunitas Salafi lebih bersifat emosional yang bersumber dari ikatan kesamaan agama, sejarah, nasib, nilai dan pandangan yang bersifat trans nasional. Rasa memiliki dan solidaritas yang bersifat trans nasional ini memainkan peran yang sangat penting pada kebangkitan aktivisme Salafi. Para Salafi tersebut, menurut Bubalo dan Fealy (2005) ibarat caravan yang bergerak lintas negara bahkan benua. Oleh sebab itu, sangat lazim jika para pengikut Salafi tidak memiliki rasa nasionalisme pada negara tertentu. Banyak di antara mereka yang melibatkan diri dalam konflik di Afghanistan, Asia Tengah, Thailand Selatan dan Filipina Selatan, walaupun mereka tidak berasal dari kawasan tersebut.
Satu hal penting lain yang harus dipahami pada komunitas Salafi adalah tentang cara mereka membayangkan masa lalu, karena pemahaman dan ide yang mereka kembangkan berbasis pada praktik pengalaman masa lalu di era Nabi dan sahabatnya; suatu era yang digambarkan sebagai sebaik-baik zaman, semakin jauh dari era tersebut dianggap semakin mengalami degenerasi. Ironisnya, perilaku-perilaku simbolik yang tampak menonjol untuk mengikuti pola hidup para salafusshaleh tersebut adalah memelihara janggut, memakai jubah dan pakaian di atas mata kaki dan makan dengan tiga jari. Dalam varian Salafi yang menekankan jihad, seperti kelompok Imam Samudra, yang mereka bayangkan bukan hanya masa lalu di era Nabi, tapi juga penderitaan yang dialami umat Muslim di Palestina, Irak, Afghanistan, Philipina Selatan, Asia Tengah dan kawasan lainnya. Inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk berjihad. Bisa dikatakan bahwa, para Salafi berusaha untuk menggiring masa kini ke masa lalu, dan menjadikan masa lalu sebagai satu-satunya basis legitimasi perilaku di masa kini (Adonis 2002).
Membayangkan masa lalu adalah permasalahan yang berkaitan dengan memori, yang disebut oleh Sorabji sebagai individual’s awareness of memory (Sorabji 2006: 3). Dalam proses pembentukannya, memori tersebut, menurut Halbwachs dipengaruhi oleh suatu konteks sosial (dikutip via Sorabji 2006: 2). Artinya, faktor eksternal memiliki peran penting dalam proses konstruksi dan rekonstruksi. Karena Gerakan Salafi bersifat kolektif, maka memori individu pada konsep Sorabji bisa dikembangkan ke memori sosial yang dibagi (share), dirasa dan pada saat yang sama mengontrol kehidupan para Salafi sehari-hari. Dalam pengertian ini, memori bisa juga dipahami sebagai a form of practical wisdom (Lambek, dikutip via Sorabji 2006: 3).
Ada dua klasifikasi memori yang berkembang dalam psikologi: episodic memory dan semantic memory. Episodic memory mengacu pada episode dalam kehidupan yang dialami langsung oleh seseorang, sementara semantic memory mengacu pada suatu fakta yang dipelajari (Sorabji 2006: 12). Berdasarkan pengertian ini, keterlibatan langsung Tarmiji dalam konflik di Ambon dan Poso, Imam Samudra, Jafar Umar Thalib dan Umar Patek di Afghanistan serta Dulmatin di Mindanao bisa dilihat sebagai bagian dari episodic memory dalam hidup mereka. Sementara keinginan para Salafi lainnya untuk makan dengan 3 jari tangan, memelihara janggut dan memakai jubah putih khas Arab merupakan bagian dari memori yang dipelajari (semantic memory). Menurut saya, sangat penting bagi kita untuk meneliti lebih dalam bagaimana memori sosial tersebut membentuk gagasan dan perilaku para Salafi. Dalam hal ini, konteks sosial politik, seperti penderitaan kaum muslim di tempat tertentu, ataupun ancaman dari penetrasi budaya asing berperan sangat penting. Hal ini sejalan dengan Novak dan Rodseth yang menganalisa memori sosial melalui massacre dan collective violence yang terjadi (Novak dan Rodseth 2006: 2).
Gerakan Salafi di Indonesia
Dalam sejarahnya, gerakan Salafi pertama kali muncul di Saudi Arabia dengan nama gerakan Wahabi, kemudian tersebar ke Afrika, Anak Benua India hingga Asia Tenggara. Azra (1996: 110-112) menggolongkan Gerakan Salafiyah Wahhabi sebagai fundamentalisme Islam pra modern, yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari segala penyimpangan. Saat ini, gerakan Wahabi di seluruh dunia masih dibiayai oleh Saudi Arabia (Haghayeghi 2002: 318). Ada 1500 masjid, 210 Islamic Centers dan hampir 2000 colleges yang dibiayai Saudi, dimana paham Wahabi kemudian diajarkan dan ditransformasikan (Gadzey 2005: 303).
Di Indonesia, Gerakan Salafi dalam pengertian umum telah lama muncul. Muhammadiyah, Persis dan gerakan Paderi yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam sangat dipengaruhi paham Wahhabi yang berkembang di Saudi Arabia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) juga punya hubungan erat dengan Saudi Arabia dalam membendung gerakan Kristenisasi (Bruinessen 2004: 39). Gerakan-gerakan tersebut muncul dalam konteks kebangkitan Islam, yang dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi dan modernitas, pengaruh internasional dan ketegangan politik (Mehden 2001: 266-270).
Gerakan Salafi di Indonesia bergerak secara institusional maupun individual. Di Yogyakarta, komunitas Salafi membangun lembaga pendidikan sendiri yang bertujuan untuk mendidik kader-kader muda Salafi. Sekolah Salafi Madukismo, Pesantren Jamilurrahman, Pesantren Imam Bukhari dan Pesantren Bin Baz merupakan contoh dari beberapa lembaga tersebut. Para santri belajar setiap hari tanpa terikat oleh hari libur nasional. Walaupun kenyataan ini secara sekilas menunjukkan adanya perbedaan antara lembaga pendidikan Salafi dengan negara, namun, terlalu dini untuk menilai bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan kita dalam memahami konsep negara kebangsaan Indonesia. Dibutuhkan informasi yang lebih mendalam untuk memahami secara lebih baik seluruh perilaku, pandangan dan juga memori sosial para Salafi tersebut. Ketergesaan dalam memberikan klaim dan ‘tuduhan’ terkadang sama sekali tidak menambah pemahaman kita terhadap mereka.
Secara individual, gerakan ini berjalan melalui relasi personal antar kenalan. Suatu ketika, pada bulan November 2006 di Yogyakarta, ada sebuah pengumuman tentang kamar kos yang ditempel di beranda Masjid UGM. Berbeda dari biasanya, mahasiswa yang akan diterima disyaratkan menganut mazhab salaf. Dalam kasus ini, tampak bahwa mazhab salaf telah menjadi identitas yang menetukan, apakah seseorang menjadi bagian dari self atau other.
Kecenderungan untuk membangun boundary di kalangan para Salafi ini terrefleksi dari adanya penilaian bahwa gerakan Islam lainnya kurang berpijak pada syariah (Karim al-Aql 2003: 114-115). Kecenderungan tersebut terekspresi dalam perilaku sosial politik mereka, sehingga menimbulkan perlawanan dari komunitas lain yang dituduh tidak Islami, seperti yang terjadi di desa Sesele Lombok, Nusa Tenggara Barat, dimana sebuah pesantren Salafi diserang dan para Salafi diusir dari desa oleh masyarakat (Kompas: 18 Juni 2006). Tampak jelas bahwa kecenderungan untuk memonopoli kebenaran ini memiliki implikasi sosio-relijius yang sangat besar pada, terutama, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kehidupan politik, kecenderungan ekslusifitas para Salafi menyebabkan mereka mengambil sikap yang bertentangan dengan kebijakan negara. Sebagai contoh, para Salafi menolak berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia dengan alasan: (1), pemilu adalah bagian dari sistem demokrasi yang bertentangan dengan syariat Islam; (2), nilai suara seorang muslim dan non muslim sama, seharusnya, suara muslim lebih tinggi; (3), nilai suara seorang laki-laki dan perempuan sama, seharusnya, suara seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Disini terlihat perbedaan kategori sosial budaya antara para Salafi dengan negara.
Monopoli kebenaran yang dilakukan oleh para pengikut Salaf didasarkan pada hadits Nabi yaitu: (artinya): “sesungguhnya umat Islam akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Semua golongan tersebut di neraka, kecuali satu: al jamaah”. Menurut para Salafi, maksud al jamaah di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan Salafisme adalah nama lain ahlu sunnah wa al jamaah. Berarti, satu-satunya golongan yang selamat hanyalah Salafisme (Karim al Aql 2003: 16-18).
Di tengah eksklusifitas tersebut, realitas internal Salafi sendiri menunjukkan banyak varian, masing-masing mengaku paling benar. Akibat kuatnya kecenderungan untuk mengklaim kebenaran ini, perbedaan-perbedaan paham dan pandangan terhadap berbagai permasalahan selalu diikuti dengan aksi saling menyalahkan di antara mereka. Sebagai contoh, Luqman Baabduh, tokoh Salafi Yogyakarta dituduh Murjia oleh kelompok Ngruki Solo. Sebaliknya, kelompok Ngruki dianggap Khawarij oleh kelompok Luqman Baabduh (2005). Baabduh juga mengecam model perjuangan yang dilakukan oleh Imam Samudera dan Hasan al-Banna (As Syariah, vol. II no 20: 2005). Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Baabduh ini kemudian dibantah oleh Zulfidar (2006), tokoh yang juga sering diafiliasikan sebagai pengikut Salaf dengan grup al-Kautsar di Jakarta. Tokoh Salafi lainnya, Imam Samudera dalam bukunya Aku melawan Teroris (2004: 3) secara eksplisit membagi Salafisme menjadi dua: Salafi murni dan yang telah terdistorsi. Salafi pertama adalah mereka yang konsisten dengan idealisme perjuangan untuk menegakkan agama Islam; sementara kelompok kedua adalah mereka yang takut untuk berjuang demi agama. Di Yogyakarta, istilah Salafi merujuk pada dua kelompok penting: Salafi Lor yang menjadi markas Lasykar Jihad di bawah kendali Jafar Umar Thalib, dan Salafi Kidul yang berpusat di Bantul.
Perbedaan paham dalam Gerakan Salafi, dalam tataran tertentu, bukan hanya disebabkan oleh perbedaan paham keagamaan, tapi juga afiliasi politik. Para pengikut Salaf biasanya memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan patron politik mereka. Secara garis besar, ada dua patron tertinggi yang mendominasi pengikut Salaf di Indonesia pada saat ini: Syaikh Muqbil bin Hadi di Yaman, dan Syaikh Bin Baz di Saudi Arabia. Pemahaman lebih lanjut mengenai Gerakan Salafi di Indonesia harus mampu mengungkap pola relasi patron-client antara para Salafi di Indonesia dengan guru-guru mereka di Yaman dan Saudi Arabia. Perbedaan utama antara Salafi Yamani dan Saudi Arabia adalah, yang pertama lebih memiliki kecenderungan pada aktivisme, sehingga sering terlibat pada konflik fisik, sebagaimana yang terlihat pada kasus Lasykar Jihad yang dikirim ke Ambon.
Transformasi ajaran Salafiyah ke Indonesia, secara umum masuk melalui tiga jalur (lihat Bubalo dan Fealy 2005: 47-64) yaitu: (1) pendidikan, dengan banyaknya mahasiswa Indonesia yang menuntut Ilmu di Saudi Arabia dan Yaman, baik dalam pendidikan formal maupun non formal; (2) human movement yang masuk ke dalam caravan Salafi internasional dan mereka bergerak lintas negara, terutama di daerah-daerah konflik seperti Afghanistan, Pakistan, Asia Tengah, Thailand Selatan dan Filipina Selatan; (3) internet dan penerbitan buku-buku yang menyebarkan ajaran Salaf. Baik Salafiyah Yaman ataupun Saudi Arabia masuk melalui ketiga jalur ini.
Untuk tataran yang lebih lanjut, ada indikasi bahwa kelompok Salafi yang menganut garis keras (aktivisme) sudah merasa kurang aman berada dalam payung Salafisme disebabkan faktor keamanan seiring gencarnya Densus 88 melakukan operasi. Informasi awal yang saya dapatkan tentang ini baru sebatas wilayah Sumatra Barat dan Riau. Kelompok yang dijadikan sebagai ‘tempat pelarian’ adalah Jamaah Tabligh yang selama ini dikenal tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik apapun. Akibatnya, karakter non politik yang selama ini melekat pada Jamaah Tabligh mulai dipertanyakan seiring ditemukannya keterlibatan beberapa orang anggota Jamaah sebagai pelaku pemboman di Jakarta. Dalam konteks ini, hal yang perlu diteliti lebih lanjut sebenarnya adalah: (1) apa dan bagaimana konteks relasi antara Salafi di Indonesia dengan Salafi Timur Tengah? (2) Bagaimana proses transformasi mazhab Salafi menjadi suatu tindakan dan gerakan sosial yang berbasis keagamaan dengan segala variannya?; dan (3) bagaimana jaringan dan gerakan sosial tersebut memberi pengaruh pada gerakan Islam di Indonesia?
Keberhasilan dalam menemukan informasi mengenai pertanyaan di atas akan sangat membantu kita untuk memahami penyebab eksternal kemunculan Gerakan Salafi Indonesia dan bagaimana bentuk relasi patron-client antara murid dan syaikh yang memegang otoritas keputusan tertinggi. Di samping itu, informasi tersebut juga akan membantu kita untuk memetakan Gerakan Salafi dan varian-variannya, memberikan pemahaman mengenai proses terbentuknya identitas keagamaan di kalangan Salafi, dan bagaimana identitas ini kemudian menggerakkan para Salafi untuk melakukan suatu gerakan.
Untuk konteks ke depan, konfrontasi antara kelompok fundamentalis Muslim--termasuk Salafi--dengan pemerintah akan sangat bergantung pada tiga hal: kebijakan pemerintah, apakah memihak pada isu-isu yang menjadi concern kelompok fundamentalis atau sebaliknya; rangsangan eksternal yang dipicu oleh kebijakan Barat yang dianggap tidak adil dan menzalimi kaum Muslim; dan inisiatif dari kelompok fundamentalis itu sendiri sebagai jawaban dari challenge yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Dekmejian 2001: 24). Kondisi ekonomi yang semakin memburuk dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan sebab-sebab yang juga dominan dalam mendorong kemunculan gerakan fundamentalis. Kenyataan tersebut mereka pahami sebagai simbol kegagalan sistem sekuler dalam memakmurkan rakyatnya. Berdasarkan kenyataan ini, mereka kemudian merasa memiliki alasan kuat untuk menerapkan sistem yang mereka yakini Islami dan mampu menciptakan keadilan ekonomi sebagai ganti dari sistem sekuler yang terbukti gagal. Kenyataan ini menunjukkan bagaimana kemunculan kelompok-kelompok fundamentalis harus diletakkan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, baik dalam skala lokal, regional maupun global.
Penutup
Makalah singkat ini sebenarnya lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban disebabkan keterbatasan informasi primer mengenai Gerakan Salafi. Sangat sedikit, kalau tidak mau dikatakan tidak ada, studi-studi yang berbasis pendekatan etnografi--sehingga memungkinkan penulisnya untuk hidup lebih dalam dengan para Salafi—yang dihasilkan oleh para peneliti tentang kehidupan para fundamentalis, terutama para Salafi. Oleh sebab itu, pemahaman kita tentang Gerakan ini masih bersifat parsial dan terkadang menyimpang dari yang sebenarnya. Riset lanjutan sangat diperlukan dalam kerangka untuk pemahaman yang lebih baik, dan dalam tataran tertentu, juga untuk mencegah semakin berkembangnya social boundary di masyarakat akibat menguatnya semangat ekslusifitas para Salafi. (Andri Rosadi, Staf Jurusan SKI).
 Sulit untuk dibantah, Muhammad Natsir menjadi salah satu "legenda" demokratisasi dan Islam politik Indonesia. Natsir yang dikatakan George Kahin sebagai demokrat-religius nan bersahaja (karena hanya memiliki sehelai kemeja ketika ditunjuk menjadi Menteri Penerangan tahun 1946 ini) sampai hari ini dianggap sebagai "Bapak" intelektual Islam Indonesia sekaligus figur utama dalam mengakomodasi partai a-la "barat" dengan keteguhan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan teologis (Islam).
Sulit untuk dibantah, Muhammad Natsir menjadi salah satu "legenda" demokratisasi dan Islam politik Indonesia. Natsir yang dikatakan George Kahin sebagai demokrat-religius nan bersahaja (karena hanya memiliki sehelai kemeja ketika ditunjuk menjadi Menteri Penerangan tahun 1946 ini) sampai hari ini dianggap sebagai "Bapak" intelektual Islam Indonesia sekaligus figur utama dalam mengakomodasi partai a-la "barat" dengan keteguhan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan teologis (Islam).