oleh : DR. Yasmadi Kajian ilmu nahu selama ini lebih menitikberatkan pada persoalan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk jabatan satu kata dalam kalimat. Dapat juga dikatakan bahwa pelajaran nahu lebih fokus untuk mengetahui bagaimana bentuk akhir sebuah kata, i`râb ataukah mabni. Misalnya, menentukan apakah kata itu termasuk kategori marfû`ât, mansûbât, ataukah majrûrât untuk kata-kata yang berbentuk ism, atau kata tersebut masuk kategori marfû`at, mansûbat, ataukah majzûmat untuk kata-kata yang berbentuk fi`il.
Kajian ilmu nahu selama ini lebih menitikberatkan pada persoalan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk jabatan satu kata dalam kalimat. Dapat juga dikatakan bahwa pelajaran nahu lebih fokus untuk mengetahui bagaimana bentuk akhir sebuah kata, i`râb ataukah mabni. Misalnya, menentukan apakah kata itu termasuk kategori marfû`ât, mansûbât, ataukah majrûrât untuk kata-kata yang berbentuk ism, atau kata tersebut masuk kategori marfû`at, mansûbat, ataukah majzûmat untuk kata-kata yang berbentuk fi`il.
Maka pelajaran nahu selama ini lebih kepada membicarakan harkat akhir sebuah kata dan kemudian menjelaskan sebab-sebab dan ilalnya. Paling tidak materi-materi seperti inilah yang dijumpai dalam pembelajaran nahu dari tingkat ibtidai, bahkan sampai perguruan tinggi di Indonesia sampai saat sekarang.
Beberapa dekade belakangan ini, orientasi kajian ilmu nahu mulai terjadi pergeseran di kalangan akademisi, terutama oleh mereka pemerhati ilmu linguistik Arab. Yang semula kajian ilmu nahu Arab lebih bersifat normatif dan aplikatif sekarang muncul kecendrungan yang kuat untuk membawa kajian dan pemikiran ilmu nahu dalam tinjauan filsafat dan sejarah. Memahami sejarah pemikiran ilmu nahu penting untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan-perbedaan dalam penetapan kaidah-kaidah nahu yang berimplikasi pada sikap penerimaan dan keterbukaan dalam menerima perbedaan tersebut. Yang juga jauh lebih penting adalah dengan memahami sejarah pemikiran ilmu nahu akan dirasakan betapa pentingnya perumusan dan perwujudan ilmu nahu ketika itu dalam kerangka menjaga keotentikan atau kemurnian al-Qur’an, termasuk juga memelihara geniusitas bahasa Arab dalam makna yang lebih umum. Dapat dikatakan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahu berhubungan secara signifikan dengan fenomena yang terjadi dalam sejarah perkembangan dan peradaban Islam.
Umat Islam Masa Khulafa Rasyidin
Selintas dalam perspektif sejarah Islam terlihat bahwa periode Khulafah Rasyidin terkenal dengan masa integrasi, ekspansi dan kemajuan dalam tahap awal. Dalam hal ekspansi misalnya, sebelum nabi Muhammad wafat tahun 632 M., seluruh semenanjung Arabia telah berada di bawah kekuasaan Islam. Pada masa-masa berikutnya daerah-daerah di luar Arabia jatuh ke bawah kekuasaan Islam pada periode Khulafa Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar (w. 13 H), Umar bin al-Khattab (w. 44 H), dan Usman (w. 36 H). Negara Islam yang masih “bayi” ketika itu disebut oleh ahli sejarah sebagai suatu kekhaisaran besar dan kekuatan baru yang terbesar. Mahmudunnasir melihat hal itu sebagai kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab dalam sepuluh tahun kekhalifahannya dengan berhasil menaklukkan Irak, Iran, Siria, Palestina, dan Mesir.
Keberhasilan umat Islam menduduki wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan nonmuslim, terutama pada abad pertama hijrah periode Umar, telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi peradaban Islam. Penaklukan tersebut telah melahirkan gerakan perubahan yang cukup luas mengenai pola perdagangan internasional, perniagaan warga perkotaan, pertanian, kemiliteran, dan pengaturan sistem pemerintahan. Di sisi lain, dengan semakin bertambahnya komunitas Islam yang berasal dari bangsa Persia dan bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Romawi sebelumnya maka juga menimbulkan persoalan baru bagi dunia Arab Islam yaitu terjadinya distorsi dalam penggunan bahasa fusha oleh mereka sebagai bangsa “pendatang” terhadap mereka yang terbiasa dengan menggunakan bahasa Arab secara fasih.
Kondisi ini membawa keprihatinan yang begitu tinggi di kalangan ulama melihat semakin banyaknya jumlah pemeluk Islam dan orang yang berada di bawah kekuasaan Islam dengan semakin intensnya mereka menggunakan simbol-simbol bahasa keagamaan. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika banyak dari mereka yang melafalkan al-Qur’an secara tidak benar. Tetapi, fenomena tersebut telah menjadi sebuah realitas faktual yang harus dihadapi umat Islam ketika itu dan dari satu sisi dapat dikatakan sebagai implikasi negatif dari ekspansi yang dilakukan umat Islam.
Berangkat dari realitas tersebut lahirlah sebuah kesadaran di kalangan para sahabat dan ulama untuk membuat ketentuan-ketentuan yang baku tentang tata bahasa Arab, dalam hal ini nahu, guna menjaga orisinilitas dan keotentikan Qur’an. Di sisi lain, mereka yang bukan berasal dari bangsa Arab atau orang-orang yang telah menjadi “Arab” juga merasakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan nahu tersebut. Mereka turut serta mempelopori dan memprakarsai usaha ini, karena itu pulalah ilmu nahu tidak lahir di jazirah Arab, tetapi ilmu ini justru muncul pertama kali di Irak, Basrah. Adanya kesadaran relatif tinggi oleh kedua pihak meskipun dengan alasan dan kepentingan yang berbeda maka nahu kemudian dirumuskan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelahiran Nahu
Berbeda dengan cikal bakal sejarah penyusunan dan pembakuan hukum Islam misalnya, yang berawal dari terjadinya berbagai perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang juga berimplikasi pada pemahaman terhadap wacana hukum Islam, penyusunan kaidah-kaidah nahu justru didorong oleh karena telah semakin banyaknya penganut Islam dari orang-orang berkebangsaan asing (`ajam) atau non-Arab. Maka dapat dikatakan bahwa penyusunan kaidah-kaidah nahu berawal dari keprihatinan yang cukup mendalam di kalangan ulama akan hilangnya pertalian yang kuat antara bahasa Arab dengan bahasa al-Qur’an, serta hilangnya orisinilitas dan keotentikan Qur’an sebagai kitab utama dan pedoman umat Islam.
Pada mulanya yang mendorong ulama dalam perumusan dan penyusunan kaidah-kaidah nahu bukan karena terjadinya perpecahan ataupun perbedaan mazhab di kalangan ulama-ulama nahu, tetapi justru karena semakin banyaknya orang asing yang menggunakan bahasa Arab dengan latar belakang bahasa yang amat beragam sebelumnya. Kondisi ini pada gilirannya mempersubur terjadinya salah ucap atau lahn dalam berbahasa. Jika dirumuskan secara umum ada dua faktor utama yang mendorong ulama melakukan hal tersebut, yaitu teologis, dan non-teologis.
Pertama, faktor teologis, ad-dîniy
Faktor agama, yaitu ketika itu adanya keinginan yang kuat di kalangan ulama melafalkan ayat-ayat al-Qur’an secara fasih dan benar. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya kasus lahn (salah ucap) terjadi dalam bacaan-bacaan ritual keagamaan. Lahn sebenarnya telah berlangsung cukup lama, bahkan telah terjadi sejak masa Rasulullah saw, periode Umar ibn Al-Khattab, dan seterusnya, meskipun dalam jumlah yang masih relatif sedikit. Seiring dengan perkembangan dan penyebaran agama Islam yang berakibat pada banyaknya daerah taklukan Islam yang memeluk agama Islam dimana mereka berasal dari daerah yang baragam dan bahasa yang juga beragam, maka lahn pun kian subur dan semakin banyak terjadi. Ketika itu banyak anak keturunan Arab yang terlahir dari ibu-ibu yang berasal dari warga “asing” atau non Arab yang secara otomatis mewariskan gaya bahasa, gaya bicara, dan dialek asing kepada mereka. Latar belakang inilah yang mendorong ulama untuk (الصواب من الخطأ في الكلام) membetulkan kesalahan-kesalahan dalam ucapan karena jika tidak diantisipasi lahn akan terus terjadi dan berkembang sehingga dikhawatirkan berimbas pada pengucapan ayat-ayat al-Qur’an al-karim.
Beberapa contoh kasus lahn
Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa kasus lahn tidak saja terjadi pada periode Khalifah Rasyidin, di masa Rasul pun kejadian lahn pernah ada, sehingga Rasul berkomentar (أرشدوا أخاكم فقد ضل ). Ibn Qutaibah juga meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang Arab badui mendengar muazin berkata (أشهد أن محمداً رسولَ الله) dengan menasbkan kata (رسولَ) yang seharusnya dibaca raf` karena khabr (أن). Lalu ia berkata, “celakalah ia.” Tetapi kemudian ketika orang tersebut mengunjungi sebuah pasar alangkah terkejutnya ia melihat banyaknya terjadi lahn dalam pembicaraan orang-orang yang ada di sana. Al-Jahiz juga mengemukakan seseorang yang mengucapkan (هذه عصاتي) seharusnya ia baca (هذه عصاي). Kemudian di Irak juga ia dengar orang mengucapkan (حيِْ على الصلاة) dengan kasrah harkat ya’ (ياء) yang seharusnya dibaca fath.
Ada ungkapan Umar yang cukup “ekstrim” berkaitan dengan lahn dalam membaca Qs. at-Tawbah (9):3. Ia mengatakan bahwa sebelum membaca al-Qur`an sebaiknya seseorang itu mengerti dengan bahasa Arab. Umar juga mengatakan : (تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة), pelajarilah bahasa Arab (nahu) maka akan memperkuat pemahaman dan menambah kewibawaan dan harga diri. Latar belakang munculnya statemen Umar ini karena ada seseorang yang membaca Qs. at-Tawbah (9):3 dengan menkasrahkan kata (رسوِلهِ) pada ayat tersebut:
(وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُو ُلِهُ)
Jika dibaca dengan menkasrahkan kata (رسوِلهِ) maka yang dipahami adalah Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul-Nya, padahal yang sebenarnya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.
Dari satu sisi, kiranya statemen Umar itu tidaklah berlebihan ketika dipahami bahwa Al-Qur’an adalah merupakan pedoman utama dalam agama Islam. Di dalamnya termuat ketentutan-ketentuan yang wajib dipedomani dalam berbagai aspek kehidupan, baik tentang persolaan ibadah, muamalah, akhlak, hubungan individu, sosial atau bermasyarakat. Maka untuk memahami semua ketentuan dasar tersebut perlu pemahaman yang utuh terhadap teks al-Qur’an yang kesemuanya memiliki keterkaitan erat kajian-kajian kebahasaan, seperti makhraj-makhraj hurufnya, tanda-tanda i`rabnya, huruf-huruf dari kata-katanya, susunan kata-katanya, fungsi kata dalam susunan kalimatnya, dan lain-lain.
Contoh kasus lahn yang lain, Al-Anbari menceritakan bahwa faktor yang mendorong Ali bin Abi Thalib tergerak untuk merumuskan ilmu nahu ini adalah ketika ia mendengar seorang membaca Qs. al-Hâqah (69):37: yang seharusnya dibaca (لاَ يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ) tetapi oleh orang tersebut ayat itu dibaca (لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئين َ).
Ada sebuah riwayat Abu Aswad Ad-Duali yang menceritakan bahwa suatu ketika anak perempuannya berkata kepadanya, (يا أبت ما أشدُ الحر). Lalu Abu Aswad malah juga bertanya kepada anaknya (أي زمان الحر أشد؟). Mendengar hal tersebut anaknya kemudian berkata bahwa dia bermaksud hanya menyampaikan suatu berita (dengan adat ta`ajjub), bukan tujuan untuk bertanya. Namun terjadi kesalahan pengucapan (ما أشد) yang seharusnya difathkan harkat huruf dalnya.
Kasus lahn menjadi persoalan besar bagi ulama yang mendorong mereka untuk berbenah dan segera merumuskan kaidah-kaidah nahu. Karena itu pula kemudian ketika muncul perbedaan pendapat ulama tentang apakah pembahasan pertama atau yang paling awal dalam bangunan ilmu nahu, sebagian kalangan berpendapat adalah bahasan tentang masalah-masalah yang telah diiventarisasi dan masuk dalam kategori lahn. Di samping itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pembahasan pertama dalam ilmu nahu adalah tentang apa yang banyak muncul dalam komunikasi lisan, seperti fa`il, maf`ul bih, mubtada’, khabr, dan lain-lain.
Perbedaan Qiraat Qur’an
Di samping persoalan lahn, perbedaan qiraat Qur’an juga menjadi faktor pendorong bagi para ulama dalam membuat suatu kaidah nahu yang baku. Hanya saja secara kuantitas kasus-kasus perbedaan qiraat Qur’an banyak muncul dan terjadi di kalangan ulama Kufah yang memang lebih dulu disibukkan dengan qiraat Qur’an jika dibandingkan dengan ulama-ulama Basrah. Perbedaan qiraat Qur’an tersebut secara kualitas kemudian menginpirasi ulama-ulama Kufah untuk menempatkannya sebagai dasar pertama (sumber simâ`) dalam penetapan kaidah-kaidah nahu. Dari perbedaan qiraat ini pulalah kemudian yang memicu terjadinya perbedaan-perbedaan kalangan Kufah dan Basrah dalam menetapkan sumber atau adillah an-nahwi untuk perumusan kaidah-kaidah nahu.
Munculnya qiraat-qiraat Qur’an juga menimbulkan persoalan baru di kalangan ulama yaitu bagaimanakah kedudukan qiraat Qur’an dan apakah qiraat-qiraat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber dalam penetapan kaidah-kaidah nahu. Hamzah misalnya berpendapat boleh mengatafkan isim zahir kepada domir yang majrûr, seperti kata (َالأَرْحَامِ) dalam ayat (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام ِ). Mayoritas ulama Basrah berpendapat tidak boleh mengatafkan isim zahir pada domir, tetapi Hamzah membolehkan padahal pada ayat tersebut tidak terjadi pengulangan huruf jarr. Ibn `Amr juga berpendapat bahwa boleh memisahkan kata mudaf dan mudaf ilaihnya dengan menempatkan maful bih di antara keduannya, sehingga Qs. al-An`am (6):137 (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ) menurut qiraat Ibn `Amr ayat tersebut dapat dibaca dengan (قَتـْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَآؤِهِمْ).
Di antara ayat dan qiraat Qur’an yang juga menjadi perdebatan, antara lain, misalnya kasus (اسْتَحْوَذ) yang seharusnya huruf ilat tidak berharkat. Para ulama sepakat bahwa boleh berhujjah dengan semua ayat-ayat Qur’an, baik dari kata-kata yang mutawatir, ahad, ataupun syâzz, tetapi tidak bisa mengkiaskan pada kata-kata yang dipandang sebagai syâzz seperti pada kata (اسْتَحْوَذ). Begitu juga kasus (َيَأْبَى) , yaitu fath harkat huruf ba’ (باء) sebagai `ain fi`ilnya sedangkan huruf tersebut tidak termasuk halq. Menurut Al-Farrâ’ (w. 207 H), tidak pernah ditemukan sebelumnya dalam tradisi orang Arab (فعَلَ يفعَلَ) padanan kata dengan harkat fath pada kedua `ain fi`ilnya, kecuali huruf kedua atau ketiga dari kata tersebut terdiri dari huruf halq.
Al-Kisâ’i (w. 189 H) dan beberapa imam qiraat lainnya juga berhujjah bahwa boleh menempatkan lâm amr (لام الأمر) pada kata mudhari` yang diawali dengan tâ’ khithab (المضارع المبدوء بتاء الخطاب), seperti kata (فَلْتَفْرَحُواْ) yang terdapat dalam Qs. Yunus (10):58, sebagaimana juga boleh menempatkan lâm amr (لام الأمر) pada kata mudhari` yang diawali dengan nun mudhara`ah, seperti pada kata (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ).
Di samping itu, munculnya ahli-ahli qiraat, seperti `Ashim (w. 127 H), Hamzah (w. 154 H), dan Ibn `Amr (w. 156 H), yang oleh mayoritas ulama diklaim mengandung kelemahan karena dianggap banyak memunculkan qiraat syazz -bahkan menurut As-Suyuti telah masuk dalam kasus lahn-. Namun perbedaan qiraat tersebut kemudian disikapi secara berbeda oleh ulama-ulama nahu. Mayoritas ulama Kufah menerima dan mengambil qiraat-qiraat itu secara umum. Mereka berhujjah dengan qiraat-qiraat tersebut terkait dengan kasus-kasus bahasa Arab jika ditemukan perbandingan atau ada unsur kesamaannya dalam khazanah bahasa Arab. Jika tidak ditemukan, mereka tolak. Terkait dengan qiraat Ibn `Amr misalnya tentang Qs. Al-An`am (6):137 (قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَآؤِهِمْ), mereka menerimanya sebab dalam tradisi dan khazanah bahasa Arab juga ditemukan kasus yang serupa dengan itu. Lain halnya bagi kelompok Basrah, menolak qiraat tersebut karena menurut mereka mudaf dan mudaf ilaih satu posisi (بمنزلة شيء واحد) dan antara mudaf dan mudaf ilaihnya hanya dapat dipisahkan dengan zharf dan huruf jarr.
Kedua, faktor non-teologis, ghair ad-dîniy
Faktor non agama dapat dirumuskan dalam dua hal. Pertama, nasionalisme Arab (قومي عربي) artinya bahwa orang-orang Arab amat menghargai bahasa mereka (bahasa Arab), mereka sangat memuliakan bahasa tersebut sehingga mereka sangat khawatir bahasa Arab akan rusak dan mengalami distorsi ketika bercampur dengan bahasa asing. Inilah yang mendorong para ulama untuk menyusun gramatika Arab agar bahasa Arab itu tidak hilang, atau lebur dengan bahasa asing. Di sisi lain, melalui bahasa agaknya orang-orang Arab ingin menampakkan identitas mereka selaku bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi. Dari sini telah mulai lahir cikal bakal nasionalisme Arab yang pada abad-abad berikutnya telah menjadi wacana yang menonjol bagi kalangan pemikir-pemikir moderat Islam Timur Tengah. Kedua, aspek sosiologis (اجتماعي) artinya bahwa bangsa-bangsa yang telah menjadi bangsa Arab memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap bahasa Arab itu sendiri dengan semua gramatika dan tata aturannya, sehingga mereka dapat berbicara secara baik dan benar sehingga mereka merasa diterima dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa Arab.
Kedua faktor utama di atas tadi saling berkaitan, artinya bahwa orang Arab butuh merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab untuk melanggengkan bahasa mereka sehingga terbebas dari pengaruh bahasa Asing. Dan melalui bahasa Arab isu-isu nasionalisme Arab terangkat dan menempatkan posisi yang layak. Di sisi lain, orang-orang non Arab yang telah menjadi bangsa “Arab” sangat butuh dengan kaidah-kaidah bahasa Arab agar mereka dapat menggunakan bahasa Arab secara baik dan benar sehingga keberadaan mereka diakui di sana. Maka upaya perumusan nahu ketika itu menjadi keharusan bersama yang penting untuk diwujudkan secepatnya.
Sedikit demi sedikit dimulailah perumusan kaidah-kaidah nahu yang diawali dengan kasus-kasus lahn yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dikumpulkan dan diiventarisasikan oleh Abu al-Aswad ad-Dual³. Atau dapat dikatakan, secara tidak langsung proses pengajaran dan pendidikan bahasa Arab secara informal telah berlangsung sejak itu. Perkembangan baru terpenting yang terjadi dalam bidang nahu ini berawal di kota Basrah disebabkan oleh karakter masyarakatnya yang cendrung responsif dengan tradisi keilmuan dan mereka siap dengan dialektika wacana peradaban, sebab mereka sebelumnya telah bersinggungan dan bersentuhan dengan peradaban Yunani yang pada masa itu dianggap sebagai peradaban yang modern.
Selasa, 27 Januari 2009
Akar Sejarah Kelahiran Ilmu Nahu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

























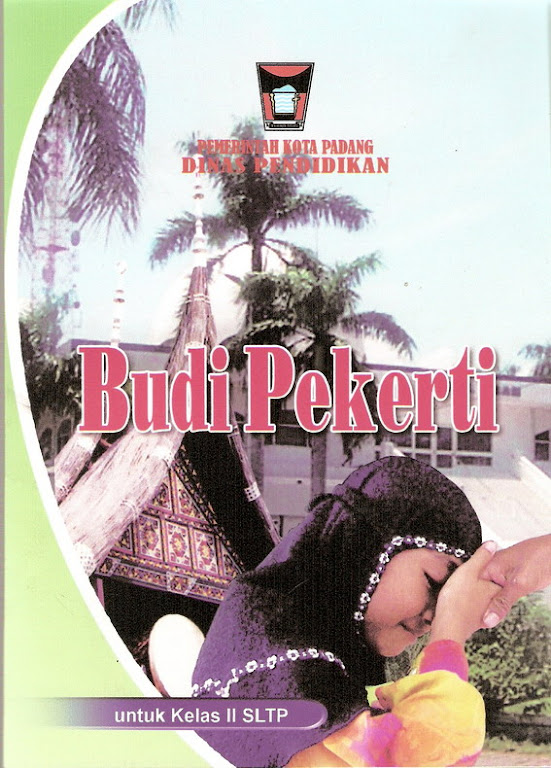





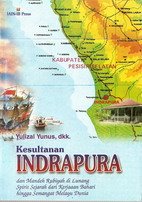




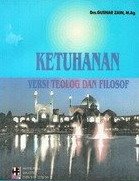
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar