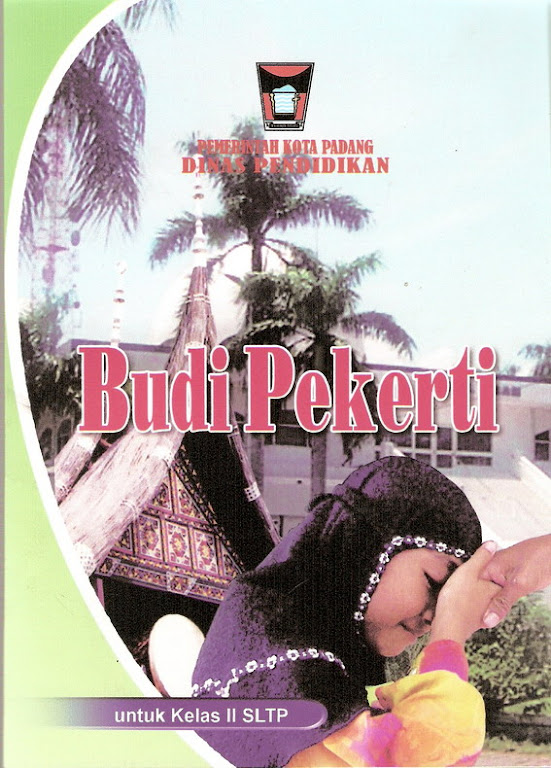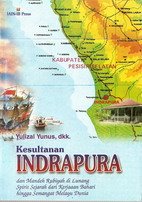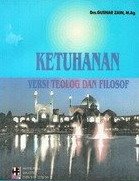Oleh : Muhammad Ilham

Selama ini, definisi ulama yang dikonstruk atau dipersepsikan oleh masyarakat adalah orang yang mengkaji fiqh, tasawuf, akhlaq, tafsir, hadits, dan sebagainya. Berangkat dari hal ini, seharusnya ulama tidak sebatas dilekatkan pada diri seseorang yang memahami tentang fiqh, tauhid, tasawuf, dan akhlaq saja melainkan orang yang mengetahui dan memahami tentang segala hal yang terkait dengan objek yang dikaji. Jika demikian penggunaan arti ulama, maka ulma bisa dilekatkan pada berbagai orang yang mendalami ilmu tentang apa saja, termasuk misalnya kedokteran, ekonomi, sains, teknik, dan bahkan juga seni dan budaya.
Selanjutnya tidak diperlukan lagi pembedaan istilah intelek dan ulama, karena pada hakekatnya ulama yang intelek dan intelek yang ulama tidak memilki perbedaan. Penggunaan konstruk dan persepsi yang berbeda terhadap fenomena yang sama tetapi berbeda objeknya saja ternyata terjadi dalam banyak hal. Misalnya menggunakan istilah madrasah yang berbeda dengan sekolah, guru dengan ustadz, kitab dengan buku, asrama mahasiswa dengan pondok pesantren, perpisahan dengan akhirussanah, dan lain sebagainya.
Sementara itu, Syekh, juga dapat ditulis Shaikh, Sheik, Shaykh atau Sheikh (Bahasa Arab: شيخ), adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti kepala suku, pemimpin, tetua, atau ahli agama Islam. Istri atau anak seorang Syekh sering disebut Syeikha (Bahasa Arab: شيخة). Di Timur Tengah, istilah Syekh secara harfiah berarti orang yang lanjut usianya, yang mana pengertian ini digunakan dalam bahasa Arab Al Qur'an. Belakangan pengertiannya berkembang menjadi gelar yang berarti pemimpin, tetua atau bangsawan, terutama di Jazirah Arab dimana Shaikh telah menjadi gelar tradisional pemimpin suku Badui pada beberapa abad terakhir. Pemakaian sebagai tetua juga digunakan oleh Arab Kristen, yang mana menunjukan bahwa pemakaian tersebut tidak tergantung pada agama tertentu. Di Teluk Persia, gelar ini digunakan oleh para pemimpin masyarakat, yang dapat berupa para manajer atau pejabat tinggi, pemilik perusahaan besar, atau pemimpin lokal. Para anggota keluarga kerajaan Kuwait, yaitu keluarga al-Sabah, dan keluarga bangsawan Bahrain dan Qatar juga menggunakan gelar Syekh, sebagaimana juga sebagian besar keluarga bangsawan negara-negara di Teluk Persia. Di Afrika, gelar tersebut digunakan oleh sebagian penguasa muslim di keluarga kerajaan Ethiopia, para penguasa Bela Shangul, dan para bangsawan muslim suku-suku Wollo, Tigray dan Eritrea.
Secara khusus, dalam agama Islam gelar tersebut juga digunakan untuk menyebut ahli-ahli agama Islam di berbagai bidang, seperti para faqih, mufti, dan muhaddith. Dalam tarekat Sufi, Syekh adalah gelar kehormatan bagi seseorang yang telah memperoleh izin pemimpin tarekat untuk mengajarkan, membimbing dan mengangkat para murid dari tarekat tersebut. Di Indonesia, gelar Syekh biasanya digunakan oleh para muballigh keturunan Arab atau para ulama besar dan ahli agama Islam, baik yang menyebarkan ajaran berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah maupun yang menyebarkan faham yang bersifat tasawuf. Lain halnya dengan sebutan Kiyai atau Kyai, yang bukan istilah baku dari agama Islam. Panggilan Kiyai bersifat sangat lokal, mungkin hanya di pulau Jawa bahkan hanya Jawa Tengah dan Timur saja. Di Jawa Barat orang menggunakan istilah Ajengan. Biasanya istilah Kiyai juga disematkan kepada orang yang dituakan, bukan hanya dalam masalah agama, tetapi juga dalam masalah lainnya. Bahkan benda-benda tua peninggalan sejarah pun sering disebut dengan panggilan Kiyai. Melihat realita ini, sepertinya panggilan Kiayi memang tidak selalu mencerminkan tokoh agama, apalagi ulama.
Sedangkan panggilan Ustadz, biasanya disematkan kepada orang yang mengajar agama. Artinya secara bebas adalah guru agama, pada semua levelnya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan kakek dan nenek. Namun hal itu lebih berlaku buat kita di Indonesia ini saja. Istilah ini konon walau ada dalam bahasa Arab, namun bukan asli dari bahasa Arab. Di negeri Arab sendiri, istilah ustadz punya kedudukan sangat tinggi. Hanya para doktor (S-3) yang sudah mencapai gelar profesor saja yang berhak diberi gelar Al-Ustadz. Kira-kira artinya memang profesor di bidang ilmu agama. Jadi istilah ustadz ini lebih merupakan istilah yang digunakan di dunia kampus di beberapa negeri Arab, ketimbang sekedar guru agama biasa.
Sementara itu, Penceramah – sebuah konsep yang identik dengan tabligh – memang boleh siapa saja dan juga bisa bicara apa saja. Dari masalah-masalah yang perlu sampai yang tidak perlu. Dengan merujuk langsung kepada literatur hingga yang hanya opini saja. Bahkan terkadang cenderung bersifat entertain – menghibur penonton – sehingga terkadang seorang penceramah, apalagi dengan kemajuan media ellektronik dan perteleviasian sekarang ini, cenderung berperan sebagai seorang ”penghibur”. Bedanya dengan para artis, para penceramah ini adalah ”penghibur rohani”. Biasanya ceramah mereka selain lucu, juga komunikatif serta seringkali mengangkat masalah yang aktual. Sehingga yang mendengarkannya betah duduk berjam-jam. Itu sisi positifnya. Positif yang lainnya penceramah model begini adalah mampu merekrut massa yang lumayan banyak. Mungkin karena juga dibantu dengan media. Tetapi kekurangannya juga ada. Misalnya, umumnya mereka bukan orang yang lahir dan dibesarkan dengan tradisi keilmuan yang mendalam. Juga bukan jebolan perguruan tinggi Islam dengan disiplin ilmu syariah. Padahal point ini cukup penting, sebab yang mereka sampaikan ajaran agama Islam, tentunya mereka harus mampu merujuk langsung ke sumbernya. Agar tidak terjadi keterpelesetan di sana sini. Yang kedua, kelemahan tokoh yang dibesarkan media adalah akan cepat surut sebagaimana waktu mulai terkenalnya. Namun lepas dari keutamaan dan kelemahannya, para penceramah ini sudah punya banyak jasa buat umat Islam di negeri ini.
Banyak orang yang tadinya kurang memahami agama, kemudian menjadi lebih memahami. Yang tadinya kurang suka dengan Islam, berubah jadi lebih suka. Semua itu tentu saja tidak bisa kita nafikan, sekecil apa pun peran mereka. Tentu bukan pada tempatnya bila mereka melakukan hal-hal yang kurang produktif, kita lalu mencemooh, memaki atau bahkan bertepuk tangan gembira melihat bintang mereka mulai pudar. Kekurang-setujuan kita dengan beberapa hal yang mereka lakukan, jangan sampai membuat kita harus melupakan peran dan jasa mereka selama ini. Bahkan belum tentu kalau kita sendiri yang berada pada posisi mereka, kita akan mampu memenuhi harapan semua orang. Dalam kata pengantarnya, seorang cendekiawan muslim Indonesia, Jalaluddin Rahmat, pernah menulis mengenai ”reduksi makna dan nilai seorang ulama” karena perubahan situasi. Ia mengatakan : "Untuk konteks situasi saat sekarang ini, ulama pada hakikatnya bukan sekedar yang enak diorbitkan media, tetapi mereka yang sekolah ke Timur Tengah dengan serius, hingga mendapatkan ilmu yang cukup. Lalu ketika pulang ke negeri ini, mereka bekerja dengan baik menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Mungkin tidak ada salahnya, jika tiap masjid di negeri ini berinvestasi untuk melahirkan satu ulama. Bila kita membaca sejarah Islam di nusantara pada masa dahulunya, banyak ulama-ulama yang belajar ke Mekkah dengan dibiayai oleh masyarakat dikampungnya – walaupun untuk bekal keberangkatannya saja. Bahkan, Tan Malaka, dalam sejarahnya pergi sekolah ke Haarlem Belanda atas biaya orang kampungnya (Orang Pandam, Suliki – bahkan Tan Malaka ketika pulang ke Indonesia masih berutang pada orang-orang kampungnya : Penulis). Misalnya, dengan memilih lulusan pesantren yang punya nilai tinggi, untuk dibiayai kuliah S-1 dan S-2 ke Mesir, Saudi, Kuwait, Pakistan, Jordania, Suriah atau pusat-pusat ilmu lainnya seperti Iran, bahkan bila perlu ada juga yang belajar agama Islam ke negeri-negeri Barat ... mengapa tidak ?. Dengan asumsi, 4 tahun lagi mereka akan segera lulus S-1. Itu saja sebenarnya sudah jauh lumayan dari pada sekedar penceramah. Apalagi kalau bisa sampai S-2 atau bahkan S-3, tentu akan lebih baik lagi. Nantinya diharapkan tiap masjid dipimpin oleh lulusan-lulusan yang berkualitas seperti mereka. Mereka yang jadi imam, mereka yang juga mengajarkan ilmu-ilmu di masjid, dan mereka juga yang dijadikan rujukan dalam masalah agama. Orang-orang cukup datang ke masjid untuk berkonsultasi masalah syariah. Dan itu bisa dilakukan tiap hari dalam tiap waktu shalat. Sebab mereka memang dipekerjakan dan digaji oleh masjid, tentunya dengan standar yang baik. Sehingga para imam masjid ini tidak perlu nyambi jadi tukang ojek, atau jadi karyawan di pabrik dan perusahaan tertentu. Waktunya bisa dimanfaatkan 24 jam untuk umat dan beliau stand-by di masjid”.
Terkait dengan apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rahmat diatas, salah seorang ulama Sumatera Barat saat sekarang ini mengatakan : ”Bila masyarakat datang ke Masjid pada saat sekarang ini, mereka tidak menemukan ulama di masjid tersebut, akan tetapi mereka hanya menemukan gharin. Lalu dimana ulama berada ? Mereka bekerja mencari nafkah, bila ceramah saja mereka datang ke masjid. Harusnya, ulama-ulama tersebut dibiayai oleh negara sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Hingga mereka bisa fokus melayani ummat. Efeknya adalah, timbul persepsi ditengah-tengah masyarakat yang cenderung menyederhanakan ulama sebagai profesi pekerjaan ekonomis.”
Ulama merupakan salah satu figur sentral-penting dalam pendidikan di Minangkabau. Di Minangkabau ulama merupakan tokoh kunci dalam membangun karakteristik (building of characteristic) Minangkabau yang berasaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dari segi pemikiran, ulama sebenarnya telah membentangkan pemikirannya melalui institusi pendidikan yang didirikannya sendiri, terutama sekali melalui institusi pendidikan surau. Pendidikan dalam pergerakan eksistensi ulama sekurang-kurangya telah memberikan dua sumbang sih, yakni; sebagai penyebaran aliran, ajaran agama Islam, dan kedua sebagai penyebaran pemikiran ulama itu sendiri. Penyebaran pemikiran ini, kemudian menjadi cikal bakal pergerakan dan kemudian membuat jaringan guru dengan murid tidak terputus dan dapat ditelusuri. Dalam kultur jaringan seperti ini, sangat mempercepat penyebaran Islam dan transformasi masyarakat Minangkabau. Silfia Hanani mengatakan bahwa eksistensi ulama tidak bisa dipisahkan dari institusi pendidikan. Seorang ulama mewakili dua dunia yang harus dimilikinya, yaitu dunia transformasi jiwa imani (surau dalam artian tempat ritual) dan institusi pendidikan seperti surau maupun madrasah sebagai transformasi pencerahan keilmuan. Salah seorang diantaranya berasal dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat, yang menuntut ilmu pada Syekh Abdul Rauf, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu di Aceh yang sangat mendalam ilmunya tentang Islam, muridnya datang dari segala penjuru. Setelah murid dari Ulakan tadi tamat belajar, dia diberi gelar Syekh Burhanuddin, yang kembali ke Ulakan dan pada tahun 1680 Masehi mendirikan sebuah surau di sana. Surau itu dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam, yang banyak didatangi murid dari seluruh daerah Sumatera Barat. Mula-mula yang menjadi murid Syekh Burhanuddin adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar surau itu, kemudian dari daerah Sumatera Barat lainnya.
Di Sumatera Barat dahulu, orang laki-laki dewasa yang belum kawin tidak biasa tidur di rumah orang tuanya pada malam hari. Tempat yang dipilih adalah balai perternuan yang terdapat di daerah itu, dan di tempat inilah berkumpul pemuda yang masih bujangan pada malam hari untuk tidur bersama-sama. Setelah Islam masuk ke Sumatera Barat, tempat itu ada yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, kemungkinan tempat itulah yang bernama surau kemudian harinya, karena musyawarah dalam bahasa Arab disebut syurau atau asyura menjadi surau saja. Sidi Gazalba yang telah mempelajari masalah ini secara mendalam mengatakan sebagai berikut : "Surau atau langgar yang mula-mula, merupakan unsur kebudayaan asli, setelah Islam masuk menjadi bangunan Islam. Dahulu tempat ini bertujuan sebagai tempat bertemu, berkumpul, berapat, dan tempat tidur pemuda-pemuda yang bersifat daerah. Pada masyarakat Mentawai yang masih dalam keadaan asli, bangunan sejenis masih menjalankan fungsi dan kepercayaan asli”.
Sesudah agama Islam berkembang di Sumatera Barat, surau tidak lagi diambil dari tempat pertemuan itu, melainkan sudah didirikan khusus oleh guru agama Islam (Syekh, Tuanku atau Ulama) dan khusus sebagai tempat pengajian. Fungsinya sebagai tempat tinggal masih tetap, yaitu sebagai tempat tinggal guru mengaji dan tempat bermalam bagi murid laki-laki atau pemuda lainnya. Tempat yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan merupakan sebuah surau dan merupakan surau yang pertama di Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan pada fungsinya yang sudah merupakan sebuah surau yang dikenal pada akhir abad ke-19. Pada waktu itu fungsi surau adalah sebagai pusat pendidikan agama Islam tempat beribadat serta sebagai tempat tinggal, yang berkembang di Sumatera Barat selama abad ke-17, ke-18, dan ke-19 Masehi.
Syekh Berhanuddin bukanlah pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat, karena jauh sebelumnya sudah ada pedagang Aceh yang menyebarkannya. Di samping Syekh Burhanuddin di Ulakan ada pula seorang yang bergelar Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar pada tahun 1191 Masehi. Tetapi Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar itu bukanlah seorang Ulama Islam yang tinggal menetap pada suatu tempat, melainkan berpindah-pindah. 10) Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar itu datang dari tanah Arab melalui Aceh masuk ke Sumatera Barat. Mengajar di Batuhampar-Payakumbuh selama 10 tahun, Kumpulan Bonjol selama 5 tahun, Ulakan selama 11 tahun, Kuntu Kampar selama 15 tahun sampai dia meninggal di sana pada tahun 1191. Agama Islam sudah mulai masuk ke Sumatera Barat kira-kira pertengahan abad ke-12 M. yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang meninggal di Kuntu Kampar. Pada abad berikutnya disebarkan oleh pedagang Islam yang datang dari arah utara Sumatera Barat. Pendidikan Islam pada waktu itu belum diselenggarakan pada tempat khusus. Syekh Burhanuddin Ulakanlah yang pertama mendirikan sebuah surau sebagai pusat pendidikan agama Islam, yang berkembang di Sumatera Barat.
Sebelum awal abad ke-19 banyak praktek agama Islam yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Antara ajaran agama Islam dengan adat setempat tidak terlihat lagi batasnya yang tegas, seperti pertaruhan besar pada acara mengadu ayam yang dinamakan "menyabuang”. Kebiasaan mabuk-mabukan dalam upacara adat, menganggap keramat seorang guru, percaya kepada takhyul, meminta berkat pada kuburan orang terkenal, dan berbuat syirik, jelas bertantangan dengan ajaran Islam. Pada tahun 1803 tiga orang haji pulang dari Mekah, yaitu : Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka tidak setuju melihat praktek agama Islam yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Timbul pikiran mereka untuk memperbaharui keadaan tersebut, rakyat harus dididik untuk dapat menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Gagasan pembaharuan pendidikan Islam mereka jalankan dengan keras, langsung memerintahkan penghentian seluruh kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Tindakan tersebut menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat, terjadi pembenturan antara kebiasaan yang telah menjadi darah daging anggota masyarakat di satu pihak dengan perintah penghentiannya yang keras di pihak lain. Akhirnya timbullah pertentangan antara golongan adat sebagai pendukung kebiasaan itu dengan golongan agama yang berkeinginan menjalankan ajaran agama Islam secara murni menurut Al-Quran dan Hadis Nabi. Timbullah perang saudara antara sesama orang Minangkabau, yaitu antara penganut agama Islam yang berhaluan keras dengan penganut adat yang memegang teguh kebiasaannya. Tetapi yang keluar sebagai pemenang dari perang itu bukan salah dari kedua pihak, melainkan orang Belanda yang sedang berusaha menanamkan kekuasaannya di Sumatera Barat.
Gagasan pembaharuan dari ketiga orang itu ditujukan terhadap penyimpangan ajaran Islam oleh para penganutnya sendiri waktu itu di Sumatera Barat. Tetapi, karena caranya sangat keras, akibatnya sangat lain yang diharapkan, walaupun akhirnya beberapa tujuan pembaharuan tercapai juga, tetapi korban jiwa sudah banyak. Semenjak itu seluruh daerah Minangkabau praktis dapat dikuasai oleh Belanda tanpa banyak mengeluarkan tenaga. Namun demikian ide pembaharuan dari ketiga orang haji dapat dikatakan sebagai ide pembaharuan pertama di bidang pendidikan Islam di Sumatera Barat.
Selanjutnya ide pembaharuan pendidikan agama Islam kedua datang dari Syekh Ahmad Khatib yang lahir di Bukittinggi pada tahun 1855 12). Kemudian Syekh Ahmad Khatib menetap di Mekah dan diangkat sebagai Imam Mazhab Syafei di Masjidil Haram serta sebagai guru pendidikan agama. Ide pembaharuan dalam pendidikan Islam tidak dijalankannya sendiri, melainkan diberikan melalui murid-muridnya yang belajar ke Mekah sambil menunaikan ibadah Haji. Di antara muridnya itu terdapat tiga orang pemuda yang penuh semangat, yaitu Haji Abdul Karim Amarullah atau Inyiak Dotor dan akronim HAKA, Muhammad Jamil Jambek atau Inyiak Djambek, dan Abdullah Ahmad. Ketiga orang itu berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan murid Syekh Ahmad Khatib yang cukup menonjol dari Jawa bernama KH. Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi pendiri Muhammadiah. Ketiga orang murid asal Sumatera Barat itulah yang menjadi pelopor pembaharuan pendidikan Islam di Sumatera Barat dengan cara mereka masing-masing. Tetapi walaupun caranya berbeda tujuannya tetap yaitu pembaharuan dalam pendidikan Islam. Sebelum tahun 1900 banyak ulama Islam Sumatera Barat terkenal sebagai basil pendidikan Islam semacam itu, pengetahuan mereka tentang Islam tidak kalah dengan pengetahuan ulama Islam abad ke-20 M., bedanya pada cara menerapkan agama dalam kehidupan masyarakat. Di antara ulama Islam Sumatera Barat, yang terkenal sebagai hasil pendidikan Islam sebelum tahun 1900 adalah : Syekh Abdullah Khatib, Ladang Lawas, Bukittinggi; Syekh M. Jamil Tungkar, Batusangkar; Syekh Tuanku Kolok, Sungayang, Batusangkar ; Syekh Abdul Manaf Padang Ganting, Batusangkar; Syekh M. Saleh, Padang Kandis, Suliki, Payakumbuh; Syekh Abdullah, Padang Japang, Payakumbuh, dan Syekh Ahmad, Alang Lawas, Padang serta Syekh Amarullah, Maninjau, Bukittinggi.
Disamping menghasilkan ulama besar, pendidikan Islam pada masa ini juga menghasilkan pemimpin masyarakat yang dihormati dan dipatuhi. Untuk mendapat predikat ulama Islam terkenal memerlukan waktu lama, karena harus dipraktekkan dalam masyarakat terlebih dahulu. Penilaian yang diberikan masyarakat itu sukar didapat dengan segera. Sebagai guru mereka tidak saja mendidik orang lain, tetapi juga anak mereka, yang biasanya juga menjadi ulama besar di kemudian hari. Syekh Ahmad, Alang Lawas, Padang mendidik anaknya Syekh Abdullah Ahmad yang kemudian terkenal sebagai salah seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam Sumatera Barat dengan Sekolah Adabiah (Adabiah School). Buya Haji Abdul Karim Amarullah (HAMKA) dididik langsung oleh ayahnya Syekh Haji Abdul Karim Amarullah di Maninjau. Contoh ulama terakhir, Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dididik dan dibimbing oleh ayahnya Syekh Daud Rasyidi dan beberapa ulama lainnya yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa faktor genetic-hereditically setidaknya cukup memegang peranan yang cukup signifikan dalam melahirkan jaringan ulama di Minangkabau. Hampir seluruh Syekh mendidik sendiri anak mereka dan semuanya berhasil dengan baik.
Pada akhir abad ke-19 M. banyak ulama Islam Sumatera Barat yang belajar ke Mekah dan pada awal abad ke-20 M. mereka sudah kembali lagi ke Sumatera Barat, dan langsung mengajar di surau yang sudah ada. Sistem pendidikan Islam di Sumatera Barat pada masa ini dinamakan Sistem Pendidikan Surau, karena pusat pendidikannya adalah surau tersebut. Pada akhir abad ke-19 M. sudah ada ulama Islam Sumatera Barat yang kembali dari Mekah, yang membawa perubahan terhadap pendidikan Islam. Jumlah mata pelajaran mulai pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ke-19 bertambah banyak dari masa sebelumnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang didapat oleh para Syekh. Cara penyampaian mata pelajaran tidak satu-satu lagi, melainkan sudah diberikan beberapa mata pelajaran sekaligus, seperti sistem sekolah sekarang. Buku yang dipelajari murid sudah semakin banyak, sebelum pertengahan abad ke-19 M. hanya dipergunakan satu buku untuk satu mata pelajaran. Sesudah pertengahan abad ke-19 M. untuk satu mata pelajaran sudah dipergunakan beberapa buah buku pelajaran, sedangkan pada akhir abad ke-19 M. untuk pelajaran Nahu saja sudah dipergunakan 6 atau 7 buah buku pelajaran. Mulai pertengahan abad ke-19 sudah banyak Qari tamatan Mekah, sedangkan sebelumnya hampir semua Qari tamatan Sumatera Barat. Qari tamatan Mekah mempunyai murid lebih banyak dari Qari tamatan Sumatera Barat. Penilaian ini hanya didasarkan karena mereka tamatan luar negeri.
Pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara Pengajian AI-Quran sebelum pertengahan abad ke-19 dengan akhir abad ke-19. Tetapi pada pengajian kitab terdapat perbedaan besar yang merupakan perkembangan pendidikan Islam. Sebelum pertengahan abad ke-19 jumlah mata pelajaran hanya 4 buah saja, tetapi kemudian menjadi 12 buah, yaitu ilmu Nahu, Syaraf, Fikih, Tafsir, Hadis, Musthalah Hadis, Mantik, Maani. Bayan, Badik, dan Usul Fikih. Kadang-kadang ditambah lagi dengan ilmu Tasauf. Sebelum akhir abad ke-19 pengajian terdapat dua tempat, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Pada tingkat rendah cara mengajar hampir sama dengan sebelum abad ke-19 : murid diajar satu per satu, dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Guru menyebutkan pelajaran murid mengikutinya dan selanjutnya menghafalkan seperti yang diucapkan gurunya. Guru yang mengajar pada tingkat rendah adalah guru bantu, yaitu murid tingkat tinggi yang mendapat kepercayaan Syekhnya, biasanya dipanggil "Engku Muda" atau "Alim Muda" atau "Guru Tua". Yang memakai perdikat "Tua" adalah murid yang hampir selesai pendidikan dan dapat bertindak dalam pelaksanaan pendidikan atas nama Syekhnya. "Alim Muda" setingkat di bawah "Guru Tua", sedangkan "Engku Muda" tingkatan guru bantu yang paling bawah.
Pada tingkat tinggi cara mengajar sudah berbeda, dalam dua jam pelajaran guru sudah menerangkan dua atau tiga pelajaran sekaligus. Murid tidak lagi dihadapi satu per satu, melainkan secara bersama-sama dan cara mengajar dinamakan sistem halaqah, guru membaca dan menerangkan pelajaran, sedangkan murid menyimak saja. Sebelum pelajaran dimulai murid diharuskan membaca pelajaran tersebut lebih dahulu dan sewaktu guru menerangkan murid mencocokkan pengertian atau pemahaman yang diperolehnya dari hasil bacaan sebelumnya. Keterangan guru lebih penting karena murid menyesuaikan pemahamannya dengan apa yang telah diterangkan. Apabila pemahaman bertentangan dengan keterangan guru, maka keterangan guru itulah yang dipakai. Selama guru mengajar tidak diadakan kegiatan tanya jawab, murid belajar sendiri, kemudian guru menerangkan arti pelajaran tersebut.
Setiap pelajaran yang diberikan dan diterangkan guru merupakan kelanjutan pelajaran sebelumnya. Dalam sistem halaqah murid disuruh belajar sendiri dan sekali atau dua kali sehari mereka menyesuaikan pemahamannya dengan keterangan yang diberikan guru sewaktu pelajaran sedang berlangsung pada sistem halaqah ini masing-masing murid memiliki kitab yang sama dengan yang sedang diajarkan gurunya, sehingga mereka dapat menyimak dengan sungguh-sungguh keterangan gurunya. Biasanya guru membacakan bahasa Arab lebih dahulu, sesudah itu baru menjelaskan artinya dan makna serta maksud pelajaran dalam kehidupan masyarakat. Sementara guru menjelaskan murid mengambil tempat di sekeliling guru atau duduk setengah melingkar di depan gurunya dengan bersila. Murid tingkat tinggi terdiri dari guru bantu dan murid tingkat rendah yang dianggap mampu mengikuti pelajaran karena sangat pandai. Dasar meletakkan murid di tingkat tinggi adalah kemampuan murid itu bukan pada umur atau lama mereka dalam belajar.
Dengan bentuk ujian yang demikian sedikit sekali murid yang berhasil, sebahagian tetap tinggal di sana sampai tua atau kembali ke kampungnya untuk menjadi guru mengaji biasa. Namun demikian murid yang begini pada hari tuanya nanti juga akan dapat menjadi seorang Syekh, tergantung dari kemampuannya mengajar atau berdakwah. Gelar Syekh akan diberikan oleh penduduk di tempatnya mengajar atau oleh muridnya. Kadang-kadang gelar Syekh diperolehnya ketika sudah berumur tua sekali, hanya sekedar penghargaan atas jasanya. Seorang Syekh dalam mengajar tidak menerima gaji, karena mereka mengajar karena Allah semata, bukan untuk mencari penghasilan. Seorang Syekh mendirikan surau atau mengajar biasanya dengan biaya sendiri, kecuali kalau ada sumbangan anak negeri setempat berupa zakat dan fitrah. Tetapi kalau Syekh yang sudah terkenal banyak menerima zakat fitrah, terutama dari bekas muridnya, sehingga dengan zakat fitrah itu, ia dapat memberikan biaya bagi beberapa orang muridnya yang tidak mampu.
Muridnya tidak membayar uang mengaji atau uang sekolah. Segala keperluan mereka, mereka siapkan dan cari sendiri. Bagi murid yang betul-betul tidak mampu atau tidak dibiayai oleh keluarganya, akan menjadi "pakiah " yang sekali atau dua kali seminggu meminta-derma ke kampung-kampung guna keperluan hidupnya selama mengaji. Kadang-kadang dengan sekali pergi minta derma itu sudah mendapat hasil untuk dua minggu atau sebulan biaya hidupnya. Tetapi pekerjaan "pakiah" ini dilakukan apabila memang sudah tidak ada lagi jalan lain. Surau dengan Syekhnya yang sudah terkenal jarang mengizinkan muridnya menjadi “pakiah”, karena zakat fitrah yang diterimanya sudah lebih dari cukup untuk membiayai hidup murid. Pada masa ini pendidikan Islam masih berpusat di surau-surau, sistem pendidikan dinamakan sistem surau seperti sistem pendidikan sebelumnya. Bedanya terletak pada penyelenggaraan tingkat rendah dan tingkat tinggi, keduanya sudah dipisahkan ruang belajarnya, walaupun tidak dibatasi oleh kelas, tetapi jam pelajaran yang berlainan saja. Sistem pendidikan pada masa ini merupakan peralihan dari sistem surau kepada sistem sekolah.
Syekh yang menjadi guru agama adalah orang yang sudah kembali dari Mekah dan Mesir yang sudah mulai banyak jumlahnya. Hasil pendidikan Mekah dan Mesir, di samping membawa ilmu pengetahuan ke Sumatera Barat juga membawa buku-buku dan faham baru yang berkembang tentang Islam dan ajarannya. Majalah Al Manar yang terbit di Mesir sudah menjadi langganan Syekh itu dan menjadi bacaan pula bagi muridnya. Dengan sendirinya pandangan serta wawasan mereka menjadi luas dan menjadi orang yang haus akan sesuatu yang baru serta apresiatif terhadap inovasi-inovasi baru. Sistem pendidikan Islam yang selama ini dilaksanakan di Sumatera Barat mereka pandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sekarang, oleh karena itu, sistem pendidikan perlu diadakan pembaharuan. Pembaharuan yang mereka inginkan bukan hanya di bidang pendidikan Islam, tetapi pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Mereka merupakan orang yang terbuka dan bersedia menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan pendapat mereka. Berbeda dengan hasil pendidikan Islam sebelumnya, di mana para ulama Islam fanatik dan sukar menerima pendapat orang lain, maka pada masa ini, sebagai hasil pembaharuan pendidikan Islam, mereka sudah berpandangan luas dan ber sifat terbuka.
Selengkapnya...
 Seorang petualang Portugis yang bernama Tome Pires berkujung ke Indonesia pada abad ke 15. Dalam laporan perjalanannya, ia terkesan melihat hubungan antara maraknya kegiatan kriya, seni, dan kebudayaan di Jawa dengan menonjolnya peranan yang dimainkan dari kegiatan para ulama Islam yang sekaligus juga budayawan pada waktu itu dalam masyarakatnya. Sebelumnya, pada abad ke 14 Ibnu Batutah telah berkunjung ke Samudera Pasai -kerajaan Islam kedua di Nusantara setelah Perlak dalam perjalanannya dari India ke Cina. Kesan serupa ia rekam dalam laporan lawatannya. Tetapi setelah kesaksian Tome Pires dan Ibnu Batutah, adakah suatu kesaksian lanjutan dalam kegiatan kriya dan seni Islam di Indonesia?
Seorang petualang Portugis yang bernama Tome Pires berkujung ke Indonesia pada abad ke 15. Dalam laporan perjalanannya, ia terkesan melihat hubungan antara maraknya kegiatan kriya, seni, dan kebudayaan di Jawa dengan menonjolnya peranan yang dimainkan dari kegiatan para ulama Islam yang sekaligus juga budayawan pada waktu itu dalam masyarakatnya. Sebelumnya, pada abad ke 14 Ibnu Batutah telah berkunjung ke Samudera Pasai -kerajaan Islam kedua di Nusantara setelah Perlak dalam perjalanannya dari India ke Cina. Kesan serupa ia rekam dalam laporan lawatannya. Tetapi setelah kesaksian Tome Pires dan Ibnu Batutah, adakah suatu kesaksian lanjutan dalam kegiatan kriya dan seni Islam di Indonesia?