Oleh : Dr. Ahmad Taufik Hidayat, M.Ag (Dosen Studi Naskah FIB-Adab)
 Penelitian lebih awal mengatakan bahwa sebagian surau di Minangkabau diduga kuat pernah difungsikan sebagai skriptorium. Pengertian skriptorium di sini merujuk pada sebuah tempat penyalinan manuskrip. Menurut Rujiati Muladi, yang dimaksud dengan skriptorium adalah sebuah ruangan yang luas atau terdiri atas ruang-ruang kecil yang difungsikan untuk menyalin naskah dengan berbagai aturan ketat yang harus dipatuhi. Segala peralatan yang diperlukan di dalam skriptorium disediakan oleh seorang petugas khusus. Para petugas yang menyalin naskah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu di dalam teks, walaupun ada kesalahan di dalam teks yang dihadapinya.
Penelitian lebih awal mengatakan bahwa sebagian surau di Minangkabau diduga kuat pernah difungsikan sebagai skriptorium. Pengertian skriptorium di sini merujuk pada sebuah tempat penyalinan manuskrip. Menurut Rujiati Muladi, yang dimaksud dengan skriptorium adalah sebuah ruangan yang luas atau terdiri atas ruang-ruang kecil yang difungsikan untuk menyalin naskah dengan berbagai aturan ketat yang harus dipatuhi. Segala peralatan yang diperlukan di dalam skriptorium disediakan oleh seorang petugas khusus. Para petugas yang menyalin naskah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu di dalam teks, walaupun ada kesalahan di dalam teks yang dihadapinya.Pendahuluan
Pengertian yang diajukan Rujiati merujuk pada bentuk-bentuk skriptorium pada masa lalu, terutama yang berkembang pada kurun awal abad Masehi di Yunani, dimana aktifitas penyalinan manuskrip giat dilakukan. Pastinya sulit menemukan bentuk konkrit dari model skriptorium yang disebut Rudjiati, namun bukannya tidak mungkin pula bangunan Surau di Minangkabau pernah berfungsi sebagai dimaksud. Dalam hal ini, menarik untuk ditelusuri lebih jauh guna memperkuat dugaan-dugaan di atas, melalui telaah terhadap sebuah model Surau yang terdapat di Koto Tangah, Surau Paseban. Surau ini dipilih sebagai objek karena alasan adanya koleksi manuskrip yang relatif banyak dan menjelaskan adanya kontinuitas sebuah tradisi menyangkut skriptorium. Penting diajukan di sini bagaimana sesungguhnya sejarah sebuah skriptorium institusi keagamaan tradisional lokal yang memiliki banyak koleksi manuskrip.
Riwayat Singkat Syekh Paseban
Dari informasi yang dituturkan Imam Maulana Abdul Manaf Amin (murid Syekh Paseban) kepada muridnya Zul Asru Tuanku Rajo Basa disebutkan bahwa Syekh Paseban lahir pada tahun 1817 M di wilayah Koto Panjang, Koto Tangah Padang. Dahulu, wilayah ini masuk dalam kabupaten Padang Pariaman. Nama kecil beliau Karapiang, dengan gelar Sidi Alim. Beliau bersuku Piliang, sebuah konsul kekerabatan yang banyak menyebar di wilayah Pariaman dan sebagian Padang. wafat di Mekkah pada tahun 1937, dalam usia relatif sangat tua, 120 tahun. Rentang masa hidup Syekh Paseban bila dilihat dari perkembangan dinamika Islam di Minangkabau bertepatan dengan konflik paham keagamaan antara kaum Paderi dengan kalangan adat yang dibackup oleh ideologi tradisional Islam, antara 1831 hingga munculnya paham modernisme Islam Salafi pada awal abad XX. Dalam dinamika seperti itu, dimana terjadi beberapa gelombang pemurnian dan pembaharuan yang membentuk sikap beragama masyarakat Minang, Syekh Paseban hidup dan berkembang. Selain itu, pergesekan di tengah-tengah masyarakat juga diprovokasi oleh kehadiran pihak kolonial.
Keadaan sulit memunculkan kerinduan di masyarakat Koto Tangah akan hadirnya figur sentral yang tidak hanya berfungsi sebagai penyuluh, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat dalam situasi konflik. Namun sayang, tidak banyak yang dapat dikorek mengenai sejarah hidup beliau pada masa sebelum pergi menuntut ilmu. Sedikit informasi itu antara lain berkenaan dengan cerita-cerita mengenai tanda-tanda bahwa Syekh Paseban akan menjadi orang besar di kemudian hari. Salah satu cerita yang dituturkan oleh Buya Idris, cucu Syekh Paseban, menyebutkan bahwa pada suatu ketika semasa Syekh Paseban masih dalam gendongan ibunya, pernah datang seorang ulama dan mengatakan agar sang anak dipelihara dengan baik, karena kelak akan menjadi orang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Menurut hemat penulis alasan inilah, dan berbagai tuntutan situasi ketika itu mengapa akhirnya orang tua Syekh Paseban mengirim beliau untuk belajar ke Tanjung Medan Ulakan Pariaman.
Peran Surau bagi Pembentukkan Karakter Islam Tradisional
Secara tradisional, ada dua arena pembentukkan karakter masyarakat Minangkabau, Surau dan lapau. Keduanya sangat berpengaruh besar dalam perkembangan mental masyarakat ini. Surau adalah lambang kesakralan mencerminkan sikap relijius, sopan santun serta kepatuhan kepada Allah, sedangkan lapau mencerminkan aspek keduniawiyan (profan) yang mengandung kekerasan, keberanian. Kecendrungan perkembangan anak-anak suku Minangkabau ditentukan dari banyaknya porsi waktu yang mereka habiskan sebagai bagian hidupnya sehari-hari dari kedua tempat ini. jika seorang anak lebih banyak berada di lapau tanpa pernah atau sekurang-kurangnya jarang mengaji di Surau, maka orang menyebut mereka parewa. Sebaliknya, jika waktu yang dihabiskan oleh seseorang lebih banyak di Surau, maka orang itu disebut urang siak atau pakiah.
Karena itu, dari aspek mental keagamaan, bagi masyarakat tradisional Minang, terutama kaum pria-nya, fungsi Surau jauh lebih penting dalam membentuk karakter mereka di kemudian hari. Selain untuk memperoleh informasi, juga dijadikan ajang bersosialisasi. Semenjak berumur 6 tahun, kaum pria telah akrab dengan lingkungan Surau. Struktur bangunan rumah tradisional orang Minang yang dikenal dengan rumah gadang memang tidak menyediakan kamar bagi anak laki-laki. Karena itu, setelah berumur 6 tahun, anak laki-laki di Minangkabau seperti terusir dari rumah induk. Hanya pada maktu siang hari mereka boleh bertempat di rumah guna membantu keperluan sehari-hari. Sedangkan pada waktu malam, mereka harus menginap di Surau. Selain karena tidak disediakan tempat, mereka juga merasa risih untuk berkumpul dengan urang sumando (suami dari kakak/adik perempuan) dan mendapat ejekan dari orang-orang karena masih tidur dengan ibu. Dalam ucapan yang khas, lalok di bawah katiak mande. Tetapi, di Surau mereka bukan sekedar menginap. Banyak aktifitas penting yang mereka lakukan di sana. Belajar silat, adat istiadat, randai, indang menyalin tambo dilaksanakan berbarengan dengan aktifitas keagamaan seperti belajar tarekat, mengaji, shalat, salawat, barzanji dan seterusnya. Karakter pembentukan Islam tradisional sesungguhnya berangkat dari aktifitas seperti ini.Demikian besar fungsi Surau bagi perkembangan generasi muda Minang pada masa lalu. Karena itu sungguh sebuah ironi, bila lembaga yang demikian strategis akhirnya mengalah pada perubahan.
Surau mewadahi proses lengkap dari sebuah regenerasi masyarakat Minang, sesuatu yang sulit dicari tandingannya dalam kultur manapun di dunia ini. Segala kebutuhan yang bersifat praktis, skill, kebijaksanaan, tutur kata dan tata krama yang diperlukan orang Minang pada masa dewasanya sebagian besar diperoleh di Surau. Adat budaya yang mengacu pada konsepsi alam takambang jadi guru yang melahirkan kebijkasanaan sehingga orang Minang harus tahu di nan-ampek (kato mandaki, kato manurun, kato mandata dan kato malereang), adalah bentuk kearifan yang diperoleh melalui pelatihan terpadu yang mengintegrasikan antara konsepsi ideologis dengan norma-norma budaya dan praktis lewat lembaga semacam Surau. Masyarakat tardisional yang di-back up oleh adat sangat kaya dengan prinsip-prinsip hidup semacam ini, sekedar menyebut contoh, misalnya untuk memberi i’tibar terhadap sikap tawadhu’ ada ungkapan ilmu padi, makin barisi makin marunduak.
Seiring dengan berkembangnya Islam, Surau menjadi aset yang dapat dipergunakan untuk menyebarkan dan mengenalkan konsep-konsep dasar Islam. Kedatangan Syekh Burhanuddin di penghujung abad ke-17 dengan mendirikan Surau di daerah Ulakan Pariaman menjadi titik awal dari terbentuknya karakter tradisional Islam hampir di seluruh wilayah penyebaran maupun pengaruhnya. Hal itu disebabkan karena kemampuan Tarekat Syattariyah yang dibawa oleh Burhanuddin sangat mengakomodasi tradisi lokal. Aspek-aspek tasauf yang dikandung dalam ajaran ini—sebagaimana halnya dengan pengalama-pengalaman awal islamisasi di wilayah nusantara—memudahkan diterimanya Islam, karena memiliki kesamaan-kesamaan dengan ajaran Hindu/Budha yang telah terlebih dahulu dipraktekkan. Kedekatan emosional masyarakat Minang dengan Surau menjadi faktor kunci lestarinya pemahaman tradisional di ranah Minang dan buah dari sebuah interaksi antara dua kultur yang saling berdialog. Sudut pandang kelompok modernis terhadap Surau tradisional sesungguhnya melepaskan ikatan-ikatan kultural ini yang telah terjalin demikian lama sehingga memunculkan bentuk-bentuk Islam tradisi yang mapan di wilayah Minangkabau. Ada narasi sejarah yang terpenggal dari sudut pandang seperti ini, meskipun pada tataran kebutuhan praktis yang bersifat temporal, pembaharuan yang digaungkan Islam modernis patut diapresiasi juga. Pemaksaan atas narasi besar Islam Arabia (ideologisasi Islam seolah-olah hanya tipikal Arab-lah yang benar) di gelanggang persemaian Islam kultural tentu sulit diterima, apapun alasannya. Ada sekian proses-proses penyesuaian dalam narasi kecil Islam nusantara yang tidak harus dinilai sebagai bid’ah, kafir, jumud dan seterusnya. Dengan demikian, Surau dalam kerangka demikian—meminjam sebutan yang digunakan Nurcholish Madjid untuk Pesantren di Jawa—tidak hanya identik dengan makna keislaman, namun juga mengandung keaslian (indigenous) yang berangkat dari kearifan lokal. Dengan kata lain, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan tersendiri ketika Islam hadir dan mengidentifikasi diri terhadap unsur lokal. Kemampuan Tarekat Syattariyah melakukan pendekatan dengan cara sufistik terhadap membuat islamisasi yang terjadi di wilayah Minangkabau tidak mengancam fondasi dasar masyarakat Minang, bahkan memperkaya elemen-elemen kultural yang ada.
Dari perspektif ini,Taufik Abdullah melihat bahwa pembentukan tradisi—sebagai sesuatu yang dilestarikan dari masa lampau—lebih dari sekedar persoalan legitimasi, namun juga menyangkut persoalan otoritas dan kewenangan. Sesuatu yang disebutnya sebagai paradigma kultural untuk melihat dan memberi makna terhadap kenyataan, yang tumbuh dari proses seleksi, dimana harapan berbenturan dengan kenyataan, dan kebebasan ekspresi harus mencari bentuk terbaik dengan keharusan-keharusan sturktural. Pada saaat itu, tradisi dapat dianggap sebagai seperangkat nilai dan sistem pengetahuan yang mengarahkan sifat dan corak komunitas. Dengan kata lain, menurut Abdullah, tradisi telah memberi kesadaran identitas serta rasa keterkaitan dengan sesuatu yang dianggap lebih awal. Mengikatkan diri kepada sumber atau person-person masa lalu adalah sebuah keharusan bagi tarekat Syattariyah bila ingin memperkenalkan Islam dalam struktur adat yang sudah terbentuk. Bukankah terbentang jarak yang sangat jauh antara wilayah Minangkabau dengan pusat Islam di Timur Tengah? Dan disepakati oleh para ahli sejarah bahwa pengenalan Islam ke wilayah ini bukan dengan wajah kekerasan. Lalu bagaimana Islam mengidentifikasi diri jika tidak dengan melakukan penyesuaian pada taraf tertentu terhadap tradisi yang diyakini secara kolektif oleh masyarakat lokal, sebagaimana ia harus mengidentifikasi diri sebagai bagian otentik dari dunia Islam meskipun terpencil ?
Sebagai kelanjutan dari menguatnya posisi agama dalam struktur adat Minangkabau, maka berakibat pula pada menguatnya kedudukan ulama dan guru-guru agama. Di bawah pengelolaan ulama-ulama tradisional, Surau-Surau melanjutkan peran-peran lamanya sebagai pusat pencerdasan masyarakat dengan warna tradisional yang kental.
Surau Paseban Sebagai Lembaga Islam Tradisional
Dengan latar belakang demikian Surau Paseban muncul mengemban corak tradisionalnya. Tidak ada yang meragukan bahwa pada saat Surau ini berdiri pada penghujung awal abad XX, model pendidikan Surau pada dasarnya sudah mulai kehilangan pamor karena dianggap kurang dinamis, meskipun tudingan ini tidak sepenuhnya benar. Mendirikan Surau pada saat demikian dari logika praktis misalnya, jelas akan kalah bersaing. Kenyataannya, kita berhadapan dengan sebuah kelompok keagamaan yang memiliki keyakinan yang begitu kuat untuk eksis.
Berdirinya Surau Paseban pada awal abad XX dianggap sebagai reaksi spontan masyarakat terhadap kebutuhan akan adanya institusi yang berfungsi sebagai pencerah di tengah-tengah masyarakat. Sejauh ini tidak dapat digali apakah alasan ini cukup masuk akal dalam konteks tahun itu. Sama tidak jelasnya, mengapa pada akhirnya Syekh Paseban yang berinisiatif atau ditunjuk sebagai pendiri sekaligus pemimpin, dan itu berarti guru spiritual bagi masyarakat setempat. Tetapi jika boleh dikatakan bahwa pengaruh paham pembaruan masih belum diminati atau belum banyak diketahui oleh masyarakat di sekitar Surau, maka pilihan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tradisional mungkin tidak terlalu berlebihan bila ada semacam tuntutan dari masyarakat. Tetapi di sini kita membicarakan sebuah institusi yang pada saat berdiri sudah tidak punya “bargaining” lagi dalam konteks persaingan dengan lembaga pendidikan yang ada. Lagipula kalangan pembaru sudah menjalankan misinya lebih dari satu abad, jika dihitung dari kemunculan gerakan pemurnian Paderi. Apakah sudah demikian terkonsetrasinya komunitas tradisional? Tidak diketahui dengan pasti. Di sini perlu peninjauan lebih jauh aspek-aspek apa saja yang berkemungkinan menjadi pendorong utama, dan yang benar-benar memiliki daya dorong tentunya, terhadap kemunculan Surau ini.
Pertama, dari pelacakan nama “paseban” diperoleh sejumlah informasi penting. Kata “paseban” mengandung pengertian tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik persoalan perdata, pidana, ibadah, muamalah, moral dan sebagainya. Apapun persoalan yang muncul, selalu dibawa ke Paseban. Tetapi pengertian ini tidak banyak membantu dalam mengungkap latar pendirian Surau ini. Pengertian lain dari kata “paseban” yang diungkap oleh pewaris Surau, Buya H. Idris Adam dan beberapa tokoh masyarakat lainnya adalah penjara. Konon, persis di tempat bangunan Surau Paseban, pernah berdiri sebuah rumah tahanan. Pengertian kedua ini memiliki kesamaan dari segi makna, karena sama-sama mengandung arti tempat mengadili perkara, namun berlainan dari segi konteks historis yang melingkupi makna kata tersebut. Rumah tahanan yang berdiri sebelumnya menjelaskan sebuah dinamika politik antara pribumi dengan pihak kolonial, terkait dengan penggunaannya pada masa lalu. Dalam hal ini tentu tidak sulit menangkap kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Sebagaimana disebut dimuka, Belanda memiliki agenda kebijakan-kebijakan di tanah jajahannya seperti monopoli perdagangan, tanam paksa, belasting yang pastinya akan mendapat respon keras dari masyarakat. Sebagai sebuah sikap antisipasi, penjara didirikan untuk membungkam pentolan-pentolan pembangkang yang tidak bersedia patuh kepada pihak kolonial. Ketika issu belasting diberlakukan banyak pihak dari pribumi yang merasa dirampas hak-hak mereka atas tanah dan harta mereka sendiri. Untuk menunjukkan sikap tidak senang dengan kebijakan ini, mereka melakukan pemberontakan dan pembangkangan. Dengan demikian, ditinjau dari aspek ini, maka berdirinya Surau Paseban mengandung sebuah kesadaran historis terhadap ketertindasan pada masa lalu, mempertahankan kekayaan sumber daya lokal dan konflik dengan kolonial. Bagian pertama ini akan dibicarakan dalam sub judul kondisi geografis dan demografis.
Kedua, faktor figur sentral di Surau Paseban, yakni Syekh Paseban sendiri. Sebagaimana termuat dari biografinya, Syekh Paseban agaknya memang digadang-gadang atau “disiapkan” untuk menjadi pemimpin masyarakat sekitar. Perjalanan hidup dan pengalaman menimba ilmu yang ditempuh Syekh Paseban telah menjaga mata rantai sebuah tradisi keilmuan tarekat Syattariyah. Hal ini akan ditinjau dalam pembahasan tentang jaringan keilmuan Syekh Paseban.
Ketiga, dari dinamika yang berkembang, perasaan terancam dari sebuah dinamika keagamaan yang terus mereduksi wilayah kelompok tradisional, terutama menyangkut paham keagamaan yang mereka yakini, menimbulkan semangat untuk membuktikan eksistensi bahwa pengajaran-pengajaran “lama” masih ada, dan itu dibuktikan dengan cara mendirikan Surau Paseban.
Surau Paseban Sebagai Skriptorium
Bersamaan dengan proses pemapanan Islam di wilayah ini pada abad ke-17 dan ke-18, Surau diduga digunakan oleh para ulama dan murid-muridnya sebagai skriptorium. Dengan demikian, di Surau-Surau-lah seharusnya para penulis menuangkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan keagamaan, terutama yang terkait dengan ajaran-ajaran mendasar Islam. Dalam konteks demikian, manuskrip adalah wujud nyata dari karya penulis dan menjadi media pembelajaran yang sangat efektif, terutama dilihat dari proses isalmisasi di Minangkabau. Berkaitan dengan ini, harus diakui bahwa sebagai institusi yang mengemban tugas pendidikan sekaligus penyebaran ajaran-ajaran keislaman, yang sumber-sumber ajarannya ditulis dengan bahasa Arab, Surau beserta orang-orang yang mengajar dan belajar di dalamnya adalah mereka yang terlebih dahulu mahir mengolah aksara, dalam hal ini aksara Arab.
Penggunaan aksara Arab dalam aktifitas tulis-menulis disebabkan terutama sekali karena masyarakat Minang termasuk dalam sebagian besar suku-suku di nusantara yang tidak memiliki sistem aksara. Kebudayaan Hindu yang meninggalkan sejumlah prasasti di wilayah ini memang dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat Minangkabau telah tersentuh oleh budaya tulis baca sebelum Islam. Meskipun kebudayaan Hindu tetap bertahan hingga abad ke-15, tetapi tidak mewariskan budaya tulis terhadap masyarakat Minang dalam pengertian yang luas. Aksara Hindu hanya dipakai dan digunakan dalam lingkungan yang amat terbatas, yakni lingkungan elit kerajaan saja. Berbeda dengan aksara Arab yang dibawa Islam. Jauh sebelum keterlibatan ulama Surau dalam aktifitas tulis menulis, aksara ini telah diperkenalkan oleh pedagang-pedagang dan sekaligus pendakwah muslim melalui kitab suci al-Quran, kitab-kitab hadis maupun naskah-naskah keagamaan. Dan setelah dilakukan penulisan maupun penyalinan ulang oleh ulama-ulama Surau, masyarakat telah familiar dengan aksara ini, meskipun aksara tersebut dipakai untuk bahasa yang dikenal oleh masyarakat, yakni Melayu atau bahasa lokal dengan modifikasi tertentu dikarenakan ketidaksamaan ejaan antara bahasa Arab dan bahasa lokal.
Dengan pola kedekatan demikian, fungsi aksara Arab bagi masyarakat Minang menjadi demikian luas dan dinamis. Naskah-naskah yang termasuk ke dalam kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab sebagai bacaan keagamaan dalam konteks dakwah dan pendidikan Islam, termasuk dalam hal ini al-Quran, jelas dimaksudkan untuk disebarluaskan, diajarkan dan dibacakan kepada masyarakat yang tersentuh oleh dakwah Islam. Sedangkan naskah-naskah berbahasa Melayu atau berbahasa lokal tetapi menggunakan aksara Arab sebagai sistem kodenya, telah menjembatani antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman dalam karya tertulis. Karena itu, tidak mengherankan secara bertahap namun pasti, aksara Arab pada akhirnya menggeser aksara Hindu sebagai sebuah kebudayaan yang tidak sempat berkembang di wilayah ini.
Kemampuan yang mereka miliki dalam hal ini turut membawa dampak bagi kesusasteraan lokal non-keagamaan yang sebelumnya—kecuali hikayat —ditradisikan melalui lisan. Sebagai konsekuensinya, tradisi lokal ini pun pada akhirnya tidak terlepas dari pengaruh Islam, tidak saja terlihat dari aspek aksara yang digunakan, tetapi juga dari perubahan karakter tokoh-tokoh yang diceriterakan, alur cerita serta penambahan materi yang sesuai dengan keinginan penulis.
Secara lebih spesifik, penulisan dan penyalinan manuskrip di Surau erat kaitannya dengan pewarisan sumber-sumber rujukan kalangan tradisi. Kata “tradisional” pada aspek tertentu mengandung penegasan adanya transmisi literatur keagamaan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Surau-Surau berbasis tarekat Syattariyah yang melaksanakan penulisan manuskrip-manuskrip keagamaan pada masa lalu mengemban proses ini. Fathurahman menegaskan bahwa, Tarekat Syattariyah di nusantara dengan persebaran manuskrip-manuskripnya dapat menjelaskan matarantai keilmuan dan saling keterhubungan guru dan murid komunitas ini. dalam konteks itu, demikian Fathurahman, Surau Paseban tergolong produktif melahirkan manuskrip. Pada saat sekarang jejak-jejak produktifitas Surau Paseban dalam melahirkan naskah masih terlihat. Berdasarkan pendataan di lokasi dugaan-dugaan tersebut terlihat realistis. Terdapat 29 manuskrip dengan berbagai kondisi. Jumlah ini merupakan sebagian saja dari keseluruhan naskah yang pernah ada di Surau itu. Menurut salah satu sumber dari Surau Paseban menyebut angka 40. Konon, menurut informasi sumber tersebut, banyak diantara murid ataupun kerabat yang membawa serta diantara manuskrip-manuskrip itu meskipun tidak ada izin dari Syekh Paseban sendiri. Akibat dari pelanggaran demikian, orang yang membawa manuskrip-manuskrip itu mengalami berbagai musibah. Diluar konteks magis seperti itu, keterangan ini sedikit menjelaskan harga sebuah manuskrip bagi komunitas Surau ini pada masa lalu dalam kehidupan sosial keagamaan mereka.
Adanya dugaan bahwa Surau Paseban dijadikan sebagai tempat menulis naskah boleh jadi benar. Beberapa petunjuk dari hasil pengamatan langsung, agaknya memperkuat dugaan itu. Namun batasannya tidak terlalu kaku, terutama terkait dengan tokoh, tempat dan waktu penulisan atau penyalinan naskah. Biasanya informasi mengenai hal-hal itu diperoleh dari kolofon, namun sayangnya tidak semua penyalin menyertakan kolofon dalam kitab yang mereka tulis. Dari keseluruhan koleksi manuskrip yang ditemukan di Surau Paseban, terlihat adanya perbedaan dari segi karakter huruf dan jenis kertas. Petunjuk ini sedikit mengarahkan adanya sejumlah orang yang terlibat dalam aktifitas penulisan.
Menurut informasi yang berkembang di lokasi, secara garis besar koleksi yang terdapat di Surau Paseban dapat dipilah menjadi tiga bagian. Pertama, manuskrip-manuskrip yang dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau-Surau tempat beliau mengajar. Kedua, manuskrip-manuskrip karangan Syekh Paseban sendiri ataupun salinan dari kitab-kitab terdahulu, dan ketiga, manuskrip-manuskrip yang dikarang atau disalin ulang oleh para murid, baik ketika menetap di Surau, maupun setelah tamat belajar di Surau dan mendirikan Surau di tempat masing-masing. Keterangan dari pewaris Surau dan guru-guru dari generasi sekarang hanya menyebut bahwa sebagian manuskrip-manuskrip itu dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau Padang Gantiang dan Surau Pakandangan tempat dimana Syekh Paseban pernah menimba ilmu. Sebagian lain, menurut asumsi ini tentu ditulis oleh Syekh Paseban dan murid-muridnya di Surau Paseban sendiri. Sebagaimana maksud dari penelitian ini, keterangan atau asumsi ini akan ditinjau lebih jauh lewat telaah kodikologis.
Dari segi penggunaan bahasa, pada umumnya kitab-kitab yang terdapat di Surau ini menggunakan aksara dan bahasa Arab. Pada bagian pinggir lembaran naskah—yang biasanya ditulis untuk menjelaskan teks inti (syarah), baik berupa terjemahan dari kata-kata tertentu maupun berupa penjelasan panjang dari sebuah gagasan—sering dijumpai akasara Arab berbahasa Arab Melayu. Terkadang aksara Arab dengan bahasa Melayu ini ditulis terpisah pada beberapa lembar. Barangkali bentuk interpretasi dari seorang atau beberapa murid ketika menerima pelajaran dari guru ketika aktifitas pengajaran berlangsung. Untuk sekelompok manuskrip, model penulisan, termasuk dalam hal ini karakter huruf yang digunakan, memperlihatkan banyak kesamaan. Harusnya, keseragaman ini dapat menggiring pada kesimpulan adanya seorang penyalin naskah yang sangat aktif pada masa aktifitas pengajaran di Surau Paseban masih berlangsung atau pada masa Syekh Paseban masih hidup. Guratan-guratan pada sisi pinggir teks yang berbahasa Arab Melayu setidaknya menjelaskan difungsikannya teks pada masa itu.
Dari segi jumlah, manuskrip yang ada saat ini di Surau Paseban berjumlah 29 manuskrip dengan berbagai kondisi. Namun jumlah tersebut menurut keterangan Imam Maulana Abdul Manaf Amin, jumlahnya ratusan. Manuskrip yang disebutnya kitab-kitab tersebut tersimpan di mihrab Surau dan tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar. Bagi murid-murid atau orang lain yang ingin membaca dan menyalin isi naskah, maka harus dilakukan di dalam mihrab tersebut. Gambaran tentang keberadaan kitab-kitab (manuskrip) di Surau Paseban dapat dilihat dalam kutipan berikut ini.
“Di atas sudah kita terangkan bahwa, sesudah sekalian kitab, sudah dijemur, kemudian diletakkan kembali ke tempatnya di mihrab. Maka beliau beramanat ketika itu kepada orang banyak yang kata beliau “Siapa orang yang hendak kitab aku ini tidak boleh dilarang, tetapi isinya yang boleh diambil yang kitabnya tidak aku izinkan dan tidak aku ridhokan melampaui pintu muka.” Arti amanat beliau, siapa yang mau kitab beliau itu salinlah di mihrab, tidak boleh dibawa ke luar. Oleh karena amanat beliau itu begitu bunyinya, maka mufakatlah pengurus supaya kitab ini terpelihara jangan berserak. Maka dibuatlah bilik dalam mihrab, sekalian kitab beliau disimpan di dalam yang tukangnya Khatib Muhammad Nur, anak beliau dan saya sendiri sama membantu tukang.
Setelah kamar selesai dibangun, sekalian kitab disimpan di dalamnya. Kamar itu tidak boleh dibuka, kecuali ada orang hendak melihat atau menyalinnya. Kuncinya terpegang kepada satu tangan orang yang tetap disuruh setelah orang kembali dari Mekkah. Maka pakaian beliau yang dibawa dari Mekkah, diletakkan di atas kasur tempat duduk beliau mengajar di dalam kamar mihrab. Kasur dan pakaian beliau itu dianggap orang sebagai makam beliau. // Orang-orang yang teragak dengan beliau ke Surau dan pakaian itulah kini menemui beliau kamar itu. Dibuka selain yang yang dua ini yaitu penyalin sepeninggal beliau Syekh Paseban, Inyiak Adam mendirikan Sekolah Rakyat Al-Islamiyah di muka Surau Gadang, Kota Panjang dan ada kantornya. Pada suatu hari, Inyiak mengadakan rapat di rumah sekolah itu. Saya dan kakak saya Buya Gafur diundang menghadiri rapat itu. [Saya] Sebelum memasuki sekolah, saya menengok dahulu ke kantor sekolah, saya tercengang karena melihat empat kitab besar yaitu kitab Nahayah, kitab Syekh Paseban. Saya terheran mengapa kitab ini dibawa Inyiak ke sini? Padahal amanah beliau tidak diiizinkan melampaui pintu muka, ini berada di sini, telah jauh dari Surau, telah melanggar amanah beliau. Kemudian pada tahun 1986 Masehi Inyiak Adam mengadakan maulid di Surau Paseban. Beliau undang Buya Haji Bahar dan Buya Haji Salim dari Candung. Buya Haji Muhammad dari Jaho, Padang Panjang, Buya Batang dan saya dari Batang Kabung. Buya Syafi’i saya dan Pakih Rifin. Buya haji Bahar dan Buya Haji Salim di Surau Usang, Buya Dalil dan kami ditempatkan di Surau Baru karena Buya Dalil dan Buya Bahar tidak cocok. Di Surau Baru ada almari berisi kitab, saya perhatikan kitab itu kitab Angku Paseban, waktu Inyik akan menaik Surau itu saya berkata kepada Buya Dalil “Kitab ini tidak diizinkan beliau melampaui pintu muka.” Maka setelah Inyiak duduk, dia berkata kepada Buya Dalil “Begitu Buya perkataan // Khatib itu betul, yang dimaksud beliau itu tidak boleh melampaui pintu muka Artinya kitab itu hendaklah dipelihara, jangan disia-siakan, inikan terpelihara terletak dalam lemari yang terkunci tidak tersia-sia.” Maka saya diam saja kalau saya jawab “Yang ini betul dalam almari, tetapi yang di kantor sekolah bagaimana?” kalau saya jawab begitu mungkin beliau marah pada saya itu saya diam saja.
Sekarang kamar itu tidak terawat lagi, kadang berkunci kadang-kadang tidak dan telah menjadi tempat tidur dan kitab-kitab beliau itu telah berserak letaknya dan ada yang diambil orang. Ini menurut pendapat saya, telah melanggar amanah beliau bagaimana sebenarnya? Sudah habiskah kepercayaaan kita terhadap beliau? Sudah dipandang leceh, sudah dipandang enteng saja kata-kata beliau itu. Inilah yang saya resahkan dan menjadi perasaan di jiwa saya.”
Dari kutipan di atas diperoleh keterangan penting bahwa koleksi yang dimiliki Surau ini telah banyak dibawa keluar oleh murid dan keturunan Syekh Paseban sendiri. Kecuali beliau, murid-murid yang lain agaknya kurang memahami arti penting menjaga koleksi manuskrip warisan sang guru. Belakangan, peran menjaga koleksi itu diteruskan oleh Zul Asri, murid dari Imam Maulana. Sebagaimana gurunya, Zul Asri sendiri sangat menghargai manuskrip yang tersisa. Ada semacam penghormatan yang mendalam terhadap sosok Syekh Paseban.
Dari ke 29 koleksi manuskrip yang ada di Surau Paseban di atas sedikitnya menjelaskan beberapa hal:
Pertama, dari sisi penguasaan keilmuan, patut diduga bahwa Syekh Paseban lebih menguasai ilmu Fiqih berdasarkan komposisi koleksi naskah di Surau tersebut. Jika keterangan dari Imam Maulana di atas benar, dimana banyak naskah yang dibawa ke luar dan dimiliki secara pribadi maupun lembaga oleh oknum murid-murid beliau, maka dugaan ini bisa saja mentah kembali, tentu saja karena kemungkinan adanya manuskrip lain yang lebih banyak (misalnya tasauf/tarekat, tafsir, mantiq dan sebagainya).
Komposisi naskah berdasarkan telaah di lokasi dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Tema Naskah Klasifikasi Pembidangan Keilmuan Jumlah
1 Fiqih/Ushul Fiqh Hukum Islam 13
2 Nahwu/Balaghah Bahasa/Sastra 8
3 Tafsir Pemahaman terhadap makna dan arti ayat al-Quran 5
4 Tauhid/Ushul al-Din Ketuhanan 2
5 Lain-lain Tidak teridentifikasi 1
Dari tabel dan uraian di atas tidak ditemukan satu pun naskah yang berkaitan dengan tashauf atau pun tarekat. Padahal seperti diterangkan sebelumnya, Surau Paseban pelanjut dari tradisi tarekat Syattariyah di Minangkabau yang hingga hari ini masih diberlangsungkan oleh penerus atau murid-murid beliau. Di sini penjelasan Imam Maulana di atas menjadi penting untuk kembali melakukan pelacakan terhadap naskah-naskah lain (terutama bidang tasauf dan tarekat) yang dikoleksi oleh oknum murid.
Kedua, koleksi manuskrip yang ada menggambarkan sebuah model transmisi keilmuan Syekh Paseban berupa kepemilikan kitab-kitab keagamaan yang dibawa dari tempat beliau pernah menuntut ilmu. Di antara kitab-kitab yang dideskripsikan di atas, hanya satu yang hampir dapat dipastikan disalin di Surau Paseban oleh seorang bernama Amânullah al-Fariyâmani (kitab Itmâm al-Dirâyah li Qirâ’ah al-Nuqâyah). Hal itu berkenaan dengan keterangan di dalam kolofon mengenai tempat diselesaikannya manuskrip ini (Koto Tangah). Selebihnya berkemungkinan besar dibawa dari Surau-Surau tempat beliau menuntut ilmu. Meski hanya satu nama yang ditemukan, namun dugaan bahwa Surau ini pernah dijadikan sebagai skriptorium—dalam pengertian sebagai tempat menyalin naskah—boleh jadi benar. Sejauh ini tidak ada petunjuk lain yang berkenaan dengan kiprah kepenulisan al-Fariyâmani dalam tradisi tulis di Surau Paseban, dan Surau-Surau berbasis tarekat Syattariyah lainnya. Tetapi dari aspek kesamamaan karakter tulisan dapat diajukan dugaan bahwa orang dimaksud mungkin ditugaskan untuk menyalin kitab-kitab di Surau ini. Corak dan model karakter huruf kitab Itmâm al-Dirâyah li Qirâ’ah al-Nuqâyah yang disalin oleh al-Fariyâmani memiliki kesamaan dengan naskah-naskah:
MM.04.Paseban.10;MM.04.Paseban.11;MM.04.Paseban.12;MM.04.Paseban.13;MM.04.Paseban.14;MM.04.Paseban.15;MM.04.Paseban.16;MM.02.Paseban.01;MM.02.Paseban.02;MM.02.Paseban.03;MM.02.Paseban.04;MM.02.Paseban 05;
Pada manuskrip kitab Nahu Muqaddimah fi ‘ilm al-‘Arabiyah dengan nomor katalog MM.09 Paseban 22, ditemukan jenis huruf dan nama penyalin yang berbeda. Seperti diterangkan dalam bagian deskripsi (lihat naskah nomor 14 dari urutan deskripsi), di bagian kolofon disebutkan bahwa penulis atau penyalin adalah Imam Khatib Marah (dari) Negeri Fansur. Keterangan kolofon adalah satu-satunya petunjuk, terutama mengenai nama penyalin, bahwa manuskrip ini memang tidak ditulis di Surau Paseban. Sangat berkemungkinan manuskrip ini dibawa dari Tanjung Medan Ulakan, tahap-tahap awal Syekh Paseban menimba ilmu keagamaan dalam perjalanan pendidikannya. Ilmu Nahu sendiri merupakan kunci utama dalam mempelajari kitab-kitab keagamaan dan tentunya sangat mempengaruhi penguasaan materi sang murid pada tahap-tahap selanjutnya. Pada kitab al-Bakri (MM.04. Paseban 20) juga memunculkan nama penyalin, Khatib Intan Orang Negeri Rajo. Namun tidak ada kejelasan tempat persis ditulisnya kitab, sehingga menyulitkan pengidentifikasian.
Ketiga, dari keterangan tanda air (watermark/countermark) dalam kertas-kertas yang digunakan sebagai media penyalinan kitab, menjelaskan bahwa naskah-naskah ini berusia cukup tua. Informasi itu dapat dilihat dari tabel berikut:
No Nama watermark/countermark Negara Produsen Tahun pembuatan/penggunaan keterangan
1 Pro Patria J.H/J.H. Hessel Belanda 1778 2 Manuskrip
2 Pro Patria/B.H. Pasman Belanda 1808 2 Manuskrip
3 Pro Patria/G.R Belanda 1776 5 Manuskrip
4 Pro Patria/FKP - - 1 Manuskrip
5 Pro Patria/JHA - - 1 Manuskrip
6 Pro Patria/HV Belanda 1632-1634 1 Manuskrip
7 J. HONIG & ZOON Belanda 1737-1787 1 Manuskrip
8 Pro Patria/HIVD Elden - - 1 Manuskrip
9 Pro Patria/J.H & Z HONIC - - 1 Manuskrip
10 Pro Patria - - 1 Manuskrp
11 Pro Patria/VDL Belanda 1734 1 Manuskrip
12 Foolscap/DS Belanda Awal abad ke-17 1 Manuskrip
13 Kertas lokal - - 6 manuskrip
14 Tidak teridentifikasi - - 3 Manuskrip
Keterangan tahun pembuatan/penggunaan kertas di dalam tabel masih harus dikonversikan dengan perkiraan penggunaannya di wilayah minangkabau. Jika kertas dibawa dari pabrikan Eropa ke wilayah ini dengan menggunakan transportasi yang umum waktu itu (misalnya kapal) setidaknya memakan waktu dua sampai tiga bulan. Belum lagi persoalan teknis birokrasi kerajaan, distribusinya di wilayah nusantara hingga digunakan oleh para penulis dan penyalin. Mungkin benar perkiraan yang menyebutkan bahwa kertas-kertas Eropa yang datang ke wilayah ini memakan waktu 15 tahun ke tangan para penulis dan penyalin naskah. Jika diperkirakan Surau Paseban telah memulai aktifitas sekitar penghujung abad ke-19, maka berdasarkan data-data cap kertas yang ditemukan, agaknya naskah-naskah itu telah lebih dahulu hadir di Surau-Surau tempat beliau belajar, sebelum akhirnya mendirikan Surau, hal mana sedikitnya berhubungan dengan kesimpulan kedua di atas, bahwa pada dasarnya koleksi naskah-naskah tersebut kebanyakan tidak ditulis di Surau Paseban.
Keterangan usia kertas agaknya dapat membantu identifikasi penanggalan dalam kolofon. Kitab al-Minhâj misalnya disebutkan selesai ditulis pada tanggal 30 Rajab 1125 H/22 Agustus 1713 M. Sedangkan dari pengamatan watermark/countermark kertasnya produksi Pro Patria/GR yang berangka tahun 1776 M. Tidak mungkin ia ditulis sebelum kertas yang digunakan belum disediakan. Perbedaan mencolok juga terlihat pada kitab Muqaddimah fi ‘Ilm al-‘Arabiyah. Di dalam kolofon disebutkan bahwa kitab ini selesai disalin pada bulan Dzul Hijjah 1100 H/Oktober 1689. Padahal naskah ini menggunakan kertas Eropa dengan watermark/countermark Pro Patria/J Honig & ZOON yang diproduksi sekitar tahun 1737-1787. Malah situs data base watermark lain mendaftarkan merek ini sebagai kertas produksi tahun 1750-1799.
Informasi yang mengandung kesesuaian diperoleh dari kitab Hâdi al-Muhtâj fi Syarh al-Minhâj. Disebutkan bahwa kitab selesai disalin pada bulan Dzul Hijjah tahun 1201/September 1787. Sedangkan kertasnya adalah Pro Patria/GR yang diproduksi sekitar tahun 1776. Terdapat jarak 11 tahun dari masa kertas diproduksi hingga sampai ke tangan penyalin naskah.
Meski terdapat kejanggalan antara pengakuan penyalin dengan tahun produksi kertas pada beberapa naskah, tetapi secara umum, bahwa naskah-naskah ini berangka tahun lebih tua (dengan rentang penulisan 1632-1808 berdasarkan cap kertas dan keterangan kolofon) dari Surau Paseban dan Syekh Paseban sendiri jelas mendukung pendapat di atas, di mana pada umumnya naskah-naskah tersebut memang dibawa ke Surau Paseban, dan bukan lahir di Surau Paseban.
Keempat, ditinjau dari judul-judul naskah dan nama pengarang mempertegas bahwa Surau Paseban melanjutkan sebuah tradisi keagamaan dalam mazhab Syafi’i. Di antara nama-nama penting yang terungkap dalam naskah antara lain Abu al-Qâsim ‘Abd al-Karîm al-Fadhl Ibn al-Hasan al-Râfi’i al-Syâfi’i (w. 623 H/1266 M), Mahyu al-Dîn Abû Dzakariyâ Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi (w. 676 H/1277M), Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmân ibn al-Hasan Tâj al-‘Ârifîn al-Bakry al-Shiddîq al-Syâfi’i al-Asy’ari dalam bidang Fiqih; Abdullâh Jalâl al-Dîn Muhammad Ibn Yusuf Ibn Hishâm al-Anshâri (708 H -761 H/1308 M-1359 M), Jalâl al-Dîn al-Qazwîn (w.739 H/1338 H), dalam bidang tata bahasa Arab (terutama nahwu); Imâm Jalâl al-Dîn Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli al-Syâfi’i (791 H-864 H/1388 M-1459 M), dalam bidang tafsir; dan al-Imâm al-‘Allamah Mazîd al-‘Ish Jalâl al-Dîn al-Suyûthi al-Syâfi’iy (849 H-911 H/1445 M-1505 M), dalam bidang tauhid dan ushûl al-dîn.
Meski hanya sedikit nama pengarang yang bisa terkuak di lokasi, namun beberapa nama merupakan tokoh kunci dalam penyebaran mazhab al-Syâfi’i. Di sini akan dikupas dua nama penting dalam bidang Fiqih. Abu al-Qâsim al-Râfi’i, dapat dianggap penulis utama dalam barisan keilmuan dan keulamaan mazhab Syafi’i yang karya-karyanya banyak menjadi rujukan oleh ulama-ulama pada masanya dan sesudahnya. Hadirnya karya al-Râfi’i di Surau Paseban merupakan bukti penting bagi pengungkapan sumber awal pengajaran mazhab Syafi’i di ranah lokal. Sebagai tokoh penting dalam literatur fiqih bermazhab Syafi’i, al-Râfi’i telah meletakkan tonggak baru dalam perujukan sumber-sumber mazhab ini. Kapasitas al-Râfi’i dalam bidang ini dilanjutkan kemudian oleh Mahyu al-Dîn Abû Dzakariyâ Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, tokoh yang karyanya juga terlacak di Surau Paseban. Sebagaimaman al-Râfi’i, al-Nawawi juga melahirkan karya-karya yang menjadi sandaran dalam penulisan ataupun penyalinan kitab-kitab fiqih mazhab Syafi’i pada masa-masa berikutnya.
Keterangan ini juga membuktikan bahwa, sepanjang menyangkut pengajaran keagamaan umum, ulama lokal semisal Syekh Paseban tidak melakukan interpretasi ulang terhadap sumber-sumber utama mazhab Syafi’i. Manuskrip keagamaan yang hadir di Surau ini lebih bersifat salinan ulang dengan model yang lebih ringkas dari kitab aslinya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh al-Râfi’i maupun al-Nawawi terhadap literatur yang lebih terdahulu, dimana, selain meringkas mereka menjalankan proses kreatif dalam menyeleksi sumbe-sumber dan melakukan pen-tashih-an terhadap sumber-sumber yang dianggap benar. Mengutip Calder, Ahmad Baso memberi alasan bahwa hal itu lebih disebabkan kepada prinsip diakronik dalam bermazhab, dimana pengikut mazhab, dalam hal ini ulama mazhab Syafi’i, akan selalu menjaga loyalitasnya terhadap tradisi dengan menghargai prestasi-prestasi yang telah dicapai ulama-ulama pendahulu mereka.
Keempat point di atas merupakan sifat-sifat khusus dari koleksi manuskrip di Surau Paseban. Penelusuran aspek fisik terhadap koleksi naskah Surau ini, tentunya diluar dari naskah-naskah yang ditulis oleh Imam Maulana Abdul Manaf Amin, murid Syekh Paseban yang telah disebut di muka. Corak penulisan dan koleksi yang dimiliki oleh Imam Maulana relatif berbeda dengan apa yang ditemukan di Surau ini. 22 naskah yang ditulis oleh Imam Maulana, diakui sebagai bentuk kreatifitas, dimana ia mmerangkum dari berbagai sumber, termasuk dari manuskrip yang dimiliki oleh Syekh Paseban sendiri. Secara umum, karya-karya Imam Maulana terbagi dalam berbagai tema keagamaan: tasauf, fiqih, sejarah amalan-amalan tradisional. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Maulana Amin al-Khatib pada umumnya menggunakan bahasa Arab Melayu dengan aksen bahasa sedikit berbau Minang. sebagian besar manuskrip tulisan beliau saat ini tersimpan di Surau Surau Nurul Huda Subarang Air Batang Kabuang Koto Tangah, tempat dimana ia melanjutkan aktifitas menulis hingga akhir hayatnya yang terletak sekitar 5 km arah Utara dari Surau Paseban. Karakter hurufnya terlihat khas, mudah dikenali dan dapat dibaca dengan baik. Terkadang, sebagian kopian dari manuskrip-manuskrip peninggalan beliau dibawa ke Surau Paseban, serta Surau-Surau lain yang menjadi konsentrasi penyebaran ajaran-ajaran Syekh Paseban.
Sebuah naskah Fiqih versi kopian yang ditulis oleh Imam Maulana Abd al-Manaf Amin al-Khatib
Karangan-karangan Imam Maulana ditulis berupa saduran, ringkasan atau kesimpulan dari gagasan-gagasan yang terdapat dalam kitab-kitab peninggalan Syekh Paseban, dan catatan dari ajaran-ajaran Syekh Paseban sendiri yang disusun berbentuk kitab.
Aktifitas penulisan Imam Maulana sesungguhnya terletak pada upaya penjabaran kembali nilai-nilai tradisional, terutama dalam hal ini kelompok yang dinamakan penganut tarekat Syattariyah dalam sebuah dunia yang mulai berubah. Ada semacam spirit untuk memberi interpretasi baru dalam menyebarkan gagasan-gagasan yang secara tradisional dikembangkan oleh para pendahulu mereka. Spirit itu terlihat jelas dari karya-karya tulisan Imam Maulana yang hingga saat ini masih dibacakan di Surau-Surau yang didirikan oleh murid-murid Syekh Paseban. Selain penyederhanaan dari segi isi, uraian juga disampaikan dalam bahasa Arab Melayu, agar kendala-kendala dalam memahami kitab-kitab berbahasa Arab dapat diatasi. Untuk alasan-alasan di atas tulisan-tulisan Imam Maulana penting untuk dijadikan alat pembacaan terhadap konteks sejarah manuskrip yang ada di Surau Paseban.
Koleksi manuskrip yang terdapat di Surau Paseban memiliki arti penting guna melihat dinamika transmisi dan kesinambungan ajaran-ajaran keislaman pada awal abad XX. Dalam ranah yang lebih luas, koleksi-koleksi serupa juga banyak tersebar di wilayah Minangkabau. Terkait dengan issu penolakan terhadap paham pemurnian dan pembaharuan, secara umum naskah-naskah keagamaan yang diajarkan di Surau-Surau Minangkabau relatif seragam. Demikian pula sifat-sifat koleksi manuskrip yang terdapat di Surau-Surau pada awal abad XX, tidak banyak ditulis di Surau, melainkan dibawa dari tempat belajar sebelum mendirikan Surau.
Penutup
Surau Paseban yang dijadikan sebagai studi kasus, diketahui memiliki sedikitnya 29 manuskrip dalam berbagai cabang keilmuan. Melalui pembacaan fisik naskah diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan manuskrip di Surau merupakan bukti adanya aktifitas penyalinan dan distribusi kitab yang menjadi salah satu model transmisi ajaran-ajaran keislaman pada masa lalu, terutama memasuki awal abad XX. Sedikitnya hal itu mengindikasikan bahwa Surau tersebut pernah dijadikan sebagai skriptorium pada masa lalu. Hal itu didukung pula oleh adanya kesamaan beberapa manuskrip dari aspek tulisan dengan manuskrip yang memuat nama penyalin. Oleh karena itu, di sini dapat digagas bahwa Surau Paseban memang pernah dijadikan sebagai tempat menyalin naskah. Dari studi ini dapat pula diketahui kontinuitas dari sebuah mazhab melalui identifikasi nama-nama pengarang yang terdapat di dalam manuskrip-manuskrip tersebut. Berdasarkan penelitian ini, Surau Paseban telah memainkan peran penting dalam proses transmisi ini dengan secara aktif memainkan peran penghubung Islam tradisional pada awal abad XX dengan masa-masa sebelumnya melalui pengadaan manuskrip dan sekaligus pengajarannya di Surau. Berangkat dari hal tersebut, koleksi manuskrip yang ada di Surau Paseban merupakan gambaran tidak langsung dari penguasaan materi-materi keagamaan yang dimiliki oleh seorang Syekh.
Hasil penting lainnya dari penelitian terhadap fisik naskah adalah keterangan yang dperoleh dari cap air kertas. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa manuskrip-manuskrip yang terdapat di Surau Paseban berusia cukup tua, antara 1632-1808 M.
Selain itu, melalui penggalian terhadap manuskrip di Surau Paseban dan perjalanan keilmuan Syekh Paseban juga diperoleh infomrasi penting bahwa standar keilmuan ulama pada masa lalu dalam tradisi keulamaan yang diajarkan melalui wadah Surau sangat komplek. Penguasaan kitab-kitab keagamaan dan didukung oleh ilmu-ilmu alat yang kuat, terbukti mampu melahirkan generasi ulama dengan kualitas yang kuat berupa wawasan dan pengetahuan yang luas. kelengkapan materi keagamaan di Surau yang terekam dalam koleksi manuskrip yang ada membuktikan hal itu.
Penelusuran terhadap koleksi manuskrip di sebuah Surau, ada sejumlah saran yang perlu penulis kemukakan:
1. Perlu terus dilakukan pelacakan terhadap sumber-sumber manuskrip keagamaan yang ada di tangan pribadi agar penelitian terhadap koleksi sebuah Surau dapat dilakukan secara utuh. Apalagi di tengah kian semaraknya perhatian banyak pihak sepanjang hampir satu dekade ini terhadap keberadaan manuskrip-manuskrip keagamaan. Manuskrip-manuskrip di tangan pribadi yang dibawa dari Surau sulit diakses dengan berbagai alasan. Untuk upaya ini, perlu dijalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yang melibatkan pihak universitas (dalam hal ini Universitas Andalas, UNP, Universitas Bung Hatta dan lain-lain), IAIN, Departemen Agama RI (dalam hal ini Badan Litbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI), Perpustakaan Wilayah, Pemerintah setempat dan masyarakat luas guna mensosialisasikan pentingnya arti manuskrip bagi kehidupan masyarakat luas.
2. Berangkat dari pembacaan terhadap koleksi manuskrip yang ada di Surau Paseban terlihat sejumlah penguasaan materi-materi keagamaan pada masa lalu di Surau, dan oleh karenanya penting direkosntruksi dan direvitalisasi kembali bagi perumusan program Pemerintah dalam menggalakkan upaya “kembali ke Surau”. Hal itu tentu saja disertai dengan semangat membenahi kembali situs-situs Surau yang kondisinya kian hari kian memprihatinkan.
3. Dari aspek lain, ketersediaan manuskrip-manuskrip keagamaan dalam bentuk suntingan masih sangat langka. Kemampuan masyarakat membaca manuskrip-manuskrip berbahasa Arab dan Jawi tidak sama dengan kemampuan mengakses teks-teks keagamaan berbahasa Indonesia dengan aksara Latin. Oleh karena itu perlu digalakkan upaya transliterasi manuskrip-manuskrip keagamaan, agar dapat karya-karya tulisan tangan yang semakin rusak itu dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas untuk berbagai kepentingan.

























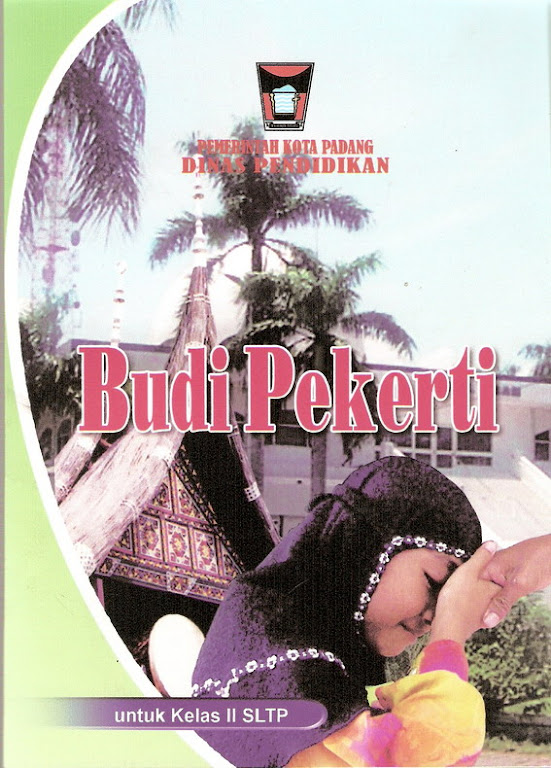





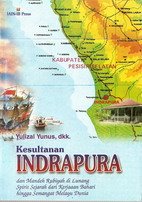




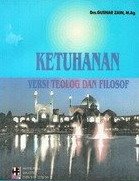
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar