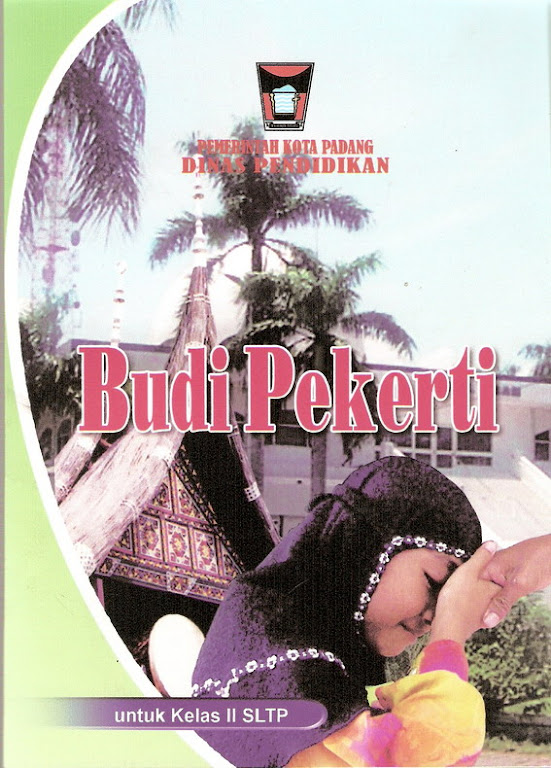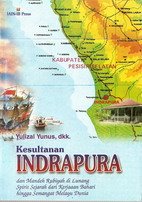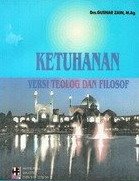Oleh : Andri Rosadi, Lc., M.Hum (Dosen Antropologi FIBA)
 Jakarta merupakan kota yang menjadi simbol perubahan menuju modernisasi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga dalam pola keberagamaan. Walaupun banyak terjadi perubahan dalam pola keberagamaan masyarakat kota Jakarta, pola-pola lama yang masih bertumpukan pada figur tunggal, pemahaman lebih berbasis pada konsumsi daripada produksi masih bisa ditemukan, yang direpresentasikan dengan baik oleh para pengikut Front Pembela Islam (FPI).
Jakarta merupakan kota yang menjadi simbol perubahan menuju modernisasi di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, tapi juga dalam pola keberagamaan. Walaupun banyak terjadi perubahan dalam pola keberagamaan masyarakat kota Jakarta, pola-pola lama yang masih bertumpukan pada figur tunggal, pemahaman lebih berbasis pada konsumsi daripada produksi masih bisa ditemukan, yang direpresentasikan dengan baik oleh para pengikut Front Pembela Islam (FPI).Pemahaman tersebut akhirnya lebih banyak menciptakan unifikasi interpretasi daripada diversitas; lebih menciptakan structur yang hegemonik daripada sebaliknya. Saya akan membahas lebih lanjut dalam tulisan ini pola-pola keberagamaan para pengikut FPI tersebut dalam kaca mata posmodernisme yang lebih menekankan pada produksi daripada konsumsi; diversitas daripada unifikasi; dan decentering daripada centering. Saya melihat bahwa pola keberagamaan para pengikut FPI tersebut, dalam banyak hal, bertolak belakang dengan spirit posmodernisme. Penggunanaan konsep-konsep posmodernisme untuk memahami pola keberagamaan FPI semata-mata bertujuan untuk meletakkan pola-pola keberagamaan tersebut dalam kerangka masa kini tanpa ada pretensi untuk mengatakan ada yang lebih baik dan unggul di antara kedua pola tersebut. Sebagai kota yang terletak di negara yang masih tergolong dalam Dunia Ketiga, saya akan menerangkan terlebih dulu berbagai perubahan yang terjadi di Jakarta dan efeknya terhadap perubahan pola keberagamaan. Kota Jakarta penting untuk diuraikan disini karena statusnya sebagai tempat lahir dan berkembang FPI.
Dunia Ketiga dalam perubahan
Dalam tulisannya, Joe Holland memaparkan permasalahan yang dihadapi oleh masing masing Dunia, mulai dari Dunia Pertama hingga Dunia Ketiga (Holland 2005: 65). Pada Dunia Ketiga, permasalahan utamanya adalah ekonomi. Apapun permasalahan kultural dan politik yang mereka hadapi, yang utama tetap permasalahan ekonomi. Pada Dunia Kedua, sisi yang menonjol adalah masalah politik. Sementara pada Dunia Pertama, yang paling menonjol adalah masalah kultural (Holland 2005: 65). Permasalahan kultural pada Dunia Pertama ini bisa juga disebut dengan permasalahan pemaknaan. Lebih lanjut, menurut Holland, inti suatu kultur adalah spiritualitasnya, karena setiap kultur pada dasarnya adalah sebuah visi spiritual tentang realitas. Artinya, krisis kultural di Dunia Pertama bisa juga dikatakan sebagai krisis spiritualitas.
Sebagai kota yang terletak di Dunia Ketiga, Jakarta dihadapkan pada permasalahan ekonomi dengan tingginya jumlah pengangguran, kemiskinan dan ketiadaan jaminan sosial dari pemerintah. Penduduk Jakarta yang bekerja pun lebih banyak di sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial. Permasalahan ekonomi tersebut kemudian mencapai klimaknya akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998. Menurut salah seorang tokoh FPI, krisis ekonomi tidak hanya menambah beratnya beban ekonomi masyarakat, tapi juga menimbulkan permasalahan kultural dan sosial.
Secara umum, warga dunia berbeda dalam merespons permasalahan yang mereka hadapi. Jika krisis kultural pada Dunia Pertama mengakibatkan orang lari dari agama, krisis ekonomi di Dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia, justru mengakibatkan hal yang sebaliknya: masyarakat justru memperkuat pola keberagamaan mereka, namun bukan relijiusitasnya. Agama menjadi wadah terpenting sebagai faktor pemersatu dan pembentuk identitas. Pola keberagamaan yang saya maksud di sini lebih dalam tataran ekspresi dan simbol-simbol formal, sementara relijiusitas merupakan aspek terdalam dari kualitas keberagamaan seseorang yang sudah tidak tergantung pada ekspresi dan simbol lagi. Perilaku pengikut Front Pembela Islam di Jakarta, yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan budaya akan saya lihat dalam konteks pola keberagamaan, bukan kualitas relijiusitas dalam perspektif posmodernisme.
Posmodernisme dan Agama
Berbicara tentang posmodernisme, berarti masuk ke dalam wilayah yang penuh ambiguitas, ketidakpastian dan disensus. Istilah ini menjadi lebih umum sejak terbitnya buku Lyotard, the Postmodern Condition, pada tahun 1979 (Mats dan Kaj 2000: 148). Istilah ini digunakan untuk mencirikan kecenderungan kontemporer dalam berbagai bidang: sastra, filsafat, arsitektur dan kajian-kajian sosial, terutama antropologi. Secara pasti, tidak ada kepastian ‘setan’ apakah posmodernisme ini. Bahkan pada tingkat yang paling jelas pun, posmodernisme tetap tidak jelas (Gellner 1994: 39). Bagi pendukung modernisme, posmodernisme adalah simbol absurditas yang berkembang ketika manusia (baca: barat) mencari kepastian dengan menggugat kepastian lama, tapi kemudian, ia dikhianati oleh setiap kepastian baru yang dipegangnya. Namun, bagi pendukung posmodernisme, gerakan ini merupakan simbol dari penolakan terhadap adanya kepastian atau Kebenaran (dengan K besar). Kebenaran sebenarnya yang boleh dipegang bersifat fragmentaris dan lokal, tanpa ada kecenderungan untuk menggeneralisasi, apalagi mendominasi.
:: makalah lengkap, (akan) diterbitkan dalam Jurnal Tabuah/Khazanah Edisi mendatang !
Selengkapnya...