Oleh : Muhammad Ilham (Dosen Jur. SKI/Ketua pSIF@ IAIN Padang)
 Ketika kita melihat perubahan-perubahan besar dalam lintasan sejarah peradaban dunia, banyak kita temukan kekuatan-kekuatan sosial dimana kekuatan-kekuatan tersebut melatarbelakangi terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan merupakan sesuatu yang jnheren dalam realitas sosial. Ketika waktu berjalan, manusia-pun berubah seiring dengan gerak waktu tersebut. Namun sebagaimana halnya manusia, perubahan tersebut bisa dikondisikan, terkondisikan, dipercepat, diperlambat bahkan perubahan secara drastis.
Ketika kita melihat perubahan-perubahan besar dalam lintasan sejarah peradaban dunia, banyak kita temukan kekuatan-kekuatan sosial dimana kekuatan-kekuatan tersebut melatarbelakangi terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan merupakan sesuatu yang jnheren dalam realitas sosial. Ketika waktu berjalan, manusia-pun berubah seiring dengan gerak waktu tersebut. Namun sebagaimana halnya manusia, perubahan tersebut bisa dikondisikan, terkondisikan, dipercepat, diperlambat bahkan perubahan secara drastis.Perubahan merupakan sesuatu yang jnheren dalam realitas sosial. Ketika waktu berjalan, manusia-pun berubah seiring dengan gerak waktu tersebut. Namun sebagaimana halnya manusia, perubahan tersebut bisa dikondisikan, terkondisikan, dipercepat, diperlambat bahkan perubahan secara drastis. Ada yang beranggapan bahwa tokohlah yang menyebabkan perubahan itu terjadi (dikenal dengan "Great-Man Theory). Ada yang berpendapat bahwa ekonomi dan strukturnyalah yang berada di belakang suatu perubahan. Ada yang beranggapan bahwa agama, institusi, ideologi, wanita-gender, golongan, umur, budaya, mitos, sex maupun ras-etnis bisa menjadi penyebab yang signifikan dalam melatarbelakangi terjadinya suatu perubahan.
Semua penyebab atau variabel diatas sering diperbincangkan dalam wacana intelektual. Namun ada satu yang seakan-akan "tabu" untuk didiskusikan karena pendekatan ini merusak nilai-nilai humanis universal, yaitu pendekatan bahwa ras-etnis menjadi faktor yang paling signifikan dalam mendorong perubahan sosial. Walaupun ada, karena pertimbangan nilai-nilai humanis tadi, yang berusaha untuk tidak melegitimasi secara keilmuan pendekatan ini, namun yang jelas, dalam sejarah panjang peradaban ummat manusia, pendekatan ini pernah dan mampu menjadi daya tarik potensial dalam menstimuli perubahan sosial, baik cepat maupun lambat. Bahkan zaman sekarang, pendekatan ini masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dikalangan intelektual humanis, pendekatan ini terasa sangat "kejam". Istilah rasis, menjadi konsep yang sangat negatif dalam tataran apapun. Baik itu dalam tataran ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Tapi harus diakui bahwa pendekatan ini pernah dipakai secara sistematis-terorganisir oleh suatu komunitas masyarakat. Klaim terhadap keunggulan suatu etnis bahkan dilegitimasi secara keilmuan. Untuk itu, betapapun "alergi"nya banyak komunitas masyarakat terhadap pendekatan ini, setidaknya pendekatan ini, sampai saat sekarang masih dipakai. Secara filosofis - sebagaimana yang diungkapkan oleh Jean-Paul Sartre, setiap manusia tidak akan pernah menganggap ras mereka sebagai ras inferior, marginal ataupun ras rendah. Setiap bangsa pasti menganggap ras mereka-lah yang paling utama. Dalam konteks sosiologis, pemahaman in-group membuat yang lain adalah out-group. Kemunculan kasta-kasta di India kuno, "negara-teror"nya Hitler dengan program program "horor" hollocaust, ambisiusnya Slobodan Milosevich yang melakukan genocide terhadap muslim Yugoslavia, fenomena politik Perancis beberapa tahun lalu dimana Jean Marie Le-Pen menjadi figur politik sentral di Perancis dengan mengusung isu Nos encestres les Gaulois etaientt Blonds (nenek moyang kita adalah bangsa Gaulis yang berambut pirang) atau fenomena penolakan suku Dayak terhadap etnik Madura di Kalimantan beberapa tahun yang lalu, memperkuat anggapan bahwa rasis adalah entitas pemikiran yang tidak akan pernah tercerabut.
Bila ditelusuri dalam sejarah, secara teoritis, teori rasis pernah mendapat tempat "sempurna" dari kalangan intelektual masa lalu. Filosof Jerman yang terkenal, GH. Herder pernah mengatakan : "Eropa merupakan wilayah yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan daerah-daerah lain karena dihuni oleh orang-orang pilihan cerdas dan diberi kelebihan-kelebihan alam". Sementara itu, peletak dasar teori "Tiga Tahap" dalam sosiologi, Auguste Comte berujar : "Ras kulit putih adalah ras tertinggi dan bahwa dengan sendirinya orang-orang Eropa merupakan elit umat manusia. Ras kulit putih telah mencapai tahap pemikiran tertinggi yaitu positivis setelah sebelumnya terkungkung oleh nuansa teologis yang penuh tahayul". Dan umumnya, pendapat Herder dan Comte tersebut merupakan pendapat mayoritas ilmuan di Eropa pada zamannya. Namun bukan berarti tidak ada yang "menetang". Popper (Karl Raymond Popper), si peletak dasar pendekatan falsifikasi dalam filsafat sejarah dan sosial ini justru pernah mencela "mimpi-mimpi manusia Eropa" tentang keunggulan ras mereka. Popper mengatakan : "Colombus berangkat berlayar dan menemukan Amerika. Apa sebenarnya yang ia cari pada abad ke 15 itu ? Sementara banyak orang Eropa mengatakan bahwa Colombus ingin mencari sebuah pengakuan akan keunggulan ras Eropa dibandingkan ras lain, justru Colombus sebenarnya mencari dua hal yaitu kehormatan dan kekayaan. Sebelum berangkat, Colombus "belajar" dengan kitab "orang lain" dari "ras lain" yang secara diam-diam diakui oleh Colombus sebagai ras unggul, bahkan jauh lebih unggul dari ras Eropa. Colombus membaca Kitab Edras yang dibaca Marco Polo ketika berkeliling ke dunia Timur. Ya .... kitab Edras merupakan kitab orang Timur. Berarti kalau begitu, saya tidak akan ke Timur, karena orang Timur telah unggul, saya harus ke"atas", kata Colombus. Ada sebuah pengakuan Colombus akan keunggulan ras selain ras Eropa dan Colombus tidak pernah mengklaim penemuan benua Amerika oleh ekspedisinya untuk mengklaim keunggulan ras-nya. Justru oleh orang-orang belakangan, ini dipelintir".
Salah seorang sejarawan Jerman (?), A. de Gobineau tertarik untuk melihat dinamika perkembangan dan keruntuhan peradaban-peradaban besar dunia seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia, Lembah Mesopotamia, Lembah Sungai Indus dan lain-lain. Sesudah ia menelusuri segala macam hal yang memungkinkan menjadi penyebabnya, seperti terjadinya dekadensi dalam berbagai dimensi kehidupan, tradisi hedonisme, tata kelola pemerintahan yang buruk, korupsi dan lain-lain, maka Gobineau berkesimpulan bahwa hanya perbedaan ras-lah yang dapat memberikan penjelasan kausalitas yang lebih memuaskan. Bagi Gobineau sudah merupakan kepastian bahkan hukum alam yang tak tergoyahkan, bahwa ras-ras tidaklah sama. Manusia yang menghuni dunia ini sepanjang sejarah, menurut Gobineau, ada tiga ras utama yaitu ras kulit putih, ras kulit kuning dan ras kulit hitam. Ras ini secara historis dan genealogis mempunyai asal yang berbeda-beda. Dan dari ketiga macam ras ini, ras kulit putih, kata Gobineau, merupakan satu-satunya ras yang mampu mencapai kemajuan dan membangun peradaban unggul. Dalam ras-ras tersebut, kata Gobineau lagi, terdapat berbagai sub ras seperti ras Slav (ras bangsa Slavia), ras Yugo (ras bangsa Yugo), ras Indo Jerman (ras bangsa bavaria Jerman), ras Goth, ras Batav (ras bangsa Nedherland), ras Viking (ras bangsa Skandinavia), ras Spanish (ras bangsa Spanyol), ras Porto (ras bangsa Portugal), ras Latin, ras Anglo-Saxon (ras bangsa Inggris), ras Ceko, ras Gaulis (ras bangsa Perancis) dan lain-lain. Di antara sub-ras tersebut, maka Gobineau berpendapat bahwa ras Aria merupakan sub-ras yang paling sempurna dan yang telah menghasilkan semua peradaban besar.
Pendapat Gobineau diatas bisa dikonfrontirkan dengan pendapat Antropolog Perancis Jean-Claud Levi Strauss. Levi Strauss mengatakan bahwa komunitas masyarakat yang tertutup dan menjalani perkawinan secara internal (perkawinan yang dilakukan terbatas diantara anggota masyarakat atau diantara suku mereka), maka konsekuensinya suku tersebut akan punah. Strauss mengatakan bahwa banyak suku-suku pedalaman yang menganggap tabu dan merasa terhina untuk melakukan perkawinan dengan outgroup mereka. Sikap ini justru membuat mereka lemah dan bahkan berpotensi punah. Bahkan secara medis, kata Strauss, perkawinan internal suku justru memperlemah genetik dan kreatifitas otak manusia. Teori Mendel memperkuat pendapat Strauss ini. Pendapat Strauss ini, sebagaimana halnya Popper di atas, setidaknya mampu membantah secara akademis pendapat Gobineau yang mengatakan bahwa ras kulit putih (khususnya sub-ras Aria) menjadi unggul karena menjaga ikatan genetik mereka. Segala sesuatu yang tertutup, justru meminimalisir potensi sebuah fenomena, demikian kata pakar perbandingan agama Karen W. Amstrong. Agama Yahudi yang dulu cukup besar, sekarang diambang kepunahan karena agama Yahudi dijadikan sebagai agama etnis dan perkawinan antar etnis dalam agama Yahudi (setidaknya yang terjadi selama ini) adalah tabu. Justifikasi terhadap ras tidak hanya dilakukan oleh kalangan ilmuan atau cendekiawan. Sejarah juga telah memperlihatkan bagaimana agama bisa digunakan untuk menjaga kemurnian dan keunggulan suatu ras. Contoh terbaik seperti sistem kasta yang terdapat dalam agama Hindu dan tafsiran terhadap ajaran-ajaran normatif yang mengatakan bahwa perkawinan internal sebagai perkawinan paling mulia dalam agama Yahudi. Sejarah juga mengajarkan bagaimana tradisi politik Yunani menempatkan penduduk asli sebagai penduduk paling utama, dan harus pula kawin dengan penduduk utama bukan dengan penduduk pendatang. Yunani, yang dalam sejarah klasik, dianggap sebagai "pionir" tradisi demokrasi, ketika berhadapan dengan ras, justru tidak mampu bersikap objektif ....... Dalam konteks ini, sejarah peradaban Islam-pun pernah dijangkiti rasis ketika Al-Mawardi dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah-nya mengatakan bahwa Khalifah hanya bisa dijabat oleh orang yang berasal dari ras pilihan, yaitu suku Qureisy.

























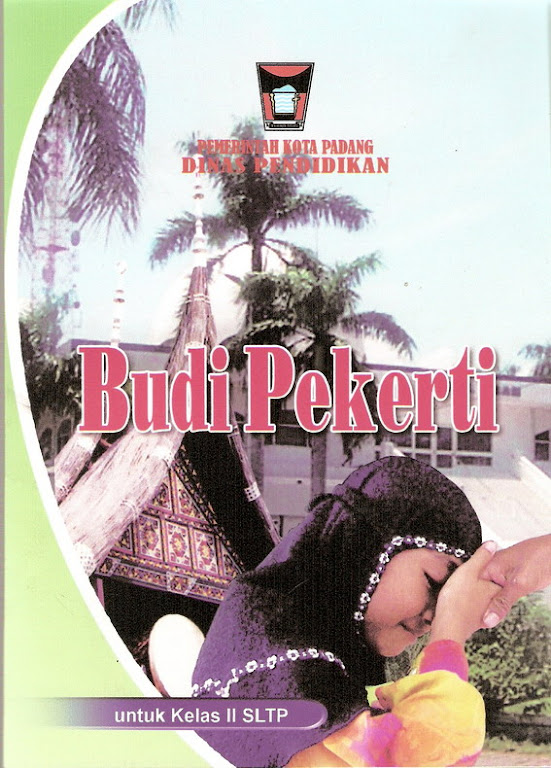





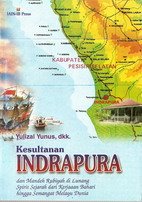




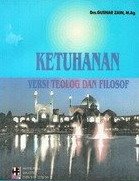
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar