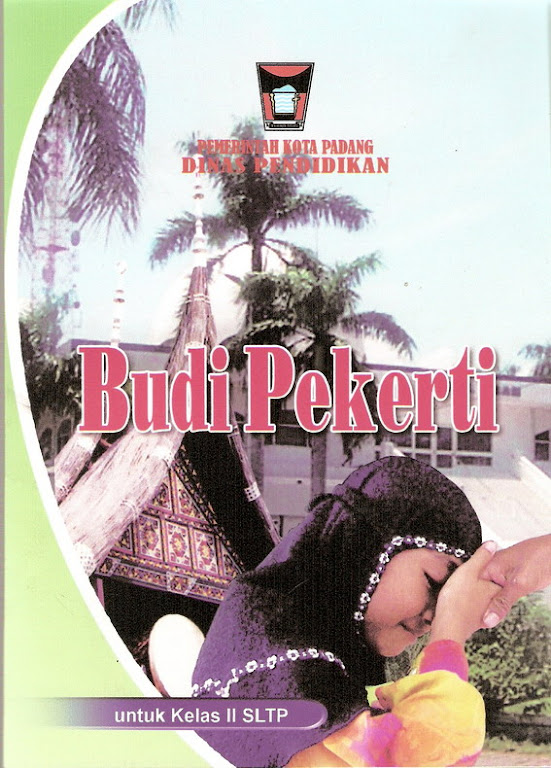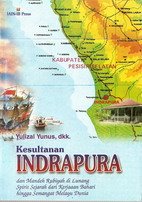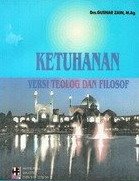Oleh : H. Khilal Syauqi, Lc (Dosen Jur. SKI)

Masa pemerintahan Dinasti Mamluk yang cukup lama, yakni sekitar 267 tahun (648-922H/ 1250-1517M), telah menunjukkan dinamika politik yang sangat fluktuatif. Ada kalanya pemerintahan Dinasti Mamluk, baik ketika dipegang oleh Mamluk Bahriyah maupun tokoh Mamluk Burjiyah, mengalami kemajuan di bidang politik dan pemerintahan dan adakala sebaliknya. Pada Bab ini hanya akan dikemukakan kemajuan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Dinasti Mamluk dalam bidang politik, termasuk pemerintahan. Walaupun pada hakekatnya, kemajuan dalam bidang politik dan pemerintahan tersebut tidak bersifat permanen dan tetap.
Oleh sebab yang dikemukakan di sini hanyalah kemajuan-kemajuan dalam bidang politik dan pemerintahan saja, dan ini bukan berarti menafikan kelemahan dan kemunduran yang pernah dialami oleh pemerintahan Dinasti Mamluk. Di antara para sultan di atas yang terkenal telah membawa kemajuan dan kejayaan adalah Sultan Baybars, Sultan Qalawun, dan Sultan Nashir Muhammad bin Qalawun. Sultan Baybars dianggap sebagai pembangun pertama dinasti Mamluk dan Sultan Qalawun dianggap sebagai pembangun keduanya, sedangkan masa Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun dianggap sebagai puncak kejayaan dinasti ini. Pada masa ini Negara manjadi kokoh dan kuat, sistem pemerintahan serta administrasinya terus berkembang begitu juga dalam bidang seni. Ahli sejarah mengatakan bahwa Kota Kairo pada masa Al-Nasir seakan-akan sebuah imperium besar yang bersatu.
Ada beberapa kemajuan dalam politik yang dicapai oleh pemerintahan Dinasti Mamluk di Mesir, di antaranya adalah sebagai berikut : Seperti yang telah dikemukakan sebelum ini bahwa di masa pemerintahan Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub melakukan pembelian besar-besaran terhadap budak-budak yang berasal dari daerah pegunungan Kaukakus Asia Tengah. Kemudian budak-budak tersebut ditempatkan di Pulau Raudhah yang terletak di Sungai Nil, sehingga mereka disebut dengan Mamluk Bahri. Setelah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan para Mamluk Bahri ini dipercayakan menjabat beberapa jabatan penting dan strategis dalam pemerintahan Bani Ayyub. Di samping itu, para Mamluk Bahri di masa pemerintahan Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub mendapat penghasilan yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup mereka.
Sebaliknya, Pangeran Tauran Syah yang dipersiapkan sebagai pengganti Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub, menurut pandangan para tokoh Mamluk Bahri tidak akan melanjutkan kebijakan ayahnya, apabila ia kelak menjadi sultan. Bahkan, ada indikasi Pangeran Tauran Syah lebih berpihak kepada para militer Bani Ayyub yang berasal dari keturunan suku Kurdi. Oleh sebab itulah, para tokoh Mamluk Bahri menyusun siasat dan strategi rahasia untuk menggagalkan Pangeran Tauran Syah menjadi sultan. Siasat tersebut dilakukan ketika Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub meninggal dunia pada 1249M dan ketika itu Pangeran Tauran Syah sedang berada di luar kota Kairo untuk menghadapi pasukan Salib yang masuk ke Mesir datang dari Eropa. Kematian Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub dirahasiakan kepada Pengeran Tauran Syah. Bahkan, diusahakan Pangeran Tauran Syah dapat dibunuh sebelum ia mengetahui kematian ayahnya, dan usaha itu berhasil. Sehingga dengan demikian, sampai dengan akhir hayatnya, Pangeran Tauran Syah tidak tahu bahwa ayahnya Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub telah meninggal dunia.
Agar jangan terkesan adanya upaya kudeta atau pengambilalihan kekuasaan oleh tokoh-tokoh Mamluk Bahri dari keturunan Bani Ayyub di Mesir, maka diangkatlah Sajarat al-Dur menggantikan kedudukan suaminya Sultan Malik al-Shaleh. Walaupun masih ada keturunan Sultan Malik al-Shaleh yang bisa diangkat menjadi sultan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan Syajarat al-Dur sebagai sultanah di Mesir, dimintalah persetujuan atau dukungan dari khalifah al-Musta’shim (640-656H/1242-1258M) di Bagdad, khalifah Bani Abbas yang memerintah waktu itu. Tetapi, ternyata permintaan tersebut ditolak dengan alasan karena Syajarat al-Dur seorang perempuan. Pada waktu itu para ulama dan khalifah masih menganut pandangan bahwa perempuan dilarang memegang jabatan publik, perempuan hanya diperbolehkan memegang jabatan non publik yaitu ibu rumah tangga.
Setelah gagal mendapat pengakuan dari khalifah al-Musta’shim terhadap kedudukan Syajarat al-Dur menjadi sultanah, selanjutnya tokoh Mamluk Bahri sepakat untuk mengusulkan seorang panglima militer dari kalangan Mamluk Bahri yang terkenal cerdas, cakap, tangkas, dan disenangi, yaitu Izzuddin Aibak. Ternyata Khalifah al-Musta’shim mengakui dan mendukung Izzuddin Aibak menjadi sultan, dan dengan demikian resmilah berdiri Dinasti Mamluk di Mesir melalui suatu upaya politik yang cerdas dari tokoh-tokoh Mamluk Bahri, tanpa menimbulkan korban, kecuali Pangeran Tauran Syah.
Keberhasilan dinasti Mamluk yang pertama sekali terlihat dalam sejarah adalah keberhasilan tokoh-tokoh Mamluk mengambil alih kekuasaan pemerintahan Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub dengan cara menyingkirkan Pangeran Tauran Syah, yang sudah ditetapkan sebagai putra mahkota atau pengganti bapaknya Sultan Malik al-Shaleh Najumuddin Ayyub. Keputusan beberapa tokoh senior Mamluk untuk mengambil alih kekuasaan dari keturunan Dinasti Ayyub merupakan keputusan yang sangat luar biasa sekaligus gambaran kearifan mereka tentang segala hal yang berkaitan dalam bidang pemerintahan, menjadi luar biasa karena latar belakang mereka sebagai orang asing di negeri itu. Setelah Sultan Malik al-Shaleh Najmuddin Ayyub meninggal dunia, tokoh-tokoh militer Mamluk, dalam hal ini Mamluk Bahriyah tidak langsung mengambil alih kekuasaan, tetapi mereka bersepakat untuk menyerahkan jabatan sultan itu kepada Syajarat al-Dur, janda Sultan Malik al-Shaleh. Tetapi karena sultanah Syajarat al-Dur tidak mendapat legitimasi (pengakuan) dari kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad karena ia perempuan, maka terpaksa tokoh-tokoh Mamluk mengusulkan seorang sultan laki-laki yaitu Izzuddin Aibak. Awalnya penobatan Aibak sebagai sultan sekedar mendapatkan legitimasi khalifah saja dan sultanah Syajarat al-Dur tetap sebagai penentu segala kebijakan dalam pemeritahan, namun dalam kenyataannya Izzuddin Aibak dapat memanfaatkan jabatan sultan tersebut dan betul-betul memonopoli pemerintahan tanpa mengikutsertakan Syajarat al-Dur yang telah dinikahinya. Dengan sikap monopoli Izzuddin Aibak dalam menjalankan roda pemerintahan di Mesir, maka berakhirlah pemerintahan Ayyubiyah di Mesir untuk seterusnya dilanjutkan oleh para Mamluk.
Sebelum Dinasti Mamluk berdiri di Mesir, sistim pemilihan dan pengangkatan khalifah atau sultan, ada dua cara. Pertama, dengan cara musyawarah dan memilih di antara calon yang terbaik. Cara seperti ini telah berlaku sejak pemilihan dan pengangkatan Khulafa al-Rasyidin, yaitu cara pemilihan dan pengangkatan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat misalnya, telah menjadi keyakinan mayoritas umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan siapa yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala Negara di Madinah. Akibatnya, golongan Anshar terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah dari kalangan mereka sendiri, maka berkumpullah para tokoh golongan Anshar di Tsaqifah Bani Sa’idah, yang saat itu jenazah Nabi Muhammad SAW sedang terbaring dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Muhajirin.
Agaknya, inisiatif golongan Anshar untuk memilih pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah adalah wajar, karena mereka adalah penduduk asli Madinah. Mereka telah sepakat memilih Sa’ad bin Ubadah, tetapi sebelum Sa’ad bin Ubadah dibai’ah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu ‘Ubadah bin Jarrah, (tiga orang tokoh Muhajirin) datang dan hadir di pertemuan Tsaqifah Bani Sa’idah tersebut dan terjadilah dialog di antara mereka dengan tokoh-tokoh Anshar yang telah menetapkan Sa’ad bin Ubadah tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Muhajirin. Masing-masing kelompok mengklaim merekalah yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah. Dengan beberapa alasan, akhirnya dalam suasana dialog yang sangat hangat tersebut pilihan jatuh kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar dibai’at menjadi khalifah, yang secara geneologi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, walaupun secara kekerabatan Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad SAW.
Demikian pula selanjutnya, Umar bin Khatab dipilih menjadi Khalifah melalui musyawarah Khalifah Abu Bakar dengan para tokoh sahabat, baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar. Seperti diketahui, Umar bin Khattab bukanlah keturunan Abu Bakar. Berikutnya hal yang sama juga terjadi pada pemilihan dan pengangkatan Khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Kedua, pengangkatan khalifah dengan cara penunjukan oleh khalifah sebelumnya terhadap anggota keturunannya (anak, saudara, keponakan, atau paman). Cara seperti ini mulai berlaku dalam pemerintahan Islam sejak Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan menunjuk dan mengangkat anaknya Yazid menjadi Putra Mahkota atau al-Waliy al-‘Ahd. Walaupun Muawiyah bin Abu Sofyan mendapat tantangan dari beberapa putra sahabat, seperti Husen bin Ali, Muhammad bin Abu Bakar, Abdullah bin Zubir, dan Abdullah bin Umar, ia tetap melaksanakan keinginannya tersebut.
Menurut pendapat penulis, ada beberapa alasan mengapa Muawiyah bin Abu Sofyan mengangkat anaknya Yazid menjadi Putra Mahkota, di antaranya adalah : a) Muawiyah khawatir akan muncul perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam, apabila urusan tersebut diserahkan kepada mekanisme musyawarah, b) Muawiyah yang sejak masa mudanya tinggal di Syiria sangat terpengaruh dan tertarik dengan sistim yang berlaku pada raja-raja Byzantium di Konstantinopel. Di sana cara penggantian jabatan raja dilakukan melalui pengangkatan Putra Mahkota yang dipilih dari keturunan raja yang sedang memerintah. Di samping itu, cara seperti ini memang telah menjadi kebiasaan raja-raja di dunia waktu itu, seperti di Cina, India, Indonesia, dan lain-lainnya. Ternyata kemudian hari cara seperti yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah berikutnya. Begitu juga oleh khalifah-khalifah Bani Abbas, Bani Ayyub, dan lain-lainnya. Kecuali itu sultan-sultan Bani Mamluk tidak sepenuhnya melanjutkan cara pemilihan dan pengangkatan sultan dari keturunan. Sultan-sultan Dinasti Mamluk menerapkan pemerintahan Oligarki militer, walaupun tidak sepenuhnya diterapkan oleh masing-masing Sultan, setidaknya Dinasti Mamluk telah memberikan satu pembelajaran politik baru dalam sejarah peradaban Islam.
Bentuk pemerintahan oligarki militer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan susuai kepemimpinan yang dipilih di antara para Mamluk yang paling kuat dan berpengaruh dan bukan melalui garis keturunan. Sistim pemerintahan oligarki militer ini merupakan kreatifitas tokoh-tokoh militer Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Bila dibandingkan dengan sistim pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, yaitu Sistim Monarki dan Sistim Aristokrasi atau pemerintahan para bangsawan, maka sistim pemerintahan Oligarki Militer dapat dikatakan lebih demokratis. Sistim Oligarki Militer lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan, sultan yang lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang Mamluk yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan lain dari sistim oligarki militer ini adalah tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan, melainkan melihat kepada keahlian dan kepiawaian seorang Mamluk tersebut. Bahkan demi menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, untuk menghindari pertikaian antara para Mamluk yang masing-masing bernama Syaikh al-Mahmudi dan Nuruz al-Hafizi, di mana kedua amir Mamluk ini saling memperebutkan tampuk pemerintahan, dinobatkanlah oleh para pendukung keduanya Khalifah Abbasiyah al-Musta’in Billah sebagai Sultan untuk sementara waktu agar tidak terjadi pertikaian yang berkelanjutan. Di antara 22 Khalifah Abbasiyah yang telah di bai’at oleh rakyat Mesir, maka Khalifah al-Musta’in Billah inilah satu-satunya khalifah Abbasiyah yang pernah dinobatkan menjadi menjadi Sultan menggantikan Sultan an-Nasir Faraj ibn Barquq tahun 815 H/1412 M.
Dinasti Mamluk di Mesir menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyyah yang sudah hancur tahun 656 H/ 1258 M di tangan Bangsa Tartar oleh Holago dan bala tentaranya. Baybars telah membuat suatu peristiwa besar selama pemerintahannya, yaitu melakukan bai’at terhadap al-Manshur (1226-1242) sebagai khalifah. Usaha menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir ini merupakan sebuah kebijakan besar sepanjang sejarah umat Islam, walaupun penobatan itu hanya bersifat politis. Karena sosok khalifah merupakan simbol persatuan. Dengan kecerdasan politiknya, Baybars juga meminta legalitas dari khalifah atas kekuasaannya. Sehingga dengan demikian ia bisa menduduki kursi kesultanan dengan cara terhormat.
Setelah dua tahun kehancuran Bagdad Sultan al-Zahir Baybars segera merencanakan untuk mengembalikan khilafah Abbasiyyah. Pada tahun 659 H/1261 M, Baybars mengundang salah seorang keturunan Abbasiyyah yang berhasil lolos dari serangan bangsa Mongol, kemudian Baybars dengan para pembesarnya seperti para Qadhi, pemuka agama serta para Amir bermusyawarah untuk memastikan keabsahan nasab keturunan al-Mustanshir, sebagai keturunan Abbasiyyah. Ketika sudah dipastikan keabsahannya, maka segeralah mereka membai’at keturunan Abbasiyyah itu untuk dijadikan khalifah resmi bagi umat Islam dengan gelar al-Mustanshir Billah. Pemikiran seperti ini bukanlah hal yang sederhana bagi seorang sultan berkuasa, karena tidak sedikit di antara para penguasa justru menganggap apa yang dilakukan Baybars akan membahayakan posisi politiknya sebagai sultan di Mesir ketika itu. Namun pada hakikatnya kebijakan ini sangat tepat dan memberikan pembelajaran politik bagi generasi selanjutnya bahwa kepentingan umat lebih didahulukan dari pada pribadi.
Lebih dari hanya sekedar menghidupkan kekhalifahan, Sultan Baybars juga menjatahkan khalifah seorang atabak al-‘askar dengan kekuatan 1000 prajurit, al-Syarabbi dengan 500 prajurit, al-Khazindar 200 prajurit, ustaz al-dar (ustadar) dengan 500 prajurit, al-Dawadar 500 orang, beberapa petugas di al-Tablakhanah, dan khalifah dibelikan mamluk (hamba) sebanyak 100 orang untuk difungsikan sebagai jamadar dan silahdar. Setiap orang diberi tiga kuda dan tiga onta. Sultan juga menetapkan administrative untuk khalifah, seperti kuttab al-insya’ (para penulis atau pengarang), sekretaris pribadi khalifah, para ulama, pembantu-pembantu, orang-orang bijak dan tabib-tabib, serta tempat tinggal yang disiagakan dengan kuda, baik yang untuk ditunggangi maupun untuk mengangkut perbekalan dan senjata. Dalam pemahaman ulama Sunni, pada masa Dinasti Mamluk di Mesir masih sangat kuat bahwa menegakkan khilafah wajib hukumnya. Apabila umat Islam tidak menunaikan kewajiban ini, maka berdosalah seluruhnya. Artinya, menegakkan khilafah adalah fardhu kifayah. Pandangan yang mengatakan bahwa wajib hukumnya menegakkan khilafah dikemukakan oleh pada umumnya ulama Suni, di antaranya al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah. Ia mengatakan bahwa menegakkan khilafah adalah fardu kifayah, sebagaimana hukumnya menuntut ilmu dan penyelenggaraan jenazah.
Sejak khalifah al-Musta’shim (1246-1258M), khalifah Bani Abbasiyyah yang terakhir di Kota Bagdad dibunuh oleh pasukan Holago Khan pada 1258 M, dunia Islam telah kehilangan khalifah untuk beberapa tahun lamanya. Oleh sebab itu, timbul kegelisahan di kalangan para ulama dan sultan-sultan yang memerintah, karena khalifah tidak ada. Sesuai dengan ayat dan hadits di atas menurut pendapat mereka, berdosalah seluruh umat Islam karena tidak memiliki khalifah. Akhirnya dengan ditegakkannya atau dihidupkannya kembali khilafah oleh Sultan Baybars, maka seluruh umat Islam di dunia terlepas dari dosa. Maka wajarlah apabila dikatakan usaha Sultan Baybars menegakkan khilafah kembali adalah suatu usaha besar dan disambut baik oleh seluruh umat Islam waktu itu, terutama umat Islam yang berpaham Suni.
Berkaitan dengan hal menghidupkan kekhalifahan ini, penulis berpendapat bahwa setidaknya ada beberapa makna di balik itu, pertama, dihidupkannya lagi kekhalifahan Abbasiyah di Mesir atas prakarsa Sultan Mamluk, mengandung arti bahwa Sultan Mamluk sangat paham dan mengerti sekali tentang kondisi politik saat itu, karena rakyat Mesir sebelumnya pada masa pemerintahan Dinasti Ayyub telah menganut paham Sunni. Dengan dihidupkannya kembali sistem khilafah, Sultan Mamluk dapat mencuri perhatian rakyat Mesir ketika itu. Kedua, kebijakan menghidupkan kekhalifahan Abbasiyah di Mesir membuktikan bahwa para Sultan Mamluk tidak rakus akan kekuasaan. Karena jika mereka rakus akan kekuasaan tentu mereka akan mengambil kesempatan tersebut untuk menguasai secara utuh wilayah-wilayah Islam. Makna yang ketiga adalah sebagai bukti bahwa para Mamluk adalah orang-orang penganut mazhab Sunni, mewarisi dari tuan-tuan mereka dahulu yaitu Dinasti Ayyubiyah.
Bahkan sampai dengan zaman modern sekarang sebahagian besar ulama Suni masih berpandangan seperti al-Mawardi, sebagaimana disebutkan di atas. Muhammad Rasyid Rida dalam bukunya al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzma juga mengatakan bahwa menegakkan khilafah wajib hukumnya. Demikian juga pandangan Abdul A’la al-Maududi dalam bukunya al-Hukumah al-Islamiyah. Hizbut Tahrir Indonesia termasuk kelompok umat Islam yang paling keras mempelopori agar khilafah Islamiyah bisa ditegakkan kembali, agar umat Islam terlepas dari dosa dan cengkraman sistim politik sekuler yang didukung oleh Barat. Sejak tanggal 3 Maret 1924 M umat Islam tidak lagi memiliki khilafah, karena lembaga ini telah dihapus oleh Mustafa Kemal Attaturk. Khalifah atau Sultan Abdul Majid sultan terakhir dari Turki Usmani diturunkan dari jabatanya dan diusir ke luar Turki. Selanjutnya, pada waktu itu masih kuat paham bahwa salah satu syarat khalifah adalah dari suku Quraisy. Al-Mawardi, seperti disebutkan di atas menyebutkan ada tujuh syarat khalifah, salah satu di antaranya adalah syarat keturunan suku Quraisy, karena adanya Nash dan Ijma’ tentang masalah ini.
Oleh sebab itu, sultan Baybars walaupun secara politik kekuasaan dan pemerintahannya sangat kuat, tetapi untuk menjadi khalifah ia tidak bisa, karena bukan keturunan suku Quraisy. Sultan Baybars seperti yang telah dikemukakan di atas adalah keturunan dari suku yang ada di daerah Kaukasus di Asia Tengah. Jika ingin menjadi khalifah, pasti ditolak oleh para ulama, terutama ulama yang berpandangan bahwa khalifah wajib dari keturunan suku Quraisy. Menurut Amany Lubis dalam bukunya Sistem Pemerintahan Oligarki Dalam Sejarah Islam, Khilafah Abbasiyyah yang dibai’at oleh rakyat Mesir sebanyak 22 khalifah. Beberapa penulis sejarah berbeda tentang jumlah Khalifah Abbasiyah yang pernah dibai’at selama pemerintahan Dinasti Mamluk di Mesir. Seperti terdapat dalam buku Tarikh al-Khulafa’ yang ditulis oleh Jalaluddin as-Sayuthi, dalam buku tersebut hanya tertulis 15 orang nama khalifah. Sedangkan menurut Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas al-Tarikh al-Araby al-Islamy, Khilafah Abbasiyyah yang berkedudukan di Mesir tercatat 17 orang. Menurut penulis perbedaan ini terjadi karena para khalifah yang pernah dibai’at tersebut adakalanya menjabat sebagai khalifah hanya beberapa saat saja setelah dibai’at yang kemudian diturunkan kembali, meninggal, atau digantikan oleh yang lain. Selanjutnya perbedaan ini terjadi karena ada di antara para khalifah itu yang menjabat lebih dari satu kali. Sehingga dalam permasalahan ini para penulis sejarah itu ada yang mencantumkan nama khalifah tersebut dan ada juga yang tidak.
Kekhalifahan Abbasiyah yang berkedudukan di Mesir berakhir setelah Sultan Salim I dari kerajaan Turki Usmani mengalahkan dan menguasai Mesir pada tahun 1517 M serta membawa Khalifah Abbasiyah yang terkahir, yaitu Al-Mutawakkil ‘Alallah ke Istambul, pusat pemerintahan kerajaan Turki Usmani dan menurunkannya dari jabatannya. Jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan Dinasti Mamluk di Mesir hampir sama dengan struktur pemerintahan dinasti-dinasti lainnya. Di antara jabatan penting dalam struktur pemerintahan Dinasti Mamluk adalah : Khalifah ; sebagaimana telah disebutkan di atas pada tahun 1260 M Sultan Baybars telah menghidupkan kembali khilafah Bani Abbas yang telah vakum sekitar dua tahun. Pada waktu itu khalifah tetap dipandang sebagai pimpinan tertinggi secara spiritual (spiritual power). Pada masa pemerintahan Dinasti mamluk di Mesir khalifah yang telah dinobatkan berfungsi sebagai pihak yang mengukuhkan kedaulatan sultan dan jabatan-jabatan para kadi serta pejabat negara lainnya. Ia ditempatkan di Benteng al-Kabsy yang menghadap ke sungai Nil dan ia diberi gaji bulanan. Berita penobatannya disebarkan ke semua wilayah, demikian pula namanya ditulis pada mata uang dinar dan dirham. Di dalam khutbah jumat nama khalifah disebut lebih dahulu baru kemudian nama sultan. Sebagai kewajibannya terhadap sultan, khalifah diharuskan menghadap ke istana setiap awal bulan arab guna mengucapkan selamat. Melihat peran yang dimainkan para khalifah di Kairo ini, maka dapat dikatakan bahwa khalifah telah menjadi sumber legitimasi bagi keberadaan sultan Mamluk.
Sultan ; kata sultan berasal dari sultan- yusaltinu-sultanan yang artinya kekuasaan (reign, mandate), menjadi penguasa, dan pemimipin (ruler). Kata ini mempunyai hubungan erat dengan sultah (kata kerjanya sallata) yang artinya kekuasaan (power) dan pemerintahan (authority). Ada kata lain yang berkaitan, yaitu as-syiyadah yang maknanya kekuasaan (rule, supremacy) dan kadaulatan (sovereignty). Dari kata-kata yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin atau sultan itu adalah orang yang berkuasa dan berdaulat atas rakyatnya. Qadi al-Qudah (Hakim Agung) ; Qadi al-qudah artinya ketua para kadi atau dapat disebut sebagai hakim agung; ia menjadi salah satu anggota permusyawaratan atau ahl al-masyurah. Jabatan ini di masa pemerintahan Dinasti Mamluk memainkan peranan penting karena para kadi menjalankan tugasnya di lingkungan Istana dan menjadi pejabat yang menjaga kemaslahatan rakyat secara umum. Di antara tugas pentingnya adalah menangani perkara-perkara di peradilan umum dan diwan al-mazalim.
Na’ib as-Saltanah (Wakil Sultan) ; na’ib berasal dari naba- yanubu, yang berarti menggantikan dan pelakunya na’ib sama dengan pengganti. Di dalam literature sejarah ditemukan bahwa na’ib adalah yang mewakili sultan atau yang menggantikannya. Wakil sultan yang dinamakan na’I as-saltanah atau wakil kesultanan adalah salah satu jabatan tinggi administratif di dalam pemerintahan Dinasti Mamluk. Sebahagian sejarawan menganggapnya sebagai jabatan tertinggi secara hierarkis setelah sultan. Wakil sultan atau disebut juga as-sultan as-sani (ad interim) melaksanakan sebagian besar tugas sultan. Wazir (Perdana Menteri) ; wazir berasal dari kata muazarah yang artinya pertolongan atau dari kata wizr yang berarti beban. Penamaan tersebut sesuai dengan tugas wazir yang memang membantu sultan di dalam pelaksanaan pemerintahan atau yang memikul sebagian beban pemerintahan dari sultan. Di dalam sejarah pemikiran politik Islam, istilah wazir atau perdana menteri dapat digolongkan menjadi dua macam. Pertama wazir tafwid adalah wazir yang diserahi oleh sultan untuk menangani urusan pemerintahan dan ia berhak berinisiatif dalam membuat kebijaksanaan serta menandatangani peraturan-peraturan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan sultan. Kedua wazir tanfiz artinya wazir yang melaksanakan perintah sultan dan mempunyai wewenang terbatas; ia tidak melakukan sesuatu kecuali atas sepengetahuan sultan. Atabak (Panglima Tertinggi) ; Kata atabak berasal dari bahasa Turki dan terdiri atas dua kata : ata (huruf kedua adalah ta) berarti bapak dan bak artinya amir atau pangeran. Makna dari atabak adalah bapak para amir. Bagi para putra sultan atau amir senior Mamluk atabak ditunjuk sebagai pengasuh para amir muda, dan ketika mereka menginjak dewasa, atabak hanya merupakan jabatan kehormatan yang tidak memiliki tugas apapun di dalam pemerintahan. Dengan berkembangnya system pemerintahan Dinasti Mamluk, atabak memainkan peran yang penting, selain menjadi pengasuh dan pendamping, ia juga menjadi penasehat sultan.
Pada masa kekuasaan Baybars perubahan demi perubahan mulai dilakukannya dalam segala bidang, baik dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam ketentaraan. Ia membangun pemerintahan dengan baik sehingga kesulthanan ini menjadi kuat. Barisan elite militernya didudukkan sebagai elite politis. Jabatan-jabatan penting dipegang oleh anggota militer yang berprestasi. Untuk mendapatkan simpatik dari rakyat Mesir, sebagiamana Dinasti Ayubiyah, Baybars menghidupkan kembali Mazhab Suni. Baybars juga merupakan sultan Mesir pertama mengangkat empat orang hakim yang mewakili empat mazhab dan mengatur keberangkatan haji secara sistematis dan permanen. Ia juga dikenal sebagai sultan yang saleh dalam soal agama dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Beberapa undang-undang untuk menjunjung tinggi akhlak mulia juga dikeluarkan Baybars, seperti perintah larangan jual beli khamar, menutup tempat-tempat maksiat dan banyak memenjarakan orang-orang yang berbuat kemaksiatan.
Di bidang diplomatik Baybars menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bersahabat yang tidak membahayakan kekuasaanya. Ia memperbaharui hubungan Mesir dengan Constantinopel serta membuka hubungan Mesir dan Sisilia. Selain itu, ia juga menjalin ikatan perdamaian dengan Barke (Baraka), keponakan Hulago Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di Golden Horde atau Kipchak Khanate (wilayah di bagian barat Kerajaan Mongol). Di tengah-tengah masyarakat Islam pada periode pertengahan ini diliputi oleh kesengsaraan akibat tidak adanya kekuatan politik yang dapat menjamin kemakmuran rakyat, di Mesir masyarakatnya dapat menikmati kemakmuran tersebut di bawah kepemimpinan sultan Mamluk. Jika Sultan Baybars telah berhasil menancapkan pundi-pundi pemerintahan dengan kokoh, maka pada masa Sultan al-Nasir Muhammad bin Qalawun dapat dianggap sebagai masa-masa menikmati kemakmuran dalam berbagai bidang. Sehingga sultan al-Nasir Muhammad menjadi sultan yang sangat disenangi oleh masyarakatnya. Sultan al-Nasir Muhammad ini memegang tampuk pemerintahan tiga kali, dengan mengalami dua kali turun tahta. Ia digulingkan pertama kali karena usianya yang masih muda –sembilan tahun- oleh panglima angkatan bersenjatanya (atabak) yang bernama al-Adil Katbuga (694-696 H/1295-1297 M) dan kemudian disusul oleh pemerintahan Sultan al-Mansur Lajin (696-698 H/1297-1299 M). Oleh karena al-Mansur Lajin tidak memperoleh popularitas di antara para Mamluk dan Rakyat, lalu al-Nasir Muhammad ibn Qalawun dinobatkan kembali. Sultan al-Nasir Muhammad kembali turun tahta ketika dilihatnya bahwa tokoh yang menjabat sebagai wakil sultan – Bibars al-Jasynakir (708-709 H/1309-1310 M) berambisi untuk menjadi sultan, akan tetapi atas dukungan mamluk-mamluk di Syam dan masyarakat, akhirnya al-Nasir Muhammad menjadi sultan hingga akhir hayatnya setelah berkuasa selama 31 tahun berturut-turut. Sejarawan Ibn Tagri Bardi menyatakan bahwa ia adalah sultan yang terhebat. Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun telah terbukti menjadi sultan yang disenangi oleh berbagai lapisan masyarakat baik dalam maupun di luar kesultanannya. Dialah yang telah melindungi Mesir dari jamahan bangsa Mongol, sehingga Mesir selamat dari kehancuran, seperti apa yang telah terjadi pada wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh tentara Mongol. Sejarah telah menjadikannya contoh dalam berdiplomasi dan pengelolaan sebuah kerajaan Islam.
Kebijakan-kebijakan politik al-Nasir Muhammad yang secara nyata memihak masyarakat di antaranya adalah bahwa dia menekan harga barang-barang sehingga tidak menyulitkan masyarakat miskin, banyak menghapus pajak yang sebelumnya menjadi kewajiban sebagian besar penduduk, kemudian menggantinya dengan memungut pajak dari orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Barangkali dari beberapa kebijakan politiknya di atas ia menjadi sangat disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Kota Kairo pada masa al-Nasir ini menjadi Ibukota bagi sebuah dinasti yang meliputi Mesir, Syam, Hijaz, dan Yaman. Atas keberhasilan Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun inilah, tahta tetap berada di tangan putra-putra dan cucu-cucunya. Terlihat bahwa sistem suksesi di masa Mamluk Bahri umumnya adalah dengan cara turun temurun dari satu jalur silsilah keluarga. Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa periode ini disebut era Dinasti Qalawun. Namun demikian, sistem suksesi lain, yakni oligarki, tetap menjadi harapan para amir Mamluk yang berambisi menjadi sultan.
Selengkapnya...
 Perdebatan tentang istilah 'kontemporer' dalam wacana seni rupa Islam, pernah mengemuka dikalangan perupa Indonesia beberaopa waktu lalu. Harian umum Republika, misalnya edisi Minggu, 11 Mei 1997, secara khusus, menurunkan berita seputar persoalan seni rupa Islam kontemporer. Ada kalangan yang setuju dengan istilah tersebut dan ada pula yang tidak. Yang tidak setuju dengan konsep ini manilai bahwa seni Islam saja belum memiliki konsep yang tegas.
Perdebatan tentang istilah 'kontemporer' dalam wacana seni rupa Islam, pernah mengemuka dikalangan perupa Indonesia beberaopa waktu lalu. Harian umum Republika, misalnya edisi Minggu, 11 Mei 1997, secara khusus, menurunkan berita seputar persoalan seni rupa Islam kontemporer. Ada kalangan yang setuju dengan istilah tersebut dan ada pula yang tidak. Yang tidak setuju dengan konsep ini manilai bahwa seni Islam saja belum memiliki konsep yang tegas.