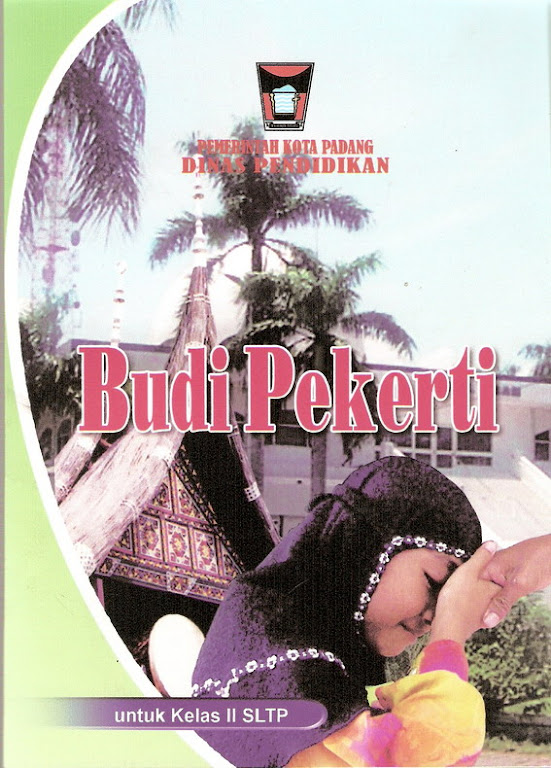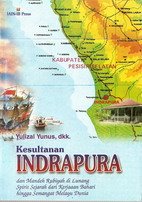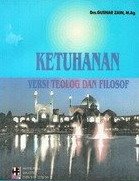Oleh : Drs. Yulizal Yunus, M.Si (Dosen Jur. BSA)

Karya Taufiq Ismail genre syair munasibat (occasional poetry), sarat nilai religius. Dalam perspektif religiositas sastra ini menempatkan karyanya pada posisi signifikan dalam khazanah kesusasteraan bagian dari al-fann al-islami (الفن الأسلامي/ seni Islam). Religositas sastranya memamsuki dimensi profetik yang sufistik, mengandung majmu’atun min al-mau’izhah wa l-hikmah wa l-irsyad (sekumpulan nilai pengajaran yang indah, hikmah dan panduan ke arah jalan yang benar).
Abstrak
Keagungan sastra Taufik terletak pada pengisian bahasa naratif dengan pengalaman religius yang cukup kaya melampaui derjat diskriptifnya terhadap fenomena. Nilai Islami pada puisinya tidak terletak pada kata-kata simbol Islam, tetapi keagungannya terletak pada makna ajaran dan keindahan narasi, ada banyak di dalamnya hikmah dan isyarat-isyarat pemahaman ke-Indonesiaan dan ke-Islaman yang benar. Dari perspektif kedalaman Taufik menyelami peristiwa akmbn (aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara) untuk bahasa politik dan diskripsinya dalam narasi diisi makna religiositas sastra yang dalam pada puisinya menempatkan Taufiq pada posisi penyair Islam terbesar di awal abad ke-21 ini.
Pendahuluan
Tak dapat dipungkiri Taufiq Ismail sebagai “seorang penyair” menempati status (kedudukan) terpandang dalam sejarah kesusasteraan Islam Indonesia modern. Karya sastranya diklasifikasi refrensi dan bergegsi ditempatkan pada etalase refrensi khazanah Kesusasteraan Islam tepenting. Di antara alasannya dari perspektif perkembangan kesusasteraan Islam di Indonesia karya sastra Taufiq khusus genre syair munasibat (occasional poetry) menunjukkan ciri spasifik dibanding sastra kitab dan syair yang digubah para ulama tradisional ahli metafisik yang sufistik dan intelektual yang menyair puisi profetik lainnya di abad ini.
Dalam tradisi bersastra khusus genre puisi, nilai Islami yang ditawarkan Taufiq berbasis pengalaman religius yang kaya sejak kecil. Ia tidak serta merta menggunakan bahasa ramziyah (/ رمزيةsymbol) Islam dan tidak pula memasang title dan thema Islami namun sarat dengan makna Islami. Dipastikan Taufiq mempunyai cara berbahasa yang khas. Kalau Dr.Thaha Mahmud Thaha (1966) menyebut sastra agung itu hanya pada bahasa yang sarat makna melampaui derjat yang jauh, maka keagungan sastra Taufik terletak pada cara menggunakan bahasa dalam mendiskripsi, menceritakan fenomena dominan politik dan mengisinya dengan pengalaman religius.
Puisi Taufiq menunjukan corak tersendiri dalam menyikat esensi kehidupan politik. Ia menuangkan shurah (صورة/ imajinasi), athifah (عاطفة /perasaan(, fikrah (فكرة/ide( dan pengalamannya dapat membuai penikmat sastra bahkan membawa lebih jauh masuk ke dalam dirinya seolah telah berada dalam peristiwa politik mulai sejak orde lama, orde baru dan era reformasi. Kalau tidak ada ditemukan berita tentang masa lalu itu, rasanya puisi Taufiq cukup mewakili mewartakan masa lalu yang tak kering dengan esensi politik.
Mengenai bentuk puisi politik Taufik ini juga dicatat Aguk Irawan Mn (Sinar Harapan, 2004), katanya “dalam bersastra, karya Taufik memang nyaris tak pernah kering dan sepi dari muatan politik. Bahkan Taufik sering membenturkan isu budaya, pendidikan, ekonomi dan sosial dengan hiruk-pikuk yang berbau politik. Demikian halnya dengan Asrul Sani, Pramoedya Ananta Toer, B. Soelarto, Muchtar Lubis, Wiratmo Soekito dan penulis-penulis lain, maka Taufik sebagai sastrawan pelopor penandatangan Manikebu ingin juga memperlihatkan bahwa dengan berkesenian serta bersastra ia tetap menekuni politik”. Namun keagungan sastra puisi politik Taufiq itu di sana sini penuh dengan esensi penyadaran kepada nilai-nilai Islami. Dimungkinkan nilai Islami yang dimunculkan Taufiq dalam puisinya dapat sebagai kontrol dalam hiruk pikuk kehidupan yang nyaris dipanglimai oleh politik.
Nilai sastra Islami yang dimaksud mengutip M.Quthub (dalam Yulizal, 1999) adalah kombinasi nilai pengajaran yang indah (mau’izhah/ موعظة), hikmah (حكمة) dan arah yang lurus menuju kebenaran atau irsyadah (ارشادة). Seni sastra Islam itu seperti menyaratkan 3ka yakni estetika, erotika dan etika. Kalau estetika saja bisa terjebak l’art for l’art atau fann li fann ( فن لفن/ seni untuk seni ), demikian pula kalau hanya estetika dan eritika saja tanpa etika bisa terjerembab kepada fornografi, artinya etika atau akhlak dalam bersastra merupakan kontrol tersosialisasinya mau’izhah, hikmah dan irsyadah dalam puisi politik Taufiq. Pemikiran ini dapat digambarkan sbb.:
Dalam event Taufiq Ismail 55 Tahun dalam Sastra Indonesia, saya seperti teman-teman kritikus sastra lainnya diminta mempresentasikan makalah membahas “Karya-karya Taufiq Ismail dalam Khazanah dan Perkembangan Kesusasteraan Islam di Indonesia” pada seminar di Studio TVRI Sumatera Barat Padang, siaran langsung jam 17.00-18.30 wib, 28 Mei 2008.
Dalam presentasi ini saya membatasi diri, melihat karya sastra Taufiq Ismail genre puisi dan posisinya yang signifikan dalam khazanah kesusasteraan Islam serta perubahannya dalam dimensi perkembangan kesusasteraan Islam di Indonesia bersamaan dengan pilar sejarah bangsa (orde lama, orde baru, dan era reformasi). Melihat posisi syair Taufiq dalam khazanah kesesusastraan Islam dimungkinkan mempersandingkannya dengan puisi yang digubah para ulama dahulu dan intelektual Islam yang menyair di abad-abad modern ini. Melihat bentuk puisi Taufiq dalam perkembanbangan kesusasteraan Islam di Indonesia, dapat dimunculkan dalam bentuk perubahannya dalam lima setengah dasawarsa.
Ulama dan Taufiq Ismail dalam Khazanah Kesusastraan Islam
Menarik memperhatikan proses kreativitas Taufik Ismail kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935 dan selama 55 tahun dalam sastra Indonesia dan sudah cukup banyak mengantongi penghargaan sastra tingkat nasional dan internasional. Ia melahirkan karya sastra yang tak bisa dilewatkan begitu saja oleh analis sastra, mahasiswa sastra Islam dan penikmat sastra lainnya. Justeru karya sastra Taufiq genre puisi peristiwa, posisinya amat signifikan dalam khazanah kesusasteraan Islam. Dari perspektif puisi peristiwa dengan elegi Taufiq kalau tidak melebihi, setara dengan rasa` (رثاء) penyair besar Arab Adonis (lahir 1930) dewasa ini.
Kepenyairan dan syair-syair Taufiq ini selama proses kreativitasnya sejak 55 tahun lalu sampai era reformasi Indonesia ini, dalam perspektif historis sastra di Indonesia mengingatkan kita kepada tradisi kepenyairan tokoh agama menulis syair yang sangat-sangat washfiyah (وصفية - diskriptif) memotret dan menarasikan fenomena dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dahulu seperti ditemukan pada sejarah ulama di daerah kelahiran Taufiq sendiri Minangkabau (Sumatera Barat), ulama banyak menulis sastra kitab termasuk syair bernafaskan Islam. Kelebihan karya sastra mereka -- genre syair (puisi)-- di samping mengajarkan Islam dengan cara bersastra, juga intens menggerakkan sosialisasi nilai sub kultur Minangkabau – adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah— dan sangat profetik. Sampai awal reformasi Taufiq juga menawarkan genre syair yang sarat dengan nilai Islami. Antara ulama dan Taufiq dapat digambarkan sbb.:
Nilai Islam yang ditawarkan Taufiq dalam bentuk sikap tidak menyukai budaya al-khadzb (الكذب /dusta) dan fenomena hilangnya budi pekerti mulia (al-akhlaq al-mahmudah/ الأخلاق المحمودة ) di bawah payung (tema) iklim budaya politik tak menentu di tanah airnya, lihat baitnya dalam “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” (1998) yang mirip syair hija` (هجاء) Arab sbb.:
“…ada pula pembantahan terang-terangan
yang merupakan dusta terang-terangan
di bawah cahaya surya terang-terangan,
dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai
saksi terang-terangan,
Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada,
tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang
menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.
…
Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak…”
Demikian pada kepenyairan Taufiq Ismail tidak dapat diabaikan, seperti karya sastra para ulama itu, deras menghembuskan semangat "profetik", yakni kombinasi nilai dimensi sosial dan dimensi transendental. Namun Taufiq memperlihatkan ciri spasifik dalam kepenyairannya, di antaranya dalam menyair kedalaman makna bahasa sudah menjadi pertimbangan dalam mendiskripsi fenomena. Lihatlah berangkat dari fenomena bangsa ini betapa Taufiq amat dalam memberi penyadaran makna kalimat “ lailahaillallah – لاإله إلاالله” dalam kaitan berbagai musibah meski tidak memakai symbol kata itu dalam syairnya "Ketika Burung Merpati Sore Melayang" (1998) berikut ini:
Ada burung merpati sore melayang
Adakah desingnya kau dengar sekarang
Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan
Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan
Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah
Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku
Tapi apakah sah sudah, ini murkaMu?
Nafas sastra profetik (memakai istilah Kuntowijoyo) seperti ini sebenarnya sudah sejak lama merupakan akar budaya nusantara lalu tenggelam. Sekarang muncul lagi dalam bentuk baru dan menjadi ciri post modern. Dalam corak baru sendiri sastra profetik ini dimunculkan Taufiq Ismail seperti penyair Islam lainnya di Indonesia. Kenapa karya sastara ulama menaruh nilai Islami yang tinggi dan sangat profetik sufistik?. Justeru para penggubahnya ialah para ulama ahli "metafisik" Islam dan mendalami metafisik Islam. Dalam lintasan kepengarangan sastra dan ulama, sejak lama telah melahirkan dan memunculkan tokoh, sebutlah seperti Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, lbnu 'Arabi, Abu 'Athahiyah, Maarri, Ibnu 'Atha, lqbal, juga ulama Indonesia Hamzah Fansuri, Amir Hamzah, Chatib Ali Al-Padani, Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi (Syeikh Bayang), Sulaiman Arrasuli (Inyiak Candung) dll. Mereka ialah ulama sufi yang dekat dengan tradisi bersastra, merupakan sumber ilham bagi ulama lainnya menghubungkan tradisi beragama dengan tradisi bersastra.
Fenomena tadi pun dicatat Abdul Hadi (1985:vi dalam Yulizal, 1999) bahwa ulama dapat menghubungkan tradisi keagamaan dengan tradisi bersastra. Hal itu dimungkinkan karena karya sastra ulama memancarkan kesahduan sufistik bahkan mencerminkan "higher sufistik". Ada kesadaran yang tinggi, sastra itu mempunyai nilai keindahan (جمال /estetik) dan berpotensi sebagai canel (wasilah/ وسيلة) mencapai Tuhan.
Keindahan yang ada pada manusia adalah tiruan dari masternya Tuhan. Mengacu teori mimetic Plato dan Aristoteles, bahwa seni yang kaya dengan keindahan adalah mimesis/ muhakah (محاكاة /mimetik, tiruan) dari kenyataan sehari-hari. Kenyataan dan kehidupan sehari-hari merupakan tiruan pula dari kenyataan tertinggi yang disebut dunia ide dan gagasan, sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Artinya, alam ide yang merupakan kenyataan tertinggi di tangan Tuhan itu adalah master, sedangkan kenyataan sehari-hari adalah gandaanya. Dimisalkan manusia membuat kursi yang merupakan salah satu perwujudan seni rupa wujud pahat, adalah tiruan dari masternya, di mana Allah swt. punya Al-'arsyistawa/ tempat bersemayam-Nya (QS 20:5). Pan¬dangan tentang dunia ide/ gagasan tertinggi yang dianut Aristoteles berbeda dengan Plato. Aristoteles melihat, keindahan dalam karya seni bukan sekedar mimetik (tiruan) seperti yang dianut Plato, tetapi adalah kemampuan pesona yang dapat dikembangkan untuk memperluas cakrawala dan khazanah manusia melebihi kenyataan sehari-hari. Tetapi kedua tokoh ini menempatkan seni di atas dari fenomena kenyataan sehari-hari dan keindahan merupakan esensi seni termasuk sastra.
Keindahan dalam karya sastra menurut Plato, mengacu kepada dunia ide. Dunia ide mengacu sifat Ilahi (Tuhan). Berarti keindahan mengacu kepada keindahan Tuhan. Pandangan ini sejalan dengan Muhammad Quthub (1973:7 dalam Yulizal, 1999), menyebut keindahan itu adalah "hakikat al-kaun" (حقيقة الكون/kenyataan/ realita alam) dan puncak keindahan itu adalah al-haq (الحق /kebenaran). Berarti keindahan adalah ide, lahir dari akal yang jernih. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat diterima akal dan logis secara mutlak dimiliki oleh Tuhan. Karena itu pula keindahan dan kebenaran merupakan unsur penting dalam seni, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan unsurnya yang lain. Keindahan dimaksud adalah indah yang menaruh kebenaran, tetapi sesuatu yang indah tidak menaruh nilai kebenaran tidaklah dapat digolongkan dengan keindahan dari perspektif seni Islam. Karena itu pula Bahauddin Al- Amiry (1982) beralasan mengatakan, bahwa al-haq (kebenaran) merupakan unsur penting dalam karya seni yang dicontohkan dalam karya seni jenis sastra genre syair.
Kalau ada budayawan atau da’i yang menolak hubungan seni dengan Islam dan Tuhan, tentulah dapat dipahami, bahwa prinsip mereka berangkat dari sisi pandangan relatifitas dan mungkin beraliran l’art for l’art. Mungkin mereka berangapan, keindahan secara mutlak berada di tangan Tuhan, sedang¬kan keindahan yang ada pada alam termasuk manusia, keindahan itu relatif bagian terkecil (dari kemahaindahan Tuhan) dan boleh lagi dintervensi agama dan etika. Islam adalah agama besar yang diredhai. Mereka menganggap Islam itu hanya berhubungan dengan Tuhan. Di dalam beribadat sebegitu jauh mereka tidak melihat ada hubungannya dengan seni. Shalat misalnya tidaklah diperlukan musik pengiring, tetapi yang diperlukan intens atau apa yang disebut istilah khusyuk.
Di dalam Islam mende¬katkan hubungan dengan Allah memerlukan keindahan sebagai unsur penting dalam seni, karena Allah itu Maha Indah (Jamil/ جميل). Ulama membangun istana indah di kalbunya terekspresi dalam tutur kata yang indah seperti doa dan syair sebagai ekspresi keindahan untuk mencari Tuhan Yang Maha Indah seperti juga lewat tariqat yang dianut dan dibelanya.
Sebelum Islam datang, manusia telah mempunyai kekayaan budaya juga. Kedatangan Islam pun tidak meniadakan kebudayan yang ada, tetapi memberikan perubahan, inovasi, rehabilitasi dan sebagainya. Yang tidak baik diperbaiki dan yang baik direkayasa dan disarati dengan nilai yang diredhai (Islami). Karena itu pula kebudayaan, khususnya seni dengan esensi keindahannya merupakan refleksi (pantulan) Islam dalam aspek kebudayaan. Islam menjadi sumber kebudayaan, khususnya seni dengan esensi keindahan. Akidah dan seni bertemu dalam jiwa muslim yang intens. Karena kata Muhammad Quthub, tashauwur Islami (تصور إسلامي /penci¬traan Islam) dalam seni dimulai dari hakikat ilahiyah (حقيقة إلهية) yang kemudian melahirkan segala wujud. Kemudian bersamaan lahirnya wujud itu, muncul bermacam-macam bentuk gambar dan puspa warna dari wajud yang ada dan ekspresi indah melalui kata-kata kemudian menjadi sastra. Ini merupakan 'inayah (عناية) secara khusus kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Allah memberikan lapangan yang luas dalam seni termasuk gambar sebagai seni rupa yang indah. Semua itu kembali kepada semua wajud yang ada. Wajud yang ada itu kembali kepada hakikat ilahiyah. Karena hakikat ilahiyah itulah masternya dan gan¬daanya harus kembali pada master.
Ternyata amat diperlukan penghayatan estetik yang dalam mencapai dimensi transendental. Karya seni yang jauh dari keindahan transendental, disertai pula lemahnya akidah, pengetahuan agama dan pengalaman religius yang rendah, maka pada giliranya seniman dalam berimajinasi dalam menuangkan ide dan pengalaman estetiknya sering terperangkap dalam suatu dilematik. Agaknya persoalan ini yang menimpa "Langit Makin Mendung" Ki Panji Kusmin yang memenjarakan HB.Yasin dan mengundang Hamka dan Bahrum Rangkuti berpolemik a lot. Hamka dan Bahrum pun diserang. Aksi menyerang ulama pengarang seperti Hamka sudah berlangsung sebenarnya tahun 1962 sebelum lahirnya Manifes Kebudayaan ditandai lahirnya Lembaran Kebudayaan Lentera Surat Kabar Bintang Timur pimpinan Pram, tahun 1962.
Berbeda dengan Najib Mahfuzh sastrawan Mesir yang meraih hadiah Nobel 1988 lalu, berimajinasi jernih dilandasi akidah yang kuat meski dalam saat tertentu di negerinya dimarjinalkan juga karena dicap `ilmaniyah (علمانية/sekuler). Dalam ceritanya Masjid di Lorong Sempit, ia seperti menempatkan iman yang kuat di atas segala-galanya dalam karya sastra. Ia menarasikan seorang pelacur yang punya setetes iman “bila masuk masjid aman”, tapi benar-benar diimaninya, dapat menyelamatkan dirinya di dalam masjid, dibanding seorang pimpinan mesjid Abd.Rabuh (imam dan da’i) yang tidak ikhlas dan imannya rapuh, mati dalam keadaan marah pasca pidatonya yang berapi-api mengusir mengusir pelacur yang terpaksa masuk masjid untuk berlindung dari ancaman bombardier pesawat tempur. Pelacur tetap tenang dan aman dalam masjid, karena ia yakin siapa yang masuk masjid aman, sementara iman karena jijik dengan pelacur disebutnya haram di gang sempit itu, ia lari ke luar masjid dan langsung disambar serpihan bom dan mati.
Esensi akidah dalam sastra, panjang lebar pernah saya urai dalam buku “Sastra Islam di Indonesia (1999)”. Dijelaskan ketika seniman melakukan proses kreatifitas dan akidah imannya rapuh, maka lahirlah karya seni (rupa, gerak, suara/ sastra) yang bisa terperosot kedalam fiqh al-batin (kode prilaku) menodai Tuhan.Terkadang agamanya terjual karena "nawaitu" yang kurang baik, dalam merebut fasilitas dari para pihak yang mungkin zalim. Dalam keadaaan seperti ini tidak lagi dapat dimasukan ke dalam seni dan keindahan yang bersumber dari Tuhan, bahkan justru membahayakan akidah dan agama. Kalau membahayakan akidah tentu dilarang dan banyak ulama mengharamkan. Karena seni seperti itu boleh digo¬longkan kepada "lagha" (perkataan sia-sia). Di dalam paham awam perbuatan seperti itu adalah prilaku jahil dan Islam menganjurkan sebaiknya ditinggalkan (QS AL Qashah:55). Untuk contoh kasus ini misalnya seorang penyanyi, yang nyanyinya berlainan dengan perbuatannya maka hasil yang diperolehnya diharamkan oleh Nabi Muhammad saw (Nailul Authar VIII:100), karena dipahami pebagai perbuatan nifaq (kemunafikan) dan penyanyinya digolongkan munafik.
Perinsip Islam kokoh dalam akidah dan syari'atnya, memadukuatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dalam arti profetik kokoh memadukan nilai dimensi sosial yang provan dan dimen¬si transedental memperjelas arah religiositas. Ulama pengarang seperti juga Taufiq memiliki kesadaran profetik yang cukup luas. Bait ulama misalnya lihatlah "NTS" (Nazam Thalub Al-Shalah) Muhammad Dalil Bin Muhammad Fatawi sbb:
Orang meninggalkan sembahyang tiap hari
Di atas dunia disiksa ilahi
Sepuluh perkara siksanya diberi
……
Sempurna wudhu' baik sembahyangnya
Apabila mati diterima amalnya
Di dalam kubur lelapnya senang
Taufiq dalam penyadaran ibadatnya mempunya syair “Sajadah Panjang”, lihat baitnya yang dipopulerkan group musik Bimbo ssb:
….
===
ada sajadah panjang terbentang
hamba tunduk dan sujud
di atas sajadah yang panjang ini
diselingi sekedar interupsi
=====
Reff:
mencari rejeki, mencari ilmu
mengukur jalanan seharian
begitu terdengar suara adzan
kembali tersungkur hamba
======
ada sajadah panjang terbentang
hamba tunduk dan ruku’
hamba sujud tak lepas kening hamba
mengingat DIKAU sepenuhnya
Dari bait tadi penyair bagaikan penyampai ajaran Nabi. Lihat pula penyadaran religius dalam bait-bait Jalaluddin Rummi sebagi berikut:
……
Lakukanlah pekerjaan dari diri ke dalam diri
Karma dengan perjalanan semacam itulah
bumi akan menjadi tambang emas
…….
Lain pula penyampaian pengalaman religius lqbal dalam baitnya berikut:
Apa arti hari-hari dan malam-malam mu
Jika bukan pekerjaan waktu tanpa siang dan malam
…
Kau adalah karya manusia yang beroleh rahmat Tuhan
O.. masjid kurtubah, keberadaanmu berasal dari cinta
Umat Islam takkan sirna sebab ia punya ajaran kekal
Terasa sekali pengalaman religius penyair dan ulama penyair mempunyai esensi higher sufisme yang sangat profetik. Ahli metafisika muslim biasa menulis sajak. Seorang sufi sebenarnya dapat menjadi seorang seniman yang terpikat oleh keindahan (Rusli Marzuki Saria 1988:6 dalam Yulizal, 1999). Fenomena syair Indonesia yang memancarkan kesyahduan nilai Islami dan tak mengabaikan sufistik sampai sekarang di Indonesia merupakan trend baru dalam perkembangan sastra modern di Indonesia era post-modernism.
Posisi Taufiq dalam Perkembangan Sastra Islam di Indonesia
Sastra Islam di Indonesia, diperkirakan telah ada sejak ma¬suknya Islam ke Indonesia. Abad ke 7 (sekitar tahun 669). Fakta social historis ada disebut-sebut kerajaan Islam di Sabak (kerajaan Islam di Timur Minangkabau) ketika itu diperintah Sri Maharaja Lokita Warman, telah didatang ekspedisi Daulat Umaiyah dengan 28 kapal. Di Sabak ini ekspedisi Umaiyah mulai membebaskan rakyat dari buta huruf, bersama raja yang berhasil di-Islam-kan, ialah dengan mencanangkan wajib pandai baca tulis huruf Arab, yang kemu¬dian dikenal dengan "Arab Melayu".
Salah satu bukti sastra telah berkembang bersama masuknya Islam adalah terdapat indikasi, bahwa Islam itu mudah dan merasuk ke kalbu masyarakat. Para pembawa Islam ketanah air mengajarkan Islam tidak dengan kekerasan, tidak dengan pidato berapi-api mengambinghitamkan para pihak yang belum menunjukkan keislamannya dengan benar, tetapi melalui sentuhan bathin, komunikasi sambung rasa dan perasaan estetik membawa penganut lebih jauh masuk kesubstansi Islam. Artinya dakwah dilakukan tidak dengan kekerasan tetapi dengan komunikasi sambung rasa, yakni komunikasi estetika seni. Banyak para muballigh dalam menyiarkan Islam mengunakan bahasa sastra (Drs. Amron Parkamin dkk, 1973, 2:68). Tidak sedikit cerita yang bernafaskan Hindu disalin dan disisipi nilai-nilai Islam, yang berakar dari akidah dan syari'ah yang benar. Cerita disuguhkan sebagai sarana penyiar¬an Islam, mudah dicerna dan tanpa dipaksakan, dengan sendirinya akidah tertancap dalam di dada masyarakat, nilai syari'at terpatri di kalbu dan lahir dalam perilaku dan amal perbuatan masyarakat, sehing¬ga tanpa disadari pula penikmat seni yang diberi nafas Islam itu beru¬bah dari pemeluk non muslim menjadi Muslim yang kuat tauhid dan baik syari'atnya. Secara kongkrit, penyair Islam memakai alas komunikasi bahasa sastra dalam wujud kesusas¬traan, seperti syair (puisi), hikayat (conte), riwayat (novel) dan seba¬gainya.
Sastra dipergunakan sebaik-baiknya sebagai bagian media dakwah. Banyak karya sastra lama yang non muslim yang di¬sipi nilai-nilai Islam yakni nilai aqidah dan syari'at Islamiyah, seperti cerita roh yang pulang ke rumah setiap petang kamis malam jum’at. Dengan cara itu masyarakat (sekaligus penikmat seni) mudah menerima aqidah dan syari'at Islamiyah lalu memeluk Islam sebagai agamanya, yakni menukar agamanya dari non Islam ke Islam meskipun belum kaffah.
Di antara fakta sosial, sastra Islam telah mulai dibina abad ke-7 itu cerderung bentuk sastra kitab. Satu di antaranya tercatat Kitab Badr Al-Hikam. Kitab ini ditulis dengan bahasa Arab Melayu oleh Sayid Badaruddin (seorang ulama yang datang dari Hadramaut tahun 1050) setelah mendirikan pesantren di Kuntu. Kemudian abad ke-14 tahun 1380, terdapat pula teks syair yang bernafaskan Islam, yakni ditulis pada batu nisan tua di Minye Tujoh, Aceh. Sya'ir itu ditulis dalam bahasa Sumatera Kuno, dengan mempergunakan motif huruf (Arab Melayu. DR.W.F. Stuterheim dan DR.C. Hooykaas (1951) memcatat sya'ir yang bernafaskan Islam itu (Raihoel Amar Datoek Besar dalam Yulizal, 1999). Syair ini mengisahkan kematian seorang penguasa yang memimpin Kedah dan Pasai, tahun 1380 M (781 H).
Sya'ir yang tertua setelah teks yang terdapat pada batu nisan tua di Minye Tujoh Aceh itu, adalah sya'ir-sya'ir yang ditulis oleh Hamzah Fansuri. la merupakan seorang penyair sufi tertua, hidup pada masa Sutan Iskandar Muda (1606-1636). Jalan hidup dan karyanya banyak dipengaruhi ulama sufi, seperti yang banyak disebutnya a.1 : Al-Junaid, Al-Halaj, Jalaluddin Rumi, Syamsu Tabriz, d1l. Pengaruh ini terlihat di dalam karya sastranya, terutama sya'irnya yang bercorak ruba'i (رباعي) dan masnawi (مثنوي).
Karya sastra dalam bentuk puisi lama yang berakar dari kebudayaan Indonesia purba seperti dongeng dari mulut ke mulut, sastra pengaruh agama non Islam, diberi nilai serta disarati nafas Islam. Juga besar pengaruh Persia, Arab, karya sastra yang bersifat sejarah, cerita-cerita panji, kitab-kitab yang, bersifat undang-undang dan hukum, disalin untuk memperkuat sastra bertendens dapat digunakan sebagai sarana dakwah. Tidak sedikit karya sastra yang bernafaskan Islam dan melahirkan sederet nama sastrawannya, antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatran, Syeikh Nurud¬din Al-Raniri, Abdul Rauf Al-Singkel, Amir Hamzah, Muhammad Ibnu Ahmad Kemas (1719-1763), Abdus Samad Al-Palembani, Kemas Fachruddin, Daud Ibnu Abdillah Ibnu Idris Pattani dll. Karya sastra yang terkenal diantaranya Kitab Seribu Masalah, Riwayat (story) Nabi-nabi, sebelum Muhammah saw. Hikayat tentang Nabi Muhammad, Hikayat tentang Para Sahabat dan Pahlawan Islam, hikayat tokoh seperti syair hikayat Amir Hamzah dsb. Termasuk karya ulama-ulama seperti "Gurindam 12" oleh raja Ali Haji (1844-1857) dan syair-syair ulama Minangkabau seperti Darul Mawa'izah dan Talabu Al-Shalah puitisasi Muhammad Dalil (Syeikh Bayang), syair syeikh Muhammad Taher Jalaluddin Al-Falaki, syair Yusuf dan Salehan oleh Syeikh Sulaiman Al-Rasuli, syair Muhallil karya Dr. Haka (ayah Hamka), syair Burhan al-Haq karya Syeikh Chatib Muhammad Ali Al-Padani, syair Nahu, syair "Nabi Bercukur" dan "Nazam Kanak Kanak" karya Labai Sidi Rajo Sungai Puar; "Kota Pariaman" yang mengisahkan riwayat ulama Syeikh Muhammad Jamil, pembawa Naqsyabandi ke Pariaman, Hikayat Hasan Hosen yang melatari kisah "Tabut Pariaman" dll.
Melihat kekayaan sastra lama dan baru, semestinya mahasiswa terajak untuk mempelajari sastra Islam di samping sastra Arab dan Inggiris dll., tidak boleh membiarkan lewat begitu saja, termasuk puisi karya Taufiq Ismail. Semestinya menjadikannya bahan utama dalam kajian sastra Islam di Indonesia. Karena dalam pandangan saya puisi lama dan baru serta modern seperti karya Taufiq ini ditempatkan pada posisi penting dalam perkembangan kesusasteraan Islam di Indonesia di era post-modernism ini. Perhatian seperti ini berpotensi menemukan substansi nilai Islami dalam sastra lama, sastra baru dan sastra modern dan merekat mata rantai sejarah sastra yang hilang. Ia menyebut sastra Islam sebagai sastra zikir. Taufik dalam perjalanan sastra Islam di Indoensia dapat digambarkan sbb.:
Dinilai Taufiq Ismail, dkk berpotensi menyambung mata rantai yang hilang itu. Karena penyair besar nasional kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, 25 Juni 1935 ini, juga pendiri majalah sastra Horison (1966) dan Dewan Kesenian Jakarta (1968), berobsesi mengantarkan sastra ke sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi itu, sudah melahirkan puisi agung cukup banyak dan menempati posisi penting kaya esensi kebangkitan dan perubahan dalam perkembangan sastra Islam di Indonesia. Di dalamnya kaya nafas Islamnya, kekuatannya bukan pada simbol-simbol Islam tetapi pada bahasa naratif mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam diskripsinya yang detail tentang fenomena tiga zaman (menyambung tradisi bersastra ulama pengarang) yakni orde lama, orde baru dan era reformasi. Secara kategoris melihat gaya yang sangat diskriptif dan detail, terkesan mengurangi kedalam makna bahasa, tetapi kalau mencermati cara Taufiq mengekspresikan perasaan, pengalaman, imajinasinya terasa kaya dan menawan penikmat seni lebih jauh membawa masuk kedalam dirinya dan suasana peristiwa politik yang dinarasikan dan didispsikannya itu.
Mungkin Taufiq tak seseru Chairil yang menerjang-nerjang menyuarakan anti kolonialism, atau tak sekental ulama membahasakan Islam mulai dari symbol, ajaran sampai kepada thema tetapi Taufiq punya cara sendiri mengikis segala bentuk penjajahan dalam puisinya meskipun dengan elegi/ ratapan yang terasa melankolis. Ada perubahan dari tradisi bersastra dibanding ulama dalam menyuarakan Islam dan dengan asas tauhidnya lahir sastra zikir nama lain dari profetik atau sastra Islam, ia kuat melawan mulhid (ملحد/atheis) yang dihembuskan marxisme dan cucunya Lekra/ PKI dkk. Ideologi atheis itu merasuki budaya bangsa, menimbulkan iklim prahara budaya bangsa (baca DS.Moeljanto dan Taufiq Ismail, 1994).
Pandangan berbeda dan kritik dimunculkan Aguk Irawan MN (2004), ”Ketika Indonesia Dihormati Dunia” disebutnya, Taufik menunjukkan ratapan yang dahsyat dan merindui masa lalu yang sudah tenggelam. Taufiq disebut pula memerankan tokoh dalam kehidupan tanpa opsi dan solusi. Sastra yang seharusnya sebagai ruang pertemuan antara batin dan kenyataan, kandas di jalan mengacu Rene Wellek, Aguk menyebut Taufik gagal memakai medium bahasa untuk institusi sosial. Juga mengacu Teeuw sastra jenis ini telah kehilangan peran dalam meredamkan ketegangan antara konvensi (tradisi) dan inovasi (pembaruan). Sebab peran sastra sepanjang masa hendak memperjuangkan peralihan-peralihan formasi baru yang dapat dianggap menjalani transformasi dan sintesis, tanpa adanya kerinduan yang berlebihan terhadap kebangkitan kembali nilai-nilai masa lalu”. Justru menurut saya dengan memunculkan peristiwa masa lalu di puisi Taufiq satu di antara setting sejarah jenis waktu referensial, akan memuncul nilai instruktif sejarah: “kalau masa lalau jelek lihat benar dan janga ditiru dan terulang lagi, jika baik lihat betul, tirulah dan maju ke garda terdepan”. Ini bagian dari solusi. Artinya masa lalu yang digoreskan itu ada nilai peringatan dan dijadikan peringatan. Islam pun mengingatkan “memperingati itu ada manfaatnya”.
Dari tahun ke tahun sebenarnya terjadi perubahan pandangan Taufik mensosialisasikan nilai Islam dalam syair naratif diskripti memotret fenomena masa lalu dan yang sedang terjadi masa hidupnya yang dominant tema politik. Sehingga suatu kali sebagai penyair yang ia juga penganut Islam yang kuat dan taat, diidentifikasi karya sastranya sebagai sastra zikir dan ada dalam mapping nama sastra Islam. Tito Yulianto (2007) memetakan (mapping) perkembangan nama lain dari sastra Islam, yakni sastra sufistik (Abdul Hadi WM), sastra profetik (Kuntowijoyo), sastra pencerahan (Danarto), sastra zikir (Taufiq Ismail), sastra dunia dalam (M. Fudoli Zaini), sastra transendental (Sutardji Calzoum Bachri) dan sebagainya yang pada dasarnya hendak mengatakan bahwa ada karya sastra yang kental dengan nuansa Islam, baik dari – secara sederhana – unsur estetikanya atau ekstra estetiknya (bentuk dan isinya).
Puisi Taufiq sisi bentuk tetap mempunyai ciri sendiri meskipun dalam pemberian topic puisi ada kemiripan dengan Amir Hamzah, misalnya “Malu (Aku)…” pada puisi Taufiq, pada topik Amir Hamzah terdapat kemiripan gaya misalnya “Berdiri Aku”, “Hanyut Aku” (lihat STA,1977). Namun sisi isi Taufiq menunjukkan intensitas yang cukup tinggi dinamikanya menyikat esensi zaman dan peristiwa yang telah/ sedang dialaminya dan disadari atau tidak sarat dengan sosialisasi nilai Islami. Perkembangan dan perubahan karya Taufiq dapat disiasati dalam tiga era periodesasi sejarah bangsa Indonesia sbb.:
1. Era orba: kalau sudah 55 tahun Taufiq dalam Sastra Indonesia, berarti sejak tahun 1953 (usia 18 tahun Taufiq) ketika menjadi siswa dan setelah jadi mahasiswa kuliah di Bogor tahun 1957 telah melirik penghayatan keindahan dan memasuki dunia sastra. Namun karyanya zaman itu belum saya temukan. Ini dimungkinkan, karena dalam pengakuan Taufiq sendiri dalam banyak sumber, tidak semua karyanya dipublikasi. Namun tema-tema yang dapat disimak menyangkut esensi kehidupannya sebagai orang muda gelisah mengahadapi situasi negeri, situasi ekonomi termasuk ekonomi keluarganya di Pandai Sikek (Sumbar) yang sering gagal tanaman kentang kakeknya, inflasi dan politik yang berselimut agama (Nasakom) dan erosi kepercayaan sampai dekrit Pressiden 1959 kembali ke UUD 45 serta ancaman perang saudara seperti terbaca dalam “elegi buat sebuah perang saudara”nya Taufiq (1960) yang mengisyaratkan apa yang sebenarnya dicegah Islam: “hentikan dendam, justru dendam membunuh”. Islam justru menyuruh “jadilah bersaudara dengan nikmat Allah”.
. Tahun 1963 Taufik menerbitkan buku Manifestasi bersama Goenawan Mohamad, Hartojo Andangjaya, et.al. dan tahun itu pula ia meraih sarjana dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia di Bogor. Tahun ini puncaknya pergolakan kebudayaan Indonesia disusupi ideologi komunis dengan ofensif Lekra/ PKI dkk. Pengarang ulama diserang satu di antaranya Hamka dan keluarganya diancam bahkan ulama ini dipenjara dipenjarakan. Muncul prahara budaya, dihadapkan pada pilihan hidup atau mati dalam sejarah pencarian strategi kebudayaan bagi Indonesia modern. Obat alternatifnya, lahir Manikebu (Manifes Kebudayaan) 24 Agustus 1963. Intinya pertama, menyatakan kebudayaan hanya perjuangan menyempurnakan kondisi hidup, kedua melaksanakan kebudayaan nasional dengan jujur dan mempertahankan martabat bangsa Indonesia, ketiga ditegaskan filsafat kebudayaan adalah Pancasila. Suasana bangsa, ketidakmenentuan politik dan iklim budaya yang tidak kondusif ini menjadi bagian tema puisi Manifestasi. Di antaranya puisi “Almamater” (1963) di samping kenangan semasa kuliah dan jasa kampus, juga terisi dengan kata “…kau telah dilantik jadi warga republik yang befikir bebas… kami bersyukur pada Tuhan…. pada ibu Bapak”. Ada sentuhan nilai Islami, yang mengajarkan bersyukur atas nikmat dan berbuat baik kepada orang tua, meski dalam berada gemuruh zaman yang memusingkan.
Ada juga kesadaan kembali ke Tuhan, terdeteksi pada puisi “kota, pelabuhan, lading, angin dan langit (1964). Kalau jalan dunia sudah buntu, Taufiq memberi isyarat jalan kelangit tetap terbuka lebar dalam puisinya (1965) “Dengan Puisi, Aku (…berdoa)”, bagian dari nilai Allahu l-shamad (الله الصمد/ Allah itu tempat meminta), dan do’a itu mukh al-ibadah (الدعاء مخ العبادة/ doa inti ibadat). Terasa betul dalam suasana ini sastra itu ibadat dan bagian ibadat penyairnya.
3. Era Orba: Tahun 1966 Taufiq menerbit buku Benteng, juga Tirani, juga mendirikan majalah sastra Horison. Kemudian dua buku ini digabung diterbitkan tahun 1993. Terasa sekali puisi ini meliput berbagai peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara. Puisi tahun 1966 ini merekam puncaknya peralihan zaman orla kepada orba. Bagaikan konsesus nasional juga. Ini juga bagian dari hasil tuntutan Taufiq bersama rekannya. Ada rasa syukur kembali dipatri dengan doa. Tidak saja doa bersyukur, tetapi juga doa mensiasati diri, kesadaran baru, dimungkinkan para pejuang melahirkan orba dan mungkin kesalahan para pihak orla. Karena mungkin tak semua kata dan langkah yang benar direspon baik, dan terasa ada salah (disengaja atau tidak) pada gilirannya mengadu kepada Tuhan, diyakini doa inti ibadat. Lihatlah puisi Taufiq “Dao” (1966):
“Tuhan kami
Telah nista kami dalam dosa bersama
Bertahun-tahun membangun kultus ini
Dalam pikiran yang ganda
Dan menutupi hati nurani
Ampunilah kami
Ampunilah
Amin
…”
Dalam era orba ini Taufiq menerbitkan buku puisi, tetap memotret peristiwa politik yang disarati berbagai aspek kebudayaan seperti sistim sosial, ekonomi, pendidikan, agama dsb. Tahun 1971 terbit puisi Sepi; Kota, Pelabuhan, Ladang, Angin, dan Langit. Tahun 1972 terbit Buku Tamu Museum Perjuangan. Tahun 1973 terbit Sajak Ladang Jagung. Tahun 1990 terbit lagi Puisi Langit dengan naratif diskriptif fenomena yang amat menarik yang dapat dicirikan sebagai syi’r munasibat (شعرالمناسبة/ occasional poetry/ sajak peristiwa).
3. Era Reformasi, tahun 1999 Taufiq menerbit buku puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia. Taufiq merekam peristiwa reformasi bergulir di Indonesia tahun 1998. Taufiq sebagai penyair memotret situasi dan kondisi politik yang terdiskripsi dalam puisinya di antaranya terlihat dalam puisinya “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia”. Malu dengan fenomena iklim budaya yang dilakoni para pihak yang menjatuhkan martabat bangsa seperti penjilat yang bisa membidani lahirnya KKN. Sikap menjilat (jilatisme) bisa jadi sogok dalam bentuk lain. Ajaran Islam: “yang menyogok dan disogok dilaknat”. Sogok itu tidak saja duit puluhan juta, ratusan juta, milyaran, trillyunan tetapi sekerling mata, seulas senyum pun yang sengaja menyenang-nyenangkan hati para pihak yang berkuasa lalu berpihak dan menghimpit kepentingan orang banyak, juga bermakna sogok. Taufiq dalam puisinya yang menaruh nilai Islami ini dan menyadarkan bangsa dalam gerakan sederhana menawarkan pemahaman ke-Indonesiaan yang bermartabat, malu berbuat salah dan malu berbudaya jilatisme, malu berbuat nepotism dengan komersialisasi jabatan, yang dalam perspektif Islam dilaknat dan dari perspektif kehidupan berbangsa membahayakan identitas, integritas dan keberlangsungan bangsa. Renungkan baris-barisnya dalam “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” (1998) berikut:
Di kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal,
anak sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden,
menteri, jenderal, sekjen dan dirjen sejati,
agar orangtua mereka bersenang hati,
Dalam perspektif intrinsik puisi ini seperti mewartakan peristiwa budaya atau kode prilaku sok kuasa. Peristiwa dalam teks puisi meminjam ungkapan Maman (2007) dapat ditelusuri dengan mencermati sekuen-sekuen yang menggelinding jadi peristiwa dan motif-motif di belakangnya. Dimungkinkan terjadi dalam struktur kekuasaan dan sementara para pihak yang berkuasa. Fenomena itu jelas memalukan. Dalam ajaran Islam, budaya malu itu bagian dari iman. Malu membudayakan kode prilaku mazdmumah (مذمومة/ budi pekerti tercela). Taufiq seperti berpesan tanamlah dan biasakan budaya malu, malu bagian dari iman. Malu tidak berbudi bagi bangsa yang berbudaya. Hidup tak berbudi, menghancurkan budaya, hancur budaya maka hancurlah bangsa. Betapa jauh Taufiq dalam perspektif kebangsaan memandang, budaya malu melindungi bangsa bagi keberlanjutan Indonesia yang sudah susah payah diperjuang menjadi Negara yang medeka. Taufiq malu jadi orang Indonesia, bukan hendak membuang bangsanya justeru mengingatkan anak bangsa ini bahwa budaya malu berbuat salah adalah manifestasi yang mahal dari kecintaan terhadap bangsa. Taufiq seperti hendak mensosialisasikan semangat Islam, hubbub l-wathan min al-iman (mencintai tanah air itu bagian dari iman). Caranya ia sebut yang salah itu salah, tentu mengingatkan: “ayo bersama membangun kekuatan untuk menghindarinya, menyebut yang benar itu benar meski pahit, dan membangun kekuatan bersama untuk melakukannya dengan baik”. Dari teknik penyiaran nilai Islam di samping pewartaan kebangsaan dalam puisi, karya sastra puisi Taufiq penting dalam era sastra Islam di Indonesia. Posisi Taufiq itu dapat digambarkan sbb.:
Pesan lain Islam tentang dijerat hutang istilah Islam ghalabat al-dain (غلبة الدين) juga disiarkan Taufiq. Nasib yang dijerat hutang dalam perspektif ketuhanan tercegat mendapatkan rahmat Allah. Dalam perspektif humanistik, melahirkan bangsa pengemis. Taufiq sangat lugas dalam “Kalian Cetak Kami Jadi Bangsa Pengemis, Lalu Kalian Paksa Kami Masuk Masa Penjajahan Beru, Kata Si Toni” (1998) memperkatakan fenomena hutang disebabkan gengsi disebut miskin, lalu berhutang dan akibatnya buruk, merusak martabat bangsa, bangsa yang tak lepas dihutang.Lihat baitnya berikut:
Kalian paksa-tekankan budaya berhutang ini
Sehingga apa bedanya dengan mengemis lagi
Karena rendah diri pada bangsa-bangsa dunia
Kita gadaikan sikap bersahaja kita
Karena malu dianggap bangsa miskin tak berharta
Taufiq dalam bait yang sangat Islami meningatkan, budaya berhutang membuat malu. Budaya ini akan melahirkan fiqh al-bathin (kode prilaku baru) yakni budaya pengemis. Islam tak suka. Sukanya Islam, berusaha keras dengan menggali seluruh potensi yang ada. Tak ada henti. Sehingga dapat memberi. Diajarkan Islam yad ‘ulya (يدعليا/ tangan di atas) lebih mulia dari yad sulfa يدسفلى)/ tangan di bawah). Sekaitan dengan nilai religiositas sastra Taufiq ini mengingatkan saya kepada sabda Nabi saw: Inna min al-syi’r hikmah (إن من الشعر لحكمة / benar-benar, sebagian besar puisi itu hikmah).
Penutup
Akhirnya diketahui dalam syair-syair naratif diskriptif Taufiq Ismail sarat nilai religius menempat karyanya pada posisi penting dalam khazanah kesusasteraan sebagai bagian dari al-fann al-islami (الفن الأسلامي/ seni Islam). Religositas sastranya memamsuki dimensi profetik yang sufistik, mengandung “majmu’atun min al-mau’izhah wa l-hikmah wa l-irsyad” (sekumpulan nilai pengajaran yang indah, hikmah dan panduan arah lurus ke jalan yang benar). Keagungungan sastra Taufik terletak pada pengisian bahasa naratif dengan pengalaman religius yang cukup kaya melampaui derjat diskriptifnya terhadap fenomena. Tegasnya, nilai Islami pada puisinya tidak terletak pada kata-kata simbol Islam, tetapi keagungannya terletak pada makna ajaran dan keindahan narasi. Juga ada banyak hikmah dan isyarat-isyarat ke-Indonesiaan dan ke-Islaman yang benar. Dari perspektif kedalaman Taufik menyelami peristiwa akmbn (aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara) dan diskripsinya dalam narasi serta diisi makna religiositas sastra yang dalam menempatkan Taufiq pada posisi penyair Islam terbesar di awal abad ke-21 ini.
Karya besar Taufiq ini pantas dicerna pelajar dan mahasiswa sastra dan dijadikan buku refrensi sastra ditempatkan dibagian refrensi perpustakaan sekolah mulai dari pendidikan dasar dan perguruan tinggi, seperti juga bagian harapannya. Sekali lagi perpustakaan di lembaga pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan daerah serta perpustakaan negara di samping arsip Negara tidak boleh lengah dengan karya dan produk bangsa sendiri.
Ada kekhawatiran, berangkat dari pengalaman sejarah naskah lama ulama pengarang, karya sastra mereka tidak banyak menjadi perhatian kritikus sastra, di samping mereka memang tidak popular sebagai penyair dibanding keulamaannya dan intelektualnya juga sebagian besar karya mereka itu tak tersimpan dan lenyap, masih mending terkubur dalam debu tumpukan buku-buku agama dan sastra atau tersuruk dalam rimba seni budaya modern, sehingga generasi hari ini baik sastrawan, kritikus dan penikmat sastra di negeri ini nyaris tak mengenalnya lagi.
Fenomena nasib naskah lama tadi berakibat perkembangan sastra modern sebagai mata rantai penyambung "masa silam" dengan "masa kini" ke “masa datang”, seperti terputus, disebabkan perpustakaan tidak cukup lengkap dan tidak rapi dalam memelihara naskah lama atau mungkin --perubahan sosial terjadi-- maka karya lama dipandang tidak punya nilai lagi dianggap buku sampah di perpustakaan, atau karena masyarakat cenderung "mem¬barat". Adalah ironis, mereka lebih akrab dengan nilai karya bangsa asing dibanding nilai yang ada pada karya sastra lama milik sendiri. Termasuk memprihatinkan perkembangan sastra daerah untuk kasus Minangkabau, boleh dikatakan ada fenomena langka cipta karya sastra modern yang ditulis dalam bahasa daerah (Minang) sejak Muhammad Yamin (1903-1962) dkk. memperkenalkan sastra modern dan mengikrarkan "berba¬hasa satu, bahasa Indonesia" pada Sumpah Pemuda tahun 1928.
Rujukan
Aguk, Irawan Mn,
2004 Sajak Melankolisme Taufiq Ismail. Jakarta: Sinar Harapan on line.
Ahmad, Mulyadi, terj.
2005 Adonis, Perubahan-Perubahan Sang Pencipta. Jakarta:Grasindo.
A.Kohar Ibrahim,
2007 Pram, Kohar & GM – Soal Berpura-pura dalam Puisi Manikebu. On line http://www.bekasinews.com
Maman, S.Mahayana,
2007 Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Moeljanto, DS; Taufiq, Ismail, ed.
1994 Prahara Budaya, Kilas Balik Ofensif Lekra/ PKI dkk. Jakata: Mizan.
Sutan Takdir Alisjahbana,
1977 Amir Hamzah Penyair Besar Antara Dua Zaman dan Uraian Nyanyi Sunyi. Jakarta: Dian Rakyat.
Taufiq, Ismail,
1993 Tirani dan Benteng, Dua Kumpulan Puisi Taufiq Ismail. Jakarta: Yayasan Ananda.
http://id.wikipedia.org/wiki/Taufiq_Ismail
Thaha, Mahmud Thaha,
1966 Qishshah fi l-Adab Al-Injliziyah (القصة في الأدب الإنجليزى/ Cerkan dalam Sastra Inggiris). Al-Qahirah: Al-Dar Al-Qaumiy.
Tito, Yulianto,
2007 Sastra Bukan Islam. On line.
Yulizal, Yunus,
1999 Sastra Islam di Indonesia, Kajian Syair Apologetik Pembelaan Tareqat Naqsyabandi Syeikh Bayang. Padang: IAIN-IB Press.
____________,
1999 Perkembangan Terakhir Sastra di 15 Negara Arab. Padang: IAIN-IB Press.
____________,
2001 Puisi Mahasiswa Genre Occasional Poetry. Padang: IAIN-IB Press
CURRICULUM VITAE
Yulizal Yunus, Dt. Rajo Bagindo Lektor Kepala dalam mata kuliah Sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya – Adab IAIN Imam Bonjol, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balaiselasa, tim ahli bidang budaya Pemda Kabupaten Pesisir Selatan.
Berdomisili di Padang, Jl.Sitawa 15 Rt.45/Rw.03 Parupuk Tabing, Koto Tangah,Padang, 25171 dan atau di Jl. Tui Raya F/ 14 Belimbing Padang. Telp. Rumah (0751) 444938, HP. 081363851007.
Pendidikan, SDN, Tj.Kandis (1969), PGA 4 Tahun Anakan (1972), PGAN 6 Tahun Salido (1974), Sarjana Muda (gelar BA) FT-IAIN Imam Bonjol Padang (1977), Sarjana (Drs.) FT-IAIN Imam Bonjol Padang (1983) dan sedang Pasca Sarjana Unand Padang. Pendidikan tambahan: Pelatihan penulisan ilmiah populer LIPI (1981), Pelatihan Penelitian Agama (PPA), Depag RI – LIPI Jakarta (1994), Lemhannas (1997), Pelatihan Penelitian Profesional, Jarlit se Sumatera (2001) dll.
Kegiatan lain, peneliti AP3TI (Asosiasi Peneliti dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Indonesia) Jakarta ( sejak 1997), peneliti Pusat Penelitian IAIN Imam Bonjol (1996), Pemimpin Majalah Ilmiah “Al-Turas” (1996),Redaksi Eksekutif Majalah Ilmiah Imam Bonjol, (1996), Ketua STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Balaiselasa (sejak 1996), HISKI (Himpunan Sarjana Kesusasteraan) Komda Sumbar, Sekretaris (1997), ICSB (Islamis Centre Sumatera Barat), Padang, Biro Penerbitan (1997), IAIN-IB Press (Penerbit), Direktur (1989), Pembantu Dekan III Fakultas Adab (Sastra) IAIN Imam Bonjol (1999), MPI (Majelis Pemuda Indonesia) Sumatera Barat, Sekretaris (2001), Dekan Fakultas Ilmu Budaya- Adab IAIN Imam Bonjol (2003 – 2007), Penanggung jawab Jurnal Internasional FIBA – UKM “Fikr wa Adab” (sejak 2004), Director Executive Centre for Police and Culture (2007), Forum Islamic Centre Sumatera Barat (2008) dll.
Karya Tulis (Buku/ Hasil Penelitian/ Makalah/ Artikel), Artikel publikasi koran dan majalah telah dimulai sejak sebelum bekerja di Skh. Semangat di Padang tahun 1976 571 topik. Menulis buku sudah dimulai sejak tahun 1981, sudah dicetakjuga hasil penelitian di antaranya:
1. Kumpulan Puisi Padi Menguning Ditinggalkan (1977)
2. Islam di Gerbang Selatan Sumbar (buku) cet.I/1998.
3. Sosialisasi di Perkampungan Wisata Padang (buku Penelitian) 1998.
4. Wanita dan Sastra (Analisa Novel Wanita di Titik Nol), makalah, Semianr Fakultas Adab, 1998.
5. Sejarah STAI Balaiselasa, 25 Tahun (buku) Cet.I/1998.
6. Sosialisasi Islam di Pasaman, Desa Binaan IAIN (Buku Penelitian) 1998.
7. Bahasa Jurnalistik (Naskah buku) belum terbit/ 1998.
8. Kumpulan Puisi Jum’at Sore 14 Mei (1998)
9. Paham Keagamaan Keliru di Sumbar dan Analisa Nazam Kanak Kanak dan Nabi Bercukur (Buku Penelitian), 1999.
10. Motivasi Keagama dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Bungus (Buku Penelitian) 1999.
11. Sentra Tarekat di Sumatera Barat (Buku Penelitian) 1999
12. Sastra dan Sejarah (Makalah Seminar Sastra) Fakultas Adab/ 1999.
13. Teknik Menggubah Puisi Cara Arab (Makalah Seminar Sastra) Studio Sastra/ 1999.
14. Teknik Menyunting (Naskah Buku) belum terbit/1999.
15. Teknik Wawancara (Naskah buku) belum terbit/ 1999.
16. Pulau Cingkuk Saksi Perjuangan Anak Pesisir (buku/ 1991) cet. III/ 1999.
17. Sastra Islam, Analisa Syair Apologetik Syeikh Muhammad Dalil (buku pen.)Cet.I/ 1999.
18. Perkembangan Terakhir Sastra di 15 Negara Arab (Buku) Cet.I/1999.
19. Objek Wisata Kawasan Mandeh Mandeh (Buku) Cet.I/1998, cet.II/1999, cet.III/ 2000
20. Geo Pengajaran Sastra Arab di Indonesia (buku) Cet.I/1999, Cet.II/2000.
21. Angkatan '98, Antologi Puisi (buku) cet.I/1999, cet.II/2000.
22. Objek Wisata Kawasan Mandeh (buku) Cet.I/2000.
23. Kumpulan puisi Anak Pesisir (2000)
24. Sejarah Pss. Selatan dari Sandiwara Bt. kapas hingga Perang Bayang (buku)Cet.I/ 2000.
25. Mencari Hari Jadi Pesisir Selatan (Makalah Seminar Hari Jadi Pss. Selatan, 12 Jan 2000.
26. Irak-Kuwait dalam Syi'r (Buku Kumpulan Syair), 2000.
27. Master/ Action Plan Pesisir Selatan 2001-2010 (Buku), 2001
28. Pesisir Selatan, Kinerja 1995 – 2000 (Buku), 2001
29. Protes Sastra terhadap Paham Keagamaan (Buku), 2001
30. Puisi Mahasiswa Genre Occasional Poetry (Buku), 2001
31. Paket Budaya Perkawinan Pesisir Selatan (Pemda Pessel, 2002)
32. Al-Qashash al-Islamiyah fi Tatsqif Syakhshiyat al-Athfal ( buku IAIN-IB Press, 2002).
33. Kesultanan Indrapura dan Mandeh Rubiyah di Lunang, Spirit Sejarah dari kerajaan Bahari sampai Semangat Malayu Dunia (buku Pemkab Pesisir Selatan – IAIN IB Press, 2002).
34. Detail Plan Pembangunan Budaya Pesisir Selatan (buku IAIN-IB Press, 2004)
35. Pesisir Selatan dalam dasawarsa 1995-2005 di bawah kepemimpinan Bupati Darizal Basir (buku IAIN-IB Press, 2005)
36. Budaya Pesisir Selatan 3 jilid (buku IAIN-IB 2006)
37. Budaya Padang 9 Jilid (buku 2007)
38. Budaya Padang Panjang 9 Jilid (buku IAIN IB Press, 2002)
39. Budi Pekerti 9 jilid (buku IAIN IB Press, 2006)
40. Bahasa Arab untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Padang Panjang 9 jilid (buku IAIN IB Press, 2002)
41. Bahasa Arab untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Padang 12 jilid (buku IAIN-IB Press 2006)
42. Prototype Polisi Masa Depan Kinerja Kapolda Sumbar (buku IAIN-IB Press, 2007)
43. Kumpulan Syair Arab Kontemporer 20001-2006 (buku IAIN IB Press, 2007) dll.
Selengkapnya...
 Hampir 70 %, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum diakui. Sehingga batas-batas teritorial yang berkaitan dengan (utmanya) laut, memiliki potensi besar dalam menciptakan konflik (Kompas, 3/3/2008). Ambalat hanya salah satu kasus yang muncul ke permukaan. Dari sejumlah masalah batas laut, penetapan yang paling cepat terwujud baru dengan Filipina. Selebihnya masalah yang dihadapi Indonesia begitu besar. Namun, tampaknya Indonesia tidak serius untuk menyelesaikan persoalan batas laut dengan negara tetangga.
Hampir 70 %, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum diakui. Sehingga batas-batas teritorial yang berkaitan dengan (utmanya) laut, memiliki potensi besar dalam menciptakan konflik (Kompas, 3/3/2008). Ambalat hanya salah satu kasus yang muncul ke permukaan. Dari sejumlah masalah batas laut, penetapan yang paling cepat terwujud baru dengan Filipina. Selebihnya masalah yang dihadapi Indonesia begitu besar. Namun, tampaknya Indonesia tidak serius untuk menyelesaikan persoalan batas laut dengan negara tetangga.