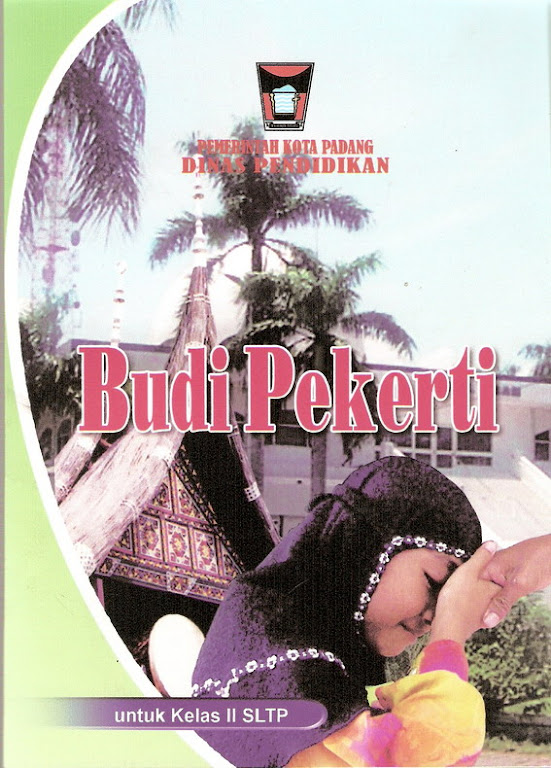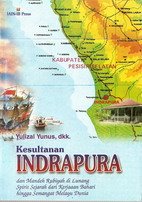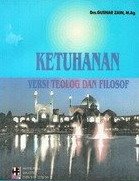Oleh : Muhammad Ilham (Dosen Jur. SKI/Ketua PSIFA IAIN Padang)
 “Kemiskinan itu lingkaran setan, dan titik pusatnya adalah kebijakan. Kemiskinan itu karena majikan tidak mengarahkan kepada kemandirian, lalu siapakah majikan itu ?” (Cordoso, 1999). Saya mulai makalah ini dengan sebuah kutipan (artikel-opini) dari koran Kompas, berikut :
“Kemiskinan itu lingkaran setan, dan titik pusatnya adalah kebijakan. Kemiskinan itu karena majikan tidak mengarahkan kepada kemandirian, lalu siapakah majikan itu ?” (Cordoso, 1999). Saya mulai makalah ini dengan sebuah kutipan (artikel-opini) dari koran Kompas, berikut :“Permasalahan terbesar yang dihadapi negara Asia-Afrika, termasuk dalam hal ini negara Indonesia, adalah permasalahan kemiskinan. Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau wanita ikut menanggung beban. Secara kumultaif, data menunjukkan, dari penduduk yang miskin, 70 persennya adalah wanita. Kemiskinan telah mendorong wanita-wanita Thailand, termasuk gadis-gadis di bawah umur menjual diri di bursa seks kelas bawah dengan tarif murah, karena kemiskinan ini pula wanita-wanita di Philipina, antara tahun 1987-2002, sekitar 261.527 orang wanita, umumnya berusia belasan tahun, memasuki Jepang sebagai wanita penghibur. Kemiskinan juga mendorong para wanita Indonesia menjadi buruh migran ataupun dalam istilah lain, tenaga kerja wanita, di beberapa Negara Timur Tengah dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Wanita, 67 % diantaranya. Kemiskinan juga bertaburan di Bangladesh, Srilanka, India, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Afrika. 35 anggota berbagai organisasi dari 11 negara Asia, yang memberikan perhatian besar terhadap wanita, menyatakan bahwa disparitas yang makin besar dalam pembangunan ekonomi, akses kepada pasar, teknologi dan sistem harga yang lebih adil dalam model pembangunan yang ditawarkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah membuat banyak negara dan manusia terjungkal dalam kemiskinan. Program penyesuaian struktural yang dipaksakan Bank Dunia dan IMF kepada negara-negara pengutang terbesar justru membuat orang miskin menjadi bertambah miskin. Kemiskinan dan berkurangnya pekerjaan produktif dengan gaji cukup di negara asal tenaga kerja, telah memaksa laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak, bermigrasi ke luar negeri. Saat ini terdapat sedikitnya 12 juta pekerja migran dari Asia, separuh diantaranya perempuan, dan jumlahnya terus bertambah”.
Dari pernyataan di atas, kita bisa melihat, bahwa kapitalisme, melalui Bank Dunia dan IMF sebagai alatnya, justru melahirkan kemiskinan yang semakin meluas di Asia dan Afrika. Di negara Sosialis seperti Cina, masalah yang dihadapi pun tidak berbeda. Kemiskinan masih menghantui sebagian besar masyarakatnya.
Dibanding wanita di belahan bumi yang lain, dari segi kesejahteraan, wanita Timur Tengah paling baik kondisinya. Meskipun para wanita ini tidak bekerja, tidak pernah terdengar adanya kemiskinan wanita. Hal ini karena nafkah mereka ditanggung sepenuhnya oleh para wali atau kalaupun tidak ada wali, negara menjamin kebutuhan mereka. Wanita Timur Tengah juga mendapatkan jaminan pendidikan sama dengan pria, bahkan banyak didirikan sekolah khusus wanita. Fasilitas khusus wanita tersedia di mana-mana, termasuk fasilitas kesehatan dan transportasi. Hijab yang mereka kenakan tidak menghalangi kemajuan. Hanya saja, peran wanita banyak dibatasi oleh negara. Sistem pemisahan mutlak antara pria dan wanita serta domestikasi peran, membatasi gerak wanita dalam aktivitas kehidupan umum. Bahkan sampai saat ini, wanita-wanita Timur Tengah tidak mempunyai hak politik, termasuk untuk sekedar memilih anggota parlemen dalam pemilu.
Dari gambaran tentang wanita di atas, kita bisa melihat beragamnya problematika yang dihadapi oleh wanita. Jika kita tinjau lebih jauh, semua problematika wanita tidak bisa kita lepaskan dari problematika manusia seluruhnya. Sebagai contoh, problem kemiskinan yang dihadapi, juga dihadapi oleh rumah tangga dengan kepala keluarga pria. Kalau dikatakan karena kurangnya akses ekonomi wanita, pendapat ini bisa gugur dengan fakta wanita di Timur Tengah yang berkecukupan tanpa harus bekerja. Bisa dikatakan bahwa tidak ada masalah wanita yang murni dapat dilihat hanya karena kewanitaannya saja.
Upaya pemecahan problema wanita yang selama ini dilakukan dengan mendasarkan pada fakta yang berbeda di tempat yang berbeda, tidak akan menuntaskan permasalahan. Karena akar permasalahan wanita pada dasarnya sama, dimanapun ia berada. Wanita diberbagai tempat dengan berbagai kondisi tetaplah merupakan bagian dari manusia, dengan kebutuhan dan naluri yang sama. Kondisi wanita yang berbeda diberbagai belahan dunia disebabkan oleh penerapan peraturan yang berbeda.
Sekiranya peraturan yang diterapkan di seluruh dunia untuk mengatur kebutuhan dan naluri manusia yang sama, tidak akan muncul masalah wanita yang beragam. Dan sekiranya peraturan yang dibuat sesuai dengan ‘kemanusiaan’ wanita, permasalahan wanita akan terselesaikan, tanpa melihat siapa yang menjalankan aturan. Dan tanpa menimbulkan permasalahan baru serta ketimpangan hubungan antara pria dan wanita. Akhirnya menjawab siapa ‘menjajah’ wanita dan siapa yang membuat wanita (secara umum) (di)miskin(kan), dapat kita katakan bahwa peraturanlah menimbulkan problematika wanita. Saya fikir, dari sinilah salah satu point kunci melihat, bahwa wanita merupakan “sosok” yang rentan dengan kemiskinan.
Dalam Laporan Pembangunan Manusia Nasional Indonesia 2004, United Nation Development Programme (UNDP) memperkirakan posisi perempuan Indonesia dengan memakai GDI (Gender-related Development Index) berada di urutan ke-91 dari 144 negara yang telah dihitung GDI-nya. Pengukuran ini membedakan antara laki-laki dan perempuan pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Angka GDI Indonesia adalah 59,2 dan menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan lebih rendah, lebih sedikit waktu mereka untuk sekolah dan memperoleh bagian pendapatan. Pendapatan hanya 38% untuk perempuan dan 62% diterima laki-laki. Padahal jumlah perempuan di Indonesia sekitar 104,6 juta orang atau lebih dari separoh total jumlah penduduk yang ada (208,2 juta jiwa). Akan tetapi kualitas hidup perempuan masih tertinggal dari kaum laki-laki. Masih sedikit peluang dan akses mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan akibatnya jumlah perempuan yang menikmati hasil pembangunan juga terbatas. Oleh karena itu, tanpa usaha penghapusan dikriminasi gender berbagai langkah dan upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan optimal.
Program pengentasan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah yang secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi merupakan hal yang mutlak bagi terealisasinya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015. Untuk itu setiap pemegang kepentingan harus berkomitmen membebaskan perempuan dari diskriminasi, kekerasan dan buruknya kondisi kesehatan yang dihadapi kaum perempuan setiap harinya. Ketidaksetaraan merupakan inefisiensi secara ekonomi, selain juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan membahayakan kesehatan.
Dalam teori sosiologi, kita kenal ada kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural ada bila ia telah menjadi sesuatu yang membudaya seperti adanya rasa malas, keengganan melakukan perubahan, atau sebagai perilaku yang dianggap lumrah. Sementara, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena cengkeraman sistem sosial maupun kekuasaan yang dzalim. Di sini budaya patriarki juga jadi sistem yang menguntungkan satu jenis kelamin dan membuat yang lain cenderung terdiskriminasi.
Saya lebih cenderung bahwa “pangkal bala” (pe)miskin(an) wanita tersebut merupakan kemiskinan structural, tanpa mengabaikan factor cultural. Namun, factor cultural ini, sejalan dengan mulai tingginya tingkat pendidikan, maka factor cultural ini akan terleminir dan tereduksi. Akan tetapi, sebagaimana yang saya paparkan dalam tulisan diatas, proses (pe)miski(nan) tersebut TERBUKTI karena factor kebijakan yang diambil oleh pemegang kebijakan (elite sosial politik).
Upaya penghapusan kemiskinan tidak akan berhasil dengan maksimal apabila perempuan belum bisa menikmati hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara penuh. Karena itu, kasus ini hanya akan bisa secara terselesaikan ketika kebijakan pendidikan, kesehatan reproduksi dan kesempatan ekonomi bagi wanita tidak diskriminatif.
1. Persamaan dan kesataraan di bidang pendidikan. Perlu disadari meskipun kesenjangan gender dalam pendidikan dasar antara anak laki-laki dan anak perempuan menyempit sejak tahun 1970, tetapi penyempitan kesenjangan itu berjalan lambat dan tidak merata, terutama di negara-negara paling miskin. Padahal, pendidikan dasar merupakan modal untuk mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan di dalam aktivitas ekonomi yang semakin bersifat intensif-pengetahuan. Dalam konstitusi Indonesia, kesetaraan dan dan keadilan gender terungkap dengan menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 31 ayat 1 uud 1945 mengamanatkan bahwa “Semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”. Hak untuk mendapatkan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin. Seperti yang tercantum pada Dokumnen Deklarasi Dakar tentang pendidikan yang menyatakan: “Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan menjelang 2015 dengan suatu fokus pada kepastian akses anak perempuan tehadap pendidikan dasar yang bermutu. Selain itu, jenjang pendidikan yang ditamatkan perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Ingat, syndrom cinderella complex.
2. Di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih sangat tinggi. Intervensi strategis terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan juga perlu dilakukan karena kesehatan reproduksi merupakan penyebab utama dari kematian perempuan usia 15-44 tahun.
3. Pendekatan makro ekonomi dan program pembangunan yang dilakukan sebagian besar masih mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan. Padahal, perempuan di negara berkembang pedesaan bertanggung jawab atas 60-80 persen produksi bahan makanan. Dalam kesempatan ekonomi, akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja menunjukkan kecenderungan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Keterbatasan perempuan dalam mengakses pasar tenaga kerja berlaku untuk semua tingkatan.
Dengan demikian peningkatan investasi terhadap perempuan khususnya dalam hal pendidikan, kesempatan usaha, HAM dan kesehatan reproduksi mutlak diprioritaskan. Setiap kebijakan pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan haruslah mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender. Jika hal itu terlaksana, cita-cita membebaskan jutaan orang dari kemiskinan, khususnya wanita, akan segera terlaksana.
Catatan penutup :
Makalah ini tidak begitu sistematis, lebih kepada mengkritisi secara “dangkal” kebijakan-kebijakan makro, bukan kasus per kasus. Semoga bisa dikembangkan dalam diskusi
DAFTAR BACAAN
Hendri Saparini, “Buruh Migran Wanita dan Persoalan Ketimpangan Ekonomi : Sebuah Taksonomi Sosi-Ekonomi”, dalam Kompas 12/8/2009
Fatima Mernisi, Kuntum Mawar dalam Kurungan, Bandung: Mizan, 2010
Wan Lathif Wan Mat, “Demokratisasi di Timur Tengah : Potensi dan Hambatan”, Haraqah Daily, 29 Oktober 2010
Emma Yohanna, “Wanita dan Keterlibatan dalam Pembangunan di Sumatera Barat”, Pidato pra-kampanye Calon Anggota DPD-RI 2009-2014, tanggal 11 Maret 2009.
www.ilhamfadli.blogspot.com/peran_politik_wanita/html
www.kalyanamitra.com/ungguh tanggal 22 Nopember 2010.
Selengkapnya...