Oleh : Erman, M.Ag (Dosen Jur. SKI)
 Fundamentalisme berasal dari bahasa Latin fundamentum yang berarti dasar atau sendi. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut orang-orang yang meyakini hal-hal yang fundamental dalam agama. Setiap muslim sesuai pengertian ini merupakan fundamentalis karena beriman kepada hal-hal yang menjadi dasar atau sendi agama Islam. Munculnya istilah fundamentalisme untuk pertama kali adalah penyebutan yang ditujukan kepada gerakan konservatif-militan dalam agama Kristen yang mengemuka di Amerika Serikat pada tahun 1920-an.
Fundamentalisme berasal dari bahasa Latin fundamentum yang berarti dasar atau sendi. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut orang-orang yang meyakini hal-hal yang fundamental dalam agama. Setiap muslim sesuai pengertian ini merupakan fundamentalis karena beriman kepada hal-hal yang menjadi dasar atau sendi agama Islam. Munculnya istilah fundamentalisme untuk pertama kali adalah penyebutan yang ditujukan kepada gerakan konservatif-militan dalam agama Kristen yang mengemuka di Amerika Serikat pada tahun 1920-an.Fundamentalisme berasal dari bahasa Latin fundamentum yang berarti dasar atau sendi. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut orang-orang yang meyakini hal-hal yang fundamental dalam agama. Setiap muslim sesuai pengertian ini merupakan fundamentalis karena beriman kepada hal-hal yang menjadi dasar atau sendi agama Islam. Munculnya istilah fundamentalisme untuk pertama kali adalah penyebutan yang ditujukan kepada gerakan konservatif-militan dalam agama Kristen yang mengemuka di Amerika Serikat pada tahun 1920-an.
Mereka menekankan kebenaran Bible dan menolak setiap temuan sains modern yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Padahal, sains modern justru telah membawa masyarakat Barat pada kemajuan. Karena itu, kehadiran kaum fundamentalis merupakan oposan dari gereja ortodoks terhadap kemajuan sains modern yang dituduh merusak sendi-sendi fundamental dalam agama Kristen. Mengingat karakter konservatifnya yang berpegang teguh pada ortodoksi agama Kristen, fundamentalisme seringkali dikonfrontasikan dengan modernisme yakni aliran yang mengutamakan setiap yang baru sebagai konsekuensi perkembangan sains modern (Asep Syamsul, 2000 : 29-30).
Setelah revolusi Islam Iran (1979), istilah fundamentalisme mulai diterapkan para orientalis dan pakar ilmu sosial untuk mengkaji gerakan-gerakan sosial dan politik yang muncul dalam Islam dengan asumsi bahwa berbagai penomena gerakan sosial dan politik itu memiliki kesemaan karakteristik dengan gejala fundamentalisme di dunia Barat. Mereka menggunakan istilah tersebut untuk menggeneralisasi berbagai gerakan sosial, politik dan keagamaan sejalan dengan munculnya gelombang yang disebut kebangkitan (revivalisme) Islam (Azyumardi Azra, 1996 : 107). Istilah fundamentalisme juga seringkali digunakan secara tidak seimbangan dan tidak netral, bahkan cendrung memiliki makna labelisasi dan penyebutan yang bersifat mapan terhadap fenomena gerakan dalam kehidupan sosial, politik dan keagamaan. Dari beberapa kajian yang dilakukan oleh para ahli, istilah tersebut cendrung memiliki makna negatif untuk memberikan gambaran buruk dan menyudutkan kelompok yang diasumsikan sebagai gerakan fundamentalis. Fazlur Rahman (1979 : 164), misalnya, menyebutkan fundamentalisme Islam sebagai orang yang dangkal, superfisial, dan anti intelektual yang pemikiran-pemikirannya tidak bersumber kepada al-Qur’an dan tradisi Islam klasik. Nurcholish Madjid (1992 : 586) juga memberikan penilaian yang pejoratif dan kurang netral dan menyebut fundamentalisme Islam sebagai sumber kekacauan dan penyakit mental yang menimbulkan akibat yang lebih buruk dibandingkan dengan masalah-masalah sosial yang sudah ada, seperti minuman keras dan obat terlarang. Untuk beberapa kasus tertentu, stigmasi fundamentalisme Islam terhadap gerakan yang muncul dalam masyarakat Islam mungkin ada benarnya karena berangkat dari fakta-fakta empirik yang menunjukkan warna gerakan yang cendrung puritan, radikal dan ekstrim. Tetapi, labelisasi fundamentalisme Islam yang bersifat sinisme itu digunakan secara mapan dan tidak berubah-rubah untuk menggeneralisasi semua fenomena gerakan sosial, politik dan keagamaan dalam Islam jelas merupakan simplikasi yang keliru. Istilah fundamentalisme Islam kadangkala juga dipakai secara overlapping dengan istilah radikalisme dan revivalisme. John L. Esposito (1994 : 17) lebih suka menggunakan istilah revivalisme untuk menyebut gerakan sosial, politik dan keagamaan dalam Islam. Sebutan fundamentalisme Islam, kata John L. Esposito, terlalu dibebani oleh praduga Kristen dan stereotip Barat yang menyiratkan ancaman monolitik yang tidak pernah ada dalam realitas empirik masyarakat Islam. Meskipun demikian, istilah fundamentalisme Islam tetap dipergunakan dalam makalah ini. Fundamentalisme Islam dimaknai sesuai dengan penjelasan dan batasan yang diberikan oleh Jamhari dan Jajang Jahroni (2004 : 3-4) yaitu suatu gerakan sosial, politik dan keagamaan yang memiliki keyakinan ideologis kuat dan fanatik yang selalu mereka perjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Upaya memperjuangkan ideologi itu seringkali meraka lakukan melalui aksi-aksi radikal, militan dan ekstrim, bahkan tidak menutup kemungkinan berperilaku kasar terhadap kelompok lain yang bertentangan dengan paham mereka.
Kemudian, kerangka yang dibuat sosiolog, marty, yang sudah dimodifikasi Azyumardi Azra ( 1996 : 109-110) agaknya juga sangat compatible diterapkan dalam tulisan ini. Pertama, kaum fundamentalis mengambil sikap perlawanan secara radikal terhadap ancaman yang dipandang mengancam eksistensi agama. Kedua, mereka menolak hermeneutika atau sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks kitab suci mesti dipahami secara literal sebagaimana adanya karena nalar dipandang tidak mampu memberikan penafsiran yang tepat. Ketiga, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalisme berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Dalam hubungan ini, masyarakat dan perkembangannya harus disesuaikan dengan kitab suci, kalau perlu dengan kekerasan dan bukan sebaliknya.
B. AKAR SOSIO-HISTORIS KEMUNCULAN KHAWARIJ
Setelah terbunuhnya Usman bin Affan, masyarakat Islam dari golongan Muhajirin dan Anshor berulang kali mendatangi Ali bin Abi Thalib dan meminta kesediannya menjadi khalifah. Permintaan tersebut selalu ditolak oleh Ali karena persoalan siapa yang menjadi khalifah tegas Ali sebaiknya diselesaikan lewat musyawarah sehingga memperoleh legitimasi dari sahabat-sahabat termuka di Madinah ketika itu. Tetapi, karena masyarakat Madinah seringkali mendesak Ali dan menyebutkan bahwa masyarakat Islam perlu segera memiliki seorang pemimpi sehingga tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali luluh juga dan bersedia menduduki jabatan khalifah. Ketika diangkat sebagai khalifah, kekuatiran Ali menjadi kenyataan karena sebagian masyarakat Islam tidak menyampaikan janji setia (baiat) kepada dirinya. Ia hanya dibaiat oleh mayoritas masyarakat Madinah yang terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshor. Beberapa sahabat senior seperti Abdullah bin Umar, Saad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tsabit dan Abdullah bin Salam yang ketika itu berada di Madinah belum mau ikut membaiat Ali. Mereka baru mau membaiat Ali jika semua umat Islam sudah menyatakan baiat (J. Suyuthi Pulungan, 1997 : 152). Karena itu, Ali diangkat sebagai khalifah tidak berdasarkan konsensus karena masyarakat Islam sebagai sistem sosial yang tersusun dari unsur yang memiliki peran yang saling berhubungan tidak saling melengkapi dan mengisi dalam menentukan eksistensi kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan yang sama. Implikasinya, instabilitas sosial dan politik dalam tubuh masyarakat Islam sulit dielakkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Salah seorang tokoh yang menolak membaiat Ali dan mengambil sikap konfrontatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Sikap Muawiyah berujung pada terklasifikasinya masyarakat Islam kepada dua kelompok besar yakni pendukung Ali dan Muawiyah. Situasi sosial demikian menggambarkan bahwa instabilitas sosial dan politik dalam masyarakat Islam sudah semakin mengkuatirkan dan nasib Ali sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Syalabi (1997 : 306) tak obahnya bagaikan orang yang menambal kain usang, jangan menjadi baik malah bertambah sobek, mengingat selama masa pemerintahannya stabilitas sosial dan politik hampir tidak pernah dialami barang satu haripun.
Salah penyebab konflik politik dalam masyarakat Islam pada masa pemerintahan Ali adalah bergelutnya beberapa kepentingan dari kelompok sosial yang ada. Muawiyah bin Abi Sufyan yang sangat berambisi menjadi khalifah yang telah dirintisnya sejak menduduki jabatan gubernur Syam selalu menuntut Ali untuk mencari dan mengadili orang yang membunuh khalifah Usman. Sebuah tuntutan yang kelihatannya suci untuk mencari keadilan ternyata mengandung dimensi kepentingan kekuasaan yang membawa pada konfrontasi terbuka terhadap Ali dan pendukungnya. Sikap konfrontatif Muawiyah semakin menguat setelah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan untuk mengganti semua gubernur yang diangkat oleh Usman bin Affan, termasuk Muawiyah sendiri, dengan para pejabat baru. Kebijakan Ali yang pada awalnya ingin mengembalikan keadaan dan citra pemerintahan seperti pada zaman Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab, justru memancing kemarahan keluarga Bani Umaiyah dan mendorong mereka membangun kekuatan untuk melawan Ali. Dalam waktu bersamaan muncul pula kelompok sosial baru koalisi Aisyah, Thalhah dan Zubeir yang beroposisi terhadap Ali dengan motif yang sama dengan Muawiyah yaitu menuntut keadilan atas kematian Usman bin Affan (Jamal Ahmad, 1984 : 42).
Konfrontasi koalisi Aisyah, Thalhah dan Zubeir terhadap Ali membawa kepada perperangan Jamal (36 H) yang dimenangkan oleh kelompok Ali. Sedangkan konfrontasi Muawiyah dan pendukungnya berujung pula pada perperangan Shiffin (37 H) yang harus diakhiri dengan tahkim atas permintaan pihak Muawiyah.
Pada perperangan Shiffin, pasukan Ali sebenarnya mampu mendesak pasukan Muawiyah dan mereka hampir saja memperoleh kemenangan. Tetapi, kesempatan itu hilang disebabkan strategi yang dimainkan oleh Amru bin ‘Ash, yang mengangkat al-Qur’an sebagai tanda meminta perdamaian. Para Qurra yang berada di pihak Ali mendesak dirinya untuk menerima tawaran itu. Akibatnya, pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah menempuh jalan damai dengan cara bertahkim (arbitrase). Sebagai pengantara dari masing-masing kelompok yang sedang bertikai ditunjuklah Abu Musa al-Asy’ari dari pihak Ali dan Amru bin ‘Ash dari pihak Muawiyah. Kedua sepakat untuk melengserkan Ali dan Muawiyah dari jabatan khalifah.
Ketika hasil tahkim diumunkan kepada masyarakat Islam, Abu Musa al-Asy’ari menyebutkan bahwa sesuai dengan kesepakatan majlis tahkim, maka Ali dan Muawiyah diturunkan dari jabatannya. Amru bin ‘Ash menyampaikan hal yang berbeda dari kesepakatan yang sudah dibuat dan mengumumkan hanya Ali yang turun dari jabatan dan Muawiyah tidak. Keputusan yang disampaikan oleh Amru bin ‘Ash membuat tahkim bukannya menyelesaikan ketegangan untuk mencara perdamaian antara Ali dan Muawiyah melainkan ketegangan semakin menguat yang membawa kepada terjadinya dualisme pemerintahan.
Pasca tahkim, mayoritas umat Islam tetap mengakui Ali sebagai khalifah dan dua bulan berikutnya diiringi pula oleh Muawiyah yang memproklamirkan diri sebagai khalifah. Karena merasa ditipu, Ali bin Abi Thalib tidak mau meletakkan jabatan khalifah hingga akhirnya hayatnya (Harun Nasution, 1986 : 4). Hasil tahkim yang tidak adil juga mendapat protes dan kecaman dari sebagian pendukung Ali. Mereka bukan hanya tidak setuju dengan keputusan majlis tahkim melainkan juga menyatakan keluar dari kelompok Ali. Kelompok yang keluar inilah yang sangat populer dengan sebutan kaum Khawarij. Karena itu, munculnya kaum Khawarij dalam perspektif sosio-historis adalah refleksi dari kekecewaan kepada hasil tahkim yang tidak adil. Atas nama kepentingan, tahkim tidak mampu mengakomodasi kepentingan semua masyarakat Islam. Mereka juga kecewa terhadap Ali yang mau menerima ajakan Muawiyah untuk menyelesaikan pertikaian politik dengan cara bertahkim.
Sebagai refleksi kekecewaan, lebih-kurang 1200 orang kaum Khawarij sebagamana dikatakan oleh Abdul Aziz Dahlan (2001 :42) berkumpul di Harura untuk menyusun barisan dan mengangkat Abdullah bin Wahab al-Rasibi sebagai pemimpin. Dengan diangkatnya Abdullah bin Wahab al-Rasibi sebagai pemimpin oleh kaum Khawarij berarti bertambah pula kelompok sosial baru yang menjadi kekuatan sosial politik pasca peristiwa tahkim yang melakukan gerakan sosial dan politik sesuai kepentingan mereka.
C. GERAKAN FUNDAMENTALISME KHAWARIJ
Labelisasi fundamentalisme Islam terhadap gerakan kaum Khawarij agaknya terlalu sulit untuk dielakkan, mengingat sikap perlawanan yang mereka ambil pasca peristiwa tahkim mengaktual dalam bentuk aksi-aksi radikal, ekstrim dan bertolak-belakang dengan kelompok mayoritas umat Islam. Mereka seringkali terlibat dalam pemberontakan dan tindakan kekerasan pada masa pemerintahan Ali, Daulah Bani Umaiyah dan Abbasiyah. Kehadiran mereka menjelma sebagai kelompok garis keras yang dalam mencapai tujuan tertentu hampir tidak mengenal kompromi. Dalam hubungan ini, sebagian dari karakteristik fundamentalisme Islam sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya sangat melekat pada setiap gerakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij.Kaum Khawarij yang disebut sebagai fundamentalisme Islam klasik dalam menyikapi hasil tahkim melakukan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan dengan cara keluar dari kelompok Ali dan membangun prinsip-prinsip perjuangan yang radikal dan ekstrim. Bagi mereka, semboyan tiada hukum selain hukum Allah yang dikutip dari surat al-Maidah ayat 44 merupakan landasan idiologis yang berharga mati dan mesti diperjuangkan di manapun dan kapanpun. Sebagai bentuk gerakan memperjuangkan idiologis, mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena sudah menyelesaikan konflik dengan cara bertahkim yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan (Abdul Aziz Dahlan, 2001 : 46-47).
Tidak puas dengan hanya mengkafir Ali dan Muawiyah, mereka memandang kafir pula setiap orang yang tidak sepaham dengan mereka dan menurut sikap radikal mereka orang tersebut halal darahnya untuk ditumpahkan. Tuduhan kafir yang ditujukan terhadap Ali, Muawiyah dan orang tidak sepaham dengan mereka sekalipun tidak lagi termasuk dalam diskursus politik karena sudah merambah masuk ke dalam wilayah teologis, kehadiarnnya tetap saja sebagai respon yang mengambil sikap perlawanan terhadap kekuasaan yang masih berlangsung dan berfungsi untuk melegitimasi aksi-aksi radikal mereka. Dalam dunia politik, kondisi seperti itu lumrah terjadi di mana orang atau kelompok yang merasa tidak puas dengan suatu keputusan politik mengambil sikap yang berlawanan (oppositinalism) dan bernaung di balik nilai-nilai suci agama untuk melegitimasi tindakannya. Fenomena ini terlihat secara jelas pada setiap gerakan kaum Khawarij setelah mengetahui hasil penyelesaikan sengketa politik perang Shiffin melalui majlis tahkim.
Radikalisme pemikiran sebagai karakteristik fundamentalisme yang djumpai di kalangan kaum Khawarij bermula dari pemahaman yang dangkal dan literalis terhadap kitab suci al-Qura’n. Kecendrungan tersebut tergambar dari komentar Abu Zahrah (t.t : 77) yang menyebutkan bahwa selain surat al-Maidah ayat 44 mereka juga menggunakan surat Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji untuk mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ayat ini dipahami oleh kaum Khawarij secara harfiyah (literal) untuk mengkafirkan semua orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Padahal, ayat tersebut tegas Abu Zahrah menyebutkan bahwa sifat kafir hanya bisa ditujukan kepada mereka yang mengingkari kewajiban ibadah haji.
Sikap skripturalistik yang menjadi karakteristik kaum fundamentalisme Islam klasik (Khawarij) mendorong mereka untuk memahami doktrin agama dengan cara berlebihan-lebihan (ekstrim) dan biasnya mereka melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan missi kitab Suci. Gerakan mengkafirkan Ali, Muawiyah dan mereka yang tidak sepaham merupakan gambaran dari sikap ekstrim kaum Khawarij. Faktor yang mewarnai pemikiran mereka adalah lingkungan geografis dari mana mereka berasal. Mereka menurut Abu Zahrah (t.t, : 35) merupakan orang-orang Arab Baduwi yang berpikir sederhana dan berwatak keras, serta hidup secara nomaden di lingkungan geografis padang pasir yang panas dan gersang.
Masyarakat Arab Baduwi kata Ahamad Syalabi (1992, : 347) suka memberontak dan berperang meskipun karena sebab-sebab yang irrasional. Salah satu kasus adalah perperangan Basus yang berlangsung selama bertahun-tahun dan menelan korban yang tidak sedikit. Penyebabnya adalah karena Kulaib bin Rabi’ah, kepala suku Taghlib, memanah seekor unta kepunyaan Jassas bin Murrah. Karena tidak memaafkannya, Jassas membunuh Kulaib. Padahal Kulaib sendiri adalah suami saudara perempuan Jassas.
Di samping sikap skripturalistik, kaum Khawarij mengambil sikap perlawanan secara radikal terhadap Ali dan para pendudukungnya. Pasca persitiwa tahkim, mereka seperti diungkap oleh Ahmad Salabi (1992 : 318-319) mulai menyusun strategi untuk melakukan pemberontakan dan konfrontasi terbuka terhadap pendukung Ali yang berujuang pada perperangan di Nahrawan, sebuah daerah yang terletak dekat Baghdat. Sekalipun perperangan dimenangkan oleh pihak Ali, namun tidaklah mengurangi semangat gerakan kaum fundamentalisme Islam klasik itu untuk melakukan pemberontakan dan kekerasan. Sebaliknya, kekalahan melahirkan dendam yang semakin besar kepada Ali karena mengingat apa yang sudah dialami oleh saudara-saudara mereka di Nahrawan.
Puncak dari kemarahan tersebut, mereka menyusun strategi untuk membunuh Ali, Muawiyah dan Amru bin ‘Ash yang mereka anggap paling bertanggungjawab terhadap hasil tahkim yang tidak adil. Pembunuhan Ali, Muawiyah dan Amru bin ‘Ash yang dianggap oleh kaum Khawarij sebagai tugas suci dan diserahkan kepada tiga orang. Masing-masing mereka menurut Ahmad Syalabi (1997 ; 306-307) adalah Abdurrahman bin Muljam yang berangkat ke Kaufah untuk membunuh Ali, Barak bin Abdillah al-Tamimi pergi ke Syam untuk membunuh Muawiyah dan Amru bin Bakar al-Tamimi pergi ke Mesir untuk membunuh Amru bin ‘Ash. Di antara mereka hanya Abdurrahman bin Muljam yang behasil membunuh Ali dengan cara menusuknya dengan pedang ketika beliau hendak melaksanakan shalat Shubuh. Barak bin Abdillah al-Tamimi juga berhasil menikamkan pedangnya ke tubuh Muawiyah meskipun tidak berujung kepada kematian. Sedangkan Amru bin Bakar al-Tamimi gagal menjumpai Amru bin ‘Ash di Mesir.
Pada masa pemerintahan Ali, kaum Khawarij seringkali melakukan tindakan kekerasan dan merampas harta-harta orang-orang menentang gerakan mereka. Kaum Khawarij juga membolehkan untuk membunuh siapa saja dari masyarakat Islam yang tidak mau bergabung dengan mereka. Salah seorang yang menjadi korban kekerasan mereka dalah Abdullah bin Kabbab yang mengakhiri hidupnya dengan cara dibunuh. Ali pernah meminta kepada kaum Khawarij untuk menyerahkan orang membunuh Abdullah bin Kabbab. Tetapi, mereka menyembunyikannya dan mengatakan kepada Ali bahwa mereka semua ikut terlibat dalam pembunuhan itu (Ahmad Syalabi, 1992 : 317-319).
Setelah Ali terbunuh, beberapa tindakan radikal tetap dilakukan oleh kaum Khawarij pada masa pemerintahan Daulah Bani Umaiyah. Salah satu bentuk perlawanan kaum Khawarij yang dianggap gemilang terhadap kekuasaan Daulah Bani Umaiyah adalah sepeninggal Muawiyah bin Abi Sufyan sekitar tahun enam puluh Hijriyah. Mereka mengangap dengan meninggalnya Muawiyah berarti belenggu yang membatasi gerak mereka sudah lepas. Di samping itu, muncul pula kegoncangan situasi sosial dan politik dalam kehidupan umat Islam sepeninggal Muawiyah. Situasi demikian dimanfaat oleh pemimpin kaum Khawarij, Nafi’ bin Azraq, untuk memperoleh pengaruh dan kesuksesan yang besar. Ia berhasil menaklukan daerah Ahwaz dan berhasil menegakkan kekuasaan di Aswad, Basrah (Ahmad Syalabi, 1992: 324). Nafi’ bin Azraq juga berhasil memasuki kota Basrah dan menghancurkan penjara untuk membebaskan orang-orang Khawarij yang ditahan sebagai tawanan perang oleh Bani Umaiyah.
Selama belasan tahun terjadi banyak pertempuran sengit antara kaum Khawarij dan pasukan Bani Umaiyah. Kalau tidak terjadi perpecahan dalam tubuh mereka tegas Abu Zahrah (t.t. : 80) pertarungan terhadap Bani Umaiyah akan berjalan lebih lama lagi.
Sikap perlawanan yang diambil oleh kaum Khawarij pada masa Daulah Bani Umaiyah masih memiliki hubungan dengan kekecewaan mereka terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan pada peristiwa Tahkim. Lawet semboyan tiada hukum selain hukum Tuhan, mereka sudah mengkafirkan Muawiyah dan menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Sesuai dengan pandangan politik mereka, kaum Khawarij menyebut pemerintahan Daulah Bani Umaiyah adalah pemerintahan yang tidak sah. Para penguasa mereka tidak dipilih oleh masyarakat Islam ketika itu (J. Suyuthi Pulungan : 199). Pandangan yang sama mereka gunakan pula pada masa berikutnya untuk meligitimasi tindakan mereka yang radikal dan ekstrim pada masa Daulah Bani Abbasiyah.
Sebagai aliran sempalan, sikap perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij memang sangat literal, radikal, militan dan ekstrim. Beberapa karakteristik fundamentalisme sangat melekat pada setiap gerakan yang mereka dilakukan. Karena itu, penyebutan fundamentalisme Islam terhadap gerakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij sangat beralasan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abu Zahrah, Muhammad, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Dar al-Fakir al-‘Arabi, Mesir, t.t.
Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam, Paramadina, Jakarta, 1996
Dahlan, Abdul Aziz, Teologi dan Akidah dalam Islam, IAIN IB Press, Padang, 2001
Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
John L. Esposito, Ancaman Islam, Mitos atau Realitas, t.p., Bandung, 1994
Madjid, Nurcholish, Islam : Doktrin dan Peradaban, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
M. Romli, Asep Syamsul, Demonologi Islam, Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam, Gema Insani, Jakarta, 2004
Nasution Harun, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Perbandingan, UI Press, Jakarta, 1986
Pulungan, Suyuthi J, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1997
Rahman, Fazlur, Islam and modernity, and Intelectual Transformation, Bibliotheca, Minneapolis, 1979
Syalabi, Ahamd, Sejarah Kebudayaan Islam, PT. al-Husna Zikra, Jakarta, 1992

























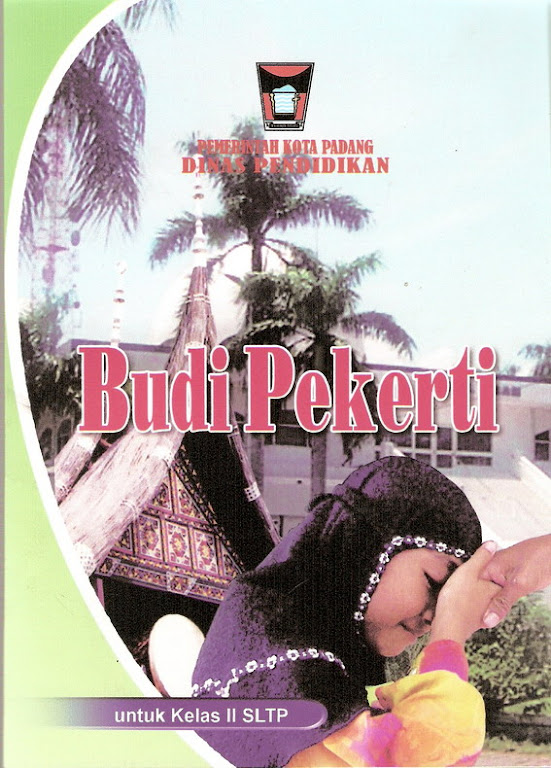





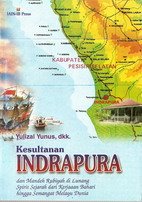




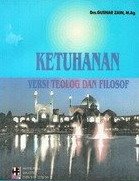
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar