Oleh : Drs. Zulkarnaini, M.Ag (Dosen Prodi PAD)
 Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengambil scope yang lebih kecil yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaannya khususnya tentang Ulama dan Politik di Aceh, Responnya terhadap kolonialisme Belanda. Dengan scope yang lebih kecil ini akan dapat mengetahui isi dari topik tersebut lebih rinci dan mendalam, sehingga dengan demikian akan dapat menggugah kembali semangat juang dan petriotisme, akan mengembalikan semangat kebersamaan senasib sepenanggungan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengambil scope yang lebih kecil yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaannya khususnya tentang Ulama dan Politik di Aceh, Responnya terhadap kolonialisme Belanda. Dengan scope yang lebih kecil ini akan dapat mengetahui isi dari topik tersebut lebih rinci dan mendalam, sehingga dengan demikian akan dapat menggugah kembali semangat juang dan petriotisme, akan mengembalikan semangat kebersamaan senasib sepenanggungan bagi masyarakat Indonesia.A. Pendahuluan
Mencermati kehidupan bernegara masyarakat Indonesia saat ini sangat membuat kita marasa prihatin, yaitu dengan menururunnya semangat patriotisme, rasa persatuan dan kesatuan yang makin menipis, telah berkurangnya rasa senasib dan sepananggungan. Kehidupan masyarakat sudah cendrung kearah kehidupan individual yang kadangkala telah terlupakan bahwa ia hidup di dalam suatu masyarakat. Yaitu suatu masyarakat yang diikat dalam suatu negara yaitu negara Republik Indonesia dengan tujuan hidup bernegara sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi ketika Indonsia telah mencapai kemerdekaan yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dalam bernegara sesuai dengan tujuan luhur bangsa tersebut, agaknya kita perlu bercermin kembali kepada perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya, yaitu suatu perjuangan yang dilandasi dengan semanagat patriotisme yang tinggi, semangat kebersamaan, senasib sepenanggungan dalam menghadapi kolonial, terutama kolonial Belanda.
Julukan Aceh sebagai bumi Serambi Mekkah, tidak terlepas dari eksistensi proses Islamisasi di Aceh. Proses Islamisasi di daerah ini merupakan proses Islamisasi yang paling awal bila dibandingkan dengan wilayah lain diseluruh Nusantara. Para ahli sejarah juga berbeda pendapat tentang waktu pertama kali masuknya agama Islam ke Aceh. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Islam mulai masuk ke daerah Aceh pada pertengahan abad ke 2 H, dan ada pula yang mengatakan pada abad ke 3 H. Ada lagi yang mengatakan pada abad ke 13 M atau abad ke 7 H, masing-masing ahli sejarah mengemukakan pendapatnya dengan argumennya masing-masing.
Beberapa abad kemudian, yakni pada akhir abad ke 16 sampai pertengahan abad ke 17 muncullah ulama-ulama besar yang memiliki kelas internasional dari negeri Aceh itu, seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syams al Din Pase al Sumatrani, Syeikh Nur al Din al Ramiry dan Syeikh Abd al Rauf al Singkily adalah nama-nama yang tidak asing lagi sampai kini, membuat nama Aceh Serambi Mekkah bertambah harum.
Pada tulisan ini penulis ingin menyingkap seberapa jauh kiprah ulama dalam perpolitikan di Aceh, dan seberapa jauh pula respon ulama dan masyarakat Aceh terhadap kolonialisme Belanda di daerah ini. Kolonial Belanda melakukan exspansinya ke Aceh tahun 1873 sampai pendudukan Jepang di Nusantara tahun 1942.
B. Ulama dan Politik Di Aceh
Kata “ulama” berarti seorang yang ahli tentang ilmu Islam ( Zainal Bahri, 1996: 334 ), sedangkan kata “politik” diartikan sebagai ketatanegaraaan dan cara bagaimana melaksanakan kebijkasanaan-kebijaksanaan pemerintah hingga dapat mencapai apa-apa yang diinginkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. ( Zainal Bahri, 1996: 254 ). Apabila kita membicarakan masalah ulama dan politik di Aceh berarti kita membicarakan sejauh mana peran ahli agama Islam dalam ketatanegaraan/kerajaan/kesultanan dalam melaksanaan suatu kebijkasanaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Awal masuknya Islam ke daerah Aceh sudah beberapa kali diseminarkan, namun demikian masih belum dicapai kata sepakat. Dalam seminar-seminar tersebut diatas, Prof. A. Hasymi berpendapat bahwa pada tahun 173 H sebuah kapal layar telah berlabuh di Bandar Peureulak, membawa angkatan dakwah dibawah pimpinan Nahkoda Khalifah yang datang dari Teluk Kambay Gujarat. Pada tanggal 1 Muharram 225 H Kerajaan Peureulak di proklamirkan menjadi sebuah Kerajaan Islam dan Sayid Abd al Aziz dilantik menjadi rajanya, dengan gelar Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abd al Aziz Syah, ( A. Hasymi, 1981: 145 ) dan selanjutnya Prof. A. Hasymi menjelaskan bahwa silsilah keturunan Meurah Silu (Al Malik al Shaleh) yang memerintah Samudera Pasai tahun 650-688 H/ 1261-1289 M menunjukkan bahwa beliau keturunan raja Islam yaitu Makhdam Sultan Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat (365-402 H/ 976-1012 M), bukannya seorang yang beragama Hindu, kemudian di Islamkan oleh Syeikh Ismail seperti cerita dongeng. Syeikh Ismail adalah seorang Syarif dari Mekkah ( A. Hasymi, 1981 : 425 ) dan sultan Makhdam Abdul Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat adalah Raja Peureulak yang ke tujuh.
Dari uraian itu sudah dapat ditangkap tanda-tanda atau sinyal-sinyal peran ulama dalam bidang politik di Aceh (sekarang Nagro Aceh Darussalam) terutama dengan penggunaan bahasa Arab yang identik dengan bahasa Islam dalam Pemerintahan.
Para ulama Aceh memberikan andil dan peran yang sangat besar dalam bidang politik di Aceh. Hal ini kita jumpai banyak bukti dalam gambaran perjalanan sejarah Aceh. Aceh sebagai salah satu wilayah Asia Tenggara termasuk kedalam apa yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra, bahwa sebagian besar kosa kata Arab yang diadopsi bahasa Melayu Indonesia, berkaitan dengan konsep atau soal-soal keagamaan: ibadah, hukum Islam, pendidikan dan tradisi sosial atau adat. Sebagian lagi diantara kosakata itu menyangkut politik. Untuk menyebut contoh dalam hal terakhir ini misalnya “daulat” Sultan, Malik (raja), Khalifah (penguasa), Bai’at tabdir (administrasi), “harb” (perang) jihad, aman, amar (keputusan), wathan (tanah air), majlis, musyawarah, umat, siasat, hizb (partai atau kelompok) dan syarikat. Istilah keagamaan yang sering digunakan dalam konteks politik, seperti adil, dzalim, amanah, hukum, qanun (Azyumardi Azra, 2000: 77 ).
Pengadopsian bahasa Arab kedalam bahasa politik di Aceh lebih kental dari daerah lain seperti undang-undang dasar Kerajaan Darussalam yang disebut dalam “qanun maukuta alam” adalah berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas (A. Hasymi, 1976 : 11 ) , sehingga jelas sekali terlihat bahwa nama kitab undang-undang kerajaan dinamakan “qanun” berasal dari bahasa Arab yang berarti undang-undang, dan yang sangat prinsip adalah dijadikannya sumber ajaran Islam sebagai dasar hukum Negara.
Selanjutnya peran Ulama dalam politik Aceh mencapai kecemerlangannya sejak berdirinya kerajaan Aceh Dar al Salam yang diproklamirkan tanggal 12 Zulqaidah tahun 916 H ( Ismail Sunny, 1986 : 58 ) dan kerajaan Aceh Dar al Salam merupakan gabungan dari hasil peleburan kerajaan Islam di Aceh, yaitu kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Pasei, kerajaan Islam Benua, kerajaan Islam Pidie, kerajaan Islam Jaya yang meliputi wilayah Aru (pulau Kampai) sampai ke Pancu di pantai utara dan barus di pantai barat serta Pagaruyung, Rengat, Jambi, Palembang sampai ke selat Malaka ( A. Hasymi, 1977 : 9) dan hampir seluruh Sumatera berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Dar al Salam pada awal berdirinya.
Dalam periode ini ulama telah mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai penentu dalam kebijaksanaan negara. Hal ini telah dikemukakan, bahwa telah tercantum dalam kitab undang-undang kerajaan “qanun” bahwa kerajaan berdasarkan atas hukum Islam, dan untuk merumuskan hukum, mensosialisasikan, serta pelaksanaan dan pengawasannya sudah dapat dipastikan akan banyak melibatkan para ulama.
Dalam bidang pendidikan A. Hasymi mengemukakan bahwa Dayyah Teungku Chik, barang kali lebih tepat kita namakan “akademi” menurut istilah sekarang, dan yang betul-betul telah merupakan sebuah perguruan tinggi dalam arti sungguh-sungguh (universitas), yaitu Jami’ah “Baitul Rahman” di Banda Aceh (Universitas Bait al Rahman ). Pada masa Iskandar Muda disempurnakan pembangunan Mesjid Bait al Rahman sekaligus dijadikan sebagai pusat kegiatan Ilmu ( A. Hasymi, 1983 : 194 ) dan zaman ini merupakan zaman keemasan dalam sejarah Aceh.
Akibat pengaruh dan respek dari dinamisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para ulama dan mubalig membuat Islam semakin menembus masuk ke dalam jantung kebudayaan Aceh. Dalam pemerintahan yang diperundangkan, hak-hak agama tetap terpelihara sebagai mana ketentuan yang telah digariskan secara bersama. Ulama tetap jadi penentu, gambaran ini tercermin dalam pernyataan A. Hasymi yang dinyatakannya. 1. Segala cabang dalam kehiduan negara dan rakyat haruslah berjiwa dan bersendi Islam. 2. Wajah politik dan wajah agama Islam pada batang tubuh masyarakat Aceh telah menjadi satu. 3. Sifat gotong royong telah menjadi khas Islam menjadi landasan berpijak bagi masyarakat dan keajaan Aceh yang dalam bahasa Aceh di sebut “ meusuraya ”berdasarkan Hadih Maja tersebut yang telah menjadi filsafat hidup rakyat dan Kerajaan Aceh Dar al Salam dan telah menjadi ketentuan pasti sebagai jalan hidup (way of live) rakyat Aceh, termasuk seni budaya, seni sastra bahkan menjadi sumber cita dan cinta sehingga karenanya Aceh bergelar Serambi Mekah ( A. Hasymi, 1977 : 194 ), sehingga konsekuensi Aceh terhadap Islam secara utuh dan mendalam terdapat diadalam kehidupan rakyat Aceh dan tercermin dalam falsafah hidupnya “ hukum ngoen adat hanjeut crei lage dat ngoen sipeut “ artinya, Hukum agama tidak bisa dipisahkan dari adat, seperti tidak dapat dipisahkannya zat Tuhan dengan sifat-Nya. Sebelum perang Aceh melawan Belanda, para ulama selain menguasai Ilmu pengetahuan dibidang agama, juga bnayak diantara mereka yang menguasai pula bidang-bidang lain seperti teknokrat, politikus, negarawan, dan sebagainya ( Ibrahim Afian, 1987: 19 ), sehingga dapat diprediksi bahwa ulama memegang peranan yang dominan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini tidak mengherankan kita bahwa banyak diantara Sultan dan Kepala pemerintahan lainnya di Aceh berasal dari ulama, seperti Sultan Iskandar Muda sendiri adalah murid dari Syeikh Hamzah Fanshuri yang seorang ulama.
C. Respon Masyarakat Aceh Terhadap Kolonial Belanda
Sejak berdirinya Kerajaan Aceh Dar al Salam, dalam perjalanan sejarahnya, pernah mengalami zaman-zaman naik menanjak ke mercu kebesaran, dan ada kalanya mengalami masa-masa menurun menuju lembah kemunduran. Masa-masa semenjak Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah (916 H) sampai pada masa Ratu Tajul Alam Safiuddin adalah zaman gemilang yang menanjak. Sementara zaman-zaman setelah itu, semenjak pemerintahan Ratu Nur l Alam Naqiyatuddin sampai kepada Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah adalah masa suram yang terus menurun. Sultan Alaiddin Ali Mughayat Syah Al Qahhar Iskandar Muda dan Ratu Tajul Alam Safiuddin adalah mutiara utama dalam mata rantai silsilah raja-raja Aceh. Kerajaan Aceh Dar al Salam yang mengambil Islam menjadi dasar negaranya, telah sanggup membangun tamaddun dan kebudayaan yang tinggi di kawasan kepulauan nusantara, terutama di Sumatera dan Malaya ( A. Hasymi, 1983 : 61 ) dan kemudian ketenangan itu terusik sewaktu mulai terjadinya konflik dengan pemerintahan kolonial Belanda.
Pada pergantian abad ke 18 secara resmi pemerintahan Indonesia pindah dari tangan VOC ketangan Hindia Belanda. Setelah pada tahun 1795 izin kontrolnya ditiadakan. Pada tahun 1798 Voc dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden ( Marwati Junet, Puspo Negoro, Nugroho Noto Susanto 1993 : 1 ) dan kemudian kaum liberal dikalangan pemerintah Belanda, antara lain yang mempunyai pembicaraannya Dirk Van Hogendrop melancarkan gagasan baru dalam menjalankan politik kolonial yaitu didasarkan atas kebebasan dan kesejahteraan umum dari pendudukan. Mereka mengusulkan pemerintahan langsung serta system pajak (Marwati Junet Puspo Negoro, 1993 : 2 ) yang bersifat tekanan kepada penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam.
Pemerintahan Hindia Belanda dan umat Islam Indonesia masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Disatu pihak pemerintahan Hindia Belanda dengan segala daya berusaha memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya, sementara di lain pihak umat Islam Indonesia berdaya upaya pula untuk melepaskan diri untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan tersebut yang pada suatu ketika dapat menimbulkan konflik. Sebagai respon atas rasa tidak senang terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Suatu kenyataan yang meemrlukan sikap serius bagi Belanda untuk menghadapinya, adalah karena agama ini akan selalu menyadarkan pemeluknya bahwa mereka dibawah cengkraman pemerintahan kafir dan bahwa cinta tanah air adalah termasuk sebagian dari Imannya ( Aqib Suminto, 1985 : 1) dan mempertahankan jiwa, agama dan tanah air adalah wajib hukumnya, dan hal ini tentulah erat hubungannya dengan kebijaksaaan yang ditempuh oleh para ulama. Sejak masuknya Islam di Nusantara, dan mengikat kita dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menyuburkan nasionalisme dan patriotisme (Muhammmad Syamsu AS, 1999 :154 ) yang dapat mengorbankan semanagt jihad mereka. Semangat jihad seperti ini sudah dapat dipastikan akan lebih hebat di wilayah Aceh, dibandingkan dengan wilayah lain di Nusantara, karena Aceh merupakan kerajaan Islam terbesar di nusantara waktu itu.
Respon ulama dan masyarakat Aceh terhadap kebijakan kolonial Belanda di Aceh, penulis bagi menjadi dua bagian yakni: Respon pada masa sebelum Snouck Hurgronje di Aceh (1863-1891), dan responnya ketika setelah Snouck Hurgronje di Aceh sampai pendudukan Jepang tahun 1942.
RESPON ULAMA DAN MASYARAKAT ACEH PARA SNOUCK HURGRONJE DI ACEH (1873-1891)
Saat kerajaan Aceh masih merupakan negara merdeka dan diakui oleh Kerajaan Inggris maupun Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian antara kedua negara kolonial tersebut. Isi perjanjian tersebut antara lain:
1. Inggris boleh berkuasa di Malaysia dan Singapura
2. Belanda boleh berkuasa di Bangka dan Belitung dan sebagian besar di Sumatera, tetapi harus menghormati kedaulatan Aceh.
Sekitar tahun 1870 M Aceh mulai tegang dengan penguasa Belanda, sebab sudah tampak oleh Sultan Aceh bahwa Belanda ingin mengendalikan perdagangan Aceh dengan negara luar. Sebagai negara merdeka Aceh merasa memiliki kebebasan untuk melakukan perdagangan dengan negara mana saja. Sedangkan Belanda khawatir jika Inggris akan mendahuluinya untuk munguasai Aceh sehingga sebelum Inggris bertindak, Belanda bertindak lebih dahulu dengan dalih Kerajaan Aceh tidak mematuhi perjanjian persahabatan ( Muhammmad Syamsu AS, 1999 : 176 ) yang menurutnya akan dapat mengancam keamanan pemerintahan Hindia Belanda sebagai alasan yang dibuat-buat.
Kerajaan Aceh barangkali telah mendengar bahwa di daerah lain di Nusantara sudah terjadi peperangan anatara pribumi dengan pemerintah Belanda, seperti di Palembang sudah dimulai perang tahun 1819 M, di Makasar mulai tahun 1653 M, Diponegoro tahun 1825 M, perang Paderi tahun 1821 M, perang Jambi mulai tahun 1858 dan perang Aceh baru dimulai tahun 1873.
Pada akhir bulan Maret 1873, sepucuk surat Gubernur Hindia Belanda sampai ke tangan Machmud Syah penguasa kesultanan Aceh Darussalam. Dalam surat itu disebutkan bahwa Belanda menginginkan agar Acek takluk kepadanya, tetapi Machmud Syah menolak dan berbarengan dengan itu ia pun segera mengkonsolidasi kekuatan rakyat ( M. Dawan Raharjo, 1985 : 174 ). Dalam kaitan itu sultan Aceh melalui wazir Ramasetia/ wakil angkatan perang Said Abdullah Tengku Dimenlauk atas nama kerajaan mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh yakni “ Bismillahirrahmnairrahiim, wahai Tuan-tuan sekalian, kita semua marilah bersiap-siap dengan senjata yang ada pada kita masing-masing, karena kita semua akan menghadapi bahaya maut dua perkara yaitu, pertama menang, kedua mati syahid, ketiga tidak ada sekali-kali menyerah kalah pada Holanda” ( A. Hasymi, 1977 : 23 ).
Konsolidasi yang dilakukan oleh Sultan Aceh memberikan hasil yang sangat gemilang dan cukup mengagumkan. Agresi Belanda pertama dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler pada tanggal 5 April 1873, dan mendapat perlawanan cukup sengit dari seluruh lapisan masyarakat. Pertempuran yang berlangsung selama 18 hari itu hanya menghasilkan tewasnya Kohler dan terpukul mundurnya serdadu Belanda ke pantai ( M. Dawan Raharjo, 1985 : 174 ) sehingga cukup banyak negara penjajah Barat terkejut karena di abad XIX yang cemerlang buat bangsa Barat rupanya masih bisa dikalahkan oleh bangsa berwarna dari Timur yang sedang luntur dan merupakan peristiwa pahit bagi Belanda.
Setelah agresi Belanda pertama gagal total, maka pemerintah Hindia Belanda di Batavia secara diam-diam mengirimkan sejumlah mata-mata yang akan menyelidiki situasi dan kondisi Aceh, kemudai disusul dengan pengangkatan Letnan, Jenderal J. Van Swieten sebagai Komandan Ekspedisi kedua untuk menaklukkan Aceh dengan kekerasan. Agresi kedua ini berlangsung pada tanggal 23 November 1873 dan tiba di Aceh bulan Desember 1873 dengan personil dan senjata lebih lengkap. Pendaratan tersebut dibawah dipimpinan wakil Panglima Perang Mayjend Verspick. Sementara dipihak Aceh hanya memiliki personil perang terbatas dan sederhana, namun berkat semangat jihad yang dikobarkan oleh para ulama, rakyat Aceh rela mengorbankan segala yang dimilikinya, harta dan jiwa sekalipun ( Taufik Abdullah (Ed), 1983 : 40 ).
Kenyataan yang dihadapi Belanda dalam menghadapi rakyat Aceh memang dinyatakan cukup rumit, selama 11 tahun sejak dimulainya agresi ke Aceh, Hindia Belanda telah mengerahkan kekuatan militernya secara optimal dan besar-besaran namun sampai saat ini Aceh belum mampu ditaklukkan, dan belum ada tanda-tanda Aceh akan menyerah pada kekuasaan Belanda. Malah sebaliknya pada tahun 1883 tekanan-tekanan pasukan Aceh di Kutaraja semakin aktif dan opensif. Gerakan maju pasukan kaum muslimin Aceh bertambah efektif dan terkoordinasi dibawah komando Sultan yang masih muda Mahmud Daud Syah (putra almarhum Mahmud Syah) dibantu oleh para ulama dan Uleebalangnya. Disamping itu istana Sultan yang telah diduduki Belanda sebelumnya terus menerus mendapat tekanan dari pasukan muslim Aceh dan membuat kerugian tidak sedikit bagi pihak Belanda dan sejak berkobarnya perang Aceh sejak tahun 1874 Indonesia (Hindia Belanda) debebani hutang sebesar 400 juta gulden ( Marwati Junet, Nugroho Noto Susanto, 1993 : 13) , selanjutnya Ibrahim Alfian menyebutkan sidang-sidang Staten General (16-17 Juni 1884) memutuskan untuk kembali kepada pasteline atau garis-garis pas yang mengelilingi pusat-pusat pendudukan Belanda dan melakukan blacckade terhadap negeri-negeri ditepi pantai. Kolonial Verslag 1885 mengaku bahwa perlawanan terhadap Belanda bertambah, dan keadaan perbendaharaan Belanda semakin parah ( Ibrahim Alfian, 1987 : 78 ). Keberhasilan muslim Aceh mematahkan serangan-serangan Belanda tidak lepas dari peran seorang tokoh sebagaimana menurut beberapa penulis sejarah bahwa didalam negeri Aceh sendiri ada perselisihan sesama pemimpin saat itu. Dalam situasi demikian Habib Abd Al rahman Al Zakir tiba di Aceh. Habib Abd Al Rahman adalah seorang ulama Arab yang mempunyai peranan penting dalam perang Aceh. Tanggal kedatangannya ke Aceh tidak diketahui secara pasti tetapi pada tahun1864 beliau diangkat menjadi penasehat kesultanan Aceh sedangkan sebelum tahun 1862 pernag bekerja pada Sultan Johor Malaysia ( Muhammad Syamsu AS, 1999 : 177 ) dan Habib Abd Al Rahman ditugaskan untuk meghubungi Turki dan negara-negara Eropa agar dapat membantu Aceh dalam menghadapi Belanda ( Muhammad Syamsu AS, 1999, 179). Di Penang Malaysia bantuan luar negeri buat Aceh diatur dan disini pula Habib Al Rahman tinggal sementara sebab belum bisa memasuki Aceh, karena pantai Timur Aceh di blokade oleh Belanda. Terbentuk pula dewan nan delapan suatu pusat bantuan buat Aceh, yang terdiri dari empat orang Aceh, dua orang Arab dan dua orang muslim India ( Muhammad Syamsu AS, 1999 : 184 ).
Sebab keberhasilan Aceh yang utama adalah faktor antropologi suku bangsa Aceh yang memiliki semacam sifat dan watak asli yang dikatakannya dengan tabiat gemar berperang dan sejak dulu lebih mencurahkan perhatiannya kepada perang dibandingkan dengan suku bangsa manapun di pulau-pualu sekitarnya ( Snouck Hurgronje, 1985 : 25 ). Watak dan sifat liar tersebut bertemu dengan Islam dimana konsep jihad diperkenalkan kepada masyarakat Aceh yang menurutnya ada kesepadanan, sehingga dalam perkembangannnya memperlihatkan keterpaduan dalam suatu wadah yaitu “Sabil Allah” tanpa memberikan perubahan dari watak asli masyarakat Aceh.
Selain faktor antropologis yang terpenting lainnnya yaitu faktor sosiologis. Masyarakat Aceh pada dasarnya memiliki dua kutub kekuatan, yakni golongan Uleebalang (Teuku) dan golongan ulama (Teungku). Golongan adat dan agama sebelum agresi Belanda merupakan dua kubu yang saling bersaing memperebutkan pengaruh, tapi bersifat persaingan seahat, karena masing-masing dapat berpegang kapada falsafah hidup mereka yakni, “ Hukom ngon adat hanjeut crei, lagei dat ngon sipeut “. Tetapi selama perang Aceh berlangsung, ulama atau teungku semakin berpengaruh dan terkemuka sebagai orang-orang yang berkuasa dinegeri itu. Artinya, faktor agama semakin berperan dan semakin besar pengaruhnya dalam masyarkat Aceh.
Sejak berlangsung perang Aceh dari tahun 1873 rakyat Aceh telah melakukan perlawanan dengan semangat jihad. Islam telah menjiwai semangat perlawanan rakyat Aceh menghadapi orang kape Belanda. Dengan semangat ini tidak menjadi soal apakah pemimpin tertangkap atau tewas, namun perlawanan terhadap kape berajalan terus dengan dipimpin para ulama seperti Teungku Cik Di Tiro dan lain-lain ( Muhammad Syam AS, 1999 : 189 ), dan semangat perlawanan seperti ini terus berlanjut sampai datangnya Snouck Hurgronje ke Aceh.
RESPON ULAMA DAN MASYARAKAT ACEH SEJAK SNOUCK HURGRONJE DI ACEH SAMPAI TAHUN 1942.
Kesulitan pemerintah Hindia Belanda dalam proses penanggulangan masalah Aceh adalah karena kurangnya pengetahuan tentang politik dan sosial masyarakat Aceh sehingga mengalami kesulitan dalam merumuskan politik Aceh dengan tepat. Untuk menghadapi kesulitan ini Snouck Hurgronje mengemukakan bahwa dalam bulan Juli 1891, “saya berkunjung ke Aceh memenuhi instruksi pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari khusus mengenai unsur keagamaan dalam kondisi politik di negeri itu. Ketika berada di Arab (1884-1885) dan terutama di Mekah saya berkesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam megenai pengaruh fanatisme Islam atas sikap orang Aceh yang tengah gigih melawan kekuasaan Belanda, saya perlu berhubungan langsung dengan orang Aceh dinegeri mereka sendiri selama beberapa waktu, guna membulatkan pengetahuan yang sudah saya peroleh dari kepustakaan dan dari pengalaman saya dikota suci Arab” ( Snouck Hurgronje, 1985 : 17 ) dan secara ringkas penulis ingin mengemukakan tentang Snouck Hurgronje.
Snouck Hurgronje yang mempunyai nama lengkap DR. Cristhian Snouck Hurgronje, dilahirkan pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout Belanda, dalam usia 18 tahun masuk Universitas Leiden (1875). Mula-mula sebagai mahasiswa fakultas Theologi, kemudian pindah ke fakultas Sastra Jurusan Arab. Sekitar tahun 1884 Snouck pergi ke Mekkah untuk mempreroleh pengetahuan praktis bahasa Arab selama satu tahun dan pada tahun 1885 kembali mengajar di Leiden ( Aqib Suminto, 1985 : 115-116 ) dan di negeri Arab ia telah memeluk agama Islam, mengenai cara masuk Islamnya Snouck untuk sementara, orang dapat berbeda pendapat. Atas dasar keterangan dari buku harian kecil Snouck di Jeddah telah dikonstruksikan jalannya peristiwa itu yang paling mungkin, bahwa masuk Islamnya berlangsung secara resmi melalui pengucapan syahadat dihadapan Qadhi Jeddah dengan dihadiri dua orang saksi pada tanggal 16 Januari 1885 ( P.S.J Van Konings Veld, 1989 : 125 ) dan bagaimana Snouck Hurgronje bisa memasuki kota suci yang pada hakikatnya tetutup bagi non muslim ini, jawabannya sederhana, Snouck pergi atas nama muslim dengan nama Abdul Gaffar ( Aqib Suminto , 1985 : 120 ), dan diperkirakan Snouck Hurgronje antara tahun 1891-1892 dan 1898-1903 telah melakukan pengalaman tujuh kali ke Aceh. Secara keseluruhan sekurang-kurangnya ia tinggal empat puluh bulan dalam wilayah Aceh ( P.S.J Van Konings Veld, 1989 : 251 ).
Kedatangan snouck Hurgronje di aceh sejak Juli 1891 sampai Februari 1892 cukup membawa pengaruh terhadap perkembangan politik Hindia Belanda di daerah ini. Politik dengan pola konsentrasi yang sedang diterapkan mendapat kritik cukup tajam darinya dengan mengatakan bahwa orang Aceh setiap saat leluasa dan dengan cara yang paling cocok dengan mereka, serta tanpa biaya atau kerugian dapat mengganggu garis benteng serta pos-pos didaerah pesisir kapan saja mereka inginkan. Pasukan-pasukan yang ditempatkan didaerah garis-garis perbentengan itu tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah ataupun menghukum mereka setelah terjadinya serangan ( Snouck Hurgronje, 1985 : 24 ) dan perubahan total politik Hindia Belanda terhadap Aceh, baru dimulai setelah Snouck mengadakan studi riset didaerah ini. Melalui hasil riset tersebut, pemerintah Hindia Belanda baru dapat memahami dan menyadari dimana Aceh memadukan kekuatan melalui dua jenis struktur pimpinan kemasyarakatan yang telah terikat kuat oleh naluri Islam dan keAcehan atau pemimpin agama dan pemimpin adat.
Dua struktur kepemimpinan Aceh tersebut dikemukakan oleh Ibrahim Affan. Pertama, pemimpin-pemimpin adat terdiri dari Sultan dan kerabat-kerabat pembantunya, para Uleebalang atau raja-raja kecil serta kerabat-kerabat yang membantu mereka. Kedalam golongan adat dapat pula dimasukkan Geucik-geucik atau petua-petua yang menjadi kepala kampung sebagai penghubung rakyat dan raja-raja kecil atau para Uleebalang itu. Kedua, para pemimpin agama adalah para ulama, yaitu guru-guru agama yang mendapat penghargaan atas keahlian yang berbeda-beda dan para pejabat agama yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan agama ( Ibrahim Alfian, 1987 : 34), dan jalinan kedua jenis struktur tersebut cukup jelas dan tegas dinyatakan dalam “Qanun” yakni adat bak poteu meureuhom, hukom bak syi’ah kuala, keduanya diikat dengan kalimat sakral lagei dat ngon sipeut hanjeut crei sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan selanjutnya Snouck Hurgronje menjelaskan tentang perang Aceh, ada tiga kekuatan di Aceh yaitu: 1. Pihak Sultan. 2. Pihak kaum Feodal dan Adat. 3. Pihak agama / golongan agama sebagai golongan yang tidak kenal kompromi, karena itu harus dipukul paling keras ( Muhammad Syamsu AS, 1999 : 191 ).
Penelitian Snouck Hurgronje di Aceh dianggap cukup berhasil. Disinilah keluar karya besarnya yang cemerlang De Atjechers yang terdiri dari dua jilid. Kemudaian dari hasil penelitiannya itu berhasil dirumuskan suatu sistem politik yang cukup tepat dan ampuh untuk menaklukkan Aceh.
Dalam meghadapi perang Aceh Snouck Hurgronje cukup lihai memanfaatkan Islam sebagai senjata yang paling ampuh. Dia cukup memahami betapa pentingnya Islam dalam pandangan Aceh sebagai agama yang telah berabad-abad dianut oleh masyarakat dan telah menjadikan agama sebagai Way of Live sehingga Islam tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik. Oleh karena itu ada beberapa faktor penting berupa advis politiknya pada pemerintahan Hindia Belanda dengan mengedepankan sifat kehati-hatiannya dalam menghadapi problem Aceh.
Pertama, Islam telah menciptakan persatuan yang cukup kokoh dikalangan masayarakat Aceh, dan persekutuan antara raja (sultan), Uleebalnag dengan tokoh Agama (ulama) sehingga sulit untuk ditundukkan. Salah satu strategi untuk menghancurkan Aceh harus dilakukan pemisahan (memecah) golongan raja-raja dengan para ulama. Golongan raja-raja dan bangsawan diberi tempat dan kedudukan, pangkat dan gaji besar serta anak-anak dan familinya disekolahkan disekolah-sekolah Belanda, sementara itu alim ulama harus ditindas, dikejar dan ditangkap ( M. Hasan Gayo, 1983 : 109 ) dan gagasan tersebut memang menjadi kenyataan, dalam tahun 1904 kebanyakan Uleebalang sudah tidak lagi terlibat dalam gerakan perlawanan dan dijadikan adaministator Hindia Belanda.
Kedua, Snouck menyadari akan posisi kunci perjuangan Aceh terletak ditangan para ulama. Kemudian ia menyatakan bahwa para teungku atau pemimpin agama selama perang berlangsung semakin kedepan sebagai orang-orang yang berkuasa dinegeri itu yang menteror kepala adat serta penduduk yang memperlihatkan kecenderungan untuk berdamai ( Ibrahim Alfian, 1987 : 26 ) yang intinya melakukan politik adu domba diantara pimpinan masyarakat, disamping usaha memojokkan para ulama agar dibenci oleh masyarakat. Kemudian ia menganjurkan bagi agama yang moderat agar dirangkul dan yang radikal harus ditumpas habis.
Gagasan ini didukung oleh Gubernur Aceh pada masa Van Heutzs. Pada masa itu operasi militer menumpas gerakan-gerakan perlawanan Mujahidin Aceh dianggap cukup sukses. Kerja sama Snouck dengan Van Heutzs sangat erat sekali, sehingga politik, taktik dan strategi militer dapat diatur secara sistematis dan seefektif mungkin ( M Hasan Gayo, 1983 : 113 ) dan Snouck sering kali mengunjungi tempat-tempat peribadatan umat Islam, seperti mesjid-mesjid, meunasah-meunasah dan temapt ibadah lainnya untuk mengadakan propaganda-propaganda membendung orang-orang yang pergi berjuang, dengan membesar-besarkan kekuatan Belanda dan meyakinkan rakyat untuk tidak bisa melawan kekuatan Belanda yang lebih besar dan lengkap persenjataanya ( M. Hasan Gayo, 1983 : 252 ) dan tentunya dengan argumen-argumen yang didasarkannya kepada ajaran Islam.
Ketiga, apabila Aceh berhasil dikalahkan dalam arti militer, maka untuk menundukkan atau menaklukkan dalam arti sesungguhnya, pemerintah Hindia Belanda perlu membangkitkan rasa toleransi dikalangan orang-orang Aceh terhadap pemerintahan Hindia Belanda dengan Asosiasi politik melalui politik etis, yaitu kebijaksanaan politik trehadap Indonesia berdasarkan hutang budi. Politik etis tersebut merupakan politik dimana agar pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak pribumi agar dengan mudah masuk sekolah negeri. Maksud Snouck adalah dengan demikian anak-anak negeri dapat dilepaskan dari agama mereka ( Umar Hasyim, 1979 : 52 ).
Keempat, untuk menghilangkan rasa konfrontatif yang dibangkitkan oleh kekuatan rasa beragama, pemeritah Hindia Belanda harus mentolelir umat Islam dengan sifat netral. Snouck menganjurkan pemerintah kolonial Belanda harus mengembangkan sikap netral terhadap Islam, dan sikap keras, tegas terhadap Islam sebagai gerakan politik, dan pemerintah kolonial sekaligus harus mengakui golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia yang agak tipis keIslamannya, yaitu kaum elite tradisional dan pemimpin-pemimpin kaum adat diluar Jawa ( Nurkholis Madjid, 1989 : 195 ) termasuk Aceh.
Setelah kehidupan Snouck Hurgronje di Aceh, usaha-usaha penaklukkan Aceh dalam waktu belakangan mengalami kemajuan dan perubahan–perubahan yang sangat pesat dan mengagumkan. Pada akhir tahun 1910-1913 denga gugurnya ulama-ulama Tiro dapatlah dianggap perang Belanda di Aceh telah berakhir sebagai simbol patahnya perlawanan fisik pihak Aceh dalam peperangan yang telah makan waktu sekitar 40 tahun ( Ibrahim Alfian, 1987 : 24 ). Namun demikian menurut Vant Veer walaupun perang gerilnya telah lampau, Aceh harus berada dalam keadan gawat dengan terjadinya banyak serangan terhadap orang-orang Eropa, pembunuhan-pembunuhan oleh orang Aceh berakhir tahun 1942 ( Paul Van Veer, 1985 : 248 ), yang terkenal denga Aceh Moor.
Melihat kondisi masyarakat Aceh yan semakin tertarik terhadap pendidikan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1910-1913, dan ketiadaan pendidikan agama didalamnya membuat kaum ulama merasa khawatir, akan kelangsungan keagamaan putra-putri Aceh masa mendatang . Untuk tahap awal para ulama Aceh membangun tempat-tempat belajar (Dayyah) seperti munculnya perguruan Islam dibawah pimpinan Teungku Abd al Wahab di Seuleumum (mencapai bentuknya tahun 1926), Madrasah Ahl al Sunnah wa al Jama’ah di Aceh timur tahun 1928 oleh Said Hasan, Al Islam di Peusangan Bireun tahun 1930 oleh Teungku Abd al Rahman, Jam’atu al Diniah tahun 1931 oleh Teungku Syaikh Ibrahim di Montaseik. Dan kemudian yang agak lebih modern Jami’at al Diniah didirikan oleh Teungku Daud Beureu’eh pada tahun 1930 di Gorout Aceh Sigli ( Anthony Reid, 1987 : 56 ).
Selama perang Aceh berlangsung Aceh telah banyak kehilangan ulama-ulamanya, rasa tidak mungkin lagi menentang kekuatan Belanda secara fisik yang semakin kuat, serta adanya perpecahan paham agama yang semakin kuat serta adanya perpecahan paham agama yang semakin tegang, Aceh menginginkan merubah wujudnya dengan sistim dan pola baru. Dalam masa yang lama sejak kalah perang tercetuslah suatu ide untuk mmepersatukan suatu ulama yang dinamakan PUSA (Persatuan Ulama di Seluruh Aceh) lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H, bertepatan denga tanggal 5 Mei 1939 ( Taufik Abdullah, 1983 : 58 ) sebagai wadah penampung aspirasi para ulama Aceh dalam melanjutkan perjuangan yang bertujuan; Pertama berusaha untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Kedua berusaha untuk mempersatukan paham para ulama Aceh tentang hukum-hukum Islam. Ketiga memperbaiki dan mempersatukan Leer Plan sekolah-sekolah agama diseluruh Aceh ( Taufik Abdullah, 1983 : 60 ) dan gejala-gejala sosial masyarakat Aceh sejak Aceh ditaklukkan sampai tahun 1940 dianggap tidak berbahaya lagi oleh pemerintah Hindia Belanda, dari sisi lain pemerintah Hindia Belanda mengalami benturan dalam menagani pendidikan di Aceh disebabkan kurangnya fasilitas, tenaga guru dan kekurangan biaya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh PUSA untuk mengembangkan sayapnya, dan PUSA menerobos untuk menentukan masa depannya sebagai wakil Aceh. Pada kurun waktu terakhir menjadi kenyataan bahwa PUSA telah muncul sebagai kekuatan penggerak revolusi menetang kolonial Belanda menjelang Jepang mendarat di Nusantara.
D. Kesimpulan
Ulama Aceh telah memberikan warna yang kental terhadap corak perpolitikan Aceh. Sinyal-sinyal dari peran tersebut terindikasi dari pemakaian kosa kata Arab dalam bahasa politik wilayah itu. Bahkan yang paling fundamental adalah dasar hukum kerajaan Dar Al Salam yang menjadikan Al qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas sebagai dasar negara. Disamping nama undang-undangnya juga dari bahasa Arab yaitu, “Qanun“ yang berarti undang-undang.
Respon ulama dan masyarakat Aceh terhadap kolonial Belanda dilakukan melalui reaksi keras tanpa kenal kompromi. Walaupun masyarakat Aceh terdiri dari beberapa struktur sosial yaitu; Sultan dengan Uleebalang dan pembantunya, golongan adat dan ulama, namun mereka telah diikat dalam suatu falsafah hidup hukom ngeon adat hanjeut crei, lagei sipeut, ngoen dat, yang artinya hukum dan adat tidak bisa dipisahkan seperti tidak dapat dipisahkannya sifat Tuhan dengan zat Nya. Kebiasaan Aceh yang suka berperang, kemudian dipadukan dengan semangat jihad yang ada dalam agama Islam, telah membuat ulama dan masyarakat Aceh tidak kenal menyerah menghadapi kolonial Belanda yang mereka anggap kaum kafir.
Kedatangan Snouck Hurgronje ke Aceh dengan membawa Islam sebagai senjatanya, mampu meredam perjuangan masyarakat Aceh yang selama ini telah membuat pihak Belanda kocar kacir. Bahkan selama perang Aceh pemerintah Hindia Belanda telah mengalami kerugian yang besar. Keberhasilan Snouck terlihat jelas pada tahun 1913 setelah ulama Tiro dan lain-lain gugur. Namun setelah itu ulama yang radikal tetap melanjutkan gerilnya sampai tahun 1942.
Sebagai saingan terhadap pendidikan pemerintah, ulama juga mendirikan sekolah-sekolah agama swasta yang disebut Dayyah. Bahkan sekolah ini bisa mengungguli sekolah pemerintah. Hal ini untuk menepis kekhawatiran ulama terhadap keyakinan putra-putri Aceh dikemudian hari.
Disamping itu tahun1939 ulama Aceh juga mendirikan wadah perkumpulan ulama dengan nama PUSA ( Persatuan Ulama Seluruh Aceh) untuk menyiarkan, mempertahankan, dan menegakkan agama Islam serta untuk mengurus semua kepentingan agama. Kemudian PUSA muncul sebagai gerakan Nasionalis untuk menuju suatu Negara Merdeka.
DAFTAR PUSTAKA
A.Hasyim, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. PT Al Ma’arif. Bandung.1981
Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bulan Bintang. Jakarta. 1976
59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Pemerintah Ratu. Bulan Bintang. Jakarta. 1977
Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Benua. Jakarta.1983
Anthony Reid, Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Sinar Harapan. Jakarta.1987
Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. LP3S. Jakarta. 1985
A.S. Harahap, Sejarah Perjanjian Islam di Asia Tenggara cetakan II. T.B Islamiyah. Medan. 1951
Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara cetakan II. PN. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.2000
Ibrahim Alfian, Perang Salib di Jalan Allah. PN. Sinar Harapan. Jakarta 1987
Ismail Sunny, Bunga Rampai Tentang Aceh. Bharata Karya Aksara. Jakarta.1986
Marwati Junet, Puspo Negoro, Nugroho Noto Susanto, Sejarah Nasional Indonesia V. Balai Pustaka. Jakarta. 1993
M. Dawan Raharjo (Ed), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah. PP Pesantren. Jakarta.1985
M. Hasan Gayo, Perang Gayo Alas Melawan Kolonial Belanda. Balai Pustaka. Jakarta. 1983
Muhammad Syamsu AS, Ulama Pembawa Islam di Indonesia. PN. Lentera. Jakarta.1999
Nurkholis Madjid, Islam Kemodernan dan KeIndonesiaan. Mizan. Bandung. 1989
Paul Van Veer, Perang Aceh. Grafiti Press. Jakarta.1985
P.S.J. Konings Veld, Snouck Hurgronje dan Islam, Giri Mukti Pusaka, Jakarta. 1989
Snouck Hurgronje, The Achehnese. Terjemahan Yayasan Soho Guru. Jakarta. 1985
Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial. PN.Rajawali. Jakarta.1983
Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Agama Dalam Islam. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1979
Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik. PN.Angkasa. Bandung.1996

























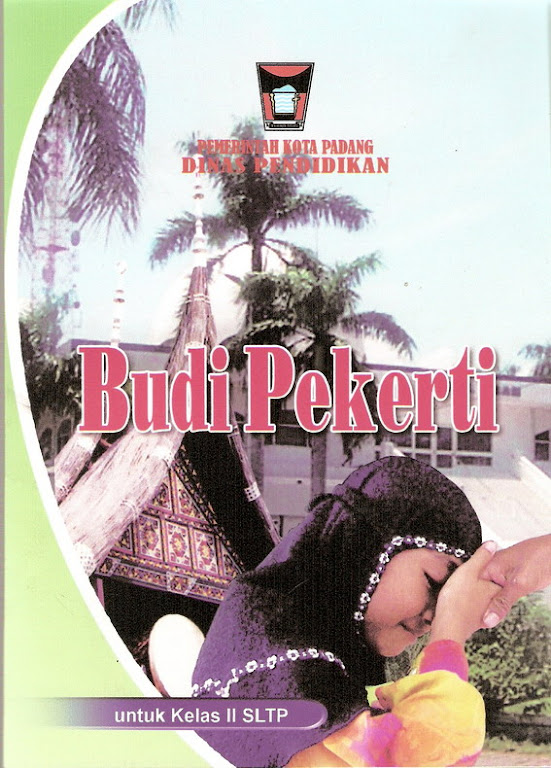





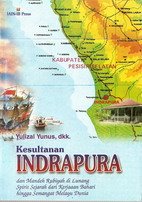




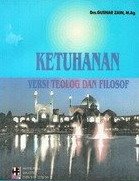
















Tidak ada komentar:
Posting Komentar